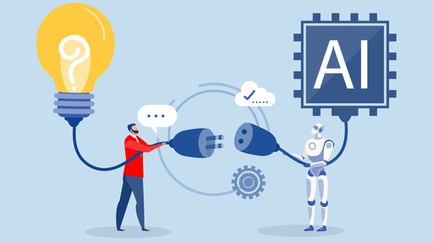tirto.id - Selain soal lidah, rasa juga berkaitan dengan ruang tempat kita tumbuh. Ketika ruang hidup berubah dari sawah ke apartemen, dari hutan ke taman kota, rasa pun bertransformasi.
Indonesia kiwari sedang mengalami transisi diet yang signifikan dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Perubahan pola konsumsi makanan dari tradisional menuju modern terjadi di seluruh wilayah, mulai dari perkotaan, perdesaan, hingga kawasan hutan dengan tingkat kehilangan tutupan pohon yang berbeda-beda.
Pola makan menjadi cermin dari relasi manusia dengan ruang dan waktu. Di ruang yang serba cepat, makanan pun dituntut adaptif: cepat dimasak, cepat dimakan, cepat dibuang. Sementara di desa yang kehilangan tutupan hutan, makanan tradisional menjadi jejak masa lalu yang kian sulit diakses.
Fenomena ini tak berdiri sendiri. Ia berkait erat dengan arus urbanisasi dan deforestasi yang secara perlahan mengubah lanskap gizi masyarakat.
Urbanisasi dan Konsumsi Serba Instan
Kota tumbuh bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam membentuk ulang kebiasaan dan nilai masyarakat. Di tengah gedung-gedung menjulang dan arus kendaraan yang tak henti, perubahan besar pun terjadi dalam cara masyarakat berinteraksi dengan makanan.
Munculnya minimarket 24 jam, layanan antar makanan, dan iklan digital yang agresif telah mereduksi makan menjadi aktivitas fungsional, bukan lagi ritual sosial yang sarat makna.
Tak hanya soal kenyamanan, preferensi terhadap makanan ultra-proses juga menjadi respons terhadap tekanan hidup urban. Gambar makanan yang menggoda di layar gawai lebih menentukan selera dibanding riwayat kuliner keluarga.
Dapur rumah pelan-pelan kehilangan fungsinya, tergantikan oleh microwave dan kemasan plastik. Pilihan konsumsi tak lagi mencerminkan tradisi, melainkan tuntutan mobilitas dan visualisasi gaya hidup. Makan kerap menjadi ritual personal yang berlangsung di depan layar gawai, bukan lagi kebersamaan di meja makan.
Penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan konsumsi yang mencolok pada beberapa kategori makanan modern. Konsumsi gandum mengalami kenaikan yang pesat, terutama dalam bentuk produk olahan seperti roti, mie, dan pasta.
Ayam broiler menjadi pilihan protein hewani yang semakin populer. Tingkat konsumsi daging ayam broiler per kapita mencapai 0,532 kg pada 2019, naik menjadi 0,557 kg pada 2020, dan 0,538 kg pada 2021. Bahkan pada 2023, konsumsi daging ayam ras meningkat menjadi 7,46 kilogram per kapita per tahun, naik 4,3 persen dibanding tahun sebelumnya.
Minuman manis dan berpemanis menjadi tren yang mengkhawatirkan. Indonesia menempati posisi ketiga dalam konsumsi minuman berpemanis di Asia Tenggara dengan 20,23 liter per orang per tahun.
Laporan Center For Indonesia Strategic Development Iniatitives (CISDI) pada 2020-2022 mencatat konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan didominasi dalam bentuk air teh dalam kemasan dan minuman bersoda dengan CO2.
Makanan olahan dan ultra-olahan semakin diminati. Konsumsi ultra-processed foods (UPF) di Indonesia telah mencapai sekitar 45 persen dari total asupan kalori pada tahun 2020. Nilai penjualan retail makanan dan minuman kemasan meningkat setiap tahun, mencapai $40,11 miliar pada 2022.

Makanan siap saji dan instan menjadi pilihan praktis. Merujuk Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 Badan Pusat Statistik, sebanyak 99,43 persen rumah tangga Indonesia mengonsumsi makanan dan minuman jadi, menjadikannya komoditas makanan terbanyak kedua yang dikonsumsi di 2024.
Di sisi lain, terjadi penurunan konsumsi makanan tradisional yang memprihatinkan. Konsumsi sayuran hijau mengalami penurunan drastis. Di daerah-daerah yang dulu hijau dan beragam, lanskap kini berubah menjadi lahan gundul atau perkebunan monokultur.
Deforestasi bukan hanya kehilangan pohon, tetapi juga kehilangan rasa. Sayur hutan, buah lokal, dan rempah yang dulunya menjadi bagian dari memori keluarga kini mulai hilang dari meja makan. Masyarakat yang sebelumnya memiliki hubungan ekologis dengan pangan beralih menjadi konsumen produk yang berasal dari jauh, diolah di pabrik, dan dipasarkan lewat algoritma.
Kemiskinan ekologis ini tak terlihat dalam angka ekonomi formal, tapi nyata dalam berkurangnya pilihan gizi yang sehat dan berakar budaya. Anak-anak tumbuh tanpa mengenal rasa daun gedi atau buah kecapi, misalnya, tetapi hafal merek sereal dan camilan impor. Dari segi nutrisi, transisi ini menciptakan sistem pangan yang homogen, mudah terganggu, dan jauh dari prinsip keberlanjutan.
Data Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan hanya 21,25 persen remaja di Jawa Tengah yang mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi 3-4 kali seminggu. Lebih dari 96 persen masyarakat Indonesia masih kurang dalam mengonsumsi sayur dan buah.
Kacang-kacangan segar juga mengalami penurunan konsumsi di berbagai wilayah. Padahal, kacang-kacangan merupakan sumber protein nabati penting dalam pola makan tradisional Indonesia.
Makanan pokok lokal seperti umbi-umbian mengalami penurunan konsumsi yang signifikan. Data menunjukkan penurunan konsumsi singkong, ubi jalar, kentang, dan sagu. Umbi-umbian bahkan menjadi komoditas makanan dengan tingkat konsumsi terendah pada 2024.
Ketika Tutupan Pohon Hilang, Pangan Lokal Menyusut
Studi terbaru dari CIFOR-ICRAF yang dipublikasikan pada Juli 2025, menyoroti bagaimana modernisasi pola makan terjadi lebih cepat di wilayah perkotaan dan daerah dengan tingkat tree cover loss (TCL) yang tinggi.
Studi tersebut menghasilkan beberapa temuan, salah satunya daerah perkotaan menunjukkan adopsi makanan modern yang paling cepat. Masyarakat kota cenderung mengonsumsi makanan cepat saji, makanan kemasan, dan minuman berpemanis dalam jumlah yang lebih tinggi. Urbanisasi yang cepat membuat masyarakat kota lebih mudah mengakses makanan modern dan praktis.
Temuan lainnya ialah deforestasi yang mengancam ketahanan pangan tradisional. Hutan berperan penting dalam menyediakan pangan bergizi. Kehilangan hutan menyebabkan hilangnya tradisi makan sehat yang telah turun-temurun.
Kawasan hutan menyediakan sumber mikronutrien yang beragam, termasuk buah-buahan hutan, umbi-umbian, biji-bijian, hingga protein dari fauna liar. Sistem agroforestri lokal terbukti mendukung ketahanan pangan.
Masyarakat di kawasan ini masih mengonsumsi makanan pokok lokal, telur kampung, dan sayuran hijau dalam jumlah yang lebih tinggi. Mereka juga masih memanfaatkan pangan hutan seperti buah-buahan liar, umbut-umbutan, dan protein dari fauna liar seperti yang dilakukan Suku Mapur di Benak, Provinsi Bangka Belitung.
"Ini untuk lalapan malam ini. Cukup direbus, atau langsung dimakan juga bisa. Enak, tinggal dan berkebun di sekitar hutan, sayuran tidak perlu beli," ujar Nek Yu (75) yang secara teratur mengumpulkan sayuran hijau liar setelah bekerja di kebun mereka, dikutip dari Mongabay.

Penelitian CIFOR-ICRAF juga menemukan perubahan pola makan yang membawa dampak kesehatan beragam. Kualitas diet mengalami penurunan di semua area, dengan penurunan paling cepat terjadi di daerah perkotaan. Daerah perkotaan menunjukkan penurunan keragaman diet dan peningkatan konsumsi makanan ultra-olahan.
Kebiasaan tersebut berkontribusi pada triple burden malnutrition di Indonesia, yaitu kekurangan gizi (stunting), kelebihan berat badan (obesitas), dan kekurangan mikronutrien. Hampir sepertiga anak balita di Indonesia mengalami stunting dan satu dari sepuluh anak balita mengalami gangguan kesehatan, menurut data Kementerian Kesehatan pada 2019.
Lain itu, peningkatan prevalensi penyakit tidak menular menjadi konsekuensi serius. Konsumsi makanan ultra olahan yang tinggi berhubungan dengan peningkatan prevalensi obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Indonesia bahkan menempati peringkat ketujuh di dunia dengan jumlah penderita diabetes terbesar, sekitar 10,7 juta orang pada 2021.
Survei Populix pada Juli 2024 dengan 1.252 responden mengungkap pola konsumsi gula masyarakat Indonesia. Sebanyak 35 persen responden memilih gula asli dibanding pemanis buatan karena dianggap lebih alami. 28 persen mencari produk berlabel less sugar atau tanpa gula tambahan sebagai upaya hidup lebih sehat. 22 persen rajin membaca label untuk mengecek kandungan gula sebelum membeli. Sedangkan 15 persen di antaranya tidak peduli dengan kandungan gula dalam produk yang dibeli.
Begitu pula malnutrisi ganda yang menjadi tantangan besar. Masyarakat mengalami kekurangan gizi (defisiensi zat besi, vitamin A, atau protein) sekaligus kelebihan gizi (obesitas). Sekitar 100 juta orang atau 40 persen populasi Indonesia menderita satu atau lebih defisiensi mikronutrien.
Ruang, Rasa, dan Pilihan yang Tak Lagi Bebas
Mengingat dampak kesehatan yang beragam dari diet modern, kebijakan harus mengantisipasi dampak negatif sambil mempertahankan aspek positifnya. Pemerintah telah mulai mengimplementasikan kebijakan seperti pelabelan gizi dan pajak gula untuk mengurangi dampak negatif konsumsi makanan ultra-olahan.
Penganekaragaman pangan menjadi kunci penting. Hutan adat menyediakan tanaman pangan alternatif seperti sagu, aren, dan talas hutan yang dapat menjadi sumber karbohidrat selain padi. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sayur dan buah perlu terus digalakkan.
World Resources Institute (WRI) Indonesia dalam laporan bertajuk "Membangun Ketahanan Pangan Indonesia 2030" membahas tantangan ketahanan pangan dan perubahan pola makan, termasuk data tentang malnutrisi dan impor pangan.
Laporan juga menekankan pentingnya empat pilar sistem transportasi pangan: pola makan sehat, produksi pangan berkelanjutan, mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan, dan kolaborasi banyak pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum, sangat penting dalam upaya menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan.
Transisi pola makan di Indonesia mencerminkan perubahan global menuju modernisasi pangan. Namun, tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan kemudahan dan kepraktisan makanan modern dengan mempertahankan kearifan pangan tradisional yang terbukti lebih sehat dan berkelanjutan.
Dalam pusaran modernisasi, harapan tak selalu harus berbentuk nostalgia. Kita bisa membayangkan bentuk baru dari keberlanjutan kuliner, yang menggabungkan elemen lokal dan inovasi urban.
Pertanian vertikal di atap gedung, revitalisasi pasar tradisional dengan pendekatan digital, hingga gerakan komunitas yang memasak bersama dari bahan lokal, semua adalah bentuk resistensi terhadap homogenisasi gizi.
Makanan yang sehat bukan sekadar organik atau diet rendah kalori. Ia adalah makanan yang punya akar pada tanah, pada tradisi, dan pada rasa komunitas.
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id