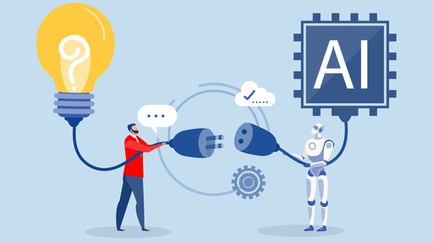tirto.id - Bayangkan sebuah dunia ketika sisir terbuat dari gading, bola biliar dari taring gajah, dan lensa film fotografi dicetak dari kaca rapuh. Penuh romantisisme, tetapi mahal dan hampir selalu berkorban darah.
Dari sanalah plastik lahir sebagai pendongkrak zaman, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai penyelamat. Namun, seperti mitos Prometheus dalam tragedi klasik, sang penyelamat perlahan berubah menjadi ancaman.
Serupa virus, plastik menginfeksi prahara budaya masyarakat. Manusia tidur di atas bantal berisi plastik, membersihkan gigi dengan gagang dan sikat dari plastik, menulis dengan papan ketik plastik, minum dan makan dari wadah plastik. Tak ada satu pun hari yang terlewat tanpa menggumuli plastik.
Penelitian dari jurnal Environmental Studies (2019) menyebut, kontaminasi polusi plastik telah meningkat secara eksponensial sejak 1945. Para ilmuwan menganalogikan, setelah zaman perunggu dan besi, periodisasi antroposentrisme kini dikenal sebagai zaman plastik.
Analisis terperinci pertama tentang peningkatan polusi plastik diadopsi dari sedimentasi lapisan tanah tahunan di lepas pantai California selama periode 1834-2009. Peneliti menemukan, plastik di lapisan tanah itu mencerminkan peningkatan eksponensial dalam produksi plastik selama 70 tahun terakhir.
Pertanyaannya, bagaimana manusia bisa sampai ke periode zaman plastik?
Dari Parkesine sampai Bakelite
Plastik sintetis pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Parkes di Pameran Internasional London tahun 1862 dengan material yang disebut Parkesine—diambil dari nama penemunya. Parkesine terbuat dari nitroselulosa, bersifat lentur saat dipanaskan dan mengeras dalam berbagai bentuk sesuai kehendak setelah mendingin.
Parkes terinspirasi dari berbagai peranti “plastik alami” yang dibuat dari tanduk, kulit kura-kura, dan karet yang telah beken sejak zaman kuno. Dia merancang senyawa sintetis yang dapat membebaskan industri mebel dan aksesoris mode dari kekangan hewan langka.
Bagai kain sutra buatan yang pertama kali mengusap kulit, Parkesine membuka tabir kemungkinan baru dalam manufaktur massal.
Berselang hampir berdekatan, John Wesley Hyatt menyempurnakan formula Parkesine menjadi seluloid pada 1869. Dia mencampurkan serat kapas dengan kamper, lalu menambahkan alkohol. Sebuah bahan baru ditemukan, yang dapat “meniru” zat alami seperti kulit kura-kura, tanduk, linen, dan gading.
Penelitian John Wesley Hyatt didorong oleh sayembara salah satu perusahaan New York yang menjanjikan hadiah sebesar 10.000 dolar bagi siapa saja yang dapat menemukan pengganti gading. Sebab, meningkatnya permintaan produksi bola biliar kala itu mulai membebani pasokan gading gajah yang dicangkok lewat penyembelihan liar.
Penemuan Hyatt sungguh revolusioner. Pertama kalinya, industri manufaktur manusia tak lagi bergantung pada kesediaan alam yang terbatas. Sejak itu, manusia sudah dapat mengolah dan menciptakan bahan baru. Hal itu juga membantu manusia lepas dari kendala sosial dan ekonomi akibat kelangkaan sumber daya alam.
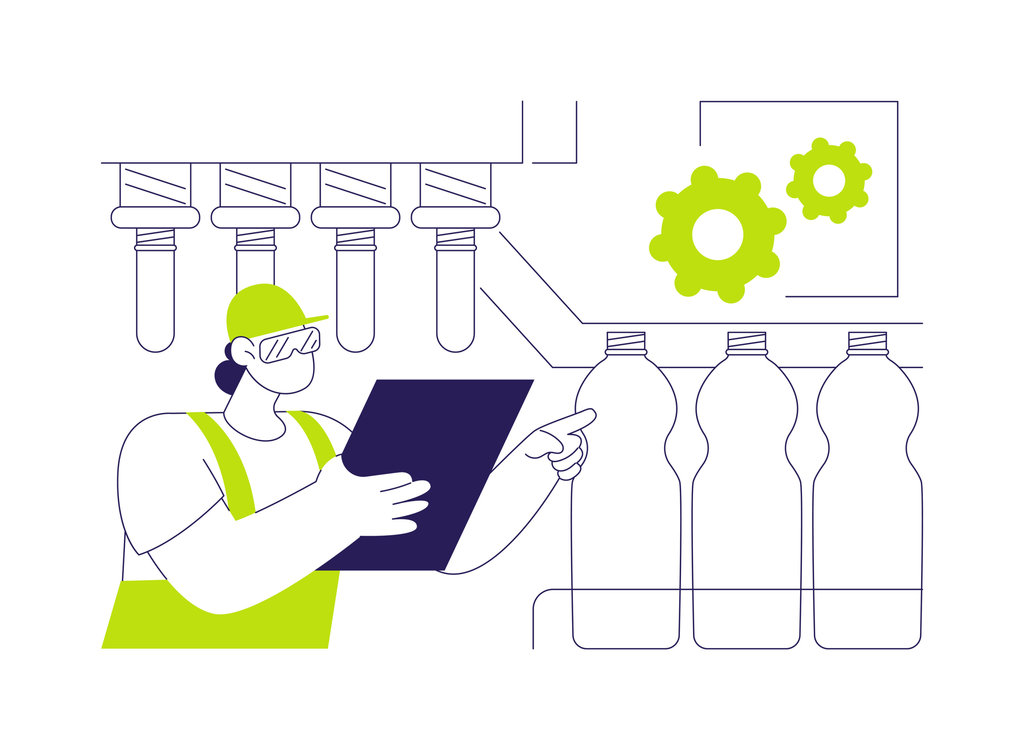
Warsa 1907, Leo Baekeland meretas batas berikutnya lewat bahan yang dia namakan Bakelite, plastik pertama yang sepenuhnya sintetis. Artinya, bahan tersebut sama sekali tak mengandung molekul yang ditemukan secara “alami”.
Diklaim tahan panas, kuat, dan mudah dicetak, Bakelite bukan hanya isolator yang baik untuk kebutuhan elektrifikasi, tetapi juga sangat cocok untuk produksi massal mekanis. Baekeland menjuluki penemuannya sebagai “bahan seribu guna”, menyusuri jalan lapang peranti telepon, peralatan dapur, hingga komponen militer.
Ledakan di Medan Perang dan Simfoni Kapitalisme
Perang Dunia II menjadi medan laga megah untuk plastik. Nilon—ditemukan oleh Wallace Carothers pada 1935—menggantikan sutra untuk kebutuhan parasut, tali, pelindung tubuh, dan helm serdadu. Sementara itu, Plexiglas menyalip kaca di kokpit pesawat.
Artikel Joseph L. Nicholson dan George Ross Leighton bertajuk “Plastics come of age” yang terbit di HarpersMagazine mencatat, karena perang, “Plastik telah diubah menjadi kegunaan baru dan kemampuan beradaptasi plastik ditunjukkan lagi,” (hlm. 36).
Di Amerika Serikat, produksi plastik melonjak 300 persen demi kebutuhan militer. Setelah perang, masyarakat yang lelah dengan kekhawatiran perang dan resesi justru memuja plastik sebagai lambang kesejahteraan.
Dialah anasir kapitalisme yang maha ringan, murah, dan serba guna.
Penggunaan plastik terus melonjak meski dunia mengalami Masa Depresi Besar.
“Dalam produk demi produk, pasar demi pasar, plastik menantang bahan tradisional dan menang, menggantikan baja di mobil, kertas dan kaca dalam kemasan, dan kayu dalam furnitur. Bahkan kereta Amish sekarang sebagian terbuat dari plastik yang diperkuat serat yang dikenal sebagai fiberglass,” tulis Susan Freinkel dalam Plastic: A Toxic Love Story (2011: 6).
Tak butuh waktu lama, plastik telah beralih orientasi dari alternatif menjadi standar produk. Pada 1979, produksi plastik melebihi baja. Dalam waktu singkat, plastik telah menjadi kerangka, jaringan ikat, dan kulit licin kehidupan modern.
Plastik vs. Kertas: Pertarungan Media dan Kemasan
Ketika kantong kertas bergemerisik di jalanan ibu kota, plastik menyelinap bak angin musim semi: tak basah saat hujan, tak robek oleh gesekan, dan tentunya tak membikin kantong jebol.
Korporasi petrokimia raksasa seperti DuPont, ExxonMobil, dan Dow Chemical memainkan peran penting dalam kampanye tersebut. Mereka tidak hanya memproduksi plastik, tetapi juga membentuk narasi bahwa plastik adalah simbol kemajuan, efisiensi, dan masa depan.
Iklan-iklan di televisi dan majalah memamerkan rumah tangga modern yang serba plastik. Misalnya, ibu-ibu menata plastik merek Tupperware yang berkilau, supermarket berisi kantong plastik berwarna cerah, hingga mainan anak-anak yang bebas tumpah.
Dengan sekali sablon logo merek, plastik menjadi billboard berjalan yang merajai mobilisasi barang dan komunikasi visual rumah tangga modern.
Tak bisa dimungkiri, masalah plastik kian menggerayangi. Para korporasi besar yang kadung bergantung padanya dipaksa ambil tindakan. Coca-Cola, misalnya, meluncurkan inisiatif World Without Waste untuk membersihkan botolnya. Itu adalah bentuk politik Corporate Social Responsibility (CSR) yang mengonstruksi wacana end-of-life, sebuah kampanye yang penuh ambivalensi.
Mereka memosisikan industri dan kampanyenya sebagai pelopor daur ulang, meski tetap menjadi salah satu produsen botol plastik terbesar. Artinya, kampanye perusahaan tak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi menyasar arah kebijakan lingkungan.
Banyak kritik menyebut bahwa kampanye Coca-Cola lebih tepat disebut menunda solusi daripada menyelesaikan masalah. Fokusnya adalah daur ulang dan pembersihan, bukan pengurangan produksi. Itu tak ubahnya seperti menyapu lantai sambil terus menumpahkan air dari ember.

Kutukan Inovasi Plastik
Kini, plastik telah berserakan di mana-mana, dari bungkus mi instan sampai benang kusut yang menjubel di saringan lubang selokan. Plastik menyusup ke tubuh ikan, lalu jatuh di wajan penggorengan, dan disantap di meja makan.
Plastik bisa saja kembali lewat kutukan dalam bentuk yang liyan. Dalam skala tertentu, mikroplastik dapat menjangkit, bahkan tanpa manusia sadari.
Produksi plastik melambung dari 15 juta ton pada 1964 menjadi 390 juta ton pada 2021. Akan tetapi, bahkan setelah tahu dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem kehidupan, manusia tetap menggilainya.
Mengapa? Karena plastik adalah cermin dari manusia dan modernitas: cepat, praktis, dan sering kali abai. Ia adalah anak revolusi industri yang tumbuh besar dalam pelukan kapitalisme.
Plastik lahir dari gairah manusia mengatasi keterbatasan alam. Di satu sisi, ia mengupayakan inovasi dan menurunkan biaya hidup. Di sisi lain, ia menimbun sampah tak terurai dan mencemari jaringan kehidupan.
Sebagaimana pisau bermata dua, plastik menantang kita untuk memilih: merawat atau terus membiarkannya melahap dunia ini.
Plastik bukanlah iblis; ia adalah ciptaan manusia. Bukan mereka yang mengutuk lingkungan, tetapi bumi yang makin hari tak kuasa menahan luka akibat ulah manusia.
Banjir bandang akibat penyumbatan aliran sungai, air bersih kian menipis, bahan konsumsi primer jadi tercemar, dan berbagai bencana lainnya. Kini, semua bergantung pada laku manusia yang menentukan masa depan. Mau sampai kapan terus menggilai plastik?
Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id