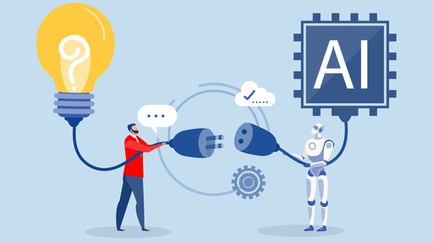tirto.id - Dulu, atau mungkin sampai kiwari, masyarakat Indonesia sering mengidentikkan nama-nama bulan berakhiran "ber" dengan musim hujan. Tentu penyebutan itu berdasarkan pada musim yang berulang secara presisi, saat kondisi iklim normal.
Namun belakangan, akibat pemanasan global, bulan-bulan berakhiran "ber" tak selalu menjadi musim hujan. Bahkan lebih parah, yang turun dari langit saat hujan, sekarang tak selalu air.
Dalam studinya berjudul "Atmospheric Transport and Deposition of Microplastics in a Remote Mountain Catchment" (Nature Geoscience, 2018), Steve Allen menemukan mikroplastik yang larut dalam aliran Sungai Alpine di Pergunungan Pyrenees, Prancis.
Berjarak sekitar 6 kilometer dari permukiman terdekat, mikroplastik tersebut tak muncul gara-gara aktivitas warga sekitar, tetapi bersumber dari hujan.
Mikroplastik ini turun dari langit dengan kuantitas rata-rata sebesar 100 hingga 300μm (micro meter) setiap kali tetes hujan membasahi, dengan kuantitas tertinggi sebesar 3.000μm, mengikuti turun naik curah hujan setempat.
Seturut dengan studi berjudul "It is Raining Plastic" (U.S. Geological Survey, 2019), tim peneliti yang diketuai Gregory Wetherbee menemukan kandungan mikroplastik pada 90 persen hujan yang turun di daerah Front Range, Colorado, Amerika Serikat.
Dua temuan mencengangkan ini seakan mengamini prediksi V. E. Yarsley dan E. G. Couzens pada 1941 dalam artikel yang mereka tulis untuk Science Digest, menjadi penanda mutlak "Plastic Age" atau Zaman Plastik.
Zaman ini, menurut Yarsley dan Couzens, penuh kecemerlangan bagi umat manusia karena plastik memiliki sifat "kuat, aman, dan bersih". Pas digunakan untuk segala keperluan.
Namun, sifat "kuat" yang dimiliki plastik akhirnya menjadi mimpi buruk bagi lingkungan tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya.
Samudra Jadi Tempat Pembuangan Sampah
"Merujuk hukum internasional, pelbagai negara di dunia mengendalikan perairan dalam jarak dua ratus mil dari pantai mereka," tutur Edith Widder dalam "Below the Edge of Darkness: A Memoir of Exploring Light and Life in the Deep Sea" (2021).
Di luar jarak tersebut, lautan dan segala isinya dianggap sebagai "warisan bersama umat manusia". Wilayah ini dalam istilah yang digaungkan International Seabed Authority disebut sebagai "The Area". Dalam The Area inilah para ilmuwan dunia memercayai keberadaan "harta karun" yang luar biasa jumlahnya.
Misalnya, terkandung enam kali lebih banyak kobalt, tiga kali lebih banyak nikel, dan empat kali lebih banyak logam yttrium dibandingkan di darat. Atau, paling sederhana, harta dari kapal-kapal yang tenggelam juga keanekaragaman hayati makhluk hidup "super" yang tinggal di dasar lautan.
Atas dasar ini, upaya mengeksploitasi lautan yang terangkum dalam The Area digalakkan. Mula-mula dilakukan pada 1974 oleh Howard Hughes atas pemintaan CIA di Midway Atoll--untuk mengangkat kapal selam milik Uni Soviet yang tenggelam.
Dan perlahan-lahan, individu/institusi/perusahaan melakukan langkah serupa, termasuk oleh Ocean Minerals, perusahaan eksplorasi laut asal Amerika Serikat yang mencoba mengeksploitasi harta karun di The Area sekitar California.
Sama-sama menggunakan jasa milik Hughes, selain berhasil menemukan mineral yang diincar serta ikan-ikan bioluminescent (ikan yang menghasilkan cahaya melalui reaksi enzim luciferin yang terdapat dalam tubuh mereka) di dasar lautan, Ocean Minerals juga menemukan "harta lain" berupa sampah plastik.
Hanya diproduksi sekitar 15 juta ton pada 1960-an untuk pelbagai keperluan, plastik kini diproduksi tak kurang dari 335 juta ton setiap tahun di seluruh dunia, dengan 40 persen dari angka tersebut dimanfaatkan untuk segala jenis bungkus/kemasan.
Karena plastik terurai dalam tempo lambat serta hanya sembilan persen dari total plastik yang diproduksi per tahunnya dapat didaur-ulang, maka terakumulasi sampah plastik yang menggunung.
Limbah ini mengotori daratan, hutan, dan sungai. Merujuk penelitian yang dilakukan Jenna Jambeck dalam "Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean" (Science, 2015), 10 persen di antaranya atau sekitar delapan juta metrik ton mencemari lautan.
Jumlah super besar yang menurut Jambeck, "setara dengan lima kantong plastik yang dipenuhi plastik yang dibuang setiap 30 meter sepanjang garis pantai di seluruh dunia."
Atau, merujuk temuan Charles Moore dalam "Plastic Ocean: How a Sea Captain's Chance Discovery Launched a Determined Quest to Save the Oceans" (2011), "sampah plastik memiliki massa lebih banyak dibandingkan zooplankton, makhluk hidup yang berada di posisi terbawah strata rantai makanan, di pusaran samudra (ocean gyre)."
Akumulasi sampah plastik yang tiba di lautan, secara kasat mata, akhirnya membentuk Great Pacific Garbage Patch yang berada di The Area di sekitar lautan California dan Hawaii, alias tempat pembuangan sampah raksasa yang mengapung di samudra.
Karena area ini hanya merangkum sekitar satu persen kuantitas sampah plastik, sisanya tersebar tak karuan di lautan di seluruh dunia. Hal ini salah satunya menewaskan paus sperma yang terdampar di perairan Indonesia. Di dalam perut ikan ini ditemukan 5.9 kilogram sampah.

Upaya Pembersihan dan Tantangannya
Sejumlah upaya membersihkan laut dari sampah plastik kemudian digalakkan. Salah satunya dilakukan oleh organisasi nirlaba Ocean Cleanup dengan menggandeng Youtuber di seluruh dunia (#TeamSeas). Mereka mengumpulkan sampah plastik yang ada di garis pantai.
Upaya lain dilakukan oleh Plastic Fischer yang juga organisasi nirlaba. Mereka mencoba mencegah sampah plastik tiba di lautan via aliran sungai.
Memanfaatkan teknologi murah-meriah dan sederhana yang mereka kembangkan bernama TrashBoom, sampah yang hendak menuju lautan dibendung di sungai dengan alat ini untuk kemudian dibawa ke daratan dan diproses.
Hal ini telah dipraktikkan di sungai-sungai yang ada di Indonesia, Vietnam, dan Thailand. TrashBoom rencananya akan dipasang dalam kuantitas 500 unit di seluruh dunia dengan perkiraan sampah yang bisa ditanggulangi berjumlah 3 juta ton.
Sayangnya, upaya menanggulangi sampah plastik di lautan memiliki satu masalah krusial yang sukar ditanggulangi. Sampah plastik yang ada di lautan umumnya sudah tidak utuh, dalam bentuk ember misalnya, tetapi telah terurai menjadi bentuk-bentuk kecil, dan, paling berbahaya telah berevolusi menjadi mikroplastik.
Mikroplastik tidak terlihat secara kasatmata dan tidak mengambang di permukaan laut.
Merujuk studi berjudul "Risks of Floating Microplastic in the Global Ocean" (Environmental Pollution, 2020) yang digagas Gert Everaert, sebagian sampah plastik yang telah menjadi mikroplastik mengendap di dasar lautan (tak sampai 1 persen), dan sebagian lagi (sekitar 0,17 persen) terapung di tengah lautan, khususnya di bagian timur Laut Mediterania.
Sisanya yang mayoritas, atau hampir 99 persen mikroplastik di lautan tak diketahui keberadaannya secara pasti.
Hal ini membuat ilmuwan menjuluki ketidaktahuan mereka atas mikroplastik dalam jumlah besar sebagai "dark plastic". Namun yang pasti, terurainya sampah plastik menjadi mikroplastik di lautan merupakan kunci mengapa di Pergunungan Pyrenees, Prancis, atau di daerah Front Range, Colorado, Amerika Serikat, terjadi fenomena hujan plastik.
Fenomena ini terjadi atas takdir alamiah bernama "siklus air" dan hasrat tak berkesudahan umat manusia yang terus-menerus menggunakan plastik.
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id