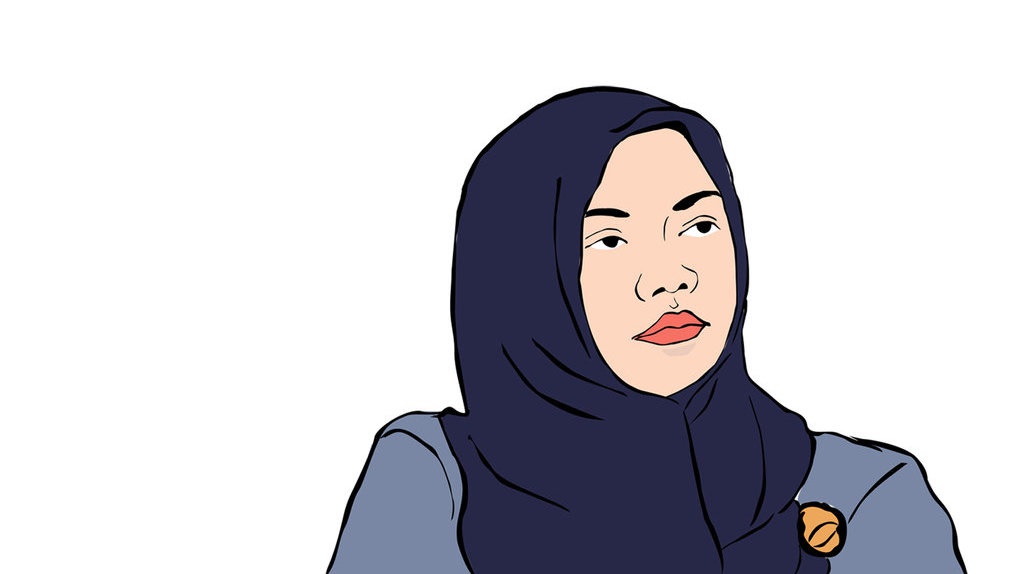tirto.id - Sejumlah jenderal TNI dan Polri diusung partai-partai politik untuk bertarung setidaknya pada tiga Pilgub 2018: Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Jumlahnya kecil bila dibandingkan total ada 171 daerah pada Pilkada serentak 2018. Namun, bagi Titi Anggraini, ini bukan persoalan angka empat atau lima jenderal yang berpolitik.
“Ini sangat mengganggu ... mereka melakukan komunikasi politik saat masih berstatus perwira atau personel aktif,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tersebut.
Menurutnya, pilkada serentak 2018 menjadi sorotan karena teknologi informasi berkembang sedemikian rupa sehingga komunikasi politik para jenderal bisa ditangkap dan dilihat oleh publik. Di Indonesia, TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan hal itu sudah jelas belaka.
Tapi para perwira aktif ini, dari Letjen Edy Rahmayadi sampai Irjen polisi Anton Charliyan, selalu berlindung di balik UU Pilkada yang memang tidak melarang mereka dekat dengan parpol dan tidak harus mengundurkan diri sejauh belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Parpol pun tak bikin tembok tinggi dengan memanfaatkan celah tersebut.
Tetapi gelagat macam itu tetap dinilai "tidak etis" dalam soal netralitas TNI dan Polri, menurut Aggraini. "Netralitas itu mewajibkan mereka tidak berpihak, tidak ikut dan tidak membantu dalam aktivitas politik," tambahnya.
“Ketika para jenderal melakukan komunikasi politik secara terbuka terkait proses pencalonan, mereka sudah melakukan politik praktis,” kata Anggraini, yang sudah lama punya perhatian terhadap politik elektoral di Indonesia.
Berikut petikan wawancaranya bersama Reja Hidayat via telepon, awal pekan lalu.
Bagaimana Anda menilai pencalonan para jenderal Polri dan TNI pada Pilkada 2018?
Fenomena ini bukan sesuatu yang baru meskipun pasca-reformasi dwifungsi ABRI dihapuskan. Tetap ada ruang bagi mereka untuk masuk ke ranah politik sepanjang mengundurkan diri. Misalnya, deretan kepala daerah dari purnawirawan TNI adalah Letjen (Purn) Sutiyoso di Jakarta, Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo di Jawa Tengah.
Pilkada serentak 2018 membuat calon jenderal lebih mudah terdeteksi oleh publik. Ini berkat teknologi, media sosial, dan pemberitaan media. Beda hal dari sebelum pilkada serentak, sehingga sorotan publik tak terlalu luas dan masif.
Pilkada sekarang, isu pencalonan diangkat bersamaan, publik langsung menyorot secara keseluruhan. Tidak banyak, memang ... mungkin hanya empat atau lima orang.
Jumlahnya kecil ... tetapi empat atau lima jenderal itu mengendalikan berapa pasukan? Itu yang harus jadi sorotan tajam. Beda misalnya bila perwira pensiunan yang dicalonkan.
Selain itu, konsep kaderisasi partai gimana? Bukankah saat membangun koalisi mestinya yang ditawarkan kader organik partai? Pencalonan ini menurut aturan harus secara terbuka dan demokratis. Nah, orang demokratis itu membuka ruang diaspora politik. Orang-orang yang memiliki kapasitas, kompetensi, serta diberi ruang untuk akses kepemimpinan menjadi kepala daerah oleh partai politik secara terbuka.
Mekanisme demokratis yang saya pahami, partai harus melakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan struktur internal partai. Tapi pencalonan jenderal pada Pilkada 2018 ini kelihatan sekali menggunakan mekanisme top-down. Pengambilan keputusan di partai biasanya hanya melibatkan elite.
Celah dalam UU Pilkada dipakai oleh parpol maupun perwira aktif untuk saling "berkomunikasi" demi pencalonan. Tanggapan Anda?
Mereka memaknai netralitas secara sempit. Bahwa yang dimaksud netralitas ketika sudah ditetapkan sebagai calon. Netralitas itu secara sempit dimaknai tidak lagi berstatus TNI dan Polri ketika mendaftar. Proses komunikasi politik dengan partai tidak dianggap sebagai konsep netralitas, padahal UU TNI dan Polri menyatakan dengan tegas dua institusi itu wajib netral.
Makna netralitas itu dengan tidak berpihak, tidak ikut, tidak bantu aktivitas politik apa pun. UU TNI dan Polri sudah tegas bahwa personel aktif harus netral. Jangan dibuat rancu. Maka ke depan UU Pilkada harus menegaskan netralitas TNI dan Polri sebagaimana diatur dalam UU TNI dan Polri dengan memperkuat pengaturan mundur itu idealnya satu tahun sebelum pencalonan sehingga tidak membawa institusi mereka.
Etika politik ini sering dilanggar, seharusnya bagaimana?
Sebagai penggiat pemilu, saya melihat polisi maupun tentara sepanjang masih perwira aktif tidak boleh cawe-cawe politik praktis, meski UU Pilkada mewajibkan mundur ketika ditetapkan sebagai pasangan calon.
Partai yang mengusung perwira TNI dan Polri harus menjelaskan kepada publik terkait keputusan penunjukan para prajurit aktif. Kenapa kita menuntut mereka netral? Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Juga menghindari penggunaan fasilitas jabatan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran, menghindari intimidasi karena memiliki kekuatan dan otoritas.
TNI dan Polri, selama perwira aktif, jangan ditarik ke ranah politik. Dua institusi itu tidak permisif dalam menjaga paradigma dan citra dalam politik praktis.
Ini mungkin alasan mengada-ada, yang berkata bahwa calon dari TNI/Polri bisa menguatkan "stabilitas" perpolitikan Indonesia ...
Saya agak kurang menangkap alasan itu. Apa urusannya? Kepala daerah memimpin tata kelola pemerintahan, lalu melakukan pekerjaan pelayanan publik.
Saya menilai ketidakstabilan politik bergantung penuh dengan komunikasi politik yang dibangun antara aktor-aktor politik daerah. Tentara kan jago pertahanan, sedangkan polisi di medan hukum. Sementara stabilitas politik dibangun antara aktor-aktor politik. Tapi kenapa solusinya ke [calon dari perwira] TNI dan Polri? Ini yang bikin saya gagal paham.
Ketidaksatabilan politik sebenarnya diselesaikan lewat kompromi politik, bukan pendekatan keamanan, apalagi pendekatan hukum. Kalau polisi jago dalam hukum dan tentara dalam pertahanan, lantas relevansinya apa?
Kaderisasi partai macet, ya?
Saya melihat konsep rekrutmen terbuka itu bagus untuk pilkada karena membuka profesional masuk. Tapi jangan lupa konsep demokratisnya, yang membuka ruang figur terbaik tapi tidak mengabaikan parpol sebagai institusi atau produsen kaderisasi politik.
Pertanyaan mendasar ketika posisi itu diberikan kepada pensiunan jenderal yang notabene bukan kader parpol. Apakah dia sudah mengikuti kaderisasi di internal partai sehingga kader itu bisa dikesampingkan dan memberikan ruang itu kepada pihak dari luar partai? Wajar kalau masyarakat menghubungkan dengan fungsi kaderisasi partai.
Kalau misalnya calon itu mumpuni dan di atas kader partai, memiliki kompetensi lebih baik, dipilih dalam demokrasi internal partai—itu tidak masalah. Karena konsep terbuka itu membuka ruang konsep demokratis.
Banyak juga orang berprestasi dan punya kompetensi bagus dalam menata dan mengelola daerahnya. Misalnya Nurdin Abdullah (Kabupaten Bantaeng), Tri Rismaharini (Kota Surabaya). Mereka bukan orang partai. Tapi mekanisme pemilihannya demokratis. Ini yang kita baca dalam pemilihan kepala daerah, seolah-olah semuanya itu bergantung pada ketua umum.
Diaspora, artinya mengambil dari orang nonpartai, menurut saya positif. Itu memicu kader partai untuk meningkatkan kapasitas sehingga ketika rekrutmen terbuka, mereka selalu siap bersaing dengan figur nonpartai yang punya kapasitas.
Mengapa justru elite partai cenderung dominan menetapkan calon, bahkan ada kesan penunjukan langsung dari ketua umum partai?
Ini terjadi salah satunya di hulu. Dalam partai, tidak eksplisit menyebut rekrutmen demokratis seperti apa sehingga masing-masing partai menerjemahkan sendiri-sendiri. Kenapa kemudian elite cenderung dominan? ini tidak terlepas dari kendali struktur itu sendiri, misalnya parpol sebagai institusi sangat bergantung pada ketua umum, termasuk pembiayaan pengelolaan partai. Ini yang menyebabkan referensi ketua umum cenderung diikuti.
Mekanisme pencalonan itu karena kompleksitas kepartaian kita, apalagi ada pergeseran partai mengusung calon berdasarkan elektabilitas tinggi. Saya kira mekanisme pencalonan itu didominasi oleh kemauan ketua umum karena partai kita dikelola dengan orientasi elite. Pendanaan bergantung pada elite.
Penulis: Reja Hidayat
Editor: Fahri Salam
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id