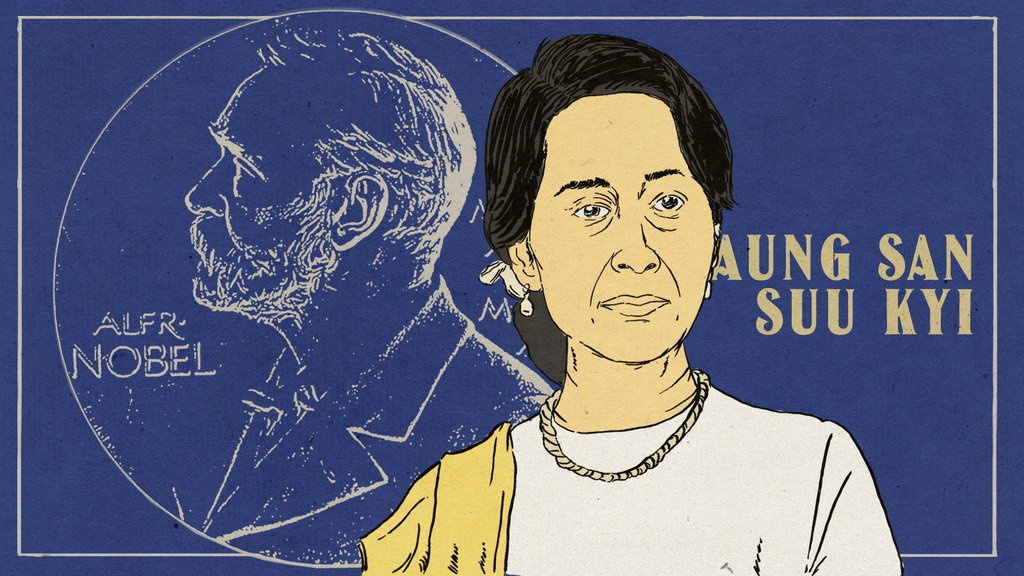tirto.id - Dua puluh delapan tahun setelah meninggalkan tanah airnya, Aung San Suu Kyi kembali ke Myanmar. Orang ini telah melanglangbuana ke berbagai negeri mengikuti ibunya yang menjadi duta besar. Setelah meraih gelar master dalam ilmu politik dari Universitas Oxford, ia memilih menjadi akademisi dan menikah dengan Michael Aris, sejarawan Inggris yang menekuni Tibet. Dari perkawinan itu, ia melahirkan dua putra.
Suu Kyi lahir pada 19 Juni 1945 di sebuah desa kecil bernama Hmway Saung. Bapaknya, Aung San, bukan orang sembarangan: founding father negara Myanmar modern yang berjuang memerdekakan bangsanya dari kolonialisme Inggris. Sementara Khin Kyi, ibunya, juga berasal dari keluarga terpandang. Pada saat belum banyak perempuan Myanmar mengenyam pendidikan tinggi, Khin Kyi sudah merasakan sekolah keperawatan. Suu Kyi adalah anak ketiga dari empat bersaudara.
Kemuraman datang melanda keluarga kecil itu dua tahun setelah Suu Kyi lahir. Sang bapak terlibat konflik politik dengan lawannya yang menyebabkan ia mati terbunuh. Selepas itu, Khin Kyi sendirian mengurus anak-anaknya.
Lahir dari keluarga terpandang memang mendatangkan keistimewaan tersendiri. Meski bapaknya tewas akibat pertarungan politik, ibunya mendapat jabatan yang bergengsi di negara Myanmar merdeka sebagai duta besar. Dari situlah kemudian Suu Kyi bisa bersekolah di luar negeri mengikuti ibunya sampai ia bisa lulus dari Oxford.
Tatkala pulang ke Myanmar pada 1988 itu, ia sejatinya datang untuk menjenguk sang ibu yang sedang sakit keras, bukan untuk tinggal lama di kampung halamannya. Apa boleh buat, takdir rupanya berkehendak lain. Krisis politik terjadi di Myanmar setelah Jenderal Ne Win, diktator yang berkuasa selama 26 tahun, mengundurkan diri. Tuntutan demokratisasi meruap di mana-mana, demonstrasi besar-besaran menentang kembalinya rezim militer melanda Myanmar.
Suu Kyi kemudian didaulat para demonstran sebagai simbol perlawanan nasional. Mereka membangkitkan lagi memori kepahlawanan sang ayahanda, Aung San, ketika berjuang melawan penjajahan Inggris.
Dengan berbagai pertimbangan, Suu Kyi akhirnya memilih untuk mengiyakan permintaan para demonstran. Ia meninggalkan kenyamanannya sebagai bangsawan Myanmar yang hidup di luar negeri demi memimpin gerakan perubahan.
Maka di tengah puncak demonstrasi pada 26 Agustus 1988, Suu Kyi tampil berpidato di hadapan 500.000 orang yang berkumpul di halaman Pagoda Shwedagon menyerukan demokratisasi. Di hari itu, ia benar-benar muncul sebagai ikon. Tapi betapapun derasnya tuntutan, militer masih terlalu kuat secara politik. Pada awal September Junta militer anyar penerus Ne Win berhasil mengambil alih kekuasaan.
Kepulangan Suu Kyi dan krisis politik itu adalah dua peristiwa yang kebetulan saja sebenarnya, tanpa ada kaitan politik apapun. Lewat “kecelakaan” politik, Suu Kyi muncul sebagai fenomena putri pendiri bangsa yang menjadi pemimpin di negaranya. Dalam konteks Asia Tenggara, kita juga mengenal Gloria Macapagal Aroyo (putri Diosdado Macapagal) di Filipina dan Megawati Sukarnoputri di Indonesia.
Akibat aktivitas politik yang membahayakan kedudukan junta militer, Suu Kyi mesti menanggung risiko paling berat. Satu tahun setelah kembali, Suu Kyi dikenakan tahanan rumah dalam waktu yang lama. Selama menjadi tahanan rumah, ia sebenarnya diizinkan pemerintah untuk bebas asalkan pergi meninggalkan tanah airnya dan tidak boleh kembali. Tapi ia memilih tetap tinggal, mengorbankan kebersamaan sebagai seorang ibu dengan suami dan dua putranya demi rakyat Myanmar.
“Sebagai seorang ibu, pengorbanan terbesar adalah melepaskan anak-anak saya, tapi saya selalu sadar dengan kenyataan bahwa orang lain telah berkorban lebih banyak dari saya,” kata Suu Kyi dalam The Voice of Hope: Conversations with Alan Clements (2008).
Pada 1990-an itu ia tak hanya populer di kalangan rakyat Myanmar. Lambat-laun, lantaran pemberitaan pers Barat soal heroisme Suu Kyi direproduksi terus menerus, ia menjelma jadi ikon kebebasan bagi orang-orang yang tertindas oleh militerisme dan rezim otoriter. Penghargaan Nobel Perdamaian yang ia dapat pada 14 Oktober 1991, tepat hari ini 29 tahun lalu, seperti meneguhkan ketokohannya.
Suu Kyi juga menjadi inspirasi bagi aktivis pro-demokrasi di Indonesia pada 1990-an. Situasi politik di Myanmar dan Indonesia saat itu hampir mirip: keduanya berada dalam cengkeraman diktator militer dan suara-suara oposisi direpresi.
Goenawan Mohamad, misalnya, merekam sosok itu dalam dalam “Catatan Pinggir” yang khusus didedikasikan untuk Suu Kyi dengan penuh simpati. Ada pula satu sajak yang ia persembahkan khusus buat Suu Kyi dengan judul persis nama lengkap tokoh oposisi Myanmar itu. Menggambarkan betapa besar hasrat akan kebebasan meski harus ditempuh dengan jalan sunyi, salah satu lariknya berbunyi:
Tapi segala heroisme Suu Kyi berubah menjadi kedegilan justru ketika apa yang paling dinantikannya tiba: kebebasan.
Pada 2010 ia dibebaskan dan segera menjadi tokoh Myanmar nomor satu. Junta militer, sementara itu, makin melemah dan terpaksa memberi beberapa konsesi bagi lawan-lawan politiknya. Salah satu konsesi yang diberikan adalah pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
Dua tahun setelah Suu Kyi bebas, partai yang dipimpinnya memenangi pemilihan umum. Tapi dia tidak bisa menjadi presiden lantaran konstitusi Myanmar tak memungkinkannya (suami dan anaknya adalah warga negara asing). Ia kemudian mendapat jabatan “hiburan” sebagai Konselor Negara.
Dalam suasana kebebasan itu, militer Myanmar yang masih memegang kekuasaan besar justru melancarkan persekusi dan pembantaian terhadap etnis minoritas Rohingnya. Sejak 2012 sampai hari ini, ribuan orang Rohingnya mati terbunuh dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi.
Reaksi Suu Kyi sebagai pejuang kemanusiaan dan pemimpin negara?
Ia tetap diam dan membiarkan pembantaian itu terjadi. Tak pernah satu kata kutukan pun terucap dari mulutnya. Bahkan ia banyak dikecam karena rasis dan punya kecenderungan sinis terhadap orang Islam.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada 2012, Suu Kyi kehilangan kesabaran ketika didesak oleh presenter yang memintanya mengutuk sentimen anti-Islam di Burma. Presenter tersebut adalah Mishal Husain, wartawati Inggris keturunan Pakistan yang beragama Islam.
“Tak ada yang bilang pada saya jika akan diwawancarai oleh seorang Muslim,” begitu keluhnya dalam komentar off-air setelah wawancara berlangsung. Tak pelak, protes pun makin menggila. Tuntutan agar panitia Nobel mencabut penghargaan untuk Suu Kyi juga bergema di mana-mana.
Bila kita menyimak pidato Suu Kyi dalam Kuliah Nobel tahun 2012, akan terasa percuma saja ia pernah mengucapkan kalimat ini:
“Di mana pun penderitaan diabaikan, akan ada benih-benih konflik, karena penderitaan merendah-hinakan dan menyakitkan dan menciptakan amarah.”
Ya, hari ini ia telah mengabaikan penderitaan bangsa Rohingnya. Itulah paradoks terbesar dalam hidup Suu Kyi. Tuntutan pencabutan Nobel, karena itu, bukan hal yang berlebihan.
==========
Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 5 September 2017 dengan judul "Paradoks Terbesar Aung San Suu Kyi". Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Zen RS & Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id