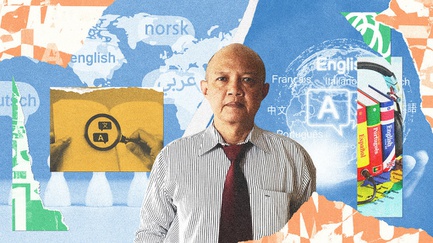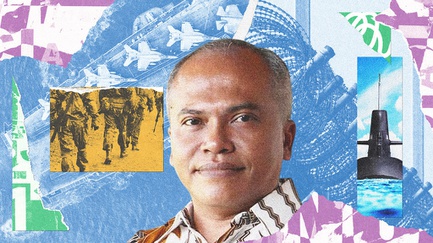tirto.id - Pemerintah, melalui Kementerian Kebudayaan, saat ini tengah menggagas penyusunan ulang Buku Sejarah Nasional Indonesia yang direncanakan terbit antara tahun 2025/2026. Proyek ini, yang berjalan dalam tempo relatif cepat, bertujuan untuk menyusun ulang narasi sejarah nasional sebagai rujukan utama. Meskipun tergolong ambisius, inisiatif ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, enam jilid Sejarah Nasional Indonesia telah disusun pada masa Orde Baru (pertama kali terbit pada 1975) dan menjadi fondasi narasi sejarah resmi negara selama beberapa dekade.
Inisiatif ini disambut sebagai langkah positif. Selama ini, narasi sejarah nasional dinilai terlalu sentralistik—berporos pada negara, elite kekuasaan, dan berorientasi Jawa-sentris. Dominasi sejarawan yang dekat dengan rezim masa lalu, seperti Djoened Marwati Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, turut membentuk historiografi yang kurang memberi ruang bagi suara-suara pinggiran: masyarakat adat, perempuan, buruh, petani, dan kelompok minoritas lainnya.
Karena itu, penyusunan ulang ini membuka peluang penting: sejarah nasional dapat ditulis dengan lebih demokratis, representatif, dan inklusif. Kalangan akademisi dari berbagai daerah dan latar belakang kini memiliki ruang untuk terlibat aktif, membawa pendekatan yang lebih reflektif dan kritis. Inilah saatnya sejarah tidak lagi ditulis dari menara gading, tetapi dari beragam tapak jejak bangsa.
Namun, kita juga perlu belajar dari pengalaman sebelumnya. Pada awal 2010-an, proyek Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) sempat menjadi angin segar dalam penulisan sejarah nasional. IDAS melibatkan banyak sejarawan dari berbagai institusi dan mengusung pendekatan multidisipliner. Meski demikian, IDAS belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang narasi negara. Ruang alternatif yang disediakan masih dibatasi oleh bingkai historiografi yang dominan.
Kritik terhadap historiografi nasional bukanlah hal baru. Pada 1975, Soedjatmoko, seorang intelektual Indonesia terkemuka, dalam pidatonya yang berjudul Historiografi Indonesia: Perspektif Indonesiasentris mengingatkan bahwa sejarah nasional pasca kemerdekaan masih banyak mewarisi pola pikir kolonial: euro-sentris, elite-sentris, dan Jakarta-sentris. Ia menyatakan, “Menulis sejarah nasional bukan sekadar mengisi kekosongan sejarah kolonial dengan nama-nama baru, tapi soal menyusun kembali orientasi berpikir sejarah itu sendiri.”
Dalam karya-karya seperti Historiografi Indonesia (1965) dan Dimensi Manusia dalam Pembangunan (1983), Soedjatmoko menekankan pentingnya keterkaitan antara sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, sejarah tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab etis dan harus mencerminkan kesadaran terhadap keragaman identitas, pengalaman, dan budaya yang membentuk masyarakat Indonesia. Ia menulis (1965), “Kita perlu sejarah yang memungkinkan manusia Indonesia memahami dirinya dalam konteks sosial-budaya yang konkret”.
Sayangnya, semangat tersebut belum sepenuhnya tecermin dalam rencana penyusunan ulang buku sejarah nasional yang baru-baru ini digaungkan. Masih tampak kesan bahwa proses ini dijalankan dari atas, dikendalikan oleh institusi pusat, dengan pelibatan publik yang cenderung formalistik. Siapa yang menyusun? Metode apa yang digunakan? Apakah suara korban, penyintas, komunitas adat, dan masyarakat daerah benar-benar dilibatkan? Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini belum dapat dijelaskan secara terbuka.
Penulisan sejarah yang adil dan inklusif tidak bisa hanya dipercayakan kepada kalangan akademisi atau sejarawan yang dekat dengan pusat kekuasaan. Proses ini perlu melibatkan berbagai lapisan masyarakat—mulai dari komunitas lokal, guru sejarah di sekolah, pelaku seni dan budaya, hingga masyarakat adat yang mewarisi dan menjaga ingatan kolektif. Mereka bukan sekadar objek kajian, tetapi subjek yang memiliki narasi dan pengetahuan historis yang sah. Tanpa keterlibatan mereka, penulisan sejarah hanya akan menjadi dokumen elitis yang jauh dari realitas sosial masyarakat.
Dalam kerangka ini, sejarah seharusnya dipahami bukan semata sebagai kumpulan fakta, melainkan sebagai refleksi kesadaran bersama yang lahir dari pengalaman kultural masyarakat. Sejarah yang demikian harus mampu merepresentasikan keberagaman identitas dan konteks sosial yang membentuk perjalanan bangsa, agar lebih bermakna dan membumi.
Sejarah nasional yang ideal bagi Indonesia adalah sejarah yang membuka ruang bagi pengalaman sosial dari berbagai penjuru Nusantara. Narasi sejarah tidak boleh terbatas pada peristiwa politik para elite, tetapi juga harus mencakup kisah petani di lereng Merapi, perempuan di pesisir Sumba, nelayan di Kepulauan Aru, serta komunitas Tionghoa, Madura, Dayak, Papua, dan lain sebagainya yang selama ini terpinggirkan.
Dalam konteks inilah, pendekatan historiografi Indonesiasentris bukan hanya proyek akademik, tetapi juga upaya kultural dan etis. Ia menegaskan bahwa sejarah Indonesia tidak tunggal, tidak linier, dan tidak hanya dimiliki oleh satu wilayah atau kelompok. Sejarah Indonesia bersifat kompleks, berlapis, dan dipenuhi dinamika lintas identitas.
Penting disadari bahwa pendekatan Indonesiasentris seharusnya bukan bentuk nasionalisme sempit atau eksklusif. Sebaliknya, ia menawarkan cara pandang yang terbuka, reflektif, dan kritis—mengajak masyarakat melihat sejarah bangsa sebagai hasil interaksi berbagai aktor dari beragam latar belakang: lokal maupun kolonial, pusat maupun daerah, elite maupun rakyat biasa. Dalam kerangka ini, sejarah berfungsi sebagai cermin untuk menumbuhkan kesadaran kolektif atas nilai-nilai yang membentuk jati diri bangsa.
Pendekatan ini juga menuntut tanggung jawab moral dalam penulisan sejarah. Artinya, sejarah harus ditulis dengan mempertimbangkan luka masa lalu, ketimpangan yang pernah terjadi, serta cita-cita akan masa depan yang lebih adil dan inklusif. Sejarah semacam ini tidak hanya mencerahkan, tetapi juga mendewasakan masyarakat—membentuk individu yang peka terhadap keragaman dan siap mengambil tanggung jawab sosial sebagai warga negara.
Oleh karena itu, proses penulisan ulang sejarah nasional perlu dikawal dengan sikap kritis agar tidak terjebak dalam pendekatan administratif semata. Proyek ini harus menjadi momentum untuk meninjau ulang narasi-narasi besar yang selama ini dominan, serta membuka ruang bagi pengalaman-pengalaman yang disisihkan. Untuk itu, dibutuhkan keberanian berpikir lintas disiplin dan kemauan untuk melibatkan berbagai suara masyarakat secara otentik.
Dengan pendekatan semacam ini, penulisan ulang sejarah nasional tidak seharusnya dipandang sebagai proyek pemerintah belaka, melainkan sebagai gerakan kebudayaan yang lahir dari kesadaran kolektif. Gerakan ini menuntut keberanian untuk merefleksikan masa lalu dengan jujur, mengoreksi ketimpangan narasi, dan berkomitmen pada pelurusan ingatan bersama demi terciptanya keadilan historis. Sejarah yang ditulis dengan semangat ini tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga memberi arah bagi perjalanan bangsa ke depan.
Soedjatmoko (1983) mengingatkan, “Tantangan terbesar pembangunan adalah membangun manusia yang sadar akan akar sejarahnya, nilai-nilainya, dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.” Maka, jika pemerintah sungguh serius, buku sejarah nasional yang baru tidak boleh sekadar menjadi cetakan teks semata, tetapi harus menjadi ruang dialog lintas generasi—antara masa lalu dan masa kini, antara pusat dan pinggiran, antara suara yang dominan dan yang selama ini dibungkam.
Sebab, sejarah yang berkeadilan bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang siapa yang akhirnya didengar.
Penulis adalah pengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya, saat ini sedang menempuh studi doktoral di Universitas Padjadjaran. Ia aktif menulis tentang sejarah intelektual dan lingkungan di era kolonial, pernah menjadi peneliti tamu di Universiteit Leiden, Belanda.
Editor: Zulkifli Songyanan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id