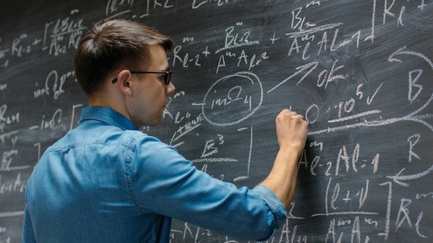tirto.id - Belakangan, kata jancuk tak hanya dipakai oleh penutur bahasa Jawa. Kata ini menjadi cukup populer digunakan di tempat lain, termasuk Jakarta, daerah yang sebelumnya kerap mengidentikkan bahasa Jawa sebagai bahasa kampungan nan lucu.
Akan tetapi, alih-alih mengucapkannya sebagai /dʒantʃoʔ/ (mirip djancuk dengan lafal /o/ serupa pada kata biro), orang-orang Jakarta mengucapkannya dengan dialek yang terdengar aneh di telinga penutur bahasa Jawa. Oleh orang Jakarta, kata jancuk kerap diucapkan dengan ucapan /dʒantʃʊk/ (dengan /j/ serupa pada kata jantung dan /u/ serupa pada kata turun) atau /dʒantʃɔk/ (dengan /u/ yang dibaca /ɔ/ serupa pada kata bencong).
Kendati perbedaan pelafalan sejatinya bukan masalah berarti, penutur bahasa Jawa mungkin akan melihatnya sebagai suatu hal yang lucu. Bagi penutur bahasa Jawa, beda penekanan dan cara pelafalan adalah hal yang mudah ditengarai. Hal ini dikarenakan bahasa Jawa memiliki taraf distingtif yang, setidaknya, lebih tinggi dari bahasa Indonesia.
Distingtif dalam ilmu bahasa adalah signifikansi elemen bunyi sebagai pembentuk makna. Mudahnya, suatu kata dapat bermakna berbeda hanya dengan penekanan yang berlainan letaknya atau seberapa lama huruf vokal terdengar di telinga.
Contoh betapa distingtifnya bahasa Jawa dapat kita lihat dalam kata wedi. Dalam bahasa Jawa, kata wedi memiliki arti takut. Namun jika kata ini diberi penekanan dan menjadi wedhi, maknanya bukan takhut, melainkan pasir.
Dengan sifat ini, penutur bahasa Jawa memang jeli dengan penekanan. Bagi mereka, penekanan bunyi adalah salah satu elemen pembentuk makna. Inilah alasan penutur bahasa Jawa memiliki karakteristik medok yang sulit dihilangkan.
Hal ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Taraf distingtif bahasa Indonesia tak setinggi bahasa Jawa. Kata putri, misalnya, akan tetap bermakna putri kendati band Jamrud melafalkannya sebagai potre dalam lagu "Putri" yang fenomenal.
Pertanyaannya, dari mana hal ini muncul? Mengapa orang Jakarta tidak luwes ketika mengumpat jancuk? Jawabannya adalah dialek.
Dialek: Bahasa Dipengaruhi oleh Identitas Penuturnya
Jika kita mendefinisikan bahasa, banyak ahli akan mengartikan kata bahasa sebagai lambang bunyi ujaran yang berfungsi menjadi sarana komunikasi. Kita bisa melihat definisi serupa itu dikemukakan linguis macam Gorys Keraf (dalam Tata Bahasa Indonesia, 1984) atau Abdul Chaer (dalam Linguistik Umum, 1994).
Mudahnya, definisi tersebut menjelaskan bahwa bahasa adalah rangkaian huruf pembentuk kata kursi, yang kita gunakan sebagai kode untuk merujuk benda yang biasa kita duduki. Serupa kata kursi, semua kata yang bisa kita ucapkan sebenarnya adalah kode untuk makna yang diwakilinya.
Namun, sebagai alat komunikasi, kita tak akan sekadar menemukan seperangkat tanda dalam bahasa. Ketika ditelisik lebih jauh, kita juga akan melihat cerminan budaya penuturnya. Atau dengan kata lain, budaya merupakan salah satu faktor pembentuk bahasa.
Kita bisa dengan mudah membayangkan betapa budaya memengaruhi pola tutur di suatu wilayah dengan melihat cara bahasa Indonesia dituturkan oleh 281 juta orang dari Aceh hingga Papua.
Ketika harus mengucap satu kalimat bahasa Indonesia yang sepenuhnya serupa, seorang Sunda akan bicara dengan gaya dan cara berbeda dari seorang Makassar, misalnya. Perbedaan ini tetap akan terjadi kendati bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi salah satu pokok pendidikan nasional.
Akan tetapi, perbedaan tersebut bukan dikarenakan pendidikan nasional yang gagal, melainkan lantaran bahasa bukanlah kemampuan bawaan manusia. Tak seperti aktivitas bernapas, kemahiran berbahasa tidak hadir seketika saat dilahirkan; ia diasah seiring waktu lewat pengalaman.
Seturut Richard A. Hudson dalam Sociolinguistics (1980), gaya tutur seorang individu "agaknya dibentuk lebih banyak oleh pengalaman (sebagai pendengar) daripada oleh bentukan genetiknya, dan sebenarnya pengalaman yang dimaksud itu terdiri dari ujaran yang dihasilkan oleh para penutur lain yang masing-masing bersifat unik."
Singkatnya, Hudson ingin bilang bahwa cara kita berbahasa adalah buah pengalaman kita mendengarkan orang lain bicara. Namun, gaya bicara orang lain yang memengaruhi kita itu juga tercipta dari pengalaman mereka mendengar cara orang selain mereka dalam menuturkan bahasa.
Melalui kerangka berpikir Hudson tersebut, menjadi masuk akal jika kita mendapati satu kalimat bahasa Indonesia akan diucapkan secara berbeda bergantung pada setiap penuturnya, baik asal daerah maupun budaya tempat mereka tumbuh.
Dalam bukunya, Hudson menjelaskan bahwa perbedaan penuturan suatu bahasa erat kaitannya dengan kecenderungan suatu masyarakat membentuk ciri khas pola kebahasaannya sendiri. Dan kekhasan ini bernama dialek.
Dialek dapat dimaknai sebagai pola kebiasaan berbahasa suatu masyarakat saat bertutur. Kebiasaan yang dipengaruhi oleh letak geografis dan karakteristik budaya ini kemudian membuat suatu wilayah memiliki dialek yang berbeda dari daerah lain, meskipun menggunakan satu bahasa yang sama.
Salah satu contoh perbedaan dialek paling kentara adalah yang terjadi pada bahasa Jawa. Bahasa ini memiliki berbagai macam dialek, mulai dari dialek Ngapak di Banyumas dan sekitarnya hingga dialek Wetanan di Surabaya dan sekitarnya.
Total, laman web resmi Peta Bahasa Kemdikbud mencatat setidaknya 32 dialek bahasa Jawa yang tersebar di Indonesia. Jumlah ini belum termasuk dialek bahasa Jawa di luar Nusantara, seperti di Suriname. Masing-masing di antaranya berciri khas masing-masing, mulai dari pemilihan kata, ejaan, cara pengucapan, hingga tata bahasanya.
Orang Banyumas, misalnya, akan menggunakan kata rika 'kamu' sebagai pronomina orang kedua. Sementara itu, orang Surabaya mamakai kata koen untuk merujuk makna yang sama.
Melalui kebiasaan tersebut (misalnya alasan menggunakan koen dan bukan rika) kita dapat menyingkap kaitan antara budaya dan bahasa. Sugeng Sriyanto dan Akhmad Fauzie dalam artikel jurnalnya berjudul "Penggunaan Kata 'Jancuk' sebagai Ekspresi Budaya dalam Perilaku Komunikasi Arek di Kampung Kota Surabaya" (2017) menemukan relasi itu dalam kata jancuk.
Dalam bahasa Suroboyoan atau bahasa Jawa dialek Arekan, terdapat satu kata yang begitu mencirikan karakteristik budaya penuturnya, yakni jancuk. Bermula sebagai makian (diyakini berasal dari kata di-ancok yang bermakna disetubuhi), kata ini mengalami ameliorasi atau perubahan makna jadi lebih positif daripada makna aslinya.
Kini, kata jancuk tak sekadar dimaknai makian oleh penutur dialek Arekan. Justru, kata ini menyiratkan rasa persaudaraan. "Kata jancuk atau penggalan katanya cuk adalah bentuk kata yang digunakan untuk menunjukan rasa keakraban, khususnya yang berdiam di kawasan Surabaya dan Malang," tulis Sriyanto dan Fauzie.
Dalam jurnalnya, Sriyanto dan Fauzie juga menemukan bahwa penggunaan kata jancuk oleh penutur dialek Arekan di Surabaya erat kaitannya dengan karakteristik budayanya. Kata itu merupakan konsep simbolik dari karakter orang Surabaya yang tertuang dalam interaksi sosial sehari-hari.
"Konsep simbolik tersebut dipahami sebagai karakter arek Suroboyo, yaitu egaliter yang dipahami dengan arti kerakyatan, demokratis yang diartikan dengan keterbukaan, dan solidaritas," terang mereka dalam tulisannya.
Sederhananya, kata jancuk kini muncul dalam dialek Arekan sebagai penanda solidaritas yang egaliter dan demokratis.
Jika ditulis dengan transkripsi fonetik, pola kebahasaan yang tercipta dalam dialek Arekan membuat penuturnya mengucap kata jancuk dengan /dʒant͡ʃoʔ/. Cara pengucapan juga bukan tanpa sebab; ada karakteristik penutur dialek Arekan yang tecermin dari cara mengucap kata jancuk.
Pengucapan jancuk yang umum dilakukan penutur dialek Arekan dapat dilihat dari tabel transkripsi fonetik berikut.
| Bentuk | Jenis | Cara Baca |
| d͡ʒ | Konsonan afrikat | Kendati ditulis /j/, namun pengucapannya serupa /dj/. Adanya afrikat menunjukkan adanya penekanan pada huruf /j/. |
| /a/ | Vokal terbuka | dibaca sama seperti /a/ dalam kata "anak". |
| /n/ | Nasal alveolar | dibaca sama seperti /n/ dalam kata “aman”. |
| /t͡ʃ/ | Afrikat pasca-alveolar tak bersuara | Pengucapannya serupa /c/ dalam kata “decak”. |
| /o/ | Vokal bulat terbuka | Diucap /o/, seperti /o/ pada kata “kroco”. |
| /ʔ/ | Hentian glotal (glottal stop) | Menutup aliran udara ketika mengucap huruf “k” secara tiba-tiba, sehingga memunculkan penekanan lebih. |
Dengan pengucapan seperti pada tabel di atas, kata jancuk yang diucap dengan dialek Arekan akan memunculkan bunyi yang dimulai dengan nada tinggi, lalu turun dengan hentakan keras di akhir. Serupa budaya penuturnya, pola pengucapan itu akan menimbulkan efek yang lebih ekspresif, keras, emosional, dan meledak-ledak, akibat dari penekanan di awal dan akhir kata.

Berbeda dengan penutur dialek Arekan, orang Jakarta yang umumnya penutur dialek Melayu-Betawi mengucapkan kata jancuk dengan fonetik berbeda, yakni /d͡ʒanˈtʃuk/. Jika dijabarkan, transkripsi fonetiknya akan terbaca sebagai berikut:
| Bentuk | Perbedaan dengan Dialek Arekan |
| /d͡ʒ/ | sama seperti Arekan. |
| /a/ | sedikit lebih pendek dari dialek Arekan dan tidak terlalu terbuka. |
| /n/ | nasal biasa. |
| /tʃ/ | diucapkan sebagai /tʃ/, namun tanpa tekanan seperti dialek Arekan. |
| /u/ | diartikulasikan lebih tertutup dari dialek Arekan. Seperti /u/ dalam kata “lucu”. |
| /k/ | Akhiran tanpa glottal stop /ʔ/ sehingga lebih ringan, tidak terkesan meledak. |
Ditengok dari transkripsi fonetiknya, kita dapat melihat bahwa cara ucap kata jancuk oleh penutur dialek Arekan dan penutur dialek lain macam Melayu-Betawi jelas berbeda. Pada penutur dialek Melayu-Betawi, kata jancuk tak terdengar meletup-letup, tidak disertai hentakan seperti yang diucap penutur dialek Arekan—selain, tentu saja, penggunaan u alih-alih o.
Budaya penutur dialek Arekan memengaruhi cara mereka mengucap jancuk. Sama halnya dengan itu, cara penutur dialek Melayu-Betawi mengucap kata tersebut sebenarnya dibentuk dari kebiasaan perilaku.
Ketika Orang Jakarta Mengucap Jancuk dengan Lucu
Barangkali, mau berapapun didengar dan dibiasakan, penutur dialek Arekan akan tetap merasa janggal ketika mendengar orang Jakarta mengucap jancuk. Akan tetapi, perbedaan pengucapan jancuk yang dilakukan orang Jakarta mungkin punya akar yang lebih jauh dari sekadar bahwa mereka tak pernah luwes menyebutnya.
Sebagai kota metropolitan, orang Jakarta terbiasa dengan laju kehidupan yang serba cepat, serba dinamis, serba efektif. Mereka terbiasa dikejar waktu. Kebiasaan itu kemudian tercermin dari cara orang Jakarta menuturkan bahasa yang mencirikan mereka.
Jika penutur dialek Arekan terbiasa dengan pengucapan satu kata yang mengandung lebih dari satu penekanan dan jeda, penutur dialek Melayu-Betawi cenderung mencari intonasi dan nada yang memungkinkan mereka menyampaikan informasi dengan cara yang paling cepat dan efektif.
Kebutuhan akan pola tutur yang dinamis itu membuat mereka terbiasa mengucap kata dengan cepat tanpa penekanan dan jeda sana-sini.
Bahkan dalam umpatan yang berfungsi sebagai penekanan situasi, orang Jakarta mengembangkan intonasi yang tetap terdengar mengumpat tetapi tanpa penekanan berlebih. Kita akan melihat hal ini, misalnya, setelah membandingkan antara cara orang Jakarta mengumpat anjing dan cara penutur dialek Arekan memaki dengan kata asu (hampir pasti akan diucap uas-su).
Alam bawah sadar orang Jakarta memilih tidak melakukan penekanan pada pola ucap karena, barangkali, itu tidak efisien bagi mereka. Terlalu banyak jeda dapat dimaknai juga sebagai terlalu banyak waktu terbuang.
Dengan demikian, pada akhirnya, memang selalu akan ada yang wagu dari cara orang Jakarta mengucap jancuk. Namun, itu tak berakar dari ketidakmampuan alat ucap, melainkan kebudayaan yang turut memengaruhi cara mereka menggunakannya.
Lagi pula, penutur dialek Arekan agaknya perlu berbangga. Fenomena ini justru mempertontonkan betapa dialek Arekan tak hanya bertahan di tengah dominasi dialek Jakarta dalam media. Lebih dari itu, ia bahkan berhasil melawannya. Setelah bertahun-tahun berada di posisi terpengaruh, kini ia berhasil memengaruhi.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id