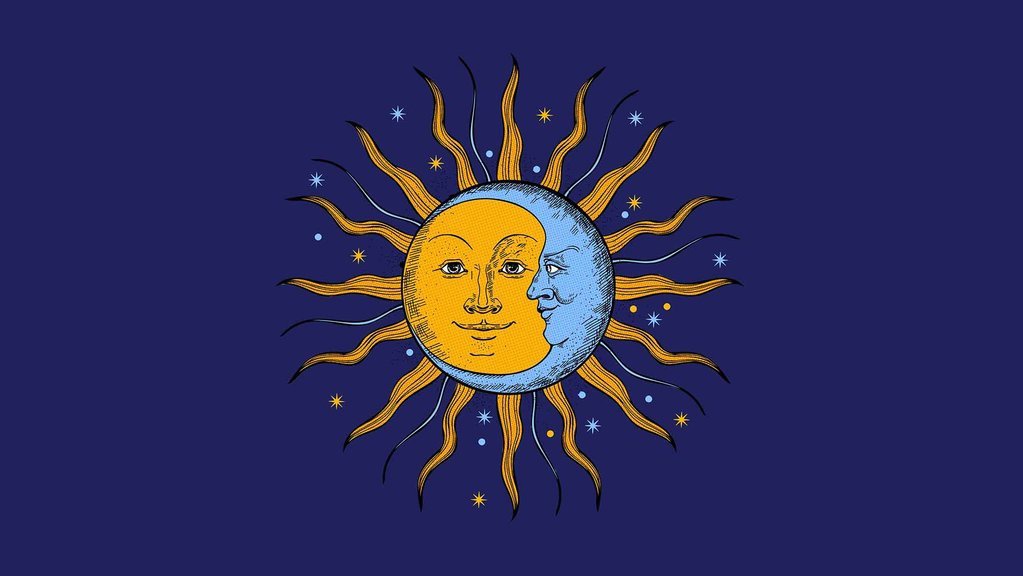tirto.id - Bagi Sumarsono, gerhana bukan sekadar fenomena alam. Penarik becak asal Demak yang sehari-hari mengais nasib di Semarang ini percaya, gerhana terjadi lantaran ulah Batara Kala, dan menjadi ancaman bagi semesta termasuk umat manusia. Bumi gelap gulita karena raksasa menakutkan itu menelan matahari atau bulan. Begitu keyakinannya.
"Saya akan pulang menyelamatkan tanaman, sebab bila tidak, berarti sumber sandang, pangan bagi istri dan anak akan habis," ucap Sumarsono dalam Kedaulatan Rakyat edisi 3 Juni 1983 yang kemudian dikutip oleh berbagai media nasional.
Apa yang ditakutkan Sumarsono datang beberapa hari berselang. Sesuatu terjadi pada 11 Juni 1983, tepat hari 37 tahun lalu. Menjelang tengah hari, tepatnya pukul 11.29 WIB, mentari yang semula bersinar terik tiba-tiba lenyap. Seisi langit pun gelap.
Sumarsono panik. Namun, ia harus turut membantu warga sekampungnya mengusir Batara Kala agar mentari bersinar lagi. Caranya, mereka beramai-ramai membuat keributan dengan memukul lesung, kentongan, peralatan dapur, dan sejenisnya, supaya raksasa jahat itu memuntahkan matahari yang telah ditelannya.
Sekitar 5 menit kemudian, sang surya perlahan-lahan muncul. Langit pun kembali terang benderang. Sumarsono dan orang-orang desa lainnya merasa lega, berucap syukur karena upaya Batara Kala kali ini bisa digagalkan.
Gara-gara Batara Kala
Gerhana matahari total itu memang memantik kepanikan. Terlebih pemerintah Orde Baru saat itu bereaksi serius dalam menyongsong terjadinya fenomena alam ini.
Pemerintah bahkan membentuk Panitia Nasional Gerhana Matahari sejak jauh-jauh jari (Jurnal Baca, Volume 8-9, 1982: 59). Panitia ini terdiri dari berbagai lembaga ilmiah maupun instansi resmi, termasuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Departemen Kesehatan, Departemen Penerangan, dan seterusnya.
Seperti dikutip dari buku Indonesia dan Masalah-masalah Pembangunan (1986, hlm. 259) karya Budhy Munawar Rachman dan F.X. Baskara, melalui siaran radio, televisi, surat kabar, dan lainnya, pemerintah secara masif berulang kali memperingatkan warga untuk tidak keluar rumah. Jika nekat melihat gerhana, mata bisa buta.
Apapun yang dikatakan pemerintahan Soeharto sangat berpengaruh dan ditaati oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Suasana mencekam pun berlangsung selama langit mendadak gelap pada siang hari.
Ketakutan warga kian besar karena mitos-mitos terkait gerhana masih sangat diyakini masyarakat, baik di Jawa maupun di daerah-daerah lainnya di Indonesia dengan kisah atau keyakinan lokal yang tidak selalu sama.
Bagi sebagian orang Jawa, termasuk Sumarsono, Batara Kala adalah biang keladi terjadinya gerhana matahari maupun bulan. Batara Kala disebut juga dengan nama Kala Rahu (Kala Rau). Menurut Suwandono dan kawan-kawan dalam Ensiklopedi Wayang Purwa (1991: 265), sosok ini dipercaya sebagai putra dewa tetapi berwujud raksasa akibat terkena kutukan.
Dalam mitologi Jawa dikisahkan, Batara Kala menaruh dendam terhadap Batara Surya (Dewa Matahari) dan Batara Soma (Dewa Bulan), terkadang muncul pula nama Dewi Ratih atau Dewi Bulan.
Batara Kala yang menyaru menjadi dewa, ikut meminum tirta amerta alias air abadi bersama para dewa lainnya. Baru minum seteguk, penyamarannya diketahui oleh Surya, Soma dan Dewi Ratih, yang segera melaporkannya kepada Dewa Wisnu, salah satu dewa tertinggi.
Akibatnya, Kala murka dan terus berupaya mengejar Surya, Soma, atau Ratih. Menurut Mudjadi dalam Adat-Istiadat Daerah Jawa Timur (1997: 69), setiap kali tertangkap, Kala akan memakan mereka sehingga langit menjadi gelap gulita.
Batara Kala diwujudkan dalam bentuk raksasa yang hanya memiliki kepala hingga leher. Itu karena hukuman Dewa Wisnu yang menebas leher Kala dengan senjata cakranya. Maka, gerhana jarang berlangsung lama. Matahari atau bulan yang ditelan Kala akan keluar lagi lewat leher bagian bawah yang sudah terpotong.
Dikisahkan pula dalam mitologi Jawa, bagian setengah leher ke bawah Batara Kala berubah menjadi lesung (tempat menumbuk padi). Maka, ketika terjadi gerhana, orang-orang beramai-ramai memukuli lesung, juga membuat kebisingan dengan berbagai cara, agar Kala memuntahkan matahari atau bulan yang dimakannya.
Mitos Jawa Seputar Gerhana
Masih berkaitan dengan Batara Kala atau Kala Rahu, muncul berbagai mitos dalam kepercayaan sebagian orang Jawa seputar gerhana matahari atau bulan. Salah satunya, seperti yang diungkapkan oleh Sumarsono, yakni bahwa ia harus segera pulang untuk menyelamatkan sumber penghidupannya di desa.
Sawah atau lahan pertanian, dalam kepercayaan orang Jawa zaman dulu, harus disirami air selama gerhana terjadi agar tidak rusak dan gagal panen. Jika punya kebun yang menghasilkan bahan pangan, seperti pohon-pohon buah, harus dipukul-pukul batangnya supaya selamat dari terjangan murka Batara Kala.
Hewan-hewan ternak juga harus dijaga jangan sampai tertidur selama gerhana berlangsung dengan cara dicambuk-cambuk pelan dengan dahan pohon. Jika tidak, hewan-hewan yang merupakan aset kehidupan itu terancam mati setelah gerhana usai.
Selain itu, selama langit gelap karena gerhana, setiap orang wajib terus terjaga, tidak boleh tidur. Ini mengacu kepada ungkapan Jawa yakni sopo sing leno bakale keno (siapapun yang terlena pasti terkena). Artinya, setiap orang harus waspada jika tidak ingin terpapar dampak gerhana.
Bagi perempuan yang sedang mengandung, sebagian orang Jawa meyakini gerhana dapat berakibat fatal. Janin dikhawatirkan lahir tidak sempurna, seperti kisah yang diungkap Dr. Hendrawan Nadesul (2009) dalam buku Dari Balik Kamar Praktik Dokter 2 (hlm. 62-63). Sang calon ibu bahkan bisa saja meninggal dunia apabila tidak diselamatkan dengan melakukan ritual.
Maka, menurut kepercayaan, wanita hamil harus diungsikan ke tempat yang dianggap aman, misalnya masuk ke kolong tempat tidur. Sementara itu, dilakukan ritual sego rogoh atau tradisi liwetan, yaitu memasak nasi beserta lauknya kemudian disantap beramai-ramai. Tradisi ini masih kerap diterapkan hingga kini di beberapa desa di Jawa.

Leluhur Justru Tak Gentar
Leluhur orang Jawa sendiri sejatinya tidak terlalu mencemaskan gerhana. Beberapa kali peristiwa penting dalam sejarah justru kebetulan terjadi bersamaan dengan hadirnya fenomena alam itu dan disikapi dengan wajar-wajar saja tanpa kepanikan yang berlebihan.
Peneliti sejarah, Suwardono, dikutip dari Media Indonesia, mencontohkan, Mpu Sindok (raja pertama Medang dari Dinasti Mataram Kuno) tetap mengesahkan Prasasti Turyan di Malang saat terjadi gerhana matahari pada 24 Juli 929 Masehi. Peresmian ini juga tercatat dalam buku 3 Prasasti Batu Zaman Raja Sindok terbitan Museum Nasional Indonesia (2003:3).
Sikap serupa ditunjukkan Wisnuwardana, Raja Singhasari periode 1248-1268, ketika meresmikan Prasasti Mulamalurung. Menurut Haris Daryono Ali dalam Menggali Pemerintahan Negeri Doho (2012: 20), prasasti tersebut disahkan tepat ketika gerhana bulan terjadi pada 1177 Saka atau tahun 1254 Masehi. Dalam prasasti itu, tercatat nama Syiwa: salah satu dewa tertinggi dalam ajaran Hindu, juga ayahanda Batara Kala yang kerap dikait-kaitkan dengan gerhana.
Selain itu, ada juga Prasasti Sucen yang berangka tahun 765 Saka atau 843 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Kedu (Jawa Tengah) atau bekas pusat Kerajaan Mataram Kuno ini juga diresmikan saat gerhana bulan. Bahkan, menurut penelitian Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia (2001) seperti dikutip dari situs Bentara Budaya, Prasasti Sucen diyakini sebagai catatan tertua tentang gerhana bulan di tanah Jawa.
Negarakertagama, naskah kuno yang kerap menjadi rujukan untuk melacak sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa, terutama Majapahit, selesai ditulis tepat ketika terjadi gerhana bulan. Menurut Bambang Pramudito dalam Kitab Negarakertagama (2006: 347), Mpu Prapanca merampungkan kitab ini antara September-Oktober 1365 Masehi atau 1287 Saka.
Raja-raja Jawa, sebagaimana pemerintah dalam konteks negara modern, punya perhitungan dan perkiraan yang lebih matang dalam menyikapi fenomena alam yang memang memperoleh tempat dan makna khusus dalam kosmologi Jawa, termasuk gerhana bulan atau matahari.
Kendati kalangan istana cenderung bersikap wajar ketika terjadi gejala alam, akan tetapi tidak bagi kaum akar rumput. Rakyat kebanyakan seringkali menanggapi kejadian-kejadian seperti ini dengan kepanikan. Itu bisa saja karena intrik politik yang sengaja dilakukan penguasa demi kepentingan tertentu, seperti halnya yang pernah diterapkan pemerintahan Soeharto saat gerhana matahari total pada warsa 1983.
Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 4 Februari 2018. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti & Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id