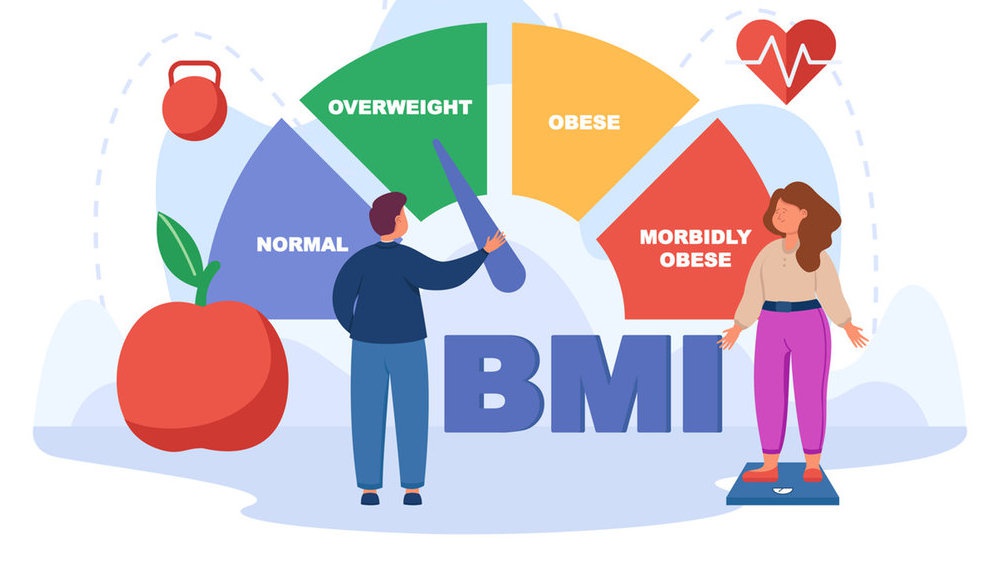tirto.id - Body Mass Index (BMI) atau Indeks Massa Tubuh telah lama digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan status berat badan seseorang, termasuk kategori kurus, normal, kelebihan berat badan, atau obesitas.
Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, makin banyak penelitian dan pakar kesehatan yang mempertanyakan keakuratan dan relevansi BMI sebagai satu-satunya indikator kesehatan.
Salah satu kesalahpahaman yang umum adalah anggapan bahwa seseorang dengan BMI tinggi (di atas 30) sudah pasti mengalami obesitas dengan peluang hidup lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki BMI lebih rendah. Kenyataannya, hal itu tidak sepenuhnya benar.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hubungan antara BMI dan harapan hidup lebih kompleks daripada yang selama ini dipahami.
BMI dan Keterbatasannya sebagai Indikator Kesehatan
Selama beberapa dekade, BMI tetap dianggap sebagai standar emas dalam mengevaluasi risiko kesehatan yang terkait dengan berat badan. Dengan menghitung BMI, seseorang bisa mendapatkan gambaran awal tentang kategori berat badannya.
Untuk menentukan kategori berat badan, kita perlu menghitung BMI terlebih dahulu dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat.
Setelah mendapatkan nilai BMI, kita dapat mengklasifikasikan berat badan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Kategori berat badan sehat memiliki indikator BMI berkisar 18,5-24,9. BMI di bawah 18,5 sudah pasti terindikasi berat badan kurang sehat. Adapun BMI di antara 25 hingga 29,9 tergolong sebagai berat badan berlebih. Di atas itu, seseorang akan dilabeli obesitas.
BMI adalah alat ukur yang murah, sederhana, dan mudah digunakan. Namun, di balik itu, tersimpan banyak kelemahan dan keterbatasan.
Pertama, BMI dianggap memiliki sejarah yang bermasalah dalam penciptaannya. Adalah astronom Belgia, Adolphe Quetelet, yang merumuskan pertama kali dan mengujinya pada sekelompok orang kulit putih di Belanda sekitar tahun 1850-an.
Adolphe menciptakan formula tersebut sebagai bagian dari upayanya memahami “manusia rata-rata” (l'homme moyen) berdasarkan data statistik populasi. Namun, data yang ia gunakan hanya berasal dari sekelompok kecil sehingga kurang mewakili populasi global yang beragam.
Beberapa ahli dan penelitian berikutnya menilai bahwa tidak ada hubungan antara berat badan dan hasil kesehatan. Oleh karena itulah akurasi BMI kemudian diragukan.
Holly Russel dalam jurnalnya menilai, dalam mengidentifikasi kesehatan seseorang, standar BMI cukup membingungkan. Di sisi lain, ia menyoroti perlunya memahami konteks sosial dibanding hanya terpaku pada kategori yang ditetapkan, misalnya bias masyarakat terhadap orang gemuk dan pengaruh industri diet.
Russel mencontohkan, pasien dengan berat badan berlebih kerap mengalami diskriminasi sosial dan komentar buruk perihal penampilannya. Ini dapat memicu rasa malu dan kecemasan, bahkan menurunkan motivasi untuk berkonsultasi ke fasilitas kesehatan. Alih-alih langsung melabeli seseorang dengan kategorisasi BMI, akan lebih baik jika melihat seseorang dengan sudut pandang lebih luas.
Kedua, BMI tidak mampu membedakan antara massa lemak dan massa otot. Seorang atlet yang berotot padat mungkin memiliki BMI tinggi sehingga dikategorikan sebagai obesitas, padahal sebenarnya kondisi fisiknya sangat baik. Sebaliknya, seseorang dengan BMI normal mungkin memiliki persentase lemak tubuh yang tinggi dan berisiko mengalami masalah kesehatan.
Ketiga, BMI tidak memperhitungkan distribusi lemak dalam tubuh. Lemak yang terkumpul di sekitar perut (lemak visceral) lebih berbahaya bagi kesehatan daripada di area lain, seperti pinggul atau paha.
Artinya, dua orang dengan BMI yang sama bisa memiliki risiko kesehatan yang sangat berbeda bergantung pada letak penyimpanan lemaknya. BMI tidak dapat mengidentifikasi perbedaan ini.
Keempat, BMI berpotensi memberikan skor “kegemukan” yang lebih tinggi pada orang jangkung. Hal itu dikarenakan perhitungan rumus BMI tidak sepenuhnya memperhitungkan proporsi tubuh.
Banyak pakar kesehatan kini menyarankan penggunaan alat ukur tambahan sebagai pelengkap BMI, misalnya pengukuran lingkar pinggang, rasio pinggang-pinggul, atau analisis komposisi tubuh. Medium perhitungan terakhir disebut bisa memberikan informasi lebih akurat tentang risiko penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi.
Selain itu, untuk menilai kesehatan secara holistik, ada banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti pola makan, tingkat aktivitas fisik, riwayat kesehatan keluarga, dan kadar stres.

BMI dan Harapan Hidup
Pandangan umum masyarakat, yang kemudian divalidasi oleh lembaga kesehatan, menilai bahwa makin tinggi BMI seseorang, makin rendah harapan hidupnya. Anggapan ini keliru dan dapat dikategorikan sebagai prasangka negatif, yaitu sikap antipati yang didasarkan pada generalisasi yang tidak tepat dan tidak fleksibel.
Sebuah studi yang diterbitkan di JAMA and Archives Journalsmenemukan, pasien dengan BMI kurang dari 23,1—menurut standar WHO, angka ini masih tergolong berat badan sehat—justru memiliki peluang meninggal lebih besar daripada mereka yang memiliki BMI 35,3. Temuan ini mengejutkan karena bertentangan dengan pandangan umum bahwa BMI rendah selalu terkait dengan kesehatan yang lebih baik.
Penelitian tersebut menunjukkan, BMI yang terlalu rendah dapat menjadi indikator masalah kesehatan, seperti kekurangan gizi, penyakit kronis, atau sistem kekebalan tubuh yang lemah. Di sisi lain, BMI yang sedikit lebih tinggi berpotensi memberikan perlindungan terhadap masalah kesehatan tertentu, seperti osteoporosis atau infeksi.
Berdasarkan studi di atas, dapat disimpulkan bahwa BMI tidak boleh dijadikan satu-satunya faktor dalam menilai kesehatan seseorang. Hal ini juga telah diakui oleh banyak pakar. Bahkan, American Medical Association (AMA) menyarankan agar dokter tidak hanya mengandalkan BMI dalam mendiagnosis obesitas dan kesehatan pasien.
“Ada banyak kekhawatiran dengan cara BMI telah digunakan untuk mengukur lemak tubuh dan mendiagnosis obesitas, namun beberapa dokter menganggapnya sebagai ukuran yang membantu dalam skenario tertentu,” ujar Mantan Presiden AMA, Jack Resneck, Jr. MD.
AMA menekankan pentingnya menggunakan pendekatan lebih holistik, yang mencakup pemeriksaan komposisi tubuh, distribusi lemak, dan faktor risiko kesehatan lainnya, seperti tekanan darah, kadar kolesterol, dan kadar gula darah.
Penggunaan alat diagnostik tambahan juga sangat direkomendasikan, misalnya pengukuran lingkar pinggang, rasio pinggang-pinggul, dan analisis komposisi tubuh menggunakan teknologi seperti bioelectrical impedance analysis (BIA) atau dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA).
Bahkan, ada penelitian yang membuktikan manfaat penggunaan metode pemindaian optik tiga dimensi (3DO) untuk mengukur komposisi tubuh. Studi tersebut sampel di berbagai kelompok gender dan usia, dengan aspek pengukuran yang beragam, termasuk tinggi badan, berat badan, BMI, persentase lemak tubuh, dan komposisi tubuh.
Subjek penelitian mengenakan pakaian yang pas di badan dan dipindai pada Fit3D ProScanner dalam waktu 10 menit. Proses pemindaian memakan waktu sekitar 45 detik dan menghasilkan representasi bentuk tubuh yang akurat.
Hasilnya menunjukkan, model 3DO secara umum akurat dan presisi dalam mengestimasi komposisi tubuh, tetapi ada perbedaan signifikan pada beberapa subkelompok tertentu, terutama pada perempuan dengan berat badan kurang dan kelompok etnis tertentu.
Temuan dari The American Journal of Clinical Nutrition tersebut menunjukkan, 3DO dapat menjadi alternatif yang dapat diandalkan untuk DEXA dalam menilai komposisi tubuh. Metode itu dinilai jauh lebih baik dibanding hanya mengandalkan BMI.
Pentingnya Pendekatan yang Lebih Komprehensif
BMI memang sering digunakan sebagai indikator awal untuk menilai status kesehatan seseorang. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa itu bukan satu-satunya acuan. Kondisi kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.
Asupan nutrisi harian, aktivitas fisik, pengelolaan stres, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, penting diperhatikan. Semua itu akan membantu memberikan gambaran lebih jelas tentang kesehatan secara keseluruhan.
Seseorang yang rutin berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, dan memiliki kebiasaan hidup sehat, secara umum memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit meskipun BMI-nya di luar kategori “ideal”.
Sebaliknya, seseorang dengan BMI normal tetapi memiliki kebiasaan merokok, pola makan buruk, dan kurang aktif secara fisik, berpotensi lebih rentan terhadap masalah kesehatan.
Selain itu, riwayat kesehatan keluarga juga berperan penting. Beberapa penyakit turunan, seperti diabetes tipe 2 dan hipertensi, memiliki komponen genetik yang signifikan. Mengetahui riwayat kesehatan keluarga dapat membantu seseorang dan tenaga kesehatan mengambil langkah pencegahan yang tepat.
Pada intinya, penilaian kesehatan tidak seharusnya hanya fokus pada deretan angka di timbangan atau hasil perhitungan BMI. Kesehatan adalah kombinasi dari banyak faktor yang saling berinteraksi.
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id