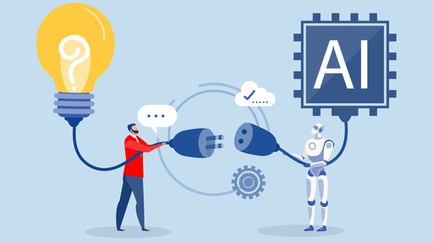tirto.id - Pernikahan mewah Jeff Bezos di Venesia, Italia, pada Juni 2025 lalu, menuai kecaman banyak orang. Penyebab utamanya: jejak karbon yang dihasilkan oleh pernikahan tersebut. Dengan banyaknya pesohor yang terbang dengan jet pribadi—diperkirakan ada 100 jet pribadi yang terlibat—jejak karbon yang dihasilkan diestimasikan mencapai 10 ribu ton CO₂, dengan buangan emisi dari penggunaan jet pribadi mencapai 8.700 ton CO₂.
Khalayak marah besar melihat kelancangan tersebut. Bagaimana bisa mereka (masyarakat kecil yang belum tentu punya kendaraan pribadi) diminta mengurangi jejak karbon, sementara para pesohor kelas wahid bisa seenaknya menggunakan jet pribadi hanya untuk menghadiri sebuah pernikahan? Perlu digarisbawahi, jejak karbon dari pernikahan orang terkaya ketiga dunia tersebut setara dengan jejak karbon yang dihasilkan 1547 orang dalam setahun.
Sebenarnya, konsep jejak karbon pernah punya tempat spesial di masyarakat. Itu merupakan bagian dari kampanye lingkungan yang membuat orang makin sadar tentang cara mereka hidup dan berinteraksi dengan alam sekitar. Gampangnya, jejak karbon adalah emisi yang dihasilkan dari aktivitas harian, mulai dari makan, bepergian, sampai penggunaan energi di rumah tangga. Makin kecil emisinya, makin kecil kontribusi orang-orang terhadap kerusakan lingkungan, dan makin "hebat" mereka.
Namun, seiring berjalannya waktu, jejak karbon mulai kehilangan harga diri. Dan, hal-hal seperti pernikahan Bezos membuat orang makin masa bodoh. Ketika emisi yang dihasilkan oleh lebih dari 1.500 orang dalam setahun saja bisa setara dengan aktivitas hedonis para miliarder hanya dalam beberapa hari, barangkali orang jadi berpikir, "Apa gunanya melacak, apalagi mengurangi jejak karbon?"
Rasa-rasanya, memang sudah waktunya kampanye jejak karbon ditinjau ulang. Apalagi, kampanye tersebut tidak lahir dari iktikad baik. Itu tidak digaungkan oleh aktivis lingkungan atau organisasi-organisasi sejenis.
Kampanye soal jejak karbon merupakan taktik busuk yang digunakan oleh raksasa minyak untuk mengalihkan tanggung jawab dari mereka (para perusak sebenarnya) kepada orang kebanyakan yang, sekali lagi, punya kendaraan pribadi saja belum tentu. Dan, raksasa minyak yang menjadi otak di balik kampanye itu adalah British Petroleum alias BP.
Akal-akalan Korporasi
Istilah dan konsep jejak karbon, atau carbon footprint, dicetuskan pertama kali pada 2004, ketika BP memperkenalkan kalkulator jejak karbon yang bisa diakses secara daring, lengkap dengan slogan "low-carbon diet"-nya. Diluncurkan dengan bantuan agensi Ogilvy and Mather Chicago, kampanye tersebut sukses besar, bahkan sempat memenangi Webby Awards pada 2007 untuk kategori "Gaya Hidup".
Namun, kesuksesan kampanye jejak karbon dari BP-Ogilvy itu, tentu saja, jauh lebih luas dibanding hanya sekadar memenangi penghargaan. Kampanye tersebut ikut membentuk pola pikir masyarakat luas bahwa setiap individu di muka Bumi ini berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Sebenarnya, ini tidak salah karena setiap insan pasti memiliki jejak emisi. Akan tetapi, yang jadi persoalan, kampanye ini kemudian menjadi cara untuk mengalihkan tanggung jawab.
Publik dipaksa ikut bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang tidak mereka perbuat. Sebagai gambaran, menurut laporan Carbon Majors Database yang dilansir The Guardian, 80 persen emisi global yang dihasilkan sejak 2016 hanya berasal dari 57 perusahaan minyak, gas, batu bara, dan semen. BP berada di posisi ketiga polutan terbesar dunia, di bawah ExxonMobil dan Shell.
Dengan emisi karbon sebesar 3,1 gigaton, BP menyumbang 1,2 persen dari total emisi global dalam kurun 2016-2022. Parahnya lagi, jika ditarik mundur sampai ke tahun 1854, BP pun masih berada di posisi ketiga, di bawah Chevron dan ExxonMobil, dengan total emisi CO₂ mencapai hampir 39 gigaton.

Saat perusahaan seperti BP bisa berbuat seenaknya seraya mengeruk profit triliunan, konsep jejak karbon juga menghasilkan efek psikologis bernama climate guilt. Singkatnya, climate guilt adalah beban moral atas emisi harian yang dihasilkan oleh seseorang.
Dengan adanya climate guilt, orang-orang pun mengubah kebiasaan hidupnya, mulai dari stop menyalakan pendingin udara kendati cuaca begitu panas hingga beralih ke moda transportasi "ramah lingkungan" kendati sebenarnya kondisi tak mendukung. Itu semua, sekali lagi, dilakukan saat perusahaan-perusahaan seperti BP, serta para miliarder yang menghadiri pernikahan Bezos, merajalela begitu saja.
Selain climate guilt, ada juga yang disebut climate shame, yaitu kondisi ketika seseorang dipermalukan karena melakukan sesuatu yang dianggap merusak lingkungan. Menurut sebuah riset dari University of Georgia yang diterbitkan pada 2020, climate shame justru kontraproduktif. Pasalnya, makin seseorang dipaksa untuk melakukan "diet karbon", makin ogah-ogahan dia melakukannya.
Impak dari kampanye pengalihan tanggung jawab ini pun tidak sampai di situ. Menurut ahli lingkungan Geoffrey Supran dalam wawancaranya dengan Vox, kampanye seperti itu dapat "melumpuhkan dan membutakan kita dari sifat sistemik dari krisis iklim serta pentingnya mengambil aksi kolektif untuk mengatasi masalah tersebut". Artinya, dengan dianggap sepelenya masalah iklim, pemangku kebijakan seperti pemerintah, khususnya, jadi tidak mau bergerak untuk menanganinya secara serius.
Kongkalikong Pemerintah-Korporasi
Ketika narasi yang dibangun adalah bahwa setiap individu bisa menjadi pahlawan lingkungan melalui tindakan-tindakan kecil, misalnya tidak pakai sedotan plastik atau tidak membawa kendaraan pribadi, tekanan untuk melakukan reformasi sistemik pun ikut menguap, lantas lenyap.
Di Indonesia, misalnya, pendekatan negara terhadap isu lingkungan masih banyak mengandalkan retorika individual. Kampanye hemat listrik, tanam pohon, hingga ajakan untuk kurangi plastik, masih menjadi tulang punggung komunikasi publik. Di sisi lain, pada saat bersamaan, kebijakan makro seperti kelanjutan pembangunan PLTU (meski sudah ada rencana untuk pemensiunan bertahap), pemberian izin tambang, atau pemberian insentif pajak untuk industri sawit, terus berjalan. Artinya, ada ketimpangan besar antara narasi publik dan realitas kebijakan.
Situasi tersebut diperparah oleh greenwashing korporasi. Perusahaan besar melakukan pencitraan ramah lingkungan tanpa benar-benar mengubah praktik produksinya. Banyak dari perusahaan itu bahkan membayar jasa konsultan ESG (environmental, social, governance) untuk menaikkan citranya di pasar modal, sembari tetap memproduksi emisi dalam jumlah besar. Menurut laporan InfluenceMap tahun 2023, lebih dari 58 persen perusahaan Forbes 2000 menggemborkan kampanye iklan yang menyesatkan publik terkait komitmen iklim mereka.

Studi InfluenceMap yang lain mencatat, pada 2020, sebanyak 25.147 iklan Facebook dari 25 organisasi sektor ekstraktif memperoleh total impresi mencapai lebih dari 431 juta. Banyak di antaranya menonjolkan “solusi iklim”, padahal produk utama mereka tetap berbasis fosil.
Fenomena ini menciptakan paradoks. Masyarakat diminta mengubah gaya hidup, sementara para pengemudi utama krisis iklim tetap melaju tanpa rem. Bahkan, seperti kasus Bezos dan tamu-tamunya, mereka seolah-olah berada di luar sistem, tidak tersentuh oleh aturan dan harapan yang ditimpakan kepada masyarakat kecil.
Akhirnya, muncul jurang kepercayaan. Ketika publik mulai menyadari bahwa mereka selama ini "dibohongi" oleh narasi carbon footprint yang dimonopoli korporasi, timbullah sesuatu yang disebut apatisme. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah, lembaga internasional, dan bahkan gerakan lingkungan, kian meluas.
Kendati dapat dipahami, apatisme dalam urusan lingkungan tentu tidak disarankan. Saat ini, jendela informasi sudah terbuka lebar. Perusahaan-perusahaan raksasa tidak bisa lagi berlindung di balik kampanye humas dan advertisement karena internet memungkinkan siapa pun melakukan penyelidikan. Di tengah keterbukaan ini, langkah yang tepat adalah mengubah fokus aksi.
Jika memang bersepeda ke kantor atau menghemat listrik dirasa baik, tidak ada salahnya untuk terus dilakukan. Akan tetapi, kita tidak bisa berhenti sampai di sana. Sembari terus mengurangi, atau setidaknya menjaga emisi individual, memberi tekanan kepada pemerintah dan korporasi untuk berbuat lebih baik juga penting dilakukan, terlepas dari sekeras apa pun upaya mereka menutup kuping, dan sekasar apa pun represi yang dilakukan sebagai wujud respons.
Penulis: Yoga Cholandha
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id