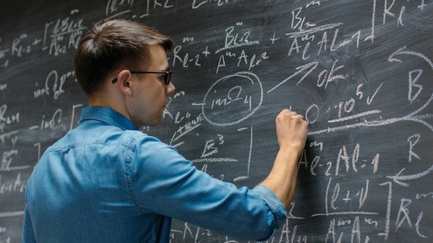tirto.id - Ketika Harmoko, Menteri Penerangan (1983-1997), mengumumkan penyesuaian harga bahan pokok pada era Orde Baru, masyarakat tahu persis bahwa yang dimaksud adalah kenaikan harga. Ketika aparat mengamankan para demonstran, tak ada yang meragukan bahwa mereka ditangkap.
Ketika perusahaan melakukan restrukturisasi, karyawan memahami bahwa PHK massal sedang berlangsung. Ini adalah wajah eufemisme di Indonesia, bahasa yang dipoles tetapi realitasnya tetap pahit.
Eufemisme, menurut KBBI daring, adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan. Ungkapan ini terutama mengakar dalam komunikasi politik dan sosial Indonesia.
Dari zaman Orde Baru hingga era digital saat ini, praktik eufemisme berkembang menjadi lebih dari sekadar kesopanan berbahasa. Ia menjadi instrumen kekuasaan untuk meredam kritik dan membentuk persepsi sosial yang lebih “terkendali”.
Peninggalan Orde Baru yang Tak Pernah Hilang
Pada masa pemerintahan Soeharto, eufemisme bukan sekadar gaya bahasa, tetapi strategi politik yang terstruktur. R.E. Elson dalam Suharto: A Political Biography (2001:245) menilai, istilah seperti pembersihan keamanan dirancang khusus untuk menyembunyikan pelanggaran HAM sistemik, termasuk penyiksaan dan penghilangan paksa.
Rezim menggunakan bahasa sebagai tameng untuk menutupi otoritarianisme dan masalah sosial sambil mempertahankan legitimasi.
Diksi gelandangan diganti jadi tuna wisma agar terdengar lebih sopan. Pelacur jadi wanita tuna susila atau WTS, kemudian berganti lagi jadi pekerja seks komersial atau PSK. Adapun kondisi kelaparan diperhalus dengan istilah rawan pangan.
Tapi, apa yang berubah? Tidak ada. Istilah-istilah itu hanya mencoba memberi wajah "manusiawi". Sementara itu, kenyataannya, masalah kemiskinan tak pernah disentuh dan diatasi.
Sebutan lain, bersih diri dan bersih lingkungan yang populer pada era Orba, misalnya, merupakan metode penyaringan politik untuk meredam setiap gerakan yang dianggap mengancam rezim. Yang tampak sebagai kebersihan moral adalah sesungguhnya pembersihan politik.
Praktik tersebut didukung oleh represi linguistik, yakni penekanan dan pembatasan kebebasan masyarakat dalam menyatakan pikiran dan perasaan melalui bahasa. Alhasil, menurut Fatimatus Zahro dalam esai “Politik Kosong: Sisi Lain Bahasa” di buku Bahasa dan Sastra dalam Kesunyian (2014:12), masyarakat kehilangan kemampuan mengkritik secara langsung dan terpaksa menerima narasi yang telah dihaluskan oleh penguasa.
Reformasi 1998 membawa angin segar kebebasan berbahasa. Namun, eufemisme tidak pernah benar-benar hilang. Dilansir oleh Antara, penggunaan eufemisme dalam media massa pasca-Reformasi memang berkurang, tetapi tidak sepenuhnya lenyap. Yang berubah adalah aktor dan konteksnya: dari alat kontrol politik rezim menjadi strategi komunikasi berbagai pihak untuk menjaga citra.
Fenomena itu tecermin dalam dunia korporat modern. Ketika TikTok Shop dan Shopee melakukan PHK massal, mereka membungkusnya dengan diksi efisiensi operasional dan relokasi sukarela. Strategi tersebut bertujuan meredam persepsi objektif di kalangan masyarakat terhadap PHK massal, yang sejatinya memerlukan prosedur hukum lebih ketat dan kompensasi lebih besar.
Gerakan Anti-eufemisme yang Berumur Pendek
Dunia jurnalistik Indonesia juga tidak terlepas dari praktik eufemisme. Penelitian terhadap berita kriminal menunjukkan praktik eufemisme yang demikian masif: singkatan, kata serapan, istilah asing, metafora, dan perifrasis.
Dalam studi kasus pemberitaan Brigadir J, media menggunakan eufemisme untuk menghaluskan fakta kekerasan sambil tetap menyampaikan informasi, misalnya penulisan frasa masih abu-abu, peristiwa berdarah, hingga menodongkan senjata. Namun, praktik tersebut menimbulkan dilema: di satu sisi melindungi sensitivitas pembaca, di sisi lain berpotensi mengaburkan realitas yang sebenarnya.

Salah satu contoh paling menarik terjadi pada 2021, ketika media massa ramai-ramai mengganti sebutan koruptor dengan maling uang rakyat. Gerakan ini merupakan upaya anti-eufemisme, sebuah perlawanan terhadap penghalusan bahasa yang dianggap telah mengaburkan realitas kejahatan korupsi.
Gerakan tersebut dimulai oleh Remotivi, lembaga kajian media dan komunikasi. Pada 23 Agustus 2021, mereka mengajak wartawan mengganti istilah koruptor dengan maling. Bukan tanpa alasan. Seruan tersebut muncul sebagai reaksi keras terhadap wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewacanakan penggunaan istilah penyintas korupsi untuk menyebut mantan narapidana koruptor.
Istilah penyintas korupsi yang diusulkan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana pada Maret 2021 menuai kritik luas. Novel Baswedan, penyidik senior KPK kala itu, menyebutnya keterlaluan.
“Ketika menyebut koruptor sebagai penyintas (korban), lalu pelakunya siapa? Negara?” tanyanya secara retoris.
Sebenarnya, gagasan menggunakan diksi maling untuk koruptor sudah lama beredar. Cendekiawan muslim, Quraish Shihab, pernah menyatakan: “Kenapa orang miskin yang mengambil yang bukan haknya dinamai pencuri? Kenapa kalau pejabat atau pegawai kita namai koruptor? Dia itu pencuri”.
Bahkan, Remotivi sebenarnya telah mengusung ide itu sejak 2017, khususnya ketika kasus korupsi E-KTP Setya Novanto mencuat.
Respons media sangat positif. Kompas.com pada 24 Agustus 2021 menggunakan judul “Komplotan Lima Maling yang Dipimpin Seorang Menteri” untuk kasus Juliari Batubara. Bahkan, sebanyak 170 media di bawah Pikiran Rakyat Media Network resmi mengganti istilah koruptor dengan maling, rampok, atau garonguang rakyat.
Sayangnya, gerakan itu tidak berlangsung lama. Dewan Pers melalui Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Arif Zulkifli mengingatkan bahwa penggunaan kata-kata tersebut memiliki konsekuensi hukum buat media itu sendiri.
Perlahan, media mulai kembali menggunakan kembali istilah koruptor dalam pemberitaan rutin, meskipun sesekali masih terdengar penggunaan maling uang rakyat, terutama dalam konteks editorial atau opini.
Menuju Komunikasi yang Lebih Jujur
Abdul Chaer & Leonie Agustina, dalam Sosiolinguistik:Perkenalan Awal (1995), menyebut bahwa eufemisme di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, globalisasi, dan tekanan sosial untuk menjaga citra dan menghindari stigma membuat masyarakat lebih memilih istilah yang terdengar positif, meski mengaburkan realitas.
Nilai kesopanan Jawa dan Melayu memang menjadi dasar penggunaannya, tetapi politisasi bahasa kemudian mengubahnya menjadi alat yang berpotensi melemahkan kejujuran sosial.
“Para politisi berlomba-lomba adu ketangkasan dalam menarik simpati publik. Padahal jika dicermati dan dikaji lebih dalam, banyak pemilihan diksi secara harfiah bermakna konotatif negatif,” demikian ditulis dalam kajian IAIN Ambon bertajuk “Eufemisme Berbahasa di Dalam Surat Kabar”.
Penelitian lain dari Balai Bahasa Aceh pada September 2022 menegaskan, ketika bahasa dipolitisasi, ia kehilangan fungsi sebagai alat komunikasi yang jujur dan, sebaliknya, justru menjadi instrumen manipulasi. Eufemisme disalahgunakan dalam politik untuk menciptakan makna ambigu dan menipu, menyembunyikan realitas dari publik, serta mengembangkan kode rahasia (argot) yang digunakan oleh kelompok korup.
Kiwari, era digital membawa kompleksitas baru dalam penggunaan eufemisme. Teknologi memungkinkan komunikasi instan di seluruh dunia, yang membawa tantangan baru seperti perbedaan budaya, regulasi konten, dan kecepatan penyebaran informasi.
Platform media sosial dan berita daring mempercepat penyebaran istilah-istilah yang dihaluskan, sering kali tanpa konteks yang memadai. Artikel berjudul “From Clicks to Chaos: How Social Media Algorithms Amplify Extremism” (2025) menjelaskan, algoritma memperkuat eufemisme dengan mempromosikan konten emosional tetapi tidak lugas, seperti penggunaan simbol atau istilah halus untuk menghindari deteksi.
Eufemisme bukan sepenuhnya negatif. Dalam konteks yang tepat, ia dapat mengurangi stigma, menjaga kesopanan, dan memfasilitasi komunikasi yang lebih konstruktif. Panggilan penyandang disabilitas menggantikan cacat adalah contoh positif penghalusan bahasa yang memberdayakan.
Dalam keseharian, kita juga kerap melakukannya. Misalnya, ketika hendak ke toilet, kita biasa berpamitan dan bilang, hendak pergi ke kamar kecil atau ke belakang agar terdengar lebih sopan.
Sebaliknya, ketika eufemisme digunakan untuk menyembunyikan ketidakadilan, menghindari tanggung jawab, atau mengaburkan realitas, ia menjadi berbahaya. Yang Indonesia butuhkan adalah keseimbangan: bahasa yang sopan tetapi jujur, halus tetapi tidak menipu, konstruktif tetapi tidak mengaburkan.
Jargon “pembangunan berkelanjutan” dan “konsep hijau” untuk proyek Ibu Kota Nusantara, misalnya, perlu dikaji ulang dalam berkomunikasi. Faktanya, protes soal penggusuran dan polusi lingkungan dari masyarakat adat di Penajam Paser Utara justru menunjukkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan undang-undang tata ruang.
Tantangan ke depan adalah menciptakan budaya komunikasi yang dapat menyampaikan kebenaran, tanpa mengorbankan substansi. Ini memerlukan kesadaran kolektif bahwa bahasa yang indah tanpa tindakan nyata hanyalah kemasan kosong yang tidak menyelesaikan masalah.
Eufemisme dapat menjadi jembatan menuju solusi, tetapi tidak boleh menjadi tujuan akhir. Yang diperlukan adalah keberanian menghadapi realitas apa adanya sambil tetap menjaga martabat dalam berkomunikasi.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak terletak pada kemampuannya menghaluskan masalah, tetapi pada keberaniannya mengakui dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang bermartabat. Eufemisme boleh menjadi awal percakapan, tetapi kejujuran harus menjadi inti.
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id