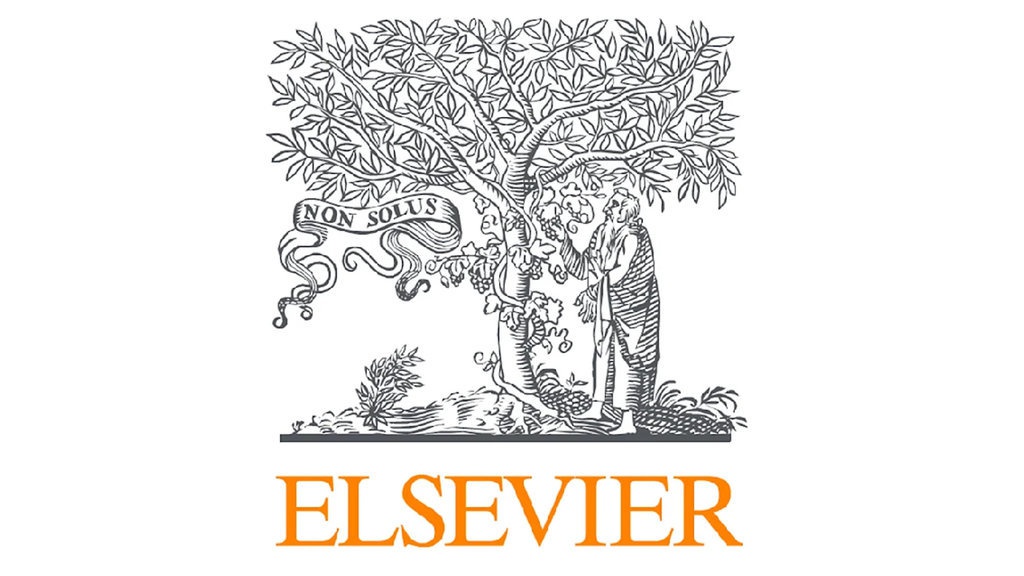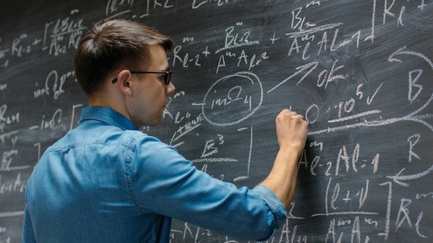tirto.id - Hingga awal Oktober 2025, hampir 21 ribu peneliti di seluruh dunia berkomitmen untuk tidak mendukung segala aktivitas industri penerbitan ilmiah Elsevier, termasuk urusan menulis, memublikasi, serta mereviu jurnal. Mereka menamakan gerakan tersebut sebagai Gerakan Ongkos Pengetahuan atau The Cost of Knowledge. Hal itu dilakukan karena Elsevier, salah satu penerbit terbesar di dunia, dianggap merugikan dan mencurangi sistem distribusi pengetahuan akademik.
Di sisi lain, tidak dimungkiri, banyak terbitan jurnal mereka merupakan karya berkualitas dan berdampak. Ia juga telah lama menjadi tempat langganan bagi para pemenang nobel memublikasikan ide dan penelitian.
Tentu tak semua orang kenal dengan Elsevier. Wajar saja, sebab Elsevier merupakan penerbit akademik yang lazimnya diakrabi peneliti, dosen, atau mahasiswa. Singkatnya, yang sempat mengecap bangku kuliah, kalaupun tidak tahu Elsevier, setidaknya pasti pernah membaca jurnal terbitan mereka.
Di antara jurnal-jurnal terbitan Elsevier termasuk The Lancet, Cell, dan Current Opinion. Scopus, lembaga pengindeks yang jadi parameter jurnal berkualitas, juga merupakan salah satu unit bisnis dari Elsevier (grup RELX). Saat ini, Indonesia menggunakan parameter dari Scopus untuk mengukur indikator kenaikan jabatan dosen di perguruan tinggi.
Namun siapa sangka, Elsevier menjalankan bisnis bermasalah. Mereka mendulang untung sangat besar, bahkan lebih besar daripada raksasa teknologi, seperti Google dan Apple. Mereka memanfaatkan celah di dunia akademik dan mengeksploitasi sumber daya para peneliti.
Memojokkan Periset dan Lembaga Penelitian
Tidak hanya Elsevier, penerbit ilmiah lain, misalnya Wiley dan Springer Nature, juga kerap memojokkan para peneliti, terlebih para peneliti dari negara-negara berkembang.
Sistem bisnis penerbitan ilmiah mereka benar-benar seperti menara gading: hanya bisa diakses, dibaca, dan disebarkan oleh kalangan tertentu, terkhusus orang-orang yang mampu membelinya dengan harga mahal.
Berbeda dari penerbit komersial populer di Indonesia, seperti Gramedia atau Diva Press, Elsevier tidak memberikan upah kepada penulis.

Sebagai perbandingan, biasanya para penerbit komersial akan melakukan kerja sama dengan penulis, baik melalui sistem royalti ataupun beli-putus. Secara tidak langsung, penulis dan penerbit menjalin simbiosis mutualisme yang diharapkan menguntungkan kedua belah pihak.
Akan tetapi, tidak demikian dengan Elsevier atau penerbit ilmiah lainnya, seperti Springer Nature dan Wiley. Untuk menerbitkan artikel di penerbit mereka, penulis bahkan harus membayar. Iya, membayar biaya yang tidak murah, mulai dari 8-70 juta rupiah per artikel.
Makin bagus reputasi jurnalnya, makin mahal biaya penerbitannya. Sebut saja salah satu jurnal bergengsi Elsevier, Computer in Human Behavior. Biaya penerbitan artikel di situ, per Oktober 2025, adalah 3.870 dolar AS atau setara Rp65 juta per artikel dengan akses terbuka (open access). Betapa mahalnya biaya (penyebaran) pengetahuan!
Sialnya lagi, untuk mengakses jurnal dan membaca artikel terbitan mereka, para pembaca harus merogoh kocek untuk membayar biaya langganan atau membeli per artikel yang sangat mahal.
Masih menggunakan patokan Computer in Human Behavior, biaya baca per artikel di jurnal tersebut menyentuh 37,95 dolar AS atau setara 633 ribu rupiah. Sejumlah itulah uang yang mesti kita keluarkan untuk mengakses tulisan yang panjangnya hanya sekitar 5-12 halaman.
Karena nyaris tak ada pembaca yang rela mengeluarkan uang demi mengakses jurnal tersebut, biasanya biaya berlangganan dibebankan kepada universitas atau lembaga penelitian yang harganya fantastis, serta tertutup antara satu universitas dan universitas lain. Para universitas pun banyak yang mengeluh atas mahalnya biaya langganan tersebut.
Saking mahalnya biaya langganan untuk jurnal ilmiah, beberapa universitas di Amerika Serikat, seperti Universitas California dan The State University of New York, memilih berhenti berlangganan Elsevier. Lebih radikal lagi, di Jerman, sebanyak 200 institusi riset tidak lagi memperbaharui kontrak individu dengan Elsevier sejak kontrak mereka kedaluwarsa.
Gerakan Boikot Elsevier
Sebenarnya, penerbit-penerbit ilmiah lain, semacam Wiley, Taylor & Francis, dan Springer Nature, juga membebankan biaya tinggi. Lalu, kenapa hanya Elsevier yang menerima kemarahan para peneliti dan akademisi?
Pada dasarnya, para peneliti sudah lelah dengan mahalnya publikasi dan ilmu pengetahuan. Karena itu, muncul gerakan open access, yaitu gerakan internasional agar ilmu pengetahuan dapat diakses bebas oleh semua orang, tanpa hambatan laman berbayar (paywall).
Melihat bahwa gerakan akses terbuka merupakan ancaman bagi bisnis mereka, Elsevier mendukung rancangan undang-undang (RUU) melawan open access. Di AS, RUU tersebut dikenal sebagai Research Works Act yang isinya melarang akses gratis terhadap penelitian yang dibiayai dana publik.
Dukungan Elsevier terhadap RUU tersebut mengundang kemarahan peneliti. Lantas, pada 2012, salah seorang matematikawan kesohor, Timothy Gowers, mengajak dan memobilisasi para peneliti lain untuk memboikot Elsevier.
Gerakan boikot tersebut berupa penandatanganan petisi untuk tidak mendukung seluruh aktivitas bisnis Elsevier, mulai dari menulis artikel, mengirim, menjadi penyunting, atau melakukan reviu atas jurnal terbitan mereka.
Sebagaimana disebut di awal, mereka menamai gerakan tersebut sebagai The Cost of Knowledge. Pemantiknya tidak spesifik pada kasus Elsevier, melainkan umum: menolak komersialisasi pengetahuan yang berlebihan.
Oleh karena itu, kendati hanya Elsevier yang diboikot, sebenarnya itu hanya simbol karena Elsevier-lah yang paling vulgar mengeksploitasi para peneliti.
Pertanyaannya, apakah boikot tersebut efektif? Apakah orang yang memboikot tetap konsisten dengan komitmennya?

Empat tahun sejak kampanye memboikot Elsevier, tiga peneliti dari Universitas Leuven, Belgia, mengevaluasi konsistensi peneliti terkait aksi boikot tersebut. Bagaimanapun, kesuksesan gerakan boikot tergantung pada komitmen para penanda tangan petisi dan luasnya skala penyebaran boikot tersebut.
Sayangnya, tuntutan dunia akademik untuk terus memublikasikan artikel, terkhusus di jurnal yang berdampak, membuat para peneliti tak punya banyak pilihan. Beberapa terpaksa melanggar resolusi mereka.
Hasil evaluasi terhadap aksi boikot tersebut mencatat, sekitar 38 persen dari penanda tangan petisi tetap menerbitkan artikelnya di Elsevier, kendati terpaksa berlawanan dengan idealisme yang mereka junjung.
Tak ayal, Elsevier dibenci, sekaligus "dicintai" (karena terbatasnya pilihan yang ada). Orang yang memboikot Elsevier pun tetap mengakses, membaca, dan mengutip artikel terbitannya karena jaminan kualitas.
Namun, kita tahu selalu ada pilihan untuk melawan mahalnya komersialisasi pengetahuan.
Bukti paling nyata adalah perlawanan Alexandra Elbakyan. Ia mendirikan Sci-Hub dan Library Genesis, dua portal ilegal yang membuka "kunci" akses berbayar terhadap ratusan ribu jurnal ilmiah, buku, majalah, hingga komik, agar bisa diakses publik secara gratis.
Alexandra Elbakyan menjadi martir karena membebaskan (sebagian) akses ilmu pengetahuan. Ia menjadi buronan internasional karena aktivitas pembajakan hak cipta terbesar di dunia.
Kendati dicap sebagai kriminal, sosoknya bak Robin Hood, didapuk sebagai pahlawan dunia ilmiah dan akademik. Bahkan, pada 2016, salah satu jurnal paling prestisius di dunia, Nature, menobatkan Alexandra Elbakyan sebagai sosok paling berpengaruh karena mampu mengubah wajah dunia akademik dan literasi dunia.
Perlawanan Elbakyan lewat Sci-Hub dan Library Genesis tentu berbeda jalur dari boikot Elsevier yang dilakukan para peneliti. Jika gerakan The Cost of Knowledge menempuh jalan etis dan legal melalui petisi serta penghentian kerja sama dengan penerbit, Sci-Hub justru menabrak batas hukum dengan membuka akses secara ilegal.
Namun, keduanya lahir dari keresahan yang sama, yaitu biaya pengetahuan yang kian tak terjangkau.
Fenomena itu menunjukkan, penolakan terhadap model bisnis ala Elsevier tidak hanya datang dari kalangan akademisi yang menandatangani petisi, tetapi juga dari aktivis digital yang memilih jalur radikal. Baik lewat meja perundingan maupun lewat peretasan (pembajakan), pesan yang disampaikan serupa: ilmu pengetahuan seharusnya menjadi hak semua orang, bukan komoditas eksklusif yang cuma diperuntukkan bagi yang mampu membayar.
Kembali pada Elsevier, hingga kini, gerakan boikot The Cost of Knowledge terus berlangsung dan digaungkan. Hal ini secara tidak langsung membongkar borok dunia penerbitan akademik, bidang yang dianggap emansipatif, tetapi ternyata mengeksploitasi para ilmuwannya sendiri.
===============
Abdul Hadi merupakan akademisi di bidang psikologi, lulusan Magister Psikologi Sosial dan Kesehatan Utrecht University. Saat ini, Hadi bekerja sebagai peneliti di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Tirto.id membuka peluang bagi para ahli, akademisi, dan peneliti, untuk memublikasikan hasil riset keilmuan. Jika berminat, silakan kirim surel ke mild@tirto.id untuk korespondensi.
Penulis: Abdul Hadi
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id