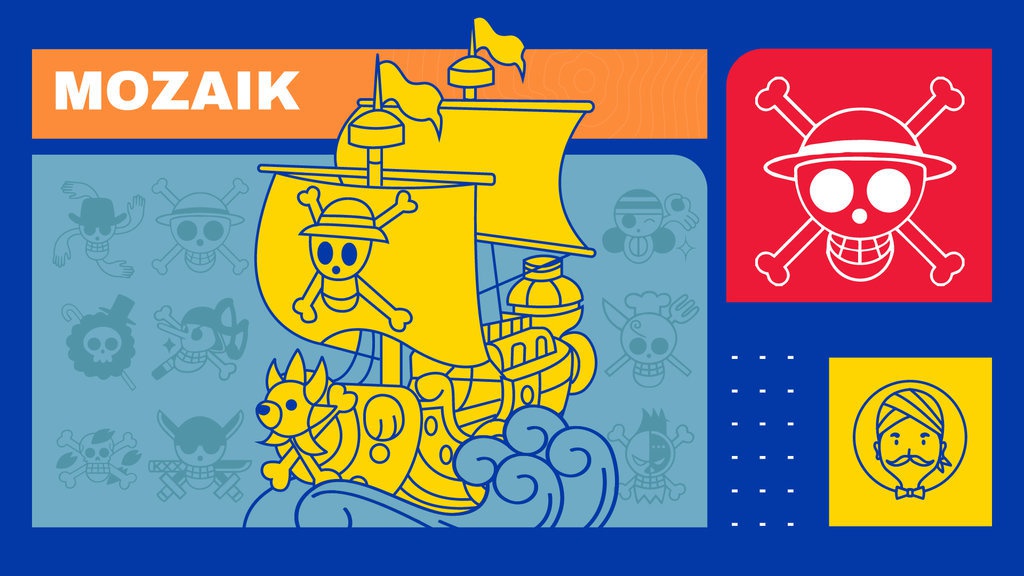tirto.id - Langit Alabasta akhirnya kembali biru. Badai pasir yang didalangi kejahatan telah sirna, dan kerajaan gurun mulai menyembuhkan lukanya di bawah kepemimpinan sang putri yang bijaksana.
Namun, di antara kelegaan dan harapan baru, ada sebuah perpisahan yang tak terhindarkan. Para pahlawan sesungguhnya, sekelompok bajak laut dengan topi jerami, harus angkat sauh. Dari atas geladak Going Merry, keheningan terasa berat. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper berdiri membelakangi pantai.
Di atas tebing yang menghadap ke laut lepas, Putri Vivi berdiri tegap, ditemani Carue, bebek setianya. Matanya terpaku pada satu titik di cakrawala, sebuah kapal kecil yang perlahan menjauh.
Tiba-tiba Luffy mengangkat lengan kirinya tinggi-tinggi ke udara. Satu per satu, krunya mengikuti.
Dari kejauhan, Vivi menyipitkan matanya. Ia melihat siluet mereka yang serempak. Lalu ia mengerti. Di bawah perban yang melingkari pergelangan tangannya sendiri, ada sebuah tanda X sebagai simbol persahabatan.
Adegan dalam anime One Piece tersebut dikenal sebagai “Perpisahan Tanpa Kata dengan Vivi” merupakan puncak emosional dari seluruh saga Alabasta. Setelah berjuang bersama rakyat Alabasta untuk menggulingkan Crocodile dan Baroque Works, kru Topi Jerami tidak bisa mendapatkan perpisahan yang layak dengan Putri Vivi.
Dua dekade setelah episode itu tayang, simbol bajak laut bertopi jerami berkibar di tiang-tiang rumah warga Indonesia, truk, hingga tiang umum, kadang berdampingan dengan Merah Putih. Di tengah perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, Jolly Roger muncul bukan sebagai lelucon fandom, tapi sebagai bahasa protes yang menggema dari ruang digital ke dunia nyata.
Awalnya muncul di TikTok dan X, lalu menyebar cepat ke dunia nyata. Banyak unggahan menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah.
Gerakan ini tak punya pemimpin, tak terorganisasi secara formal, tapi menyebar organik lewat media sosial. Justru karena anonim dan kolektif, gerakan ini sulit dibungkam, mencerminkan bentuk protes baru di era digital: cair, spontan, dan tak mudah dilacak.
Kebebasan di Bawah Topi Jerami
Diciptakan oleh Eiichiro Oda, One Piece bukan sekadar hiburan. Ia adalah kisah tentang pertualangan, persahabatan, dan perjuangan meraih kebebasan. Ratusan juta kopi telah terjual lewat manga, anime, film, dan video gim.
Di Indonesia, penggemarnya akrab disapa Nakama Indonesia, sangat besar dan loyal, terbukti dengan antusiasme mereka di berbagai acara dan interaksi tinggi di media sosial. Bahkan pada awal 2025 akun Instagram @onepiece.indo.official resmi khusus untuk penggemar Indonesia diluncurkan.
Selain itu, komunitas-komunitas penggemar yang solid telah eksis sejak lama, seperti Komunitas One Piece Indonesia (KOPI) yang didirikan pada tahun 2010 dan memiliki puluhan ribu anggota di dunia maya serta ratusan anggota aktif dalam kegiatan regional di dunia nyata.

One Piece berkisah tentang kru Bajak Laut Topi Jerami yang dipimpin Luffy. Mereka menentang penguasa global yang korup dan manipulatif. Luffy dan krunya bukan bajak laut kejam, tapi pembebas bagi negeri-negeri tertindas.
Dalam dunia One Piece, mengibarkan bendera Jolly Roger adalah tindakan menantang kekuasaan, simbol perlawanan terhadap sistem yang tidak adil. Jolly Roger sendiri pada dasarnya adalah alat bisnis. Bajak laut menggunakannya untuk mengintimidasi kapal dagang agar menyerah tanpa perlawanan, sehingga pembajakan menjadi lebih efisien.
Simbol tengkorak dan tulang bersilang memiliki akar sejarah kuno, muncul dalam budaya Mesir, Yunani, dan Kristen awal sebagai simbol kematian. Emanuel Wynn dianggap sebagai bajak laut pertama yang menggunakan Jolly Roger pada tahun 1700, yang menampilkan tengkorak, tulang bersilang, dan jam pasir.
Bagi banyak penggemar di Indonesia, bendera ini mewakili semangat melawan ketidakadilan dan budaya korup, sesuatu yang dirasa relevan dengan kondisi negeri saat ini. Mereka tak perlu menciptakan simbol baru. Cukup meminjam dari narasi yang sudah mereka kenal dan hayati.
Riset akademis menunjukkan bahwa One Piece memang sarat dengan kritik sosial dan politik. Penelitian di berbagai universitas di Indonesia mengkaji bagaimana serial ini merepresentasikan isu-isu seperti hegemoni pemerintah, perbudakan modern, dan eksistensialisme.
Fenomena bendera Jolly Roger mencerminkan bagaimana budaya pop global bisa menjadi alat kritik politik lokal. Gen Z yang merupakan generasi mayoritas di Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2020 (74,93 juta jiwa atau 27,94 persen) hidup di persimpangan budaya. Mereka menyerap nilai-nilai global seperti kebebasan dan keberagaman, sambil bergulat dengan keresahan soal identitas nasional yang kian cair.
Mereka tak hanya mengonsumsi budaya global, tapi menciptakan budaya hibrida, memadukan elemen global dan lokal untuk membentuk identitas baru yang reflektif. Dalam kasus ini, nilai-nilai dari One Piece seperti solidaritas dan perlawanan terhadap tirani diterjemahkan ke konteks Indonesia. Simbol bajak laut bertopi jerami menjadi saluran kritik terhadap demokrasi yang menyempit, korupsi, dan ketidakadilan.
Menurut penelitian Thomas Zoth (2011) yang berjudul “The politics of One Piece: Political critique in Oda's Water Seven”, serial ini menggunakan narasi untuk mengeksplorasi relasi antara individu dan negara, khususnya dalam hal keamanan nasional dan hak individu.
Paradoks muncul. Sebagian akademisi khawatir budaya global menggerus Pancasila. Tapi Jolly Roger justru digunakan untuk menuntut negara agar setia pada cita-cita kemerdekaan. Fiksi menjadi bahasa politik yang mudah dipahami, sekaligus alat audit terhadap kinerja kekuasaan.
Media Sosial sebagai Amplifier
Fenomena One Piece ini bukanlah kasus pertama di mana budaya populer menjadi medium ekspresi politik di Indonesia. Komunitas penggemar tak lagi sekadar penikmat hiburan, tapi telah menjadi kekuatan sosial-politik.
Sebelumnya, K-Pop telah menunjukkan pengaruh serupa dalam politik Indonesia, khususnya dalam Pemilu 2024. Mereka sudah menunjukkan kapasitas mobilisasi dalam isu-isu nasional seperti penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja dan gerakan #GejayanMemanggil. Mereka terorganisasi, punya motivasi ideologis, dan mampu menggalang dukungan.
Gerakan Jolly Roger menunjukkan pola serupa, meski lebih spontan dan terdesentralisasi. Komunitas penggemar One Piece punya jaringan solid, bahasa bersama, dan ruang komunikasi yang aktif. Meski awalnya bukan untuk politik, mereka cepat bereaksi saat nilai-nilai kebebasan dan perlawanan terancam.
Perbedaannya ada di metode. Aktivisme K-pop cenderung terkoordinasi, sementara Jolly Roger lebih anarkis. Tapi keduanya menunjukkan bahwa di era digital, fandom bukan lagi budaya pinggiran. Ia telah menjadi kekuatan politik yang nyata.
Media sosial, terutama TikTok dan X, berperan besar dalam menyebarkan gerakan ini. TikTok memudahkan aksi individu menjadi tren kolektif lewat video pendek yang mudah ditiru. X menjadi ruang diskusi dan artikulasi argumen. Partisipasi aktif pengguna menciptakan efek bola salju, setiap unggahan memperkuat gerakan.

Yang membuatnya masif bukan hanya kontennya, tapi juga algoritma. Konten provokatif seperti pengibaran bendera tandingan secara alami menarik perhatian. Algoritma TikTok mendorong konten dengan interaksi tinggi ke lebih banyak linimasa. Ia bukan lagi medium netral, tapi aktor tak terlihat yang mempercepat dan memperluas jangkauan protes simbolik, mengubahnya dari percakapan fandom menjadi isu nasional.
Dibandingkan dengan film-film Hollywood atau musik Barat yang sering kali juga sarat dengan pesan politik, pengaruhnya di Indonesia cenderung lebih pasif. Produk budaya pop Barat dapat membentuk cara pandang dan nilai-nilai individu, namun jarang sekali memicu sebuah gerakan kolektif yang terkoordinasi.
One Piece menawarkan narasi alternatif tentang perlawanan terhadap ketidakadilan yang lebih resonan dengan kondisi politik Indonesia saat ini.
Cermin di Tiang Bendera
Pengibaran bendera Jolly Roger bukan sekadar aksi iseng. Ia lahir dari keresahan politik pasca Pilpres 2024, terutama pernyataan-pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang terkesan anti kritik.
Dalam perjalanannya, gelombang ketidakpuasan publik jauh lebih kompleks dan berlapis. Survei Ipsos 2024 menunjukkan bahwa polisi dan politisi adalah dua profesi paling tidak dipercaya di Indonesia. Kasus-kasus besar seperti dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri dan pembunuhan oleh Ferdy Sambo memperkuat persepsi publik bahwa hukum bisa dimanipulasi.
Dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama, penyelewengan pengadaan Chromebook di Kemendikbud, hingga skandal PT Timah yang merugikan negara Rp300 triliun, memperkuat citra bahwa elite politik dan birokrasi tidak bisa dipercaya.
Meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun ke 4,91 persen pada Agustus 2024, jumlah penganggur tetap tinggi: 7,47 juta orang. Lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar. Di sisi lain, keluhan soal pajak tinggi dan ketimpangan ekonomi makin sering muncul di media sosial, memperkuat rasa ketidakadilan struktural.
Dalam iklim seperti ini, protes simbolik tumbuh. Kekecewaan seolah menyatu dengan narasi One Piece, di mana pemerintah dunia tak ingin diganggu oleh bajak laut yang memperjuangkan kebebasan. Dunia fiksi dan realitas politik saling memantulkan.
Jolly Roger jadi simbol kekhawatiran bahwa kritik akan dibatasi. Ini adalah dialog antara budaya pop dan situasi politik. Yang satu memberi konteks, yang lain menyediakan simbol.
Respons pemerintah pun terbelah. Ada yang menyebutnya ancaman, ada pula yang melihatnya sebagai ekspresi kreatif. Wakil Ketua DPR awalnya santai, lalu menyebutnya sebagai “upaya pecah belah bangsa”.
Menko Polhukam bahkan bicara soal pidana. Sebaliknya, Wamendagri Bima Arya menyebutnya ekspresi wajar selama Merah Putih tetap dihormati. GP Ansor dan YLBHI juga menilai pemerintah terlalu reaktif.
Perbedaan ini menunjukkan dua cara pandang: aparat keamanan melihat ancaman, pejabat sipil melihat kebebasan berekspresi. Ironisnya, respons keras justru memperkuat simbol itu sebagai alat protes. Pemerintah terlihat panik, tak nyambung dengan budaya anak muda. Ancaman pidana terhadap penggemar anime malah menarik simpati publik.
Secara hukum, UU No. 24 Tahun 2009 tak secara eksplisit melarang bendera fiksi. Larangan lebih ditujukan pada bendera negara asing. Namun, aturan soal tata letak Merah Putih tetap ketat. Pengibar Jolly Roger memanfaatkan celah ini, menempatkan simbol fiksi berdampingan tanpa merusak Merah Putih.
Pertanyaannya, di mana batas antara kreativitas, kritik, dan kriminalitas? Pandangan keras menyebutnya pelanggaran. Pandangan moderat melihatnya sebagai ekspresi damai. Amnesty International menegaskan, “Ekspresi damai lewat pengibaran bendera bukanlah makar”.
Respons terhadap protes tak konvensional mencerminkan kedewasaan politik. Ancaman pidana menunjukkan sisa-sisa refleks otoriter. Sebaliknya, penghargaan terhadap kreativitas menandakan pemahaman yang lebih matang.
Pada akhirnya, ini bukan soal bendera. Ini soal arah demokrasi Indonesia: apakah cukup kuat menampung kritik, atau rapuh dan mudah terguncang oleh simbol fiksi.
Di tengah dunia yang makin terhubung, generasi baru tak lagi diam. Mereka bicara lewat simbol, meme, dan cerita. Dan kadang, suara paling lantang datang bukan dari mimbar politik, tapi dari layar kecil di tangan anak muda dengan bendera hitam, topi jerami, dan harapan akan kebebasan yang tak bisa dibungkam.
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id