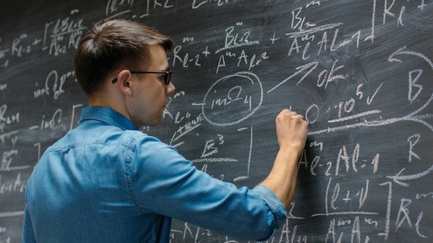tirto.id - Kita semua pernah melihatnya, atau mungkin pernah ambil bagian di dalamnya. Di berita, di film, di jalanan, kita semua pernah terlibat, entah langsung atau tidak, dalam tindak kekerasan. Di sini kita tidak cuma bicara soal perang, tetapi juga perundungan, pertengkaran pasangan, bahkan komentar kejam di media sosial. Suka tidak suka, kekerasan adalah bagian dari kita sebagai manusia.
Dari sana, kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan: Apakah kekerasan memang bagian dari kodrat manusia? Apakah kita secara alami punya kecenderungan untuk menyakiti sesama?
Pertanyaan ini jelas bukan barang baru. Para filsuf seperti Thomas Hobbes percaya bahwa, tanpa hukum dan negara, manusia akan saling membunuh demi bertahan hidup. Sebaliknya, Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik, dan justru menjadi kejam karena pengaruh peradaban. Tapi, bagaimana sains modern menjawabnya?
Ternyata, jawabannya tidak sesederhana "ya" atau "tidak." Dari studi tentang otak, perilaku primata, hingga sejarah masyarakat pemburu-pengumpul, para peneliti menemukan bahwa kekerasan memang ada dalam repertoar manusia. Namun, ini bukanlah sesuatu yang tak bisa dihindari.
Pembanding Evolusioner
Sebuah studi yang dimuat di jurnal Nature mengamati 152 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh simpanse liar di 18 komunitas berbeda. Hasilnya cukup mengejutkan: mayoritas pembunuhan dilakukan oleh kelompok jantan dewasa terhadap jantan lain dari kelompok yang berbeda. Motifnya? Teritorial. Simpanse membentuk koalisi, menyerang kelompok luar, dan merebut wilayah. Ini adalah bentuk kekerasan yang terorganisasi, dan mirip dengan konsep “perang skala kecil.”
Yang menarik, ketika peneliti membandingkan dengan bonobo—kerabat dekat simpanse—hasilnya jauh berbeda. Bonobo nyaris tidak menunjukkan kekerasan mematikan antarsesama. Bahkan, hanya ada satu kasus dugaan pembunuhan bonobo selama periode pengamatan yang sama. Padahal, kedua spesies ini punya nenek moyang yang sama.
Kesimpulannya, kekerasan mungkin memang punya akar evolusioner, tapi ia tidak bersifat universal. Bahkan dalam keluarga kera besar sekalipun, ada spesies yang bisa hidup hampir tanpa kekerasan fatal.
Lantas, bagaimana dengan manusia?
Sebuah artikel dari Live Science merujuk pada studi perbandingan terhadap lebih dari 1.000 spesies mamalia. Hasilnya menunjukkan bahwa primata—termasuk manusia—memiliki tingkat kekerasan terhadap sesama yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok hewan lain. Rata-rata, sekitar 2 persen dari kematian pada manusia disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh manusia lain, dan angka ini ternyata konsisten dengan rata-rata primata lain.
Artinya, kekerasan bukanlah anomali dalam diri manusia. Tapi itu juga bukan sesuatu yang tak terelakkan. Spesies kita bukan satu-satunya yang bisa berlaku kejam, tapi juga bukan satu-satunya yang cinta damai. Ini menempatkan manusia pada posisi menarik karena kita punya kapasitas biologis untuk melakukan kekerasan, tapi juga punya kebudayaan dan moral untuk menolaknya.
Kekerasan Proaktif vs Reaktif
Jika kekerasan secara inheren merupakan bagian dari manusia, pertanyaannya kemudian jadi lebih tajam: jenis kekerasan seperti apa yang paling alami buat kita?
Dalam sebuah makalah yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Sciences, antropolog Richard Wrangham membagi kekerasan manusia menjadi dua tipe utama: reaktif dan proaktif. Ini bukan cuma soal kapan kekerasan terjadi, tapi juga apa yang mendorongnya.
Kekerasan reaktif adalah jenis yang paling mudah dikenali—emosional, impulsif, meledak dalam situasi marah atau terancam. Jenis ini sering kita lihat dalam perkelahian jalanan atau amukan karena rasa cemburu, misalnya. Uniknya, Wrangham menunjukkan bahwa manusia justru lebih jarang menunjukkan kekerasan reaktif dibandingkan simpanse. Kita, katanya, sudah melalui proses “self-domestication” atau penyaringan evolusioner terhadap individu yang terlalu gampang marah atau sulit dikendalikan.

Sebaliknya, manusia punya kecenderungan yang jauh lebih besar melakukan kekerasan proaktif. Yakni, kekerasan yang direncanakan, dihitung, dan dilakukan dengan tujuan strategis. Ini termasuk perang, eksekusi, penyiksaan, atau pembunuhan yang dirancang sedemikian rupa untuk meraih kekuasaan atau sumber daya. Dalam konteks ini, "kebejatan" manusia bahkan melampaui kebanyakan hewan lain. Kita bukan cuma bisa membunuh, tetapi bisa merencanakannya dengan sangat efisien.
Wrangham juga mengusulkan satu teori yang disebutnya “paradoks eksekusi”. Ia berargumen bahwa, di masa lalu, masyarakat pemburu-pengumpul mungkin menggunakan hukuman mati sebagai alat untuk menyingkirkan individu yang terlalu agresif secara reaktif. Dengan kata lain, kita jadi “lebih jinak” sebagai spesies justru karena kita memilih untuk membunuh mereka yang terlalu meledak-ledak. Ini tentu menimbulkan dilema moral karena kedamaian yang kita rasakan merupakan hasil dari tindak kekerasan.
Dari sini, terlihat bahwa kekerasan bukan satu bentuk tunggal. Ada yang lahir dari emosi spontan, ada pula yang tumbuh dari perhitungan dingin. Celakanya, justru yang terakhir inilah yang lebih kuat melekat pada manusia.
Nikmatnya Melakukan Kekerasan
Sampai di titik ini, kita sudah bicara soal kekerasan sebagai strategi bertahan hidup, sebagai warisan evolusi, dan sebagai reaksi emosi. Tapi ada satu sisi lagi yang sering tidak nyaman untuk diakui: rasa nikmat yang bisa muncul dari kekerasan itu sendiri.
Sebuah eksperimen yang dilakukan pada tikus jantan menunjukkan bahwa perilaku agresif bisa memicu aktivasi area otak yang sama dengan yang aktif saat hewan itu mendapat makanan, seks, atau zat adiktif. Dengan kata lain, melakukan kekerasan bisa terasa menyenangkan. Para tikus bahkan menunjukkan perilaku mencari-cari situasi untuk bertarung lagi; bukan karena lapar atau terancam, tapi karena otak mereka mengasosiasikan kekerasan dengan reward.
Studi tersebut bukan studi tentang manusia, tetapi sistem dopamin dan pusat kenikmatan di otak mamalia bekerja dengan prinsip yang mirip. Artinya, sangat mungkin bahwa manusia juga menyimpan jejak biologis serupa.
Ini bukan berarti manusia tidak punya kontrol. Justru, bagian penting dari peradaban adalah kemampuan kita untuk mengatur dan mengarahkan impuls-impuls seperti ini. Dalam kondisi normal, kebanyakan orang tidak akan bertindak agresif hanya karena itu terasa menyenangkan. Ada norma, ada etika, ada hukum, dan manusia juga memiliki rasa empati pada orang lain.
Dengan kata lain, meskipun ada kemungkinan bahwa kekerasan bisa terasa "rewarding" bagi otak, manusia juga dilengkapi dengan kemampuan untuk berkata tidak pada godaan-godaan tersebut.
Budaya, Lingkungan, dan Variasi Manusia
Satu hal yang menarik dari semua penelitian ini adalah kesimpulan bahwa kekerasan bukan sesuatu yang muncul secara seragam dalam sejarah manusia. Tidak semua masyarakat, tidak semua waktu, dan tidak semua tempat memperlihatkan pola kekerasan yang sama.
Para peneliti mencatat bahwa manusia purba tidak selalu bersifat agresif. Kekerasan cenderung meningkat bersamaan dengan pertumbuhan kompleksitas sosial dan tekanan atas wilayah. Artinya, semakin besar kelompok manusia, semakin kompleks struktur kekuasaan, dan semakin tinggi kompetisi atas sumber daya, semakin besar pula peluang konflik.
Perbedaan ini tampak jelas jika kita melihat masyarakat pemburu-pengumpul. Ada kelompok seperti !Kung San di Afrika Selatan yang dikenal relatif damai dan menghindari kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, ada juga masyarakat seperti Yanomami di Amerika Selatan yang sering terlibat dalam konflik antarklan dan serangan balas dendam. Kedua kelompok ini sama-sama “primitif” secara teknologi, tapi sangat berbeda secara budaya.

Antropolog Robert Sussman adalah salah satu tokoh yang menentang pandangan bahwa manusia purba itu pada dasarnya agresif. Ia percaya bahwa nenek moyang manusia justru cenderung hidup kooperatif, berbagi makanan, merawat anak secara kolektif, dan memilih menghindari konflik daripada berkelahi. Menurutnya, kerja sama adalah strategi bertahan hidup yang jauh lebih efisien di lingkungan yang keras.
Namun pandangan ini bukan tanpa sanggahan. Raymond C. Kelly, antropolog lainnya, berargumen bahwa terobosan teknologi seperti lemparan tombak atau alat berburu jarak jauh justru membuka pintu bagi kekerasan terencana. Begitu manusia bisa menyerang dari jauh, tanpa risiko langsung, maka konsep serangan mendadak terhadap kelompok lain alias raiding menjadi lebih menarik dan lebih sering terjadi.
Peran Budaya dan Institusi
Pada bagian sebelumnya, kita sudah melihat bahwa kekerasan punya akar biologis dan evolusioner. Namun, akar bukanlah takdir. Sama seperti manusia bisa belajar membaca, berlari maraton, atau memainkan alat musik, kita juga bisa belajar untuk tidak menyakiti. Dan di sinilah budaya mengambil peran penting.
Budaya, dalam arti luas—dari norma sosial hingga sistem hukum—adalah alat penyalur dan pengendali impuls dasar kita. Ia tidak menghapus kecenderungan biologis, tapi bisa membentuk ke mana arahnya. Seperti jalan air: kekuatan alirannya tetap sama, tapi kita bisa menggali saluran baru untuk mengalirkannya ke tempat tertentu.
Penulis dan psikolog kognitif Steven Pinker pernah menulis buku setebal lebih dari 800 halaman untuk membahas ini. Dalam The Better Angels of Our Nature, ia mengklaim bahwa, sepanjang sejarah, kekerasan justru mengalami penurunan drastis berkat perkembangan institusi sosial, negara hukum, sistem pendidikan, dan nilai-nilai moral yang lebih inklusif. Kekerasan massal, penyiksaan publik, bahkan pembunuhan per kapita, semuanya menurun jika kita lihat dalam skala abad.
Meski sebagian ilmuwan menilai tesis Pinker terlalu optimistis, ia tetap menyodorkan satu poin penting bahwa evolusi budaya bisa melampaui evolusi biologis.
Pendidikan, misalnya, mampu menumbuhkan empati dan mengajarkan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Lembaga hukum memberi sanksi pada perilaku agresif. Agama, filsafat, dan seni turut menciptakan narasi tentang belas kasih, pengampunan, dan perdamaian. Bahkan hal-hal yang tampak kecil—seperti etika sopan santun di ruang publik—berkontribusi dalam mengurangi ketegangan yang bisa berujung kekerasan.
Dengan kata lain, meskipun manusia punya kapasitas untuk bertindak kejam, kapasitas itu bisa ditekan, diarahkan, atau bahkan digantikan oleh cara-cara yang lebih manusiawi, asal budaya dan sistem sosialnya mendukung.
Kita bukan simpanse, bukan pula bonobo. Kita bisa memilih untuk berperang, tapi kita juga bisa memilih untuk berdamai. Kekerasan memang ada dalam repertoar manusia, tapi begitu juga dengan empati, kerja sama, kasih sayang, dan keinginan untuk hidup damai. Evolusi memberi kita kemampuan untuk marah, tapi juga memberi kita otak yang bisa menimbang, menunda, dan memaafkan.
Sejarah telah menunjukkan bahwa tingkat kekerasan bisa berubah. Ia bisa meningkat dalam kondisi tekanan sosial, tapi juga bisa menurun ketika norma, hukum, dan institusi bekerja optimal. Dalam masyarakat yang kuat secara budaya dan adil secara struktural, kekerasan bukan hanya tidak perlu, ia bahkan menjadi sesuatu yang memalukan.
Maka, di sinilah letak keistimewaan manusia. Kita adalah spesies yang tidak hanya dibentuk oleh elemen-elemen biologis tetapi juga produk-produk kultural yang, pada akhirnya, menjinakkan tendensi kebinatangan dalam diri kita.
Penulis: Yoga Cholandha
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id