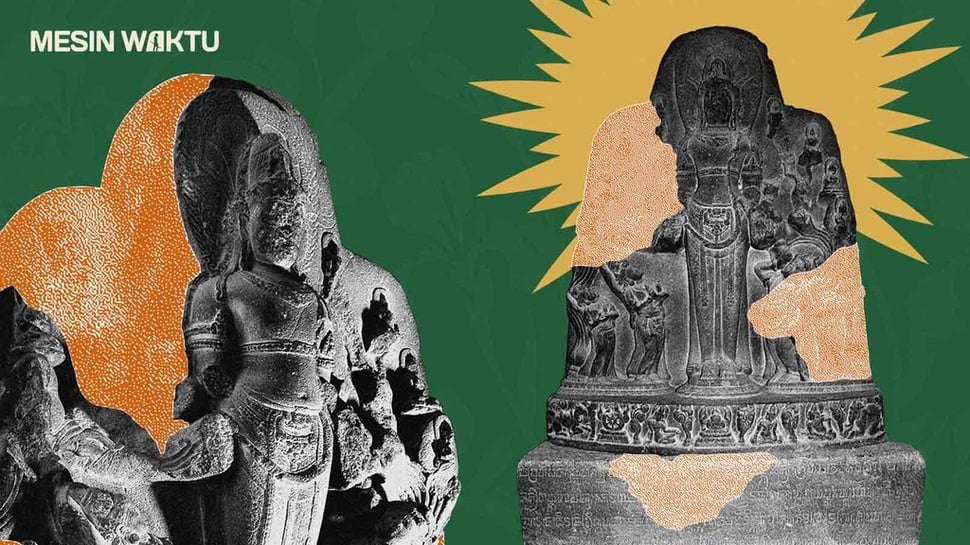tirto.id - Nusantara merupakan istilah yang amat familier dalam memori kolektif masyarakat Indonesia. Berasal dari khazanah sejarah masa Klasik, istilah Nusantara merangkum citra keagungan negeri dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Bahkan, meski mengandung bias Jawa, ia kini ditetapkan sebagai nama bakal ibu kota baru Indonesia yang tengah dibangun di Kalimantan.
Adalah Muhammad Yamin yang semula menggaungkannya dalam tulisan-tulisan sejarahnya yang terbit pada awal masa Kemerdekaan Indonesia. Dalam bukunya Gadjah Mada: Pahlawan Persatuan Nusantara (1945), Yamin mengaitkan cita-cita Nusantara dengan tokoh Gajah Mada sang Mahapatih Majapahit. Keduanya manunggal melalui Sumpah Palapa, sebuah cita-cita penyatuan seluruh pulau-pulau di Nusantara di bawah panji Majapahit.
Pada 1950-an, gagasan persatuan Nusantara itu lalu didiseminasikan kepada generasi muda melalui buku-buku sejarah di sekolah sebagai bagian dari cara membentuk karakter nasionalis warga Indonesia. Hingga kini, ia dikonstruksikan sebagai cita-cita besar yang mesti dicapai—atau malah dilampaui—oleh negara Indonesia modern.
Namun, retorika persatuan Nusantara ala Yamin yang terus diulang hingga kini ternyata juga menuai kritik. Konsep “negara” Majapahit tentulah tak bisa disamakan dengan pengertian negara modern. Klaim bahwa wilayah Majapahit meliputi hampir seluruh Asia Tenggara kepulauan dan penguasaan formal atasnya juga masih diperdebatkan.
Lain itu, G.J. Resink dalam Bukan 350 Tahun Dijajah (2012) tak tanggung-tanggung menyebut gagasan Nusantara yang digambarkan Yamin sebagai mitos dan romantisme berlebih.
Terlepas dari perdebatan-perdebatan itu, Nusantara sebagai gagasan ataupun cita-cita memang telah demikian melekat dalam benak masyarakat Indonesia. Ketika orang membicarakan persatuan negeri, rujukannya adalah Nusantara. Namun, kita mestinya tak sekadar berhenti di titik itu.
Pasalnya, tanpa pemahaman akan sejarah dan konteks kemunculannya, cita-cita Nusantara bakal jatuh jadi slogan kosong. Alih-alih jadi inspirasi, ia malah rawan menggiring kita pada fanatisme dan chauvinisme.
Pembaca, program Mesin Waktu seperti biasa akan mencoba mengurai hal itu dengan jalan kembali ke masa lalu. Kali ini, kita akan mencari jawabannya bersama Arca-Prasasti Amoghapasa tinggalan seorang leluhur raja-raja Majapahit.
Arca-Prasasti Amoghapasa
Leluhur raja-raja Majapahit yang dimaksud adalah Kertanagara. Pada 1208 Saka (1286 Masehi), raja terakhir dan terbesar Singhasari tersebut mengirim sebuah Arca Amoghapasa untuk Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa, raja Kerajaan Malayu yang berkuasa di Dharmasraya. Kini, arca bertulis tersebut disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.
Dalam sekilas pandang, ia terlihat sebagai arca tunggal. Namun, ia sebenarnya terdiri dari bagian arca dan lapik yang terpisah. Sebelum disatukan seperti sekarang, keduanya pun ditemukan secara terpisah di waktu berbeda.
Seturut laporan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschaapen, Arca Amoghapasa ditemukan pada 1884 di Rambahan (sekarang termasuk wilayah Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat). Sementara itu, bagian lapiknya di temukan pada 1911 di sekitar situs Percandian Padang Roco (kini masuk wilayah Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya).
![Arca Amoghapasa Lokeswara ditemukan tanpa lapik di daerah Rambahan, Dharmasraya, Sumatra Barat. (Sumber: Natasha Reichle [2007]) Arca Prasasti Amoghapasa](https://mmc.tirto.id/image/2023/12/08/arca-prasasti-amoghapasa-2.jpg)
Menariknya, Arca Amoghapasa tersebut rupanya juga menjadi media penulisan tiga inskripsi. Bahkan, setelah ditinjau, tiga inskripsi tersebut memiliki karakteristik dan angka tahun yang berbeda. Namun, sejauh ini, baru dua inskripsi yang telah dibaca dan dikaji oleh banyak ahli sejarah kuno. Inskripsi ketiga rupanya telah begitu aus sehingga sulit untuk pelajari.
Prasasti dengan tarikh tertua diterakan pada bagian lapik arca. Ia lazim disebut Prasasti Amoghapasa A atau Prasasti Padang Roco atau Prasasti Dharmasraya. Sang citralekha—pemahat prasasti—menoreh prasasti itu dalam aksara Jawa Kunodengan bahasa Jawa Kuno serta Sanskerta.
Ialah yang memuat kabar tentang hadiah Arca Amoghapasa oleh Sri Kertanagara. Disebutkan pula bahwa raja Singhasari itu mengutus empat pejabat tinggi kerajaan untuk mengantar langsung arca tersebut ke Swarnabhumi.
Dari informasi yang dibeberkan dalam prasasti, kita bisa menengarai bahwa pengiriman Arca Amoghapasa tersebut punya makna politik amat penting, setidaknya bagi Sri Kertanagara.
M.D. Poesponegoro dan N. Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuna (2010) menduga bahwa arca tersebut adalah “mahar” untuk memperkukuh persekutuan Jawa-Melayu. Persekutuan ini juga disebut-sebut merupakan bagian dari upaya Sri Kertanagara mewujudkan visi Dwipantara.
Dari Dwipantara hingga Nusantara
Makna Dwipantara sebenarnya belumlah terang betul. Secara harfiah, ia berarti “kepulauan antara” atau “kepulauan seberang”, nisbi serupa dengan istilah Nusantara.
Menurut Atina Winaya dalam “Cakrawala Mandala Dwipantara: Wawasan Kemaritiman Kerajaan Singhasari” (2018), Dwipantara merupakan wawasan geopolitik yang mendahului konsep Nusantara yang berkembang di zaman Majapahit.
Secara kronologis, pendapat Winaya cukup masuk akal. Istilah Dwipantara bisa dijumpai dalam Prasasti Camunda(atau Camundi) yang ditemukan di Desa Ardimulyo, Malang, Jawa Timur. Menurut pembacaan M. Suhadi dan R. Kartakusumah dalam Laporan Penelitian Epigrafi di Wilayah Provinsi Jawa Timur No. 47 (1996), prasasti ini memuat tarikh 1214 Saka (1292 Masehi) yang termasuk dalam masa kuasa Kertanagara.
Prasasti Camunda memuat baris bertulis, “Tatkala kapratisthan paduka bhatari maka tewek huwus sri maharaja digwijaya ring sakalaloka mawuyu yi sakala dwipantara.” Baris tersebut diperkirakan berkait dengan keberhasilan Raja Kertanagara menaklukkan “Dwipantara”.
Kita masih perlu meneliti lebih jauh, tapi baris tersebut jelas memberi kesan ekspansionistis bagi istilah Dwipantara. Kita juga masih perlu bertanya tentang negeri-negeri seberang mana saja yang dicakup oleh istilah Dwipantara karena Prasasti Camunda tidak menyebutkannya.
Petunjuk-petunjuk lain dapat dikail dari kakawin Nagarakertagamagubahan Prapanca. Ketika istilah Dwipantara muncul, Kertanagara tercatat telah beberapa kali mengirim ekspedisi keluar Jawa.Pada 1275 Masehi, Kertanagara mengirim pasukannya ke Sumatra untuk menundukkan negeri Melayu.
Kertanagara lalu menyerang dan menaklukkan Bali pada 1284 Masehi. Nagarakertagamajuga menyebut Pahang, Gurun, dan Bakulapura sebagai negeri-negeri yang “tunduk menekur di hadapan beliau”. Dalam nada yang agak sumir, begitu pula Tanah Sunda dan Madura.
Hingga pada 1286 Masehi, Kertanagara mengirim lagi pasukan dan delegasinya—dengan gestur lebih bersahabat—ke Sumatra untuk mengantarkan Arca Amoghapasa Lokeswara.
![Detail empat figur pengiring Amoghapasa. Kiri: Syamatara dan Sudhanakumara. Kanan: Bhrkuti dan Hayagriwa. (Sumber: Natasha Reichle [2007]) Arca Prasasti Amoghapasa](https://mmc.tirto.id/image/2023/12/08/arca-prasasti-amoghapasa-3.jpg)
Sejarawaan Slamet Muljana meyakini bahwa itu semua merupakan serangkaian upaya Kertanagara mewujudkan visinya tentang Dwipantara. Muljana sendiri dalam Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit (2012) menyebutnya Gagasan Nusantara Pertama—cita-cita penyatuannegeri-negeri seberang lautandi bawah panji Singhasari.
Yang terjadi selanjutnya adalah sejarah. Pada tahun yang sama dengan terbitnya Prasasti Camunda, Kertanagara menemui ajal yang tragisgara-garaserangan Jayakatwang dari Kediri. Seiring dengan tamatnya riwayat Kerajaan Singhasari, cita-cita Dwipantara pun turut tenggelam.
Namun, cita-cita politik itu tak benar-benar mati begitu saja. Trah Singhasari yang setelah itu mendirikan Majapahit rupanya masih merawat gagasan Sri Kertanagara sambil menunggu momentum yang tepat. Hingga akhirnya, ia dibangkitkan lagi dalam rupa cita-cita Nusantara yang diikrarkan oleh Patih Amangkubhumi Majapahit, Gajah Mada, pada 1334 Masehi.
Membendung Ancaman Kublai Khan
Lantas, apa yang membuat Sri Kertanagara merasa perlu melakukan ekspansi dan mempersatukan negeri-negeri seberang?
Untuk menjawab pertanyaan itu, Muljana dalam Tafsir Sejarah Nagarakretagama (2011) mengetengahkan keterangan yang diperolehnya dari kidung Panji Wijayakrama tentang watak ahangkara yang lekat pada diri Sri Kertanagara.
Menurut tafsir Muljana, ahangkaramerupakan kombinasi dari keangkuhan dan kesadaran penuh Kertanagara akan kuasa dan kekuatan politik yang digenggamnya. Itulah yang mendorongnya merombak total pemerintahan Singhasari warisan ayahnya, mendiang Raja Wisnuwardhana, segera setelah dia naik takhta.
Watak ahangkara pulalah yang mendasari Kertanagara melancarkan program politik ekspansionis yang nisbi belum pernah ada presedennya di masa para pendahulunya.
“Di antara raja-raja Singasari, Sri Kertanagara yang pertama-tama melepas pandangan ke luar Jawa. Ia meninggalkan politik tradisional yang berkisar pada Janggala-Panjalu. Ia ingin mempunyai kerajaan yang lebih luas dan lebih besar daripada sekadar kerajaan Janggala-Panjalu warisan Raja Erlangga,” tulis Muljana (2011).
Tak hanya itu, ambisi pribadi Kertanagara tersebut juga berkelindan dengan situasi regional Asia Tenggara. Kala itu, negeri-negeri Hindu-Buddha Asia Tenggara tengah dilanda kegusaran akibat ancaman dari utara.
Arahkan pandang ke cakrawala utara dan kau akan melihat apa yang Kertanagara lihat: tekanan Dinasti Yuan (Mongol) yang didirikan oleh Kublai Khan.

Bernard H.M. Vlekke dalam Nusantara: Sejarah Indonesia (2018) menyebut abad ke-13 sebagai Abad Mongol. Selama paruh pertama abad ke-13, Genghis Khan dan anak-cucunya menaklukkan negeri-negeri Eurasia dan menciptakan imperium yang membentang dari Rusia hingga Laut Tiongkok.
Pada 1260 Masehi, Kublai Khan mewarisi imperium besar itu. Ketika Kertanagara mengirim ekspedisi pertama ke Melayu pada 1275, Kublai Khan tengah berjibaku menundukkan seluruh Tiongkok di bawah kuasanya. Lain itu, dia mengincar pula negeri-negeri di selatan dan seberang lautan Tiongkok.
Dalam dekade 1280-an hingga 1290-anMasehi, Kublai Khan melancarkan kampanye militer ke Jepang dan negeri-negeri Hindu-Buddha di Asia Tenggara daratan.
“Mereka kurang berhasil, tapi sekadar fakta bahwa imperium Cina yang kuat tapi sebelumnya penuh damai tiba-tiba berubah jadi ekspansionis pastilah menimbulkan kegentaran di seluruh wilayah itu,” tulis Vlekke.
Ekspansi Kublai Khan itu juga merongrong ketenangan Kertanagara. Terlebih, antara 1280 dan 1287, militer Mongol dikabarkan telah merangsek ke negeri Annam dan Champa (kini Vietnam).
Kertanagara sadar bahwa ancaman Mongol itu hanya tinggal menunggu waktu saja untuk mendatangi Singhasari. Dan memang benar, utusan Mongol beberapa kali mendatangi Singhasari dan menuntut ketundukannya pada dekade 1280-an.
Kertanagara yang berwatak ahangkara tentu saja mengabaikan tuntutan-tuntutan itu. Namun, dia juga tak bisa menyepelekan ancaman Mongol begitu saja. Maka dai harus mencari cara terbaik untuk menangkis—atau setidaknya mengimbangi—tekanan Kublai Khan itu.
Menurut Vlekke, Kertanagara akhirnya mengambil dua langkah. Langkah pertama berdimensi spiritual, yakni dengan memperdalam Tantrayana untuk menandingi kualitas spiritual Kublai Khan. Langkah selanjutnya adalah konsolidasi politik dengan memperkuat “persatuan” Dwipantara.
Menurut Muljana,itulah konteks utama dari pengiriman Arca Amoghapasa Lokeswara ke Dharmasraya pada 1286 Masehi. Maka selain berdimensi politik, upaya itu juga punya nuansa spriritual.
“Pemberian hadiah arca itu boleh ditafsirkan sebagai pemberian çakti kepada raja Melayu. Pemberian çakti itu mengandung arti memperkokoh persahabatan untuk menghadapi kemungkinan serangan tentara Kubilai dari Tiongkok,” tulis Muljana (2012).
Resistensi Adityawarman
Dari Prasasti Amoghapasa A yang berasal dari Kertanagara, mari kita beralih pada Prasasti Amoghapasa B yang ditatahkan di balik stela Sang Amoghapasa. Selain berangka tahun lebih muda, ia juga ditulis dengan cara berbeda, yakni dalam aksara Sumatra Kuno dengan bahasa Sanskerta.
Sayangnya, menurut H. Kern dalam De wij-inscriptie op het Amoghapāça-beeld van Padang Candi (Batang Hari-districten); 1269 Çaka (1917), bahasa Sanskerta yang dipakai prasasti ini amat amburadul.
Hal itu terang menyulitkan proses penerjemahannya. Akibatnya, Kern dan para ahli epigrafi lain hanya bisa menebak maksud dari si penulis prasasti berdasar kata-kata Sanskerta yang tercantum padanya.
Menurut pembacaan Kern, Prasasti Amoghapasa B diterbitkan pada 1269 Saka (1347 Masehi) oleh Srimat Sri Udayadityawarman atau yang lebih populer dikenal sebagai Raja Adityawarman. Kita pun telah membahas tokoh ini saat meneroka asal-usul Arca Bhairawa dari Dharmasraya.
![Prasasti Amoghapasa B yang ditatah dibalik stela Arca Amoghapasa dari Rambahan. (Sumber: Natasha Reichle [2007]) Arca Prasasti Amoghapasa](https://mmc.tirto.id/image/2023/12/08/arca-prasasti-amoghapasa-4.jpg)
Prasasti Amoghapasa B sepenuhnya berisi puji-pujian terhadap Adityawarman. Beberapa diksinya juga memberi kita petunjuk akan unsur-unsur Buddhisme Wajrayana. Lebih dari itu, kita pun bisa menengarai suatu resistensi atas cita-cita persatuan Nusantara yang dicetuskan dari Jawa.
Petunjuk akan resistensi itu didapati para ahli epigrafi dari selipan informasi soal ritual penyucian kembali Arca Amoghapasa oleh Acarya Dharmasekhara.
Menurut Uli Kozok dan Eric van Reijn dalam "Adityawarman; Three Inscriptions of the Sumatran 'King of All Supreme Kings'" (2010), ritual penyucian kedua yang dilakukan pada 1347 Masehi itu berkenaan dengan deklarasi kemerdekaan Kerajaan Dharmasraya dari hegemoni Jawa.
Tak hanya itu, Adityawarman juga memindahkan Arca Amoghapasa tersebut dari tempat asalnya berdiri tanpa mengikutsertakan lapik arca yang bertulis prasasti dari Sri Kertanagara. Itu jelaslah bukan suatu ketaksengajaan, melainkan langkah politik Adityawarman membongkar tatanan lama bikinan Kertanagara.
“Pesannya jelas: Adityawarman tidak mau menyandang gelar maharaja rendahan seperti [Tribhuwanaraja] Mauliwarmadewa, raja Melayu yang bertakhta pada 1286,” tulis Kozok dan van Reijn.
Dalam Prasasti Amoghapasa A, citralekha memang menggurat gelar maharajaatau “raja besar” bagi Tribhuwanaraja. Sementara itu, Sri Kertanagara disebutnya dengan gelarmaharajadhiraja alias “raja tertinggi di antara para raja”.
Dengan demikian, Prasasti Amoghapasa A jelasmenegaskan hierarki di antara dua penguasa itu. Bahwa dalam lingkungan politik Dwipantara atau Nusantara, Sri Kertanagara berkedudukan lebih tinggi daripada Tribhuwanaraja.
Karenanya, Adityawarman perlu menulis sebuah prasasti untuk menyatakan statusnya yang independen. Dalam Prasasti Amoghapas B, Adityawarman bahkan mendaku dua gelar sekaligus.
Gelar pertama adalah dewa tuhan yang diperkirakan sebagai pernyataan kedudukannya sebagai dewaraja. Gelar kedua yang dia cantumkan adalahmaharajadhiraja, persis benar dengan gelar Sri Kertanagara dalam Prasasti Amoghapasa A. Menurut Kozok dan van Reijn, langkah itu merupakan cara Adityawarman menyetarakan dirinya dengan sang Raja Dwipantara.
Langkah politik Adityawarman sebagai raja mandiri selanjutnya adalah memindahkan pusat kerajaannya ke lubuk jantung Minangkabau. Dasarnya adalah taktis belaka, yakni menghindari potensi konflik terbuka dengan Majapahit yang armadanya hilir mudik di pesisir timur Sumatra.
Penulis: Muhamad Alnoza
Editor: Fadrik Aziz Firdausi