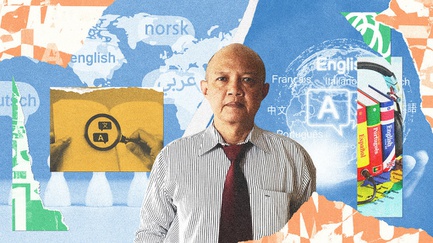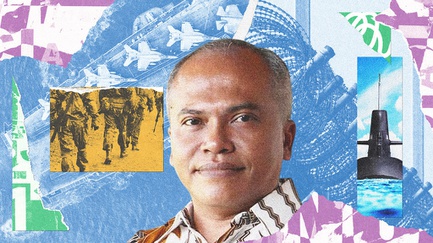tirto.id - Tragedi Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis brimob pada Kamis malam (28/8), menjadi titik balik yang menyulut kemarahan publik.
Keesokan harinya, protes menyebar ke berbagai titik terutama markas kepolisian seperti Mako Brimob dan Polda Metro Jaya. Kekacauan terus berlanjut hingga kemarin, Senin (1/9).
Di Jakarta situasi kacau. Sejumlah fasilitas umum seperti halte Transjakarta, jalan tol, dan lain sebagainya terbakar dan rusak. Gejolak ini juga terasa di dunia ekonomi. Pada Jumat (29/8), IHSG anjlok 1,53% dan rupiah melemah ke level Rp16.499,5 per dolar AS. Fenomena ini menunjukkan turunnya kepercayaan investor.
Situasi makin runyam ketika media sosial mulai dipenuhi provokasi rasial dan diskriminatif. Ramainya buzzer, akun anonim, hingga potongan video yang sengaja diplintir membuat protes politik bergeser menjadi konflik horizontal.
Kejutan lainnya adalah penjarahan terhadap rumah pribadi milik Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio yang dianggap sebagai sumber permasalahan demonstrasi di DPR pada Senin (25/8). Api kemarahan yang sama merembet ke kota-kota lain, dari Medan hingga Makassar. Merespon hal ini, pemerintah pada Sabtu malam (30/8) memutuskan pendekatan yang lebih “tegas” dengan mengerahkan aparat untuk membubarkan massa dengan kekerasan.
Dilema Eskalasi dan De-eskalasi
Negara memiliki semua instrumen untuk menggunakan pendekatan represif dengan dalih menjaga ketertiban, risiko dari eskalasi kekerasan justru sangat besar bagi stabilitas nasional. Namun, setiap tindakan yang berlebihan berpotensi memperluas kerusuhan, memperdalam amarah publik, dan memicu aksi balasan yang lebih destruktif. Bukannya meredam, kekerasan justru menciptakan lingkaran kekerasan baru.
Melihat risiko tersebut, de-eskalasi kekerasan bukan hanya soal moralitas, melainkan strategi rasional yang bertumpu pada tiga alasan utama, yaitu stabilitas ekonomi jangka panjang, legitimasi politik, dan interaksi langsung sebagai mediasi.
Hill (2006) dalam kajiannya mengenai krisis ekonomi Indonesia 1998 menegaskan bahwa pasar keuangan sangat sensitif terhadap sinyal meningkatnya otoritarianisme dan penindasan, yang meningkatkan kekhawatiran mengenai ketidakpastian kebijakan dan risiko terhadap hak milik.
Artinya, stabilitas ekonomi jangka panjang hanya dapat terjaga jika politik berlangsung stabil dan dapat diprediksi. Setiap langkah represif hari ini akan terbaca sebagai sinyal negatif, seakan-akan Indonesia kembali meluncur ke arah otoritarianisme.
Terkait legitimasi politik, Leach (2024) menekankan bahwa protes adalah bentuk demokrasi yang sah, mencerminkan kekuatan rakyat dalam menyoroti ketidakadilan yang menuntut koreksi penguasa. Legitimasi protes ini krusial. Protes yang dianggap sah secara moral maupun politik mampu menghimpun dukungan luas dan memicu perubahan sosial. Dalam konteks demonstrasi belakangan ini, publik memiliki legitimasi yang kuat, sehingga kekerasan aparat terhadap warga sipil hanya menorehkan trauma kolektif dan memperlemah legitimasi negara.
Adapun mengenai interaksi langsung sebagai strategi mediasi, Lacomba (2013) menyatakan bahwa interaksi yang berulang memungkinkan terbangunnya kepercayaan dan mengurangi pengeluaran untuk konflik, memfasilitasi de-eskalasi ketika para aktor memiliki insentif untuk bekerja sama.
Temuan ini selaras dengan pengalaman Pemerintah Daerah dalam meredam demonstrasi pada Jumat (29/8) kemarin, yang menunjukkan bahwa pendekatan personal lebih efektif.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi massa demonstran untuk menawarkan bantuan bagi korban kerusuhan sembari tetap menolak tindakan vandalisme. Sementara di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X menemui massa di Mapolda DIY, menyampaikan duka cita atas wafatnya Affan Kurniawan, dan menawarkan diri sebagai penghubung dengan pemerintah pusat.
Dua contoh di atas menegaskan bahwa kepemimpinan tatap muka jauh lebih efektif dalam meredakan ketegangan dibandingkan represi bersenjata.
Membaca Batas De-eskalasi Kekerasan
Meski De-eskalasi menawarkan solusi yang lebih damai, pendekatan ini tetap berisiko, ada potensi moral hazard jika pemerintah dianggap terlalu lunak, timbul anggapan bahwa kekerasan massa adalah cara efektif memaksa negara berkompromi. Ini berbahaya karena dapat menormalisasi aksi perusakan gedung pemerintahan dan fasilitas publik sebagai strategi politik.
Kemudian, kerugian materiil dan korban jiwa yang sudah terjadi memperlihatkan skala kerusuhan besar. Tanpa respon tegas, publik dapat menilai negara gagal melindungi warganya dan memberi kesan bahwa tindakan kriminal bisa dibiarkan.
Lalu, yang tidak kalah penting adalah dimensi digital yang ikut memperkeruh situasi. Kehadiran penyebar hoaks memelintir konten menciptakan ruang gema yang mempolarisasi masyarakat. Ketika kekerasan fisik berpadu dengan kekerasan digital, terbentuk spiral destruktif yang sulit dihentikan.
Terakhir, fragmentasi sosial yang tampak melalui serangan pada properti pribadi pejabat menandakan konflik yang makin terpersonalisasi. Jika tidak diantisipasi, de-eskalasi yang setengah hati bisa gagal meredakan konflik, dan malah memberi ruang bagi kekerasan horizontal yang lebih luas.
Strategi De-Eskalasi Terkalibrasi
Melihat kompleksitas situasi ini, de-eskalasi harus menjadi tindakan yang terukur dan bertahap, bukan sekadar kompromi. Strategi ini perlu menggabungkan pendekatan hukum, politik, dan sosial secara seimbang.
Setidaknya ada tiga komponen utama yang dapat menjadi pijakan.
Penegakan hukum selektif
Pemerintah perlu membedakan dengan jelas antara demonstran damai dan pelaku kriminal. Mereka yang hanya menyampaikan aspirasi perlu diberi ruang, sementara perusak fasilitas publik harus ditindak tegas. Pendekatan ini akan menegaskan bahwa negara tetap tegas, tetapi adil.
Konsesi substantif
Pemerintah perlu menunjukkan kesediaan untuk mendengar tuntutan rakyat dengan langkah nyata, misalnya meninjau ulang kebijakan kontroversial atau membentuk komisi independen untuk investigasi. Konsesi semacam ini penting agar dialog tidak dianggap basa-basi, tetapi berakar pada perubahan konkret.
Desentralisasi respon
Memberi ruang kepada gubernur dan pemimpin daerah untuk melakukan pendekatan sesuai konteks lokal terbukti efektif. Model kepemimpinan personal seperti yang dilakukan Dedi Mulyadi di Jawa Barat atau Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta dapat menjadi contoh. Dengan kewenangan dan fleksibilitas daerah, komunikasi dengan massa bisa lebih cair dan membumi.
Jika tiga komponen ini dijalankan dengan pemilihan waktu yang tepat, pemerintah dapat meredakan ketegangan tanpa kehilangan wibawa, sekaligus membangun legitimasi baru di mata publik maupun komunitas internasional.
Sintesis Krisis
Krisis pasca tragedi wafatnya Affan Kurniawan menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Pilihan yang diambil pemerintah akan menentukan arah apakah Indonesia akan tumbuh sebagai demokrasi yang dewasa, atau justru terperosok ke dalam lingkaran otoritarianisme.
De-eskalasi bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa negara cukup percaya diri untuk mengelola konflik tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar republik. Lebih jauh, krisis ini menyingkap pentingnya kepemimpinan politik yang mampu merangkul kearifan lokal sekaligus menjaga ketegasan negara.
Sintesisnya jelas, jalan kekerasan hanya akan memperdalam luka, sementara jalan de-eskalasi memberi kesempatan untuk membangun ulang kepercayaan, memperkuat legitimasi, dan meneguhkan komitmen bangsa terhadap demokrasi. Pilihan ini bukan sekadar soal taktik politik jangka pendek, melainkan soal arah masa depan republik.
Editor: Zulkifli Songyanan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id