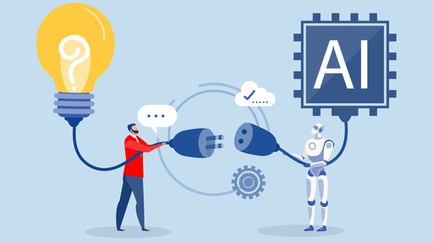tirto.id - Dengan menerapkan Nature-Based Solutions (NbS), kota Nagoya di Jepang berhasil menurunkan suhu udara hingga 1,9 °C dibandingkan wilayah sekitarnya. Penurunan ini dicapai melalui pembangunan taman di tengah kota, yang menjadi salah satu bentuk nyata penerapan NbS dalam tata ruang perkotaan.
NbS lahir dari kesadaran bahwa alam memiliki peran penting dalam mengatasi krisis lingkungan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh World Bank pada 2008, yang selanjutnya diperjuangkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Meski demikian, gagasan dasarnya sudah muncul sejak awal 2000-an melalui konsep adaptasi berbasis ekosistem. Menurut IUCN, NbS adalah tindakan melindungi, mengelola, dan memulihkan ekosistem alam, sekaligus memberi manfaat bagi manusia dan keanekaragaman hayati.
Artinya, NbS menawarkan cara baru untuk merespons tantangan krisis lingkungan dengan memanfaatkan ekosistem alam. Dengan pendekatan ini, alam tidak hanya dilihat sebagai korban eksploitasi, tetapi juga berperan sebagai aktor restorasi lingkungan bagi masa depan.
Bagaimana NbS Menanggulangi Krisis Lingkungan
Strategi NbS diakui secara global sebagai pendekatan inovatif untuk mengatasi krisis lingkungan. Strategi ini memanfaatkan kekuatan ekosistem, seperti tanaman, lahan basah, dan bahan alam lainnya untuk mengurangi risiko bencana.
Di sisi lain, penerapan NbS juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi karena dinilai lebih murah dan berkelanjutan.
Menurut laporan International Institute for Sustainable Development (IISD) pada 2021, NbS terbukti 42 persen lebih murah dibandingkan infrastruktur konvensional seperti beton. NbS juga memberikan 36 persen lebih banyak nilai sosial dan ekologis. Bahkan, setiap investasi satu dolar AS (USD 1) dapat menghasilkan manfaat sosial hingga 30 dolar AS (USD 30).
Bukti efektivitas penerapan NbS ini tampak jelas pada proyek restorasi Sungai Isar di Munich, Jerman. Pada awalnya, sungai ini mengalami tekanan besar akibat kanal yang terbuat dari beton dan meningkatnya risiko banjir yang dipicu pola hujan ekstrem serta pencairan salju di Pegunungan Alpen. Akibat peristiwa tersebut, pemerintah Bavaria mencatat peningkatan volume aliran sekitar 25 persen sebagai dampak perubahan iklim.

Sebagai penanggulangan, Pemerintah Munich memilih pendekatan NbS, alih-alih hanya memperkuat tanggul dengan beton masif. Proyek Isar-Plan (2000–2011) diproyeksikan dengan memperlebar aliran sungai dan menambahkan elemen alami seperti batu kerikil dan kayu-kayuan. Pendekatan NbS memperkuat struktur sungai, sekaligus mendukung vegetasi tetap tumbuh.
Hasilnya, risiko banjir menurun dan keanekaragaman hayati meningkat. Pertumbuhan keanekaragaman hayati ini ditandai dengan kembalinya spesies ikan asli dan tumbuhan riparian (tumbuhan yang hidup dan berkembang di tepi sungai). Burung air, amfibi, dan serangga seperti capung juga mulai berkembang.
Di sisi lain, kota tersebut juga memperoleh ruang publik hijau yang memperkaya kualitas hidup warganya.
NbS menawarkan pendekatan efektif untuk mengatasi penurunan kualitas hidup di perkotaan akibat Urban Heat Island (kenaikan suhu kota yang berlebihan dibanding perdesaan).
Sebagai contoh, Medellín, kota besar di Kolombia, menjadi contoh lain transformasi kota melalui penerapan NbS.
Kota yang dulu dikenal sebagai kawasan kota bersuhu udara tinggi ini memulai proyek Green Corridors pada 2016. Pemerintah Kolombia menanam sekitar 880.000 pohon dan 2,5 juta tanaman di 30 koridor hijau sepanjang 20 kilometer.
Koridor ini menghubungkan jalan utama, jalur sepeda, tepi sungai, dan ruang publik. Koridor hijau ini membentang membentuk jaringan hijau yang meresap ke seluruh kota.
Hasilnya terlihat jelas dalam tiga tahun. Pada 2019, suhu udara rata-rata di sekitar koridor turun 4,5°C, dari yang sebelumnya 31,6°C menjadi 27,1°C.
Sementara itu, suhu permukaan jalan dan trotoar berkurang lebih dari 10°C, dari 40,5°C menjadi 30,2°C.
Medellín kini menjadi rujukan global tentang bagaimana kota di negara berkembang dapat mengatasi urban heat melalui NbS.
Kota-kota di Indonesia yang menghadapi masalah serupa, seperti Jakarta dapat mencontoh strategi penerapan NbS. Sebab, dalam 30 tahun terakhir, fenomena UHI telah memberikan dampak yang signifikan, terutama di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Medan, Surabaya, Makassar, dan Bandung.
Peningkatan suhu di wilayah perkotaan begitu tinggi sehingga kota-kota tersebut masuk dalam 20 persen wilayah dengan Land Surface Temperature (LST)/suhu permukaan tanah tertinggi.
Urgensi pengendalian suhu kota semakin meningkat mengingat Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan Paris melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi hingga 31,89 persen sebagai bagian dari langkah menuju pencapaian net zero emissions (NZE) pada 2060 atau lebih awal.
Maka itu, integrasi NbS dalam tata kota tidak hanya relevan secara ekologis, tetapi juga strategis dalam memenuhi komitmen global dan meningkatkan kualitas hidup perkotaan secara berkelanjutan.
Hambatan Penerapan NbS
Meski NbS mulai dipertimbangkan sebagai pendekatan untuk mengurangi krisis lingkungan, penerapannya sering kali tidak mudah.
Sebuah studi dalam Journal of Environmental Management pada 2020 mengidentifikasi tiga hambatan utama, yaitu faktor politik, kelembagaan, dan pengetahuan.
Pertama, hambatan politik muncul karena lemahnya regulasi dan kebijakan yang mendorong NbS.
Banyak kota belum memiliki aturan atau insentif yang memprioritaskan pendekatan berbasis alam.
Selain itu, siklus politik yang pendek membuat fokus pemerintah mudah berubah. Pergantian kepemimpinan sering menghambat kelanjutan program jangka panjang.
Kedua, hambatan penerapan NbS juga datang dari birokrasi kelembagaan yang terfragmentasi. Kelembagaan di pemerintah cenderung terpecah belah, menyulitkan koordinasi antarsektor.
Padahal, NbS memerlukan sinergi antara sektor lingkungan, perencanaan kota, dan infrastruktur. Banyak lembaga juga kekurangan sumber daya manusia dan kapasitas teknis untuk merancang proyek NbS.
Terakhir, hambatan pengetahuan juga menjadi tantangan besar lainnya. Riset tentang NbS terus berkembang, tetapi sulit diterapkan di lapangan.
Minimnya peran pengetahuan membuat kesenjangan antara sains dan kebijakan semakin besar.
Faktor-faktor hambatan dalam penerapan NbS tersebut berkontribusi besar terhadap lambatnya perwujudan tata kota yang berkelanjutan.
Padahal implementasi NbS menuntut kerangka kebijakan yang konsisten, koordinasi antarlembaga yang efektif, serta sumber daya manusia yang mampu menjembatani antara pengetahuan dan praktik.
Tanpa perbaikan menyeluruh pada aspek-aspek ini, NbS berpotensi tetap menjadi wacana konseptual tanpa dampak signifikan terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan.
Penulis: D'ajeng Rahma Kartika
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id