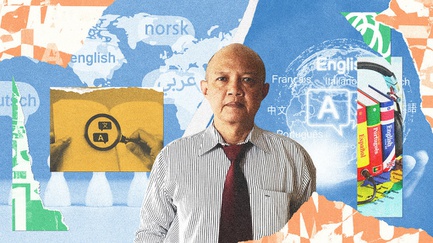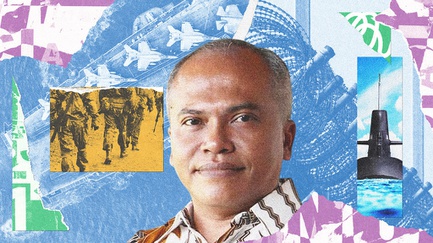tirto.id - Rojali sedang ramai diperbincangkan. Ia bukan nama orang, tetapi akronim dari Rombongan Jarang Beli, merujuk pada perilaku konsumen yang jamak ditemui di mal atau pusat perbelanjaan belakangan ini.
Mal di kota besar terlihat ramai, pengunjung berseliweran, tetapi transaksi tak sebanding dengan keramaian yang tampak. Banyak orang menafsirkan fenomena rojali sebagai tanda anjloknya daya beli masyarakat. Benarkah demikian?
Secara makro, data menunjukkan daya beli memang melemah, terutama di kalangan menengah ke bawah. BPS mencatat deflasi 0,37 % pada Mei 2025 dibandingkan bulan sebelumnya, menandakan permintaan konsumsi melemah. Indeks Harga Konsumen turun tipis dari 108,47 pada April menjadi 108,07 Mei. Inflasi tahunan hanya 1,60 %, jauh di bawah target 3–4 %.
Sementara kelas menengah atas belum kehilangan daya beli sepenuhnya, pola konsumsi mereka berubah. Alih-alih menghabiskan uang untuk barang-barang gaya hidup, mereka lebih suka mengalokasikan dana ke investasi—emas, deposito, hingga surat utang negara. Mal tetap mereka kunjungi, tetapi belanja dilakukan lebih selektif.
Bukan Barang Baru
Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum istilah “Rojali” populer di TikTok atau Instagram, kita sudah mengenal perilaku serupa. Pada masa krisis ekonomi atau menjelang akhir tahun, banyak orang datang ke mal hanya untuk “cuci mata”. Showrooming, mencari inspirasi fesyen, atau sekadar merasakan suasana modern tanpa harus bertransaksi adalah pola yang berulang.
Bedanya, kini intensitasnya meningkat, didorong oleh pandemi dan perubahan perilaku digital: orang lebih banyak berbelanja daring, sementara mal menjadi tempat rekreasi, bukan lagi pusat belanja utama. Kaum urban membutuhkan pelarian dari hiruk pikuk kehidupannya.
Meminjam konsep ruang ketiga yang dicetuskan Ray Oldenburg, mal menjadi salah satu ruang ketiga di mana warga kota bisa melepaskan diri dari kepenatan rutinitas di ruang pertama (rumah) dan ruang kedua (kantor/sekolah).
Mal menawarkan sesuatu yang tak mampu diberikan ruang kota: kenyamanan, kebersihan, fasilitas, keamanan. Di mal, orang bisa duduk tanpa terganggu lalu lintas, mengakses Wi-Fi, atau sekadar menikmati pendingin udara. Mal akhirnya menjadi ruang publik alternatif bagi warga kota.
Konsep ini sejatinya tak jauh dari Agora. Agora bukan sekadar nama mal baru di bilangan Jakarta Pusat, tetapi sebuah istilah di masa Yunani kuno yang merujuk pada ruang publik terbuka tempat warga berkumpul, berdiskusi, dan membangun kehidupan bersama. Agora lebih dari pusat perdagangan; ia adalah panggung sosial dan politik.
Jika kita tarik paralel, mal masa kini menjadi semacam Agora modern: tempat interaksi terjadi, meski orientasinya lebih komersial daripada kultural. Namun, perbedaan mendasar tetap ada: agora kuno adalah milik publik, sedangkan mal adalah ruang privat yang mensyaratkan perilaku konsumtif, meskipun tak semua orang menuruti syarat itu, Rojali misalnya.
Menghadirkan Kembali Agora
Di sinilah peran pemerintah menjadi penting. Kota tak boleh menggantungkan ruang sosialnya pada mal semata. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang membuka lima taman kota selama 24 jam adalah langkah yang patut diapresiasi. Ia terinspirasi oleh kota-kota dunia seperti London dan New York, yang menghidupkan taman sebagai ruang publik sejati.
Apakah semua orang akan langsung tertarik menghabiskan waktu di taman? Tentu tidak. Budaya itu tidak tumbuh semalam. Namun, membuka akses adalah langkah awal yang akan menumbuhkan kebiasaan. Jika orang mulai terbiasa jogging malam, membaca di ruang hijau, atau sekadar duduk bersama komunitas atau keluarga di taman, perlahan mal bukan lagi satu-satunya pelarian.
Tentu saja, menyediakan taman saja tidak cukup. Pemerintah perlu melengkapinya dengan fasilitas yang membuat orang betah: bangku yang nyaman, kamera pemantau (CCTV), penerangan memadai, akses Wi-Fi gratis, hingga ruang aman untuk kegiatan komunitas. Taman harus terasa aman, bersih, dan inklusif. Bukan hanya estetika visual, tetapi benar-benar fungsional bagi semua kalangan.
Fenomena Rojali seharusnya dibaca bukan sekadar soal ekonomi, melainkan soal ruang. Ia adalah sinyal bahwa orang mencari tempat untuk beraktivitas dan bersosialisasi, bukan semata untuk membeli. Jika mal adalah Agora swasta, tugas pemerintah adalah membangun Agora publik. Ruang kota yang tidak mensyaratkan daya beli, tetapi menyokong interaksi sosial, rekreasi, dan inklusivitas.
Jika pemerintah konsisten menyokong ruang publik seperti ini, secara bertahap taman kota bisa merebut kembali perannya sebagai ruang ketiga sejati. Tidak hanya mal yang ramai, tetapi ruang publik kota pun hidup sebagai alternatif bersama.
Editor: Zulkifli Songyanan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id