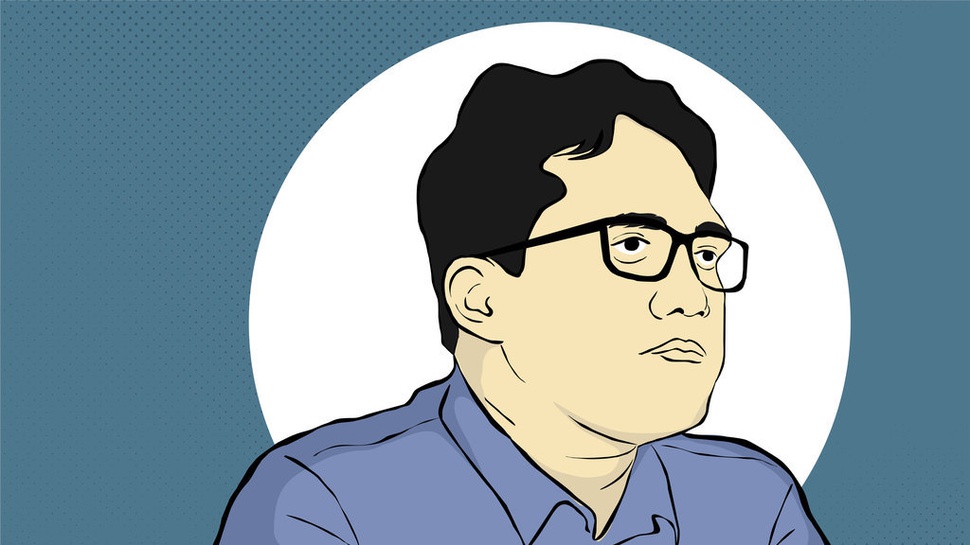tirto.id - Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, UU 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) zaman Soeharto diubah menjadi UU 17/2013. Namun Presiden Joko Widodo mengimitasi ulang era Orde Baru dengan mengeluarkan Perppu Ormas 2/2017 yang mengubah UU tersebut.
Poin utama dari Perppu Ormas tersebut, di antaranya, menghapus mekanisme peradilan dari pemerintah saat membubarkan sebuah ormas. Ini terjadi pada Hizbut Tahrir Indonesia, yang badan hukumnya dicabut lewat Kementerian Hukum dan HAM, Rabu lalu (19/07).
Perppu tersebut juga bisa mengancam kelompok yang dituduh melakukan “penodaan agama” dan gerakan politik damai yang gampang dicap “separatis” seperti di Papua dan Maluku, dua wilayah yang punya sejarah panjang gerakan pro-kemerdekaan.
Wahyudi Djafar, wakil direktur riset dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), menilai Perppu Ormas “tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum” yang menghendaki perlindungan kebebasan sipil.
“Keberadaan Perppu ini semata-mata memberikan legitimasi hukum bagi tindakan kekuasaan dari pemerintah. Sama seperti halnya ketika pemerintah Orde Baru mengatakan bertindak atas nama undang-undang,” ungkapnya, Kamis kemarin.
Ia menyatakan Perppu Ormas hadir untuk mengancam organisasi yang dianggap terlarang dan dituduh melakukan penodaan agama. Bahaya dari Perppu ini adalah “penyalahgunaan” untuk menggebuk kelompok minoritas.
“Sangat besar peluang Perppu ini menjadi 'bola liar' yang menyasar kelompok apa pun, karena batasan 'anti-Pancasila' juga luas,” ujarnya.
Simak perbincangan Wahyudi Djafar dengan Dieqy Hasbi Widhana dari Tirto mengenai konteks politik yang memunculkan perubahan UU Ormas. Sejumlah organisasi nonpemerintah termasuk Elsam pernah mengajukan evaluasi atas UU Ormas tahun 2013 itu ke Mahkamah Konstitusi. Hakim MK saat itu, Hamdan Zoelva, hanya mengabulkan sebagian pasal yang diajukan para pemohon, beberapa di antaranya sebatas pasal 29 mengenai kepengurusan.
Apa upaya dasar rezim Orde Baru membuat Undang-Undang 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan?
UU Ormas lahir pada periode terkuat kekuasaan Orde Baru, setelah selesainya periode konsolidasi pada satu dekade sebelumnya, yang ditandai fusi partai-partai politik menjadi hanya dua partai politik dan Golongan Karya.
Pada periode ini pula kelompok-kelompok oposisi terhadap Soeharto mulai menguat, sehingga Soeharto menyiapkan perangkat untuk mengontrol sekaligus menggebuk lawan-lawan politiknya. Caranya lewat 'wadah tunggal', sebagaimana fusi partai politik, sehingga kontrol dari penguasa saat itu lebih mudah dilakukan.
Mereka yang tidak masuk dalam 'wadah tunggal' akan dituduh melawan penguasa dan layak dibubarkan. Mereka juga harus berasaskan Pancasila dengan tafsiran Orde Baru. Sehingga mereka yang tidak berasaskan Pancasila, otomatis dituduh anti-Pancasila. Bahkan, dalam rangka kontrol ini, penguasa menempatkan orang-orangnya di dalam kepengurusan suatu organisasi, baik secara terbuka maupun bawah tangan.
Susilo Bambang Yudhoyono mengubah UU 8/1985 menjadi UU 17/2013. Poin apa yang kritis dari perubahan undang-undang tersebut?
Hampir semua organisasi masyarakat sipil, khususnya yang bergerak pada isu hak asasi manusia, demokratisasi, pemberdayaan, dan antikorupsi, mendesak agar pemerintah dan DPR mencabut UU Ormas. UU ini dinilai 'kelaminnya' tidak jelas, selain sarat kepentingan politik pemerintahan Orde Baru yang membentuknya.
Kenapa kelaminnya tidak jelas? Sebab dalam hal pengaturan organisasi masyarakat sipil, sebenarnya acuannya cukup dengan UU Yayasan dan UU Perkumpulan. Jadi sebaiknya pemerintah saat itu prioritasnya pada pembentukan UU Perkumpulan yang sampai saat ini rujukannya masih kepada regulasi peninggalan Hindia Belanda (Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum).
Dua undang-undang itu (UU Yayasan dan UU Perkumpulan) cukup sebagai tindak lanjut dari kewajiban negara untuk melindungi kebebasan berorganisasi, sebagaimana dimandatkan Pasal 28 dan Pasal 28E UUD 1945. Namun fakta politiknya lain. Justru pemerintah dan DPR masih menghendaki kontrol yang ketat terhadap organisasi masyarakat sipil, bahkan cenderung ingin mengintervensi.
Saat itu memang marak desakan kepada pemerintah untuk melakukan penegakan hukum, bahkan pembubaran, terhadap organisasi kemasyarakatan yang gemar melakukan tindakan kekerasan. Jadi alasan itulah yang kemudian digunakan oleh pemerintah dan DPR untuk tetap mempertahankan keberadaan UU Ormas.
Sayangnya, setelah UU baru disahkan, penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan yang gemar melakukan kekerasan tersebut tidak kunjung dilakukan.
Akhir tahun 2013 beberapa LSM berbasis HAM dan transparansi anggaran mengajukan evaluasi yudisial ke MK. MK lantas mengabulkan sebagian permohonan. Apa Anda puas dengan hasilnya?
Puas tentu tidak, karena beberapa materi kunci yang diujikan, seperti tentang definisi dan alasan pelarangan Ormas, tidak sepenuhnya dikabulkan oleh MK. Namun putusan ini layak diberikan apresiasi. MK telah berupaya memastikan tegaknya pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi, sebagaimana dimandatkan konstitusi. Setidaknya putusan ini bisa menjadi sandaran dalam melakukan perbaikan pengaturan tata kelola organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
Membaca pertimbangan hukum putusan tersebut, MK juga tidak menutup peluang lahirnya UU Perkumpulan sebagai acuan dalam mengatur organisasi yang berbasis anggota. Secara umum, dalam pertimbangannya, MK menegaskan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi, merupakan jantung dari sistem demokrasi, oleh karena itu negara tidak diperkenankan untuk campur tangan terlalu jauh. Apalagi melakukan tindakan pembatasan yang sifatnya eksesif, dapat berakibat pada terganggunya pelaksanaan hak tersebut.
Seluruh tindakan pembatasan terhadap pelaksanaan hak ini mesti mengacu pada kerangka pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta prinsip-prinsip pembatasan yang diatur dalam hukum internasional hak asasi manusia.
Soal Hizbut Tahrir Indonesia, Presiden Jokowi enggan melakukan dialog atau mengedepankan sikap persuasif. Itu terkait penafsiran atas Pancasila secara sepihak, karena melalui Perppu 2/2017, pencabutan badan hukum ormas tak perlu lewat pengadilan.
Meskipun kebebasan berserikat merupakan salah satu hak yang dapat dibatasi, tetapi sebagian ahli berpendapat bentuk-bentuk pembubaran merupakan bentuk pembatasan yang paling kejam. Sehingga harus ditempatkan sebagai upaya terakhir.
Ketentuan Pasal 22 ayat (2) ICCPR menyatakan kebebasan berserikat adalah bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights) sepanjang hal itu diatur oleh undang-undang (prescribed by law), dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis demi kepentingan keamanan nasional (national security) atau keamanan publik (public safety), ketertiban umum (public order), perlindungan akan kesehatan atau moral publik, atau atas dasar perlindungan akan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.
Selain itu, tindakan pembubaran juga harus sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip due process of law, sebagai pilar dari negara hukum, di mana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya.
Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel, kedua belah pihak—pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran—harus didengar keterangannya secara berimbang (audi et alteram partem) serta putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan lebih tinggi.
Tindakan pembubaran melalui pengadilan juga hanya bisa ditempuh setelah seluruh upaya lain dilakukan, dari peringatan, penghentian kegiatan, sanksi administratif, hingga pembekuan sementara. Hal ini juga sebagaimana diatur ketentuan Pasal 60-78 UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Artinya, pemerintah tidak memiliki hak absolut untuk melakukan pembubaran suatu organisasi, dengan dasar alasan apa pun, di sini berlaku sistem checks and balances.
Maina Kiai, mantan Pelapor Khusus PBB untuk hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, menyatakan pembubaran organisasi secara paksa merupakan bentuk pembatasan akan kebebasan berserikat yang paling kejam. Oleh karenanya, langkah semacam ini hanya dapat dimungkinkan ketika ada bahaya yang jelas dan mendesak yang mengakibatkan adanya pelanggaran yang cukup parah terhadap hukum nasional suatu negara.
Dalam melaksanakan tindakan ini, perlu ditegaskan perihal pentingnya peran pemerintah untuk menjamin proporsionalitas dari tindakan yang dilakukannya tersebut. Agar langkah yang dilakukan berkesesuaian dengan tujuan yang sah yang ingin dicapai, serta pelaksanaan langkah semacam ini hanya dimungkinkan sepanjang langkah-langkah lunak atau softer measures sudah dianggap tidak mampu mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi yang hendak dibubarkan tersebut.
Seperti apa Anda memandang subjektifitas pemerintahan Jokowi terkait unsur kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum, atau UU yang ada tidak memadai hingga harus terbitkan Perppu Ormas?
Secara teoritis, sebuah Perppu hanya dapat dikeluarkan karena suatu keadaan bahaya atau karena alasan-alasan yang mendesak, sementara proses legislasi di DPR tidak dapat dilaksanakan. Sehingga atas dasar keyakinan itu, presiden dapat mengeluarkan peraturan yang materinya setingkat dengan undang-undang.
Meskipun unsur “kegentingan yang memaksa” merupakan penilaian yang subjektif dari presiden, sesuai tuntutan mendesak dari dalam pemerintahannya untuk bertindak secara cepat dan tepat, tetapi mestinya ada kacamata objektif yang menjadi acuannya.
Putusan MK No. 145/PUU-VII/2009 misalnya memberikan tiga syarat objektif atas frasa kegentingan yang memaksa: adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai; kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Sementara UU Ormas (UU No. 17/2013) sesungguhnya sudah sangat detail mengatur proses pembubaran suatu organisasi. Dari mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan.
Artinya, alasan kekosongan hukum tidak terpenuhi di situ, karena sejatinya pemerintah tinggal menjalankan saja mandat UU Ormas. Bahkan dalam rezim hukum internasional, unsur kegentingan memaksa atau keadaan darurat ini lebih banyak: adanya ancaman bagi kehidupan bangsa dan eksistensinya; mengancam integritas fisik penduduk baik di semua atau sebagian wilayah; mengancam kemerdekaan politik atau integritas wilayah; terganggunya fungsi dasar dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga memengaruhi kewajiban perlindungan hak-hak warga negara; keadaan darurat dinyatakan secara resmi melalui sebuah deklarasi keadaan darurat; ancamannya bersifat aktual atau akan terjadi; tindakan pembatasan diizinkan untuk pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum, dan bersifat temporer atau dalam periode waktu tertentu.
Menurut Anda mengapa DPR harus menolak Perppu Ormas agar tak jadi Undang-Undang?
Penilaian subjektif atas keluarnya sebuah Perppu ada pada presiden. Sedangkan penilaian objektif akan diberikan DPR ketika Perppu telah diajukan sebagai rancangan undang-undang kepada DPR, untuk kemudian ditolak atau ditetapkan menjadi undang-undang.
Terhadap Perppu Ormas, kenapa DPR harus menolaknya? Karena mestinya DPR konsisten dengan materi UU Ormas yang dihasilkannya. Perppu ini menghapus banyak sekali ketentuan UU Ormas, khususnya yang terkait dengan mekanisme dan prosedur pembubaran suatu organisasi.
Padahal rumusan aturan mengenai prosedur pembubaran yang harus melalui jalur pengadilan ini merupakan pembeda utama antara UU Ormas saat ini dan UU Ormas masa Orde Baru. Kalau ketentuan itu dihapuskan, lalu apa bedanya UU Ormas saat ini dengan UU No. 8/1985?
Rumusan demikian jelas memperlihatkan bahwa materinya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum atau the rule of law yang menghendaki adanya perlindungan kebebasan sipil. Keberadaan Perppu ini semata-mata memberikan legitimasi hukum bagi tindakan kekuasaan dari pemerintah atau rule by law. Sama seperti halnya ketika pemerintah Orde Baru mengatakan bertindak atas nama undang-undang.
Belum lagi ancaman pidana bagi anggota ormas yang dinyatakan terlarang, termasuk mereka yang dituduh melakukan penodaan agama, yang seringkali menyasar kelompok-kelompok agama minoritas. Tegasnya, sangat besar peluang Perppu ini menjadi 'bola liar' yang menyasar kelompok apa pun, karena batasan 'anti-Pancasila' juga luas.
Bagaimana seharusnya pemerintah melindungi hak warganya untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi?
Sebenarnya UUD 1945 sudah memberikan jaminan perlindungan yang sangat bagus bagi kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Belum lagi sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Juga UU No. 39/1999 tentang HAM, yang memberikan jaminan perlindungan menyeluruh bagi hak-hak asasi warga negara.
Artinya, pemerintah tinggal mengacu pada perangkat-perangkat tersebut dalam menyusun aturan-aturan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, termasuk dalam hal pembatasannya. Konsistensi terhadap perangkat-perangkat hak asasi tersebut akan sangat menentukan tegaknya hak asasi warga, sekaligus proses demokratisasi di Indonesia.
HTI adalah ormas yang strukturnya terkait Partai Pembebasan atau Hizbut Tahrir melalui jaringan internasional. Basis gerakannya dakwah non-kekerasan: menyebarkan pengaruhnya melalui pemikiran. Menurut Anda apa ada ormas yang lebih genting untuk dikontrol dan bisa jelaskan apa alasannya?
Tadi saya sempat singgung mengenai latar belakang revisi UU Ormas saat itu, terkait banyaknya organisasi kemasyarakatan yang gemar melakukan tindak kekerasan, atau bahkan menggunakan instrumen kekerasan sebagai bahasa komunikasi mereka sehari-hari.
Nah, semestinya proses penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok tersebut diutamakan, karena selain melanggar hukum, mereka juga seringkali melakukan tindakan yang mengoyak toleransi dan kebinekaan. Bahkan tidak hanya menggunakan UU Ormas, perangkat undang-undang yang lain pun bisa digunakan, seperti KUHP untuk menindak kekerasannya, maupun penggunaan pasal hate speech untuk menjerat mereka yang gemar menyebarkan ujaran kebencian.
Sementara terhadap organisasi-organisasi yang diduga terlibat dengan terorisme, tindakan pelarangan bisa dilakukan oleh pengadilan, bersamaan proses hukum terhadap pelaku terorisme. Sebagai contoh, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Jemaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia, bersamaan dengan putusan kasus Abu Dujana pada September 2015.
Termasuk pengadilan juga bisa menyatakan ISIS sebagai organisasi terlarang, ketika mereka yang didakwa melakukan tindak pidana terorisme, bisa dibuktikan sebagai anggota ISIS. Mekanisme UU Ormas tidak bisa menjerat kelompok-kelompok ini karena mereka sendiri tidak mengakui keberadaan negara atau pemerintah.
Dokumen 73 lembar beredar berisi matriks daftar nama pengurus, anggota, dan simpatisan HTI yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, dan akademisi. Data itu menyebar dengan cara memutus mata rantai siapa pembuat dan pengedarnya. Anda sendiri mengatakan sudah mendapat data itu dari “pihak tertentu.” Siapa yang harusnya bertanggung jawab atas bocornya data ini?
Kita seringkali dihebohkan dengan beredarnya data-data semacam itu, biasanya bertujuan untuk memprovokasi publik, menciptakan kegelisahan dan rasa saling curiga di tengah masyarakat. Bila melihat materinya yang sedetail itu, kemungkinan besar pendataan dilakukan oleh aparat negara, karena hanya mereka yang memiliki kemampuan sebesar itu. Tapi kalau pemerintah bukan yang membuat dan menyebarkannya, sebaiknya segera dibuat pernyataan terbuka untuk menyangkalnya, sehingga data-data itu bisa dibilang sebagai rumor semata. Karena kalau dibiarkan, potensi terjadi gesekan di masyarakat juga besar.
Apa akibatnya dokumen semacam ini, secara sengaja atau tidak, bocor ke publik?
Kekhawatiran paling besar dari beredarnya data-data itu ialah potensi terjadinya pengecualian, stigmatisasi, dan persekusi terhadap mereka yang diduga anggota HTI atau mereka yang dituduh simpatisan HTI. Kalau sampai situasi ini terjadi, negara akan sulit mengontrol serta mengendalikannya, dan itu berarti kita mengulangi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu.
Poin “mengulangi kesalahan masa lalu” bisa Anda jelaskan?
Hampir seluruh peristiwa persekusi yang terjadi di Indonesia bermula dari penyebaran identitas. Contoh menjelang pembantaian 1965-1966, ketika daftar nama beredar untuk kemudian ditindaklanjuti dengan persekusi.
Daftar nama mereka yang akan menjadi target penembakan dalam peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, atau menjelang peristiwa dukun santet pada 1999-2000. Kemudian yang terbaru penyebaran identitas mereka yang memposting status di media sosial, yang materinya dianggap menyinggung pihak atau kelompok tertentu, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan persekusi oleh anggota kelompok tersebut.
Bagaimana seharusnya Presiden Jokowi melindungi hak dasar orang-orang yang ia anggap bertentangan dengan pancasila?
Seseorang meyakini suatu paham atau pandangan tertentu itu bagian dari kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Negara tidak bisa kemudian mengintervensinya. Sehingga sulit juga untuk mengatakan seseorang anti-Pancasila sepanjang yang bersangkutan tidak mendemonstrasikan permusuhannya terhadap Pancasila.
Jika seseorang tersebut telah secara nyata mendemonstrasikan permusuhannya terhadap Pancasila, tindakan pidana bisa diterapkan, misalnya dengan mengacu kepada KUHP atau UU Lambang Negara. Jika permusuhan dilakukan oleh suatu kelompok, selain pidana terhadap pelakunya, organisasinya bisa diproses pembubaran melalui mekanisme UU Ormas.
Namun, meski orang-orang tersebut terbukti memusuhi atau anti-Pancasila, mereka masih tetap sebagai warga negara Indonesia, yang berhak atas seperangkat perlindungan dari negara. Oleh karenanya, pemerintah selaku pemangku kewajiban terhadap hak asasi warga negara juga harus tetap bertindak dalam koridor hukum dan hak asasi manusia, tidak kemudian melakukan pembiaran persekusi terhadap mereka yang dianggap anti-Pancasila.
Bagaimana seharusnya upaya pemerintah melindungi identitas warga negara?
Kaitannya dengan perlindungan identitas warga negara, acuannya sudah ada pada sejumlah undang-undang, misalnya UU Administrasi Kependudukan dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Tegasnya data pribadi seseorang tidak bisa dipindahtangankan tanpa persetujuan si pemilik data.
Sayangnya, memang Indonesia belum memiliki UU perlindungan data pribadi, yang secara jelas memberikan batasan tentang jenis data apa saja yang masuk kategori data sensitif dan harus dilindungi, seperti agama, orientasi seksual, afiliasi politik, dan sebagainya. Perlindungan identitas atau data pribadi warga negara sangat terkait erat dengan martabat atau dignity orang tersebut, oleh karenanya semestinya negara juga bisa secara penuh menegakkannya.
Penulis: Dieqy Hasbi Widhana
Editor: Fahri Salam