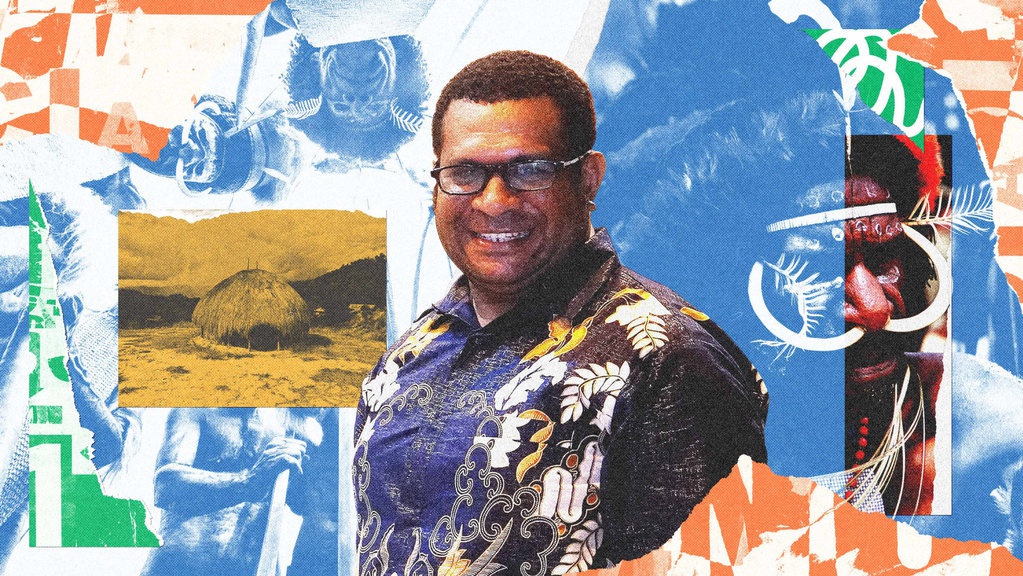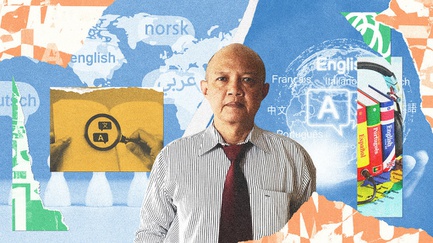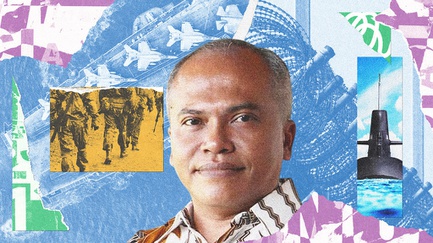tirto.id - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kebudayaan yang baru dibentuk, tengah menggagas penulisan ulang sejarah nasional. Inisiatif ini diklaim sebagai upaya membangun narasi kebangsaan yang lebih inklusif dan faktual, termasuk dengan melibatkan suara kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Namun, dalam konteks Papua, muncul pertanyaan krusial: apakah ini akan menjadi ruang pengakuan yang bermartabat atau justru menyulap luka lama dalam bahasa yang lebih halus?
Bagi banyak Orang Asli Papua, sejarah nasional Indonesia adalah sejarah yang ditulis dari luar dan untuk kepentingan di luar Orang Asli Papua sendiri. Sejarah itu lebih sering hadir dalam bentuk monolog negara, bukan dialog yang setara. Salah satu luka sejarah paling awal dan dalam bagi Orang Asli Papua adalah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Alih-alih referendum yang partisipatif, hanya 1.026 warga Papua atau sekitar 0,1% populasi yang kala itu ditunjuk untuk "berpendapat" di bawah tekanan militer. Ironisnya, proses yang oleh banyak kalangan disebut sebagai Act of No Choice ini tetap diajarkan di sekolah-sekolah sebagai wujud “kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi secara sah dan sukarela.”
Sementara negara terus mereproduksi narasi sejarah semacam itu melalui pidato resmi, buku pelajaran, dan simbol-simbol kebangsaan, testimoni masyarakat Papua tentang kekerasan, penggusuran, dan kehilangan ruang hidup terus berada di pinggiran wacana. Misalnya, kesaksian warga kampung Banti dan Opitawak di dekat area tambang Freeport yang pada 2017-2018 harus mengungsi akibat konflik bersenjata dan operasi militer, tidak pernah menjadi bagian dari narasi sejarah resmi. Dalam banyak dokumen negara, suara-suara ini bahkan dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas nasional, bukan sebagai bagian integral dari sejarah bangsa.
Jika sejarah adalah arena kuasa, maka eksploitasi sumber daya Papua menjadi bentuk dominasi struktural yang paling telanjang. Sejak akhir 1960-an, PT Freeport McMoRan dan kini PT Freeport Indonesia bersama BUMN mengoperasikan tambang emas dan tembaga raksasa di Mimika. Tambang Grasberg adalah salah satu yang terbesar di dunia, menyumbang sekitar 8% dari produksi emas global. Selain itu, proyek LNG Tangguh di Teluk Bintuni yang dioperasikan oleh PT British Petroleum (BP) Indonesia, kilang minyak Sorong, serta eksplorasi nikel di Kepulauan Raja Ampat dan Fakfak juga menjadi bagian penting dalam struktur energi dan ekonomi nasional.
Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) menunjukkan bahwa per Oktober 2024, penerimaan negara dari Tanah Papua mencapai Rp14,53 triliun—melebihi target APBN dan tumbuh lebih dari 56% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak sebesar Rp9,67 triliun menjadi salah satu yang tertinggi dari kawasan timur Indonesia. Namun, di balik angka ini, realitas kesejahteraan rakyat Papua jauh tertinggal.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada 2023 berada di angka 61,39—terendah dari semua provinsi di Indonesia. Provinsi Papua Pegunungan (pemekaran dari Papua) bahkan mencatatkan tingkat kemiskinan ekstrem lebih dari 25%.
Dalam dua dekade terakhir, alih-alih mengejar ketertinggalan, Papua malah menyandang status sebagai wilayah dengan lima hingga enam provinsi termiskin secara nasional. Ironi ini semakin menganga jika melihat bahwa Papua menyumbang triliunan rupiah dalam bentuk pajak, ekspor mineral, serta menjadi lokasi proyek-proyek strategis nasional.
Awal 2000-an menjadi titik balik ketika tuntutan referendum digaungkan kembali oleh berbagai organisasi masyarakat adat dan gereja, seperti Dewan Gereja Papua dan Dewan Adat Papua. Pemerintah meresponsnya dengan menawarkan status Otonomi Khusus (Otsus) sebagai solusi politik dan administratif. Dalam teori, Otsus menjanjikan kewenangan yang luas serta alokasi dana besar bagi daerah, bahkan mendekati 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional setiap tahun. Namun, setelah lebih dari dua dekade, dampaknya tetap jauh dari harapan.
Alih-alih membangun sistem pendidikan kontekstual atau layanan kesehatan yang berpihak, implementasi Otsus justru terjebak dalam birokrasi lemah, korupsi elit lokal, dan intervensi pusat yang tidak kunjung surut. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2018, korupsi dana Otsus menjadi salah satu kasus yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat Papua, tetapi penegakannya masih sangat minim. Banyak aktivis lokal menyebut Otsus sebagai "perangkap emas": tampak seperti hadiah, tapi mengikat dan membungkam aspirasi dasar masyarakat, termasuk soal kedaulatan tanah adat dan hak menentukan nasib sendiri.
Oleh karena itu, penulisan ulang sejarah nasional tidak bisa dilihat sebagai proyek teknokratik semata. Ia seharusnya menjadi momentum untuk membuka ruang dialog yang setara dan jujur, terutama menyentuh luka-luka sejarah yang selama ini dinafikan. Narasi sejarah yang menyembunyikan kekerasan negara, ketimpangan distribusi sumber daya, dan pengabaian terhadap sistem pengetahuan lokal hanya akan mereproduksi luka dalam wujud yang baru.
Sebagai bagian dari Orang Asli Papua yang tumbuh dan belajar dalam sistem akademik Indonesia maupun Eropa, saya ingin mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Kebudayaan dalam menggagas penulisan ulang sejarah. Ini bukan langkah kecil, mengingat kuatnya tradisi sentralistik dalam historiografi nasional kita. Namun, pembaruan ini hanya akan bermakna jika Papua tidak lagi hanya dituliskan, tetapi juga diberi ruang untuk menulis dirinya sendiri.
Sebab sejarah bukan sekadar kumpulan peristiwa, melainkan juga persoalan siapa yang punya kuasa untuk berbicara. Jika penulisan ulang ini ingin adil dan berdaya transformasi, maka suara para perempuan adat yang kehilangan ladang, kisah anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena konflik bersenjata, atau kesaksian warga kampung yang digusur demi pembangunan jalan tambang, harus menjadi bagian dari cerita besar Indonesia.
Papua bukan hanya lokasi tambang, proyek strategis, atau kawasan perbatasan. Ia adalah rumah bagi nilai-nilai budaya yang kaya, pengetahuan ekologis yang dalam, dan solidaritas sosial yang tahan uji. Penghormatan terhadap Papua harus dimulai dengan mengakui martabat Orang Asli Papua sebagai subjek sejarah bukan sekadar objek pembangunan.
Sejarah nasional bisa menjadi jembatan rekonsiliasi, tetapi hanya jika ditulis bersama, bukan dari atas. Menyusun ulang sejarah seharusnya bukan soal menambal celah narasi dominan, melainkan membongkar cara pandang yang selama ini menempatkan Papua di pinggir. Cinta pada bangsa tidak tumbuh dari rasa takut atau eksploitasi. Ia tumbuh dari kejujuran, pengakuan, dan penghormatan.
Jika Indonesia ingin dicintai oleh Orang Asli Papua, maka Indonesia harus terlebih dahulu belajar mencintai Papua bukan karena emas, gas, atau nikelnya, tetapi karena kemanusiaan yang melekat pada setiap warganya. Sejarah nasional yang baru harus memberi ruang bagi Papua untuk berkata: kami bukan hanya bagian dari Indonesia, kami adalah penulis sejarah itu sendiri.
Penulis adalah Mahasiswa Doktoral di Bonn International Graduate School – Oriental and Asian Studies, Universitas Bonn, Jerman.
Editor: Zulkifli Songyanan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id