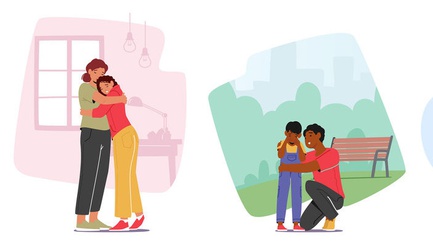tirto.id - Di Indonesia, kata numpang sering terdengar ringan dan jarang dipikirkan secara mendalam. Misalnya, orang numpang lewat, numpang tidur di rumah kawan, numpang mandi, bahkan numpang duduk; lema numpang terlontar secara spontan dan natural.
Padahal, di balik kata numpang, ada sesuatu yang lebih dari sekadar sopan santun. Ia mampu meleburkan batas antara milik pribadi dan milik komunal.
Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, rumah, atau arah tujuan, ia bisa numpang ke kawan atau keluarganya, dan itu bukan aib. Di warung kopi, di emper rumah, di grup WhatsApp RT, budaya numpang itu hidup dan berdenyut. Hal itu karena manusia mesti saling bergantung satu sama lain untuk bisa bertahan hidup.
Pada permukaannya, tindakan numpang tampak seperti transaksi sosial biasa, praktis, efisien, dan didasari oleh kedekatan hubungan. Namun, jika diamati lebih dalam, frekuensi dan kemudahan praktik numpang menyingkap fondasi budaya yang lebih kokoh. Ia bukan sekadar soal kepraktisan, melainkan refleks komunal yang tertanam begitu dalam.
Kata numpang menyimbolkan izin yang diajukan dan diterima hampir tanpa beban, sebuah penanda bahwa ruang, sumber daya, dan bahkan waktu, dalam batas-batas tertentu, adalah milik bersama. Ia tidak mengatur dengan instruksi, tapi dengan intuisi. Ia tidak memaksa, tapi mengajak. Ia tidak menghitung, tapi memahami.
Fenomena ini bukanlah anomali, melainkan norma, sebuah pilar yang diam-diam menopang struktur sosial masyarakat Indonesia.
Aku Ada Karena Orang Lain Ada
Untuk memahami makna numpang, kita bisa menengok tradisi filsafat lain. Konsep interbeing dari Buddhisme Zen dan ubuntu dari Afrika memperlihatkan bahwa numpang bukan sekadar basa-basi, tapi bagian dari pandangan hidup tentang keterhubungan.
Thich Nhat Hanh, biksu Zen asal Vietnam, menyebut interbeing sebagai hakikat bahwa semua hal saling bergantung. Ia menjelaskan hal itu lewat analogi sederhana selembar kertas.
“Jika kita terus melihat ke selembar kertas, kita bisa melihat sinar matahari di dalamnya. Jika sinar matahari tidak ada, hutan tidak dapat tumbuh. Tanpa sinar matahari, tidak ada yang bisa tumbuh, bahkan kita. Jadi, kita tahu bahwa sinar matahari juga ada di selembar kertas,” tuturnya dalam buku The Other Shore: A New Translation of the Heart Sutra with Commentaries (2017:28).
“To be is to inter-be,” katanya. Tidak ada yang berdiri sendiri. Thích Nhất Hạnh menggunakan perspektif sains dan ekologi untuk membuat ajaran kuno relevan bagi dunia modern.
Dalam kultur Indonesia, interbeing terejawantahkan dalam budaya numpang. Tindakan numpang bukanlah transaksi, melainkan pengakuan—meski tak terucap—bahwa keberadaan kita berkelindan, terjalin satu sama lain.

Jika interbeing bicara soal keterhubungan, ubuntu menekankan tanggung jawab. Konsep Afrika tersebut merangkum etika “aku ada karena orang lain ada”; bahwa hidup adalah soal komunitas, solidaritas, dan belas kasih.
Ubuntu telah didefinisikan sebagai kualitas moral manusia dalam filosofi atau etika humanisme Afrika. Bahkan, seturut artikel jurnal Philosophies Volume 9 Issue 1(2024), ubuntu bukan sekadar filosofi, tapi cara pandang yang hidup dalam praktik. Prinsip tersebut menekankan keterkaitan manusia melalui pepatah umuntu ngumuntu ngabantu 'seseorang adalah manusia melalui orang lain'.
Dalam kerja sosial, misalnya, pendekatan ubuntu menolak penanganan masalah yang bersifat individual semata. Ia lebih memilih pemulihan bersama, seperti prinsip “kalau kamu jatuh, kami angkat bareng-bareng."
Fenomena numpang yang langgeng di Indonesia bukanlah tradisi lokal belaka, melainkan pancaran nilai universal yang juga ada di belahan dunia lain. Ia merupakan titik temu antara interbeing dan ubuntu. Interbeing menjelaskan alasan kita saling membantu karena kita saling terhubung, sedangkan ubuntu menunjukkan bahwa kita membantu dengan rasa kemanusiaan yang aktif.
Kontras dari Individualisme Barat
Di Indonesia, numpang adalah jalan menuju komunitas saat hidup terasa berat. Sebaliknya, budaya individualisme di Amerika, yang mengagungkan kemandirian, justru sering menghasilkan keterasingan sosial. Fenomena itu disebut “American Drift”.
Dalam budaya individualis, impian otonomi pribadi menyebabkan ikatan sosial terkikis. Jacqueline Olds dan Richard S. Schwartz, melalui buku The Lonely American: Drifting Apart in the Twenty-first Century (2009), mengidentifikasi tren yang mereka sebut “drifting apart”, yakni ketika orang makin sibuk, makin mandiri, tapi makin sepi. Itu adalah pergerakan yang perlahan tapi pasti menjauhi koneksi sosial bermakna.
Artikel bertajuk “Social Isolation in America” mengamini fenomena itu: jejaring sosial menyusut dan makin banyak yang merasa tak punya teman bicara. Sejak lama, para sosiolog telah membahas lost community hypothesis, bahwa modernisasi dan urbanisasi melemahkan ikatan tradisional dengan komunitas dan keluarga besar, yang pada gilirannya menghasilkan anomi dan keterasingan.
Hasil penelitian Paolo Parigi dan Warner Henson II di atas menunjukkan, jejaring percakapan orang Amerika menyusut secara signifikan. Jumlah orang yang melaporkan tidak memiliki siapa pun untuk diajak bicara tentang hal-hal penting meningkat drastis.
Dalam kesehatan mental, ada istilah yang disebut “drift hypothesis”, yakni kesulitan hidup mendorong individu hanyut ke bawah dalam struktur sosial, alias makin terisolasi. Studi klasik yang meneliti istilah tersebut menunjukkan, individu dengan skizofrenia cenderung mengalami penurunan kelas sosial akibat gangguan mentalnya.
Menurut data Debt.org, kegagalan finansial, misalnya kebangkrutan, telah diatur secara hukum. Namun demikian, secara sosial, ia menjadi aib. Status bangkrut tercatat publik dan bisa diakses siapa pun, memicu rasa malu, depresi, dan isolasi.
Sebanyak 95 persen dari orang-orang bangkrut itu merasa terstigmatisasi. Mereka cenderung menyembunyikan kondisi sulit yang dialaminya, terutama dari orang tua, dan menghindari situasi yang membuatnya terekspos.
Di Indonesia—kecuali sebagian besar orang di kota besar—seseorang yang terpuruk dapat mendekat ke komunitas. Kerentananlah bukan aib, melainkan panggilan untuk saling merawat. Bukannya terisolasi, seseorang mestinya justru dirangkul.
Perbedaan ini bukan soal superioritas budaya, tapi soal pilihan: antara otonomi dan keterhubungan, antara kebebasan tanpa jaring, atau kebersamaan dengan batas yang kabur.
Sisi Gelap: Harga dari Komunalitas
Numpang bukan utopia. Di balik kehangatannya, tersimpan utang budi, tekanan sosial, dan privasi yang nyaris hilang. Kedermawanan itu jarang yang gratis; lebih sering berupa pertukaran tertunda yang melahirkan "kewajiban". Gagal membalas, bisa berarti turun derajat sosial.
Penelitian antropologis di berbagai komunitas di Indonesia mengonfirmasi bahwa jejaring resiprositas (prinsip timbal balik hubungan sosial-ekonomi) jangka panjang ini menopang kehidupan di luar jangkauan pasar atau negara.
Contoh konkretnya ialah praktik ngujur di komunitas nelayan Bali dan jaringan kekerabatan di Sumba. Keduanya menunjukkan bahwa orang membantu dan memberi bukan karena kewajiban formal, tapi karena ikatan sosial dan harapan akan dukungan saat dibutuhkan.

Utang budi di satu sisi mampu menopang solidaritas, tapi di sisi lain juga menjerat. Hubungan komunal tak selalu lembut. Ia bisa memaksa, eksklusif, bahkan menciptakan hierarki. Privasi pun jadi barang langka. Informasi pribadi mudah menyebar, dan kehidupan pribadi bisa jadi tontonan publik.
Namun, justru sisi gelap itulah yang membuat numpang berfungsi. Saat negara Barat mengandalkan hukum tertulis, konsep tersebut bergantung pada pengawasan sosial, rasa malu, dan reputasi. Mekanisme informal itulah yang memastikan roda komunal tetap berputar.
Dalam dunia numpang, rasa tidak nyaman adalah harga yang dibayar untuk rasa aman. Itu adalah sebuah tawar-menawar budaya antara kedekatan dan kebebasan, antara keterikatan dan otonomi.
Numpang Lewat: Seni, Fana, dan Filosofi Hidup
Perenungan konsep numpang itulah yang barangkali memantik seniman asal Bali, Made Djirna, untuk membuat instalasi “Transient-Continuous” di ARMA, Ubud. Ia membangun perahu dan naga dari material alam, simbol perjalanan, beban masa lalu, dan kekuatan spiritual menatap masa depan. Perahu itu membawa kayu sebagai jejak transisi; naga melindungi semesta.
Karya Djirna mencerminkan pandangan kosmologi Bali. Manusia, sebagai bagian kecil dari alam raya, terhubung dan saling memengaruhi. Baginya, “numpang” bukan sekadar izin melintas atau lewat, tapi gambaran bahwa kita semua hanya singgah sejenak di panggung kehidupan. Fana, tapi berjejak.
Di balik ungkapan “Permisi, numpang lewat!”, ada makna bahwa perjalanan hidup kita membutuhkan partisipasi orang lain. Begitu juga ketika seseorang “numpang tidur”; ia secara tidak langsung mengakui bahwa istirahatnya bergantung pada kebaikan dan kepercayaan orang lain.
Numpang menawarkan sebuah jawaban. Ia mengajak kita untuk melihat hidup sebagai ruang singgah bersama, bahwa kita hidup bukan semata berkat kepemilikan pribadi, tapi lewat kesediaan untuk hadir dalam ruang bersama, walau hanya sebentar. Kita numpang, karena kita bersama.
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id