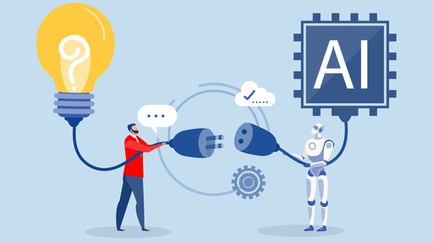tirto.id - Dari kafe estetik di sudut kota hingga mesin seduh otomatis yang terpasang di dapur rumah, kopi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat urban. Tak lagi sekadar soal kafein, kopi kini menyatu dengan ritme produktivitas, bahkan menjadi bagian dari identitas sosial dan simbol gaya hidup modern.
Kopi tidak hanya dipandang sebagai "doping" pelepas kantuk belaka. Ia telah bertransformasi menjadi minuman wajib untuk menemani aktivitas kaum muda di kafe, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi dengan teman sebaya.
Hal itu selaras dengan data survei GoodStats pada 2024 yang menyebut, tren konsumsi kopi di kalangan muda cukup tinggi. Sebanyak 71 persen anak muda usia 18–24 tahun rutin mengunjungi kedai kopi daripada menyeduh sendiri di rumah. Menariknya, mayoritas di antara mereka justru memilih mengonsumsi kopi pada malam hari (42 persen), alih-alih pagi hari untuk menunjang aktivitas kerjanya.
Meningkatnya tren minum kopi dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa dilepaskan dari pesatnya pertumbuhan bisnis kedai kopi di berbagai kota di Indonesia. Di kawasan urban, terutama di Jakarta, geliat industri ini terlihat jelas. Kedai kopi menjamur dari pusat hingga sudut kota.
Pusat pertumbuhan kedai kopi bukan hanya di Jakarta. Kota pelajar seperti Yogyakarta justru mencatat perkembangan yang lebih masif. Pada 2022, jumlah kedai kopi di Yogyakarta diperkirakan mencapai 3.000 gerai. Dua tahun kemudian, tepatnya 2024, data Kadin DIY menyebut setidaknya sudah ada sekitar 9.000 kedai yang berdiri.
Fakta tersebut menjadikan Yogyakarta sebagai daerah dengan kepadatan kedai kopi tertinggi di Indonesia, sebagaimana dikutip dari Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya(2024).
Dampak Lingkungan Akibat Konsumerisme Kopi
Indonesia bukan hanya sebagai salah satu konsumen kopi terbesar, tetapi juga produsen utama, di samping Brasil, Vietnam, dan Kolombia.
Menurut artikel yang terbit di jurnal Cogent Social Sciences, Indonesia tercatat sebagai produsen kopi terbesar kedua di Asia. Di tingkat dunia, Indonesia menduduki posisi keempat menurut data dari World Economic Forum.
Produksi tahunan kopi di Indonesia mencapai 12 juta karung kopi berukuran 60 kg. Angka ini mencerminkan betapa pentingnya peran Indonesia dalam industri kopi global.

Namun, di balik angka yang kesannya membanggakan tersebut, ada dampak ekologis yang jarang dibahas.
Salah satunya ialah ekspansi lahan tanam kopi yang terus terjadi. Alasannya tak lain adalah untuk memenuhi permintaan pasar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, luas lahan perkebunan kopi di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam setiap tahun.
Pada 2022, total luas lahan kopi tercatat sekitar 1.265,93 ribu hektar. Lalu, luasan itu meningkat menjadi 1.266,85 ribu hektar pada 2023. Artinya, pertambahannya diperkirakan sekitar 918 hektar hanya dalam satu tahun.
Perluasan lahan kopi tak bisa dimungkiri berdampak secara ekologis. Yang paling sederhana adalah pembabatan hutan. Belum lagi apabila alih fungsi lahan itu dilakukan dengan pembakaran, yang jelas bakal menambah polutan di udara dan merusak unsur hara tanah.
Bukti bahwa industri kopi turut berkontribusi pada deforestasi global kini makin kuat dengan laporan dari World Resources Institute (WRI), lembaga riset independen di bidang lingkungan. Laporan itu mengungkap, sejak 2001 hingga 2015, hampir dua juta hektar hutan dunia hilang akibat konversi menjadi lahan perkebunan kopi. Dari angka tersebut, sekitar 1,1 juta hektar digunakan untuk menanam kopi robusta dan 0,8 juta hektar untuk arabika.
Berkaitan dengan alih fungsi hutan menjadi lahan kopi robusta, Indonesia menjadi negara penyumbang laju deforestasi terbesar di dunia, dengan kontribusi 33 persen dari total global. Angka itu jauh melampaui negara-negara produsen kopi terbesar lainnya, seperti Brasil (16 persen), Madagaskar (14 persen), dan Vietnam (12 persen).
Dengan kata lain, sekitar sepertiga deforestasi hutan dunia karena ekspansi kopi robusta terjadi di Indonesia.
Kebiasaan ngopi bukanlah masalah, kecuali berlebihan. Peningkatan konsumsi kopi secara signifikan, baik di dalam maupun luar negeri, secara tidak langsung mendorong laju deforestasi.
Setiap cangkir kopi yang kita nikmati juga membawa konsekuensi ekologis yang mungkin tak terlihat kasat mata. Di balik kenikmatan satu tegukan kopi, kita ikut andil dalam penggerusan paru-paru dunia yang kian menipis setiap tahunnya.
Jejak Air dalam Setiap Tegukan Kopi
Selama ini, saat menyesap secangkir kopi, yang tampak di hadapan mata hanyalah air panas yang dicampur dengan bubuk biji sangrai. Padahal, di balik kesederhanaan itu, ada pemborosan air yang tak terelakkan, jauh sebelum kopi itu dapat diseduh sedemikian rupa jenisnya.
Arjen Y. Hoekstra, dalam laporan akademik berjudul “The Water Footprint of Food”, menyatakan bahwa proses produksi kopi dari hulu ke hilir membutuhkan air dalam jumlah besar.
Berdasarkan estimasi global rata-rata, satu cangkir kopi (125 ml) memiliki “jejak air” sebesar 140 liter air. Jejak air yang dimaksud adalah jumlah air yang digunakan dalam seluruh proses produksi kopi, mulai dari penanaman dan penyiraman tanaman kopi, pencucian buah kopi setelah panen, hingga proses pengupasan.
Bahkan, khusus pada metode pencucian “washed coffee” yang begitu populer—dengan metode itu, hasilnya dianggap lebih bersih dan terang—air digunakan dalam volume sangat tinggi untuk mencuci biji kopi berkali-kali.

Masalahnya, sebagian besar air tersebut hanya digunakan sekali dan langsung dibuang, terkadang tanpa proses daur ulang atau pengolahan limbah yang layak. Hal itu tidak hanya mengakibatkan pemborosan air, tetapi juga berpotensi mencemari air tanah dan sungai di daerah produksi kopi. Kejadian tersebut, utamanya terjadi di negara-negara berkembang.
Pencemaran air tanah dan sungai di daerah produksi kopi juga merupakan persoalan yang tak kalah serius. Hal tersebut terjadi akibat penggunaan pestisida, terutama pada budidaya kopi jenis robusta. Varian kopi ini dikenal sebagai salah satu varietas paling banyak ditanam dan dikonsumsi secara global.
Kopi robusta lumrahnya ditanam di lahan terbuka tanpa naungan. Metode ini memang membuat tanaman lebih cepat tumbuh dan menghasilkan panen lebih besar. Namun di sisi lain, paparan langsung terhadap sinar matahari dan lingkungan terbuka menjadikan tanaman ini lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Untuk mengatasinya, banyak petani bergantung pada pestisida kimia dalam skala besar.
Penggunaan pestisida jelas membawa konsekuensi serius bagi kesehatan lingkungan, terutama kualitas air di sekitarnya, sebagaimana dikutip dari Journal of Contaminant Hydrology. Laporan tersebut menyebut, bahan aktif pestisida yang digunakan dalam produksi kopi berisiko tinggi mencemari air permukaan sebanyak 44,7 persen dan air tanah hingga 23,7 persen.
Angka ini muncul berdasarkan penelitian di lembah Sungai Itapemirim, yang terletak di negara bagian Espírito Santo, Brasil. Zat aktif pestisida kimia yang ditemukan meliputi Ametryne, Cyproconazole, Diuron, Epoxiconazole, Flutriafol, Triadimenol, dan Triazophos.
Setiap tegukan kopi yang kita nikmati turut membawa jejak pemakaian air dalam skala besar dan pencemaran air di daerah sekitar. Belum lagi urusan pembabatan hutan yang masif setiap tahunnya. Semuanya demi memenuhi kebutuhan kopi harian kita yang meningkat tajam, dua, tiga, bahkan empat gelas, dalam sehari.
Mirisnya, kita tidak menyadari hal tersebut—atau lebih tepatnya tutup mata.
Penulis: D'ajeng Rahma Kartika
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id