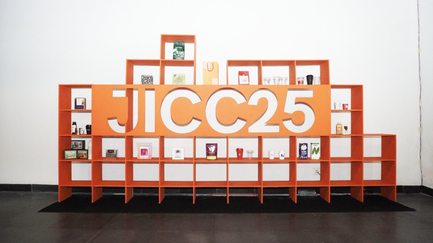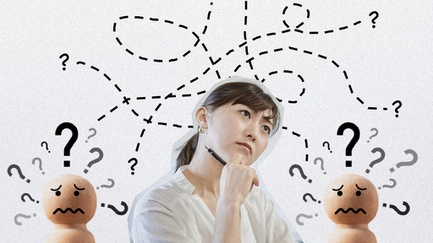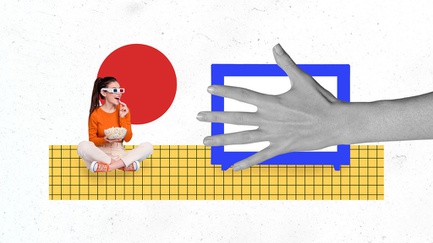tirto.id - "Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga."
You sing, you lose!
Di telinga generasi Milenial yang tumbuh besar pada era 90-an atau awal 2000-an, lirik ikonik dari soundtrack serial televisi Keluarga Cemara karya almarhum Arswendo Atmowiloto ini pasti tak asing lagi.
Cerita tentang keluarga Abah dan Emak yang hangat, sederhana, dan saling mendukung ini senantiasa “hidup” di memori kita seiring filmnya diproduksi berulang kali dan disiarkan di berbagai kanal media hiburan.
Menariknya, bagi kita, yang berbeda dari tayangan populer itu adalah kenyataan bahwa kita telah bertumbuh; orang tua semakin menua dan hidup kita tak lagi sama.
Pada momen Hari Keluarga Nasional, apa saja hal yang dapat kita refleksikan bersama?
Perayaan Hari Keluarga Nasional
Setiap tanggal 29 Juni, kita memperingati Hari Keluarga Nasional atau biasa disingkat Harganas.
Harganas adalah pengingat betapa krusialnya peran keluarga dalam masyarakat.
Keluarga merupakan unit terkecil dan paling personal yang membentuk negara, penentu kemajuan sebuah bangsa.
Di bawah satu atap rumah, keluarga yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 akan mengaktifkan delapan fungsi yang meliputi agama, sosial budaya, cinta kasih, proteksi, reproduksi, edukasi, ekonomi, dan pembinaan lingkungan.
Dalam rangka menghormati nilai-nilai inti dalam kehidupan berkeluarga, secara resmi, Hari Keluarga dirayakan di berbagai negara.
Warga Vietnam merayakannya pada 28 Juni, sementara di Amerika Serikat Family Day diperingati setiap hari Minggu pertama pada bulan Agustus. PBB menjadikan 15 Mei sebagai Hari Keluarga Internasional.
Sejarah 29 Juni: Dari Perang hingga KB
Peringatan Hari Keluarga Nasional lekat dengan sejarah kemerdekaan.
Menurut BKKBN, riwayat ini bermula dari era revolusi kemerdekaan.
Kala itu, demi mempertahankan kemerdekaan RI, negara memberlakukan wajib militer, yang memisahkan tentara dari keluarganya.
Kerinduan itu berakhir ketika Belanda mengakui kedaulatan RI pada 22 Juni 1949.
Sepekan kemudian, 29 Juni, Tentara Republik Indonesia (TRI) yang bergerilya, pulang ke rumah masing-masing.
Selain itu, 29 Juni juga tercatat sebagai klimaks para patriot Keluarga Berencana atau KB era Presiden Soeharto pada tahun 1970.
Kemudian, 23 tahun berselang, Soeharto meresmikan peringatan Hari Keluarga Nasional.
Sejak tahun 2014, BKKBN memelopori peringatan ini.
Pada setiap masa, keluarga ditantang untuk mengaktifkan keluarga—mikrokosmos dalam masyarakat—yang berkualitas dan saling memberdayakan.
Menguatkan Keluarga di Tengah Badai Multikrisis
Pemikir dan aktivis sosial asal Amerika Serikat, bell hooks, memiliki pandangan sendiri terkait cinta dalam sebuah hubungan, termasuk keluarga, yang rentan terhadap ketidakadilan dan diskriminasi.
Ia menyampaikan konsep tentang “keluarga baru” untuk menyorot upaya membersamai setiap anggota keluarga, dengan tidak membuangnya kala sudah tak lagi diinginkan.
Pada intinya, keluarga dapat menjadi ruang aman dan berdaya.
Konflik, kesulitan, penderitaan, dan tantangan tetap ada, tetapi dapat diatasi tanpa kekerasan, pengucilan, atau penghakiman.
Konsep ini tampaknya bisa jadi inspirasi sekaligus alternatif untuk menjalani hidup tenteram berdampingan lintas generasi, terlebih di tengah multikrisis hari ini.
Tahun 2025 bukan tahun yang mudah. Tantangan berlipat ganda.
Kita cemas akan gejolak geopolitik yang berpotensi mencetus Perang Dunia III. Kita dibuat gelisah pula oleh situasi ekonomi dan finansial, baik di skala nasional dan global, yang semakin tidak pasti.
Pada waktu sama, kita tengah menghadapi silver tsunami, gelombang lonjakan populasi usia lanjut (60 tahun ke atas). Ya, masyarakat Indonesia kian menua.
Angka ini diperkirakan terus bertambah hingga 20 persen pada 2045.
Menurut estimasi PBB, pada 2050, total senior kita dapat mencapai 74 juta jiwa atau setara 25 persen dari total populasi.
Di negara lain, situasinya tidak jauh berbeda.
Amerika Serikat, misalnya. Pada 2030, untuk pertama kali, mereka akan memiliki lebih banyak penduduk berusia di atas 65 tahun daripada anak-anak.
Pada periode kini, kalangan “Boomers” kelahiran 1946 hingga 1964 akan memasuki fase kehidupan yang memerlukan pendampingan.
Meskipun peningkatan jumlah senior dapat dikaitkan dengan bertambah tingginya angka harapan hidup, fenomena ini sayangnya belum cukup mendapat atensi dan penanganan yang mumpuni.
Populasi usia tua merupakan kelompok rentan yang tak hanya berisiko secara fisik, tetapi juga rawan terhadap kemiskinan dan kesejahteraan yang kurang memadai.
Situasi Penduduk Menua di Indonesia
Menurut dokumen Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024dari BPS, persentase senior di Indonesia meningkat hampir empat persen dalam satu dekade terakhir, tepatnya dari 2015 hingga 2024.
Pergerakan ini dimulai pada 2021, yang mendapati bahwa persentase warga senior telah berada di angka 10,82 persen.
Nah, penting diingat, suatu negara dikatakan berada dalam struktur penduduk tua apabila persentase seniornya melebihi 10 persen.
Artinya, dalam setiap 100 penduduk usia produktif (15 hingga 59 tahun), harus menanggung setidaknya 17 penduduk senior.
Masih melansir dokumen BPS, kebanyakan warga senior tinggal di dalam rumah tangga berisi tiga generasi (35,73 persen) dan bersama keluarga inti (34,45 persen).
Temuan dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menambahkan, sekitar 80,8 persen pengasuh senior adalah anggota keluarga terdekat seperti anak, cucu, dan keponakan.
Estafet Pengasuhan: Boomers Menua, Benarkah Gen M-Z Clueless Merawatnya?
Tentu saja, menjadi tua merupakan proses yang manusiawi.
Hanya saja, dalam perjalanannya, penuaan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pendampingan.
Tantangan semakin berlipat bagi keluarga yang perlu merawat orang tua dengan sindrom geriatri atau kondisi klinis terkait disfungsi tubuh.
Pertanyaannya, sudahkah keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang optimal?
Kerja pengasuhan memang bukan hal yang mudah. Anggota keluarga tiba-tiba berganti peran; orang tua yang sebelumnya mengasuh, kini menjadi yang diasuh.
Mirisnya, meski menua adalah suatu kepastian, selama ini kita tidak pernah diajarkan di sekolah untuk menjadi pendamping orang tua yang semakin rentan.
Di AS, pada tahun 2023, hampir 25 persen orang dewasa berusia lebih dari 40 tahun setidaknya menanggung seorang anak dan satu orang tua di atas usia 65 tahun.
Sementara itu, di Indonesia, survei Pinhome dan YouGov 2024 mencatat setidaknya 41 juta orang adalah generasi sandwich. Mereka terdiri atas 53 persen Milenial dan 25 persen Gen Z.
Kembali pada tugas perawatan di punggung kalangan lebih muda, family caregiver mustahil terbebas dari berbagai tantangan.
Sebut di antaranya kurangnya pengetahuan yang tepat mengenai cara merawat senior dengan baik, minimnya lingkar penyangga, hingga keterbatasan referensi aktivitas.
Tak ketinggalan masih adanya beban emosional dan tekanan finansial.
Lalu, kita bisa mulai dari mana?
Pertama, bekali diri dengan keterampilan esensial.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, menekankan pentingnya Milenial dan Gen Z memiliki keterampilan komunikasi, psikologi dasar, manajemen waktu, serta pengetahuan dasar medis seperti memberikan obat, menangani luka, dan nutrisi lansia.
Kedua, perkuat support system.
Ketua Umum PP Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia, Wiwin Wiarsih, menyarankan untuk menciptakan ruang bagi para senior agar bisa bercerita atau curhat. Ini sangat penting untuk kesehatan mental mereka.
Ketiga, hargai otonomi senior.
Riset oleh Profesor Ilmu Perilaku Sosial USU, Nurman Achmad, menunjukkan pentingnya menghargai hak lansia untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup dan perawatan mereka. Temuan ini juga merupakan pukulan bagi stigmatisasi lansia tidak lagi mampu berpikir jernih.
Mengakhiri renungan ini, mari kita hayati kembali syair Weinata Sairin, seorang Teolog dan Aktivis Dialog Kerukunan.
Semoga dengan pesan ini, kita menjadi lebih siap untuk menghargai masa tua dengan penuh cinta dan kebijaksanaan.
Jika dulu keluarga dibangun dengan impian orang tua untuk mewujudkan cita-cita anaknya, sekarang giliran kita untuk mendukung harapan hidup orang tua senior agar mereka senantiasa berdaya, mandiri, dan bahagia.
* Artikel ini merupakan kolaborasi Diajeng dan Senja, komunitas berbasis di Jabodetabek yang mengadvokasikan edukasi bagi family caregiver serta kegiatan bagi warga senior agar berdaya dan mandiri.
Penulis: Dewi Ananda
Editor: Sekar Kinasih
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id