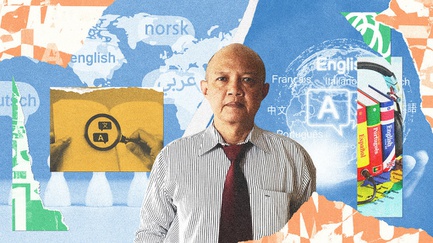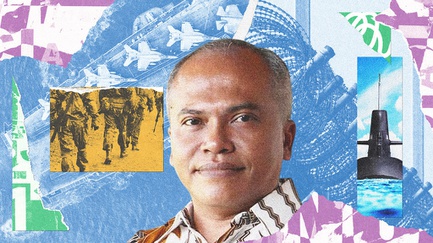tirto.id - November 2024, di Brasil, dalam forum internasional G20, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen yang sangat berani: pada 2040 atau 15 tahun ke depan, seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia akan dipensiunkan (phase out). Namun, janji ambisius yang sudah lama dinanti itu malah tidak didukung oleh regulasi yang baru-baru ini disahkan, Peraturan Menteri ESDM No 10/2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.
Selain aspek regulasi, pernyataan-pernyataan para pembantu presiden seperti Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM; hingga Hashim Djojohadikusumo, adik presiden sekaligus utusan khusus yang berfokus menangani iklim dan energi, justru bertolak belakang dengan janji presiden. Istilah “phase out” yang digunakan presiden berubah menjadi “phase down”. Artinya, dari yang semula penghentian total berubah menjadi pengurangan bertahap.
Perbedaan terminologi ini bukan sekadar semantik. Ia berimplikasi besar pada peta jalan transisi energi, seperti tecermin dalam Peraturan Menteri ESDM No 10/2025. Regulasi yang disahkan 15 April 2025 itu jelas-jelas mempertahankan sebagian besar PLTU hingga 2060, menggunakan teknologi tambahan seperti pencampuran dua bahan bakar (co-firing) antara batu bara dengan biomassa, hidrogen, ammonia, hingga penangkapan karbon (CCS).
Permen ini bahkan tidak secara eksplisit menyebutkan daftar PLTU yang akan dipensiunkan, melainkan bersifat conditional mengingat ada sederet kriteria penilaian untuk menentukan PLTU yang akan disuntik mati. Padahal, sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk menilai PLTU mana yang perlu dipensiunkan.
Saat negara seperti India telah berupaya menutup PLTU 15,65 GW (2000-2023), Indonesia justru tampak ragu, seolah tak punya sumber energi lain yang potensinya bisa dimaksimalkan.
Keterbatasan Anggaran: Alasan yang Itu-Itu Lagi
Setiap kali rencana soal transisi ke energi terbarukan dibicarakan, selalu ada satu alasan yang muncul: anggaran terbatas. Biaya pensiun dini PLTU dianggap terlalu mahal, terlalu besar, dan terlalu berisiko. Padahal, persoalan utamanya bukan anggaran, melainkan prioritas pemerintah dan keinginan politik untuk merealisasikannya.
Berdasarkan perhitungan CERAH, negara punya dana cukup besar untuk membiayai transisi energi karena ada banyak alokasi budget yang tidak efisien. Misalnya, dalam sembilan tahun terakhir, kelebihan pasokan listrik yang tidak terpakai mencapai 291 ribu GWh—dan negara membayar kompensasi hampir Rp300 triliun ke perusahaan listrik, rata-rata sekitar Rp33 triliun per tahun.
Bayangkan, berapa banyak PLTU besar yang bisa disuntik mati dengan uang sebesar itu?
Mari kita coba menghitung dari PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 1 GW, yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp13 triliun. Dengan anggaran Rp33 triliun, kita bisa menutup dua hingga tiga GW PLTU setiap tahun, tanpa perlu menunggu utang baru atau hibah asing.
Dana over capacity listrik hanya satu dari sekian banyak penggunaan anggaran yang tidak efisien. Belum lagi jika kita melihat peluang kerja sama pendanaan iklim seperti Energy Transition Mechanism (ETM) dan Just Energy Transition Partnership yang bisa dimanfaatkan. Artinya, secara anggaran kita bisa. Lalu di mana persoalannya?
Kecenderungan kebijakan yang masih berat sebelah. Di satu sisi bicara soal energi hijau, tapi di sisi lain, aturan demi aturan justru membuka jalan bagi industri batu bara. UU Cipta Kerja dan UU Minerba memberikan insentif kepada batu bara, mulai dari dipermudahnya perizinan, hingga pemberian insentif kepada perusahaan tambang. Belakangan, organisasi keagamaan diberi kemewahan mengelola tambang melalui Peraturan Pemerintah 25/2024, sementara perguruan tinggi berpeluang menerima manfaat bagi hasil dari pengelolaan tambang lewat revisi UU Minerba terbaru.
Semua kebijakan tersebut menunjukkan, kekuatan politik batu bara masih sangat dominan.
Data Indonesia Parliamentary Center (IPC) mengungkapkan, lebih dari 50% topik yang dibahas dalam rapat-rapat Komisi VII DPR hanya sektor migas dan minerba, sedangkan energi terbarukan hanya 10%.
Bahkan dokumen jangka panjang seperti Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060 pun tak memuat rencana pensiun dini PLTU secara jelas. Alih-alih mengurangi, pemerintah justru berencana menambah kapasitas PLTU hingga 26,8 GW.
Danantara dan Satgas Transisi Energi
Di tengah situasi pelik itu, Danantara—badan investasi yang digadang-gadang jadi motor penggerak investasi untuk memajukan ekonomi Indonesia–lahir, dengan fokus pada 20 sektor prioritas, salah satunya sektor energi baru terbarukan. Karena itu muncul harapan, lembaga ini bisa menarik investasi hijau dan membiayai pensiun dini PLTU yang selama ini dianggap berat di ongkos.
Sejalan dengan itu, pemerintah membentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141/2025, terdiri atas empat kelompok kerja: energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia.
Baik Danantara maupun Satgas Transisi Energi kini memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa komitmen pemerintah bukan sekadar retorika. Apa pun bentuk intervensi yang diambil, pemerintah berkewajiban bekerja secara transparan dan inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pusat, daerah, swasta, hingga masyarakat sipil.
Bukan Sekadar Tutup Pabrik
Pensiun dini PLTU bukan cuma soal mencabut kabel dan mematikan mesin. Di baliknya, ada ribuan pekerja, keluarga, dan komunitas yang bergantung pada industri batu bara. Itulah mengapa transisi energi harus dibarengi dengan transisi sosial, menyiapkan pelatihan ulang, membuka lapangan kerja hijau, dan memastikan tak ada yang ditinggalkan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menargetkan tambahan 75,6 GW energi terbarukan hingga 2035. Itu bukan angka kecil—yang berarti ada beberapa hal yang harus dilakukan.
Pertama, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan hijau (green skills). Pelatihan semacam ini bisa menjembatani kesenjangan keterampilan sekaligus mendorong pertumbuhan industri energi terbarukan yang inklusif, khususnya bagi pekerja sektor fosil, agar tidak kehilangan arah di tengah pergeseran struktur ekonomi.
Kedua, mendorong investasi teknologi energi terbarukan, salah satunya melalui skema Feed in Tariff seperti di Vietnam—yang menghasilkan ledakan instalasi energi terbarukan dan menjadikannya peringkat pertama di ASEAN. Jika kita terapkan, demokratisasi energi dapat terwujud.
Kebijakan serupa Feed in Tariff, selain dapat menciptakan peluang pekerjaan baru di sektor energi terbarukan—mulai dari pembangunan proyek energi, operasi, hingga pemeliharaan fasilitas pembangkit energi terbarukan—juga dapat menjadi solusi bagi negara yang selalu merasa memiliki keterbatasan dana.
Transisi energi bukan soal teknis semata. Tetapi lebih kepada visi: mau dibawa ke mana arah pembangunan bangsa? Janji Presiden Prabowo sudah diumumkan ke dunia. Dan kini, kita menanti keberanian Presiden untuk merealisasikan komitmen itu, agar tak sekadar omon-omon.
Penulis adalah Policy Strategist dari Indonesia CERAH. Memiliki 8 tahun pengalaman penelitian, terutama isu transisi energi dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
CERAH sendiri merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bekerja untuk memajukan kebijakan transisi energi dan iklim di Indonesia.
Editor: Zulkifli Songyanan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id