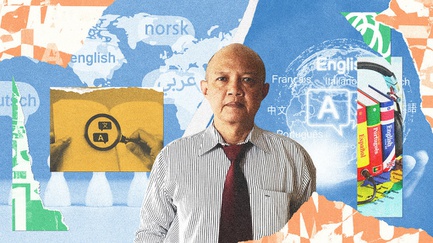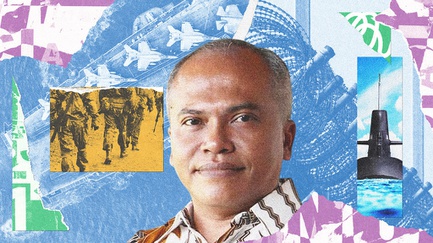tirto.id - Setiap tanggal 23 Juni, dunia memperingati Hari Janda Internasional. Namun, seperti banyak peringatan global yang sarat empati, momen ini juga kerap dibungkam dalam seremoni dan retorika. Padahal, menjadi janda alias ibu tunggal—terutama di negara-negara berkembang—bukan sekadar status sipil, melainkan penanda luka sosial yang dalam, dan jejak sejarah panjang kekerasan struktural yang belum selesai: kolonialisme.
Kolonialisme lama membunuh suami-suami. Kolonialisme baru memiskinkan mereka. Dalam keduanya, ibu tunggal hadir bukan sebagai pilihan, melainkan hasil dari sistem dunia yang terus memproduksi keterpisahan, ketercerabutan, dan keterpinggiran. Dunia merayakan janda, padahal dunia sendiri yang menciptakan mereka.
Janda Kolonial: Luka Perang dan Duka yang Diwariskan
Sejarah Indonesia dan banyak negara bekas jajahan lain adalah sejarah darah dan air mata. Perang-perang kolonial seperti Perang Aceh, Perang Jawa, atau agresi militer di berbagai pelosok Nusantara bukan hanya menghasilkan pahlawan dan kekalahan, tetapi juga ribuan janda yang ditinggal mati oleh suami mereka. Banyak kaum janda sama sekali tidak mendapat pengakuan dalam narasi besar perjuangan bangsa, padahal merekalah yang menyambung hidup, mengasuh generasi baru dalam kelangkaan, dan menjadi fondasi keluarga di tengah reruntuhan yang dibikin kolonialisme.
Ibu tunggal tidak memegang senjata, tetapi nyaris saban waktu mereka bertempur melawan sepi, kelaparan, dan keterasingan. Mereka tidak tercatat dalam sejarah resmi, tetapi memori tentang mereka hidup dalam tubuh-tubuh yang dipaksa kuat oleh keadaan.
Jika kolonialisme dulu menciptakan janda lewat peluru dan penaklukan, maka kolonialisme baru—dengan wajah utang, liberalisasi ekonomi, dan ketergantungan global—menciptakan janda dalam diam. Negara-negara berkembang yang dulu dijajah, kini dijebak dalam sistem ekonomi global yang timpang. Ketika sumber daya mereka dikuras untuk pertumbuhan negara-negara utara, rakyatnya tertinggal dalam pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.
Jutaan perempuan dari Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin dipaksa menjadi pekerja migran. Bukan karena ingin berpetualang, melainkan karena negara tak lagi menjamin kehidupan. Mereka meninggalkan anak, suami, bahkan keutuhan keluarga. Sementara itu, jutaan laki-laki juga bermigrasi, hilang dalam sistem kerja kasar dan eksploitasi. Akibatnya, keluarga hancur perlahan. Perceraian meningkat. Anak tumbuh tanpa ayah atau ibu. Dan perempuan kembali menjadi janda—bukan karena kematian, melainkan karena ketercerabutan sosial.
Fenomena ini disebut oleh para sosiolog sebagai "penjandaan tanpa kematian". Kolonialisme lama memisahkan suami dari istri lewat perang. Kolonialisme baru memisahkan mereka lewat pasar. Kedua-duanya memisahkan dengan paksa, dan hasil akhirnya selalu sama: perempuan harus menanggung beban sistem.
Peta Global Penjandaan
Saat ini, diperkirakan ada lebih dari 258 juta janda di dunia, dengan sebagian besar berada di negara-negara berkembang. India dan Tiongkok saja menyumbang lebih dari 90 juta janda. Di Indonesia, jumlah janda mencapai sekitar 9,5 juta, dan meningkat dari tahun ke tahun akibat perceraian, kematian dini, dan migrasi kerja. Banyak dari mereka hidup tanpa jaminan sosial, tanpa perlindungan hukum, dan tanpa akses terhadap layanan dasar.
Kontras dengan itu, di negara-negara maju, meski jumlah janda juga tinggi, sistem jaminan sosial dan perlindungan pensiun memberi mereka sandaran. Isolasi dan kesepian memang tetap menjadi masalah, tapi tidak disertai dengan pemiskinan struktural seperti yang terjadi di selatan global.
Dalam sistem global yang menjadikan laba sebagai tujuan utama, keluarga bukan lagi unit sosial yang dilindungi, melainkan korban pertama dari ketimpangan. Perempuan yang ditinggal suami, baik karena kematian, perceraian, atau migrasi kerja, tak hanya kehilangan pasangan, tapi juga keamanan ekonomi, perlindungan sosial, dan rasa bermasyarakat.
Dalam konteks ini, janda bukan sekadar identitas, tapi status sosial yang rentan dan disisihkan. Bahkan di banyak tempat, janda masih menghadapi stigma, diskriminasi, hingga kekerasan—baik dalam hukum waris, hak atas anak, maupun partisipasi ekonomi.
Seremoni yang Menyentuh, Sistem yang Tak Tersentuh
Ironisnya, Hari Janda Internasional diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di satu sisi, lembaga ini berperan penting dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Di sisi lain, PBB juga menjadi bagian dari tatanan global yang justru mempertahankan status quo ketimpangan: lewat sistem pinjaman internasional yang menjerat negara-negara miskin, pembiaran atas privatisasi layanan publik, serta kegagalan menekan dominasi korporasi multinasional.
Perayaan ini menjadi paradoks moral: mengangkat janda sebagai simbol empati dalam seremoni tahunan, tetapi membiarkan “mesin produksi ibu tunggal” terus bekerja setiap hari—di pabrik-pabrik yang memisahkan keluarga, di ladang-ladang yang dijual kepada investor asing, di meja-meja kebijakan yang mengabaikan perempuan sebagai subjek pembangunan.
Kita diajak terharu, tapi tidak diajak berpikir. Kita diberi wacana penyembuhan, tapi tidak diberi kesempatan melawan sumber luka.
PBB mungkin bisa menciptakan hari peringatan. Tapi hanya rakyat yang sadar dan sistem yang adil yang bisa menghentikan siklus penjandaan struktural ini.
Menggugat Dunia yang Melanggengkan Duka
Mengangkat kisah janda adalah bagian dari melawan lupa dan membongkar ilusi kemajuan. Kita tidak benar-benar merdeka jika perempuan tetap menanggung beban kolonialisme yang berganti nama. Kita belum adil jika janda terus dipinggirkan sebagai anomali, bukan sebagai konsekuensi sistem.
Sudah saatnya kita mengakui bahwa janda adalah korban sistem global yang eksploitatif. Pada saat bersamaan, mereka juga merupakan simbol kekuatan yang bertahan di tengah kehancuran. Dan jika dunia ini sungguh ingin berpihak pada keadilan, para pembuat kebijakan harus berani menata ulang sistem yang selama ini membuat perempuan terus kehilangan—sekaligus memberdayakan mereka sebagai fondasi perubahan itu sendiri.
Penulis, Dr. Mohammad Kholid Ridwan, adalah Dosen dan Peneliti Senior Universitas Gadjah Mada
Editor: Zulkifli Songyanan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id