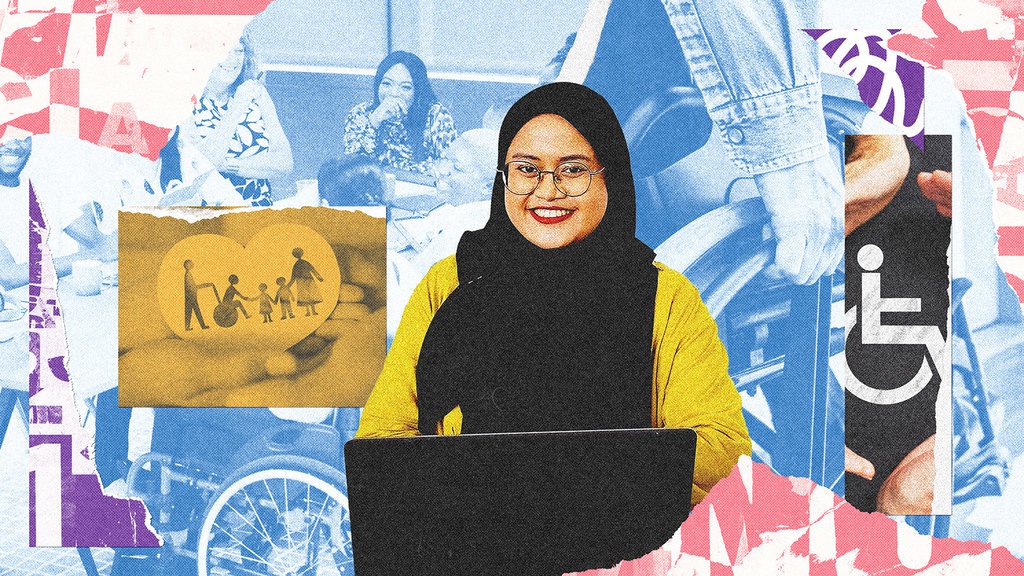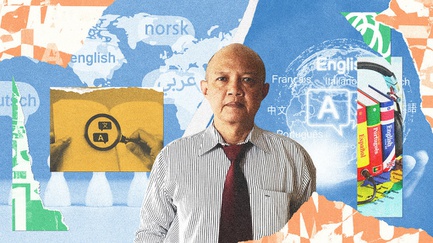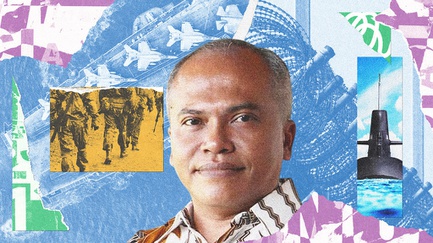tirto.id - Disabilitas bukanlah suatu aib. Bukan pula dengan memiliki disabilitas seorang individu tidak dapat berkarya sesuai bidangnya. Contohnya yaitu Stephen Hawking, seorang ilmuwan jenius asal Inggris. Terobosannya dalam bidang fisika dan kosmologi tidak perlu diragukan. Fisikawan tersebut mendapatkan diagnosis Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) – penyakit syaraf yang menyerang motorik neuron sehingga mengalami kendala dalam gerak tubuh saat umur 21 tahun. Penyakit ini membuat mobilitas Hawking semaking menurun dan membuat lumpuh. Namun demikian, Hawking dapat berkomunikasi dengan menggunakan synthesizer pidato komputer.
Kisah lain pejuang disabilitas yang inspiratif yaitu Helen Keller, perempuan pertama tuna netra dan tuna rungu yang berhasil menjadi penulis, aktivis politik, dan dosen di Amerika. Heler awalnya terlahir normal. Saat berumur 19 bulan, dia mengalami sakit demam yang saat ini diduga meningitis. Hal ini membuat Heler menjadi buta dan tuli. Akan tetapi dengan keadaan Heler yang berbeda, Heler tetap menghasilkan karya sastra yang luar biasa. Karya Heler berjudul The World I Live In dan The Story of My Life telah menjadi literatur klasik dan diterjemahkan dalam 50 bahasa.
Dengan menilik cerita Stephen Hawking dan Helen Keller, keadaan disabilitas individu tidak hanya sejak pra lahir, namun dapat terjadi pasca lahir seperti kecelakaan atau sakit. Berdasarkan data Susenas, penyebab disabilitas paling banyak disebabkan oleh penyakit (60%) diikuti bawaan sejak lahir (17%) dan kecelakaan (16%). Namun sayangnya, tidak semua penyakit dapat terlihat seperti Hawking yang tidak dapat melakukan mobilitas dengan bersifat progresif ataupun disabilitas Helen yang cenderung permanen. Tidak sedikit individu yang memiliki penyakit dengan gejala yang tak tampak dan bersifat fluktuatif. Inilah yang menjadi individu dengan sakit kronis tidak mendapatkan perlindungan yang jelas dalam UU Disabilitas No. 8 tahun 2016.
Masih Relevankah UU Disabilitas No. 8 tahun 2016 di 2025?
UU Disabilitas No. 8 tahun 2016 memiliki klasifikasi disabilitas yang terdiri atas disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan ganda. Individu dapat dikatakan disabilitas jika mengalami gejala dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen. Namun bagaimana individu yang memiliki sakit kronis seperti kanker, autoimun atau lainnya? Gejala yang dirasakan dapat fluktuatif dan cenderung tak tampak mata. Dengan gejala yang berbeda dari Undang-undang, tentunya pejuang sakit kronis tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dari negara.
Hal ini membuat individu rentan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dengan memberikan label “malas”. Padahal yang dirasakan individu dengan sakit kronis adalah nyata, bukanlah suatu ilusi. Jika pejuang sakit kronis termasuk dalam kategori disabilitas, kategori mana yang bisa didapatkan?
Sebagai perumpamaan, saya mendapatkan diagnosis autoimun Guillain Barre Syndrome – autoimun saraf dan Sjogren Syndrome – autoimun yang menyerang kelenjar air. Saya mengalami kesulitan berjalan dan berbicara ketika autoimun kambuh. Keadaan saya bisa dikatakan fluktuatif selama 3 (tiga) tahun. Jika saya termasuk kategori disabilitas fisik, nampaknya hal ini menjadi kontroversi. Berdasakan pasal 4 huruf a disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.”
Pada kenyataannya, ketika saya mengajukan pin prioritas TransJakarta, saya tidak termasuk dalam kategori disabiitas. Hal ini disebabkan sakit saya tidak termasuk dalam penyakit yang dicantum dalam undang-undang. Padahal dalam Undang-undang tertulis kata “antara lain”. Dengan demikian, kata “antara lain” adalah sebagai contoh, bukan sebagai standar baku mendefinisikan disabilitas fisik. Atau mungkin memang sakit saya tidak cukup “disabilitas” bagi masyarakat.
Negara yang Mengakui Sakit Kronis sebagai Disabilitas
Sakit kronis di berbagai negara telah diakui sebagai disabilitas. Negara yang memberikan pengakuan tersebut yaitu Inggris, Amerika Serikat, Australia. Bahkan negara tetangga Indonesia yaitu Filipina telah mengakui pejuang sakit kronis sebagai disabilitas.
Di negara Inggris, menurut Equality Act 2010, definisi disabilitas adalah apabila seseorang memiliki keterbatasan kemampuan fisik atau mental dan keterbatasan tersebut memiliki dampak yang mengganggu secara substansial dan jangka panjang pada kemampuannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam petunjuk Equality Act 2010, disebutkan beberapa penyakit yang termasuk penyakit autoimun.
Equality Act 2010 juga menyatakan bahwa dampak substansial dari keterbatasan kemampuan dianggap berkelanjutan apabila ada kemungkinan kemunculan kembali, termasuk juga apabila kemunculan kembali gejala/dampak hanya berlangsung kadang-kadang atau sebentar. Undang-Undang ini menyatakan bahwa, untuk menentukan apakah seseorang memiliki disabilitas, keterbatasan kemampuan yang jangka panjang adalah berlangsung minimal 12 bulan, atau total periode dari kemunculan gejala awal adalah minimal 12 bulan, atau kemungkinan dapat dialami seumur hidup orang yang mengalaminya.
Jika saya WNI atau Warga Negara Inggris, tentu saya dapat dikatakan sebagai disabilitas karena memenuhi kriteria yaitu memiliki keterbatasan kemampuan fisik karena sakit autoimun, gejala hanya berlangsung kadang-kadang atau sebentar dan telah mengalami lebih 12 bulan. Namun saya Warga Negara Indonesia, jadi bukan termasuk kategori disabilitas.
Sedangkan di negara tetangga, Negara Filipina melalui Republic Act No. 9442 sebagai amandemen dari Republic Act No. 7277Magna Carta for Persons with Disability menyatakan salah satu ragam disabilitas di Filipina adalah dibolehkannya orang dengan penyakit kronis (misalnya namun tidak terbatas pada kanker, penyakit jantung, gagal ginjal kronis) untuk mendapatkan kartu identitas disabilitas (PWD-Identification Card/IDC) untuk (Guidelines on the Issuance of Identification Card Relative to Republic Act 9442). Selain itu, kanker dan penyakit langka juga tercatat sebagai kategori khusus dari disabilitas.
Bukankah saatnya Indonesia lebih inklusif terhadap pejuang sakit kronis? Pejuang sakit kronis tidak pantas untuk diberikan penghakiman bahwa hal ini suatu dosa atau karma dari suatu perbuatan. Namun justru diberikan perlindungan hak-haknya, termasuk pengakuan atas disabilitas. Begitu pula suatu kata “disabilitas” yang memiliki konotasi negatif, harus terbebas dari stigma sesuai dengan UU Disabilitas No. 8 tahun 2016 dalam pasal 7: “Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.”
Pengujian Judical Review UU Disabilitas No. 8 tahun 2016
Saya dan rekan saya Raissa Fatikha mengajukan uji konstitusionalitas UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kami mengajukan permohonan uji materi karena kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Raissa sendiri adalah pejuang nyeri kronis Thoracic Outlet Syndrome (TOS) sejak 2015. Penyakit ini membuat Raissa merasakan gejala nyeri secara terus-menerus dengan intensitas yang bisa berfluktuasi di bagian tangan kanan, pundak, dan dada kanan bagian atas. Namun demikian Raissa kesulitan mendapatkan haknya seperti mendapatkan akomodasi yang layak, aksesibilitas, pencatatan sebagai disabilitas, bebas dari stigma, dan konsesi. Begitupun dengan saya, selaras dengan Raissa, sulit mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi.
Yang paling menarik adalah ketika saya mendaftar CPNS dalam formasi disabilitas. Saya tidak termasuk dalam formasi disabilitas, lagi-lagi saya tidak telihat cukup disabilitas. Jika pun saya mendaftar formasi disabilitas, salah satu syaratnya adalah harus mengunggah video bagian yang terdampak disabiltas. Namun disabilitas saya benar-benar tak tampak, bahkan terlihat orang sehat pada umumnya.
Sesuai dengan UUD No 28C: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Saya dan Raissa berhak untuk mendapatkan layanan dan aksesbilitas yang memadai. Individu dengan penyakit kronis bukan berarti tidak berdaya. Kami membutuhkan akomodasi yang layak untuk menunjang dalam berkarya
Atas dasar tersebut, kami menyatakan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau penyakit kronis dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”
Permohonan kami yang lain yaitu menambahkan ragam disabilitas yaitu “disabilitas penyakit kronis” dalam Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2016.
Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memberikan perlindungan dan mengakui individu dengan penyakit kronis meskipun gejala tidak tampak secara fisik namun memengaruhi kualitas hidup secara substansial.
Disabilitas seharusnya tidak hanya merujuk pada kondisi fisik yang terlihat, tetapi juga mencakup semua kondisi yang membatasi seseorang dalam berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan profesional. Pengakuan penyakit kronis sebagai disabilitas akan menyetarakan hak, menghilangkan stigma, dan meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang berjuang melawan keterbatasan yang tidak selalu terlihat. []
Penulis adalah survivor autoimun, Dosen Fisip UPN Veteran Jakarta.
Editor: Nuran Wibisono
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id