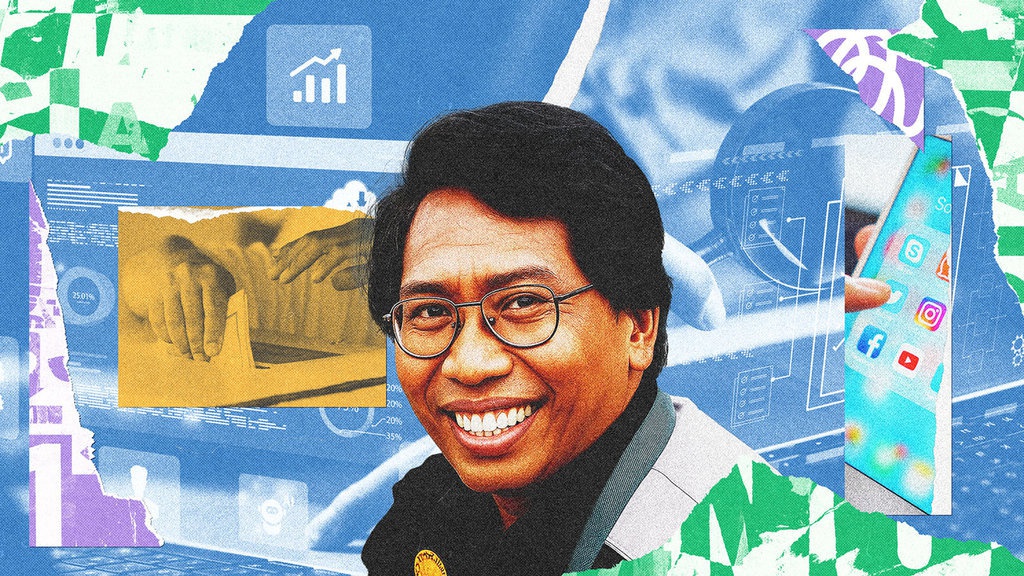tirto.id - Demokrasi sering dipahami sebagai sistem yang memberi rakyat suara untuk menentukan arah negara. Pertanyaannya, di era data sekarang ini, apakah demokrasi masih benar-benar otentik?
Seperti kita ketahui, data --sehimpun informasi tentang kebiasaan, preferensi, serta pikiran kita-- telah menjadi kekuatan yang mampu membentuk, mengarahkan, bahkan memprediksi pilihan setiap individu. Maka, keputusan yang tampak lahir dari rakyat kemungkinan bisa saja sebenarnya sudah diarahkan oleh mekanisme tersembunyi dari balik layar. Kemungkinan inilah yang kemudian menyingkap ihwal keberadaan negara bayangan.
Negara bayangan bukan pemerintah rahasia yang nyata, melainkan jaringan tak terlihat dari perusahaan, lembaga, dan elite data yang menguasai informasi. Contohnya, perusahaan big tech yang dapat memantau perilaku jutaan orang secara real time, menganalisis preferensi, dan menyesuaikan informasi yang layak diterima khalayak. Kekuasaan seperti ini halus, nyaris tak tampak, tetapi dampaknya bisa lebih besar daripada senjata konvensional yang dimiliki negara, karena ia mengontrol cara kita berpikir, memilih, dan, akhirnya, menggerakkan negara.
Dengan demikian, demokrasi modern menghadapi dilema baru, yaitu apakah suara rakyat masih benar-benar suara rakyat, atau sekadar gema dari algoritma yang diam-diam menulis arah negara? Jika jawaban condong ke yang kedua, kita sedang berada di panggung yang dikendalikan dari balik layar, dan sesungguhnya negara bayangan menjadi aktor yang paling menentukan.
Mengambil Alih Peran
Jika dulu manipulasi politik dilakukan lewat propaganda media cetak atau televisi, kini algoritma media sosial mengambil alih peran itu. Algoritma dapat menampilkan konten tertentu sesuai profil psikologis pengguna. Artinya, setiap orang bisa hidup dalam gelembung informasi yang didesain khusus untuknya. Demokrasi kemudian bergeser dari arena debat terbuka menjadi ruang gema yang sempit.
Kita mungkin sering berpikir bahwa pilihan politik lahir dari kesadaran pribadi. Nyatanya, sekarang ini, banyak pilihan dibentuk oleh paparan informasi yang sudah dipilah dan disusun oleh algoritma. Rakyat merasa bebas, padahal sesungguhnya jalur pikiran mereka sudah diarahkan. Situasi ini membuat demokrasi tampak hidup, tetapi substansinya bisa kosong.
Jika suara rakyat bisa diarahkan, bisa diprediksi dengan akurasi tinggi, apakah itu masih dianggap sebagai demokrasi?
Sekarang, coba bayangkan jika hasil pemilu bisa dihitung jauh sebelum hari pencoblosan, hanya berdasarkan kecenderungan perilaku digital warga. Demokrasi akan kehilangan unsur ketidakpastian yang menjadi ciri sehatnya. Alih-alih memilih, rakyat justru dipilih oleh algoritma.
Ketika algoritma bisa mengenali preferensi politik seseorang dari jejak digitalnya, demokrasi bergeser menjadi proyek teknologi. Ia sudah tidak lagi murni soal ide, gagasan, atau visi. Pemilu berubah menjadi arena eksperimental untuk menguji seberapa jauh data dapat mengendalikan psikologi massa.
Fenomena ini kemudianmembawa kita pada persoalan ihwal siapa sebenarnya penguasa di balik demokrasi saat ini. Apakah pemerintah resmi, partai politik, atau perusahaan data?
Jawaban untuk pertanyaan tersebut tidaklah simpel. Yang jelas, kekuatan negara bayangan kiwari kian dominan. Ia hadir di antara institusi resmi tanpa perlu tampil di panggung. Kita bisa melihatnya dalam cara iklan politik diarahkan ke audiens tertentu. Tidak semua orang menerima pesan kampanye yang sama. Pesan bisa disesuaikan dengan kecemasan, harapan, bahkan trauma pribadi seseorang. Demokrasi yang seharusnya kolektif malah menjadi sangat individualistik, personal.
Di sisi lain, negara bayangan juga mengaburkan batas antara fakta dan opini. Lewat algoritma, berita palsu bisa disebar lebih cepat dari kebenaran. Jika fakta dan kebohongan punya peluang sama untuk dipercaya, lalu bagaimana rakyat bisa membuat keputusan yang benar-benar rasional?
Dalam kondisi ini, demokrasi laksana rumah yang fondasinya reyot. Rakyat ingin membuat keputusan, tapi mereka tidak tahu lagi mana informasi yang benar dan mana yang palsu. Berita yang mereka baca di media, postingan di sosial media, bahkan iklan yang muncul di layar gawai bisa saja sengaja dibuat untuk mempengaruhi pikiran mereka. Karena tidak ada acuan yang jelas, suara rakyat pun jadi mudah diarahkan, dan demokrasi kehilangan dasarnya untuk berjalan dengan sehat.
Kondisi seperti ini terjadi di banyak negara, termasuk di negara-negara maju. Demokrasi di negara-negara berkembang bahkan lebih rentan karena literasi digital yang lemah. Pemilih bisa lebih mudah digiring oleh konten emosional daripada argumentasi rasional. Dan negara bayangan menemukan lahan suburnya.
Celakanya, regulasi negara sering tertinggal jauh dari inovasi teknologi. Pemerintah sibuk mengatur isu klasik, sementara operasi data lintas negara bergerak tanpa hambatan. Kesenjangan ini membuat demokrasi formal terlihat lamban dan tumpul. Adapun entitas negara bayangan justru lincah dan adaptif.
Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, demokrasi bisa menjadi sekadar formalitas. Rakyat tetap datang ke TPS, tetap mencoblos, tetap mendengar debat kandidat. Tetapi, hasil akhirnya sesungguhnya sudah dipengaruhi secara sistematis oleh kekuatan bayangan. Demokrasi hanya tinggal ritual, bukan substansi.
Meski begitu, bukan berarti rakyat sepenuhnya tidak berdaya. Kesadaran kritis masih bisa dibangun melalui literasi digital dan pendidikan politik. Jika rakyat paham cara kerja algoritma, mereka bisa lebih waspada terhadap manipulasi data. Pengetahuan bisa menjadi tameng melawan negara bayangan.
Transparansi juga penting. Perusahaan data harus diwajibkan membuka bagaimana algoritma mereka bekerja, terutama saat digunakan untuk kampanye politik. Tanpa transparansi, demokrasi akan selalu berada dalam posisi rawan manipulasi.
Regulasi bisa mempersempit ruang gerak negara bayangan. Namun, masalahnya adalah siapa yang akan mengatur? Jika negara sendiri sudah terpengaruh oleh kepentingan data, regulasi bisa mandek. Demokrasi jadi terjebak dalam lingkaran setan antara kekuasaan formal dan kekuasaan bayangan. Jalan keluarnya tidak akan mudah.
Beberapa ahli menyebut perlunya kedaulatan digital. Artinya, negara harus benar-benar berdaulat atas data warganya sebagaimana atas tanah dan lautnya. Tanpa kedaulatan digital, demokrasi akan selalu mudah disusupi oleh kekuatan eksternal. Artinya, negara bayangan akan tetap punya ruang gerak bebas.
Kedaulatan digital tentu saja menuntut infrastruktur teknologi lokal yang kuat. Jika semua data warga disimpan di server asing, kontrol rakyat atas demokrasi otomatis melemah. Rakyat tidak lagi punya kendali penuh atas informasi mereka sendiri, sementara keputusan politik bisa dipengaruhi oleh pihak luar tanpa disadari.
Berkejaran dengan Waktu
Kembali ke pertanyaan awal tulisan ini: apakah demokrasi masih otentik di era data?
Banyak orang percaya masih mungkin, asal rakyat sadar akan risiko dan mau membangun pertahanan. Namun, tantangannya besar karena kecepatan teknologi umumnya jauh melampaui kesadaran sosial. Karenanya, demokrasi berkejaran dengan waktu.
Sejarah sendiri menunjukkan bahwa demokrasi memiliki daya tahan. Ia mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan, dari era feodalisme hingga kapitalisme. Tantangan era data hanyalah babak baru dalam perjalanan panjang demokrasi. Dan adaptasi harus dilakukan cepat dan tepat.
Peran masyarakat sipil sudah pasti sangat krusial. Media independen, akademisi, dan organisasi masyarakat harus menjadi pengawas kekuatan bayangan yang bisa mengancam demokrasi. Tanpa peran mereka, negara bisa terlalu lemah menghadapi oligarki digital.
Tekanan dari publik memiliki kekuatan besar untuk memaksa perubahan nyata. Jika rakyat bersuara keras dan serentak mengenai perlindungan privasi data, perusahaan teknologi--termasuk platform media sosial, penyedia aplikasi, dan pengelola server global--akan terpaksa lebih berhati-hati dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan informasi pribadi.
Demokrasi tidak bisa sekadar mengandalkan aturan dari pemerintah atau lembaga resmi, tetapi harus juga digerakkan oleh kesadaran masyarakat itu sendiri. Partisipasi aktif warga, mulai dari mengkritisi praktik perusahaan teknologi hingga menuntut transparansi algoritma, tetap menjadi kunci agar suara rakyat tidak diambil alih oleh kekuatan yang tak terlihat.
Meski demikian, kita perlu pula realistis. Negara bayangan tidak akan lenyap begitu saja. Ia sudah menjadi bagian dari ekosistem global yang sulit diputus. Tantangannya adalah bagaimana meminimalisasi implikasi buruknya. Ruang publik tidak boleh dibiarkan dikuasai algoritma komersial semata. Demokrasi tidak boleh berhenti hanya pada ritual pencoblosan. Ia harus dijaga setiap hari melalui kesadaran, keterlibatan, dan kontrol publik.
Tanpa itu, negara bayangan akan lebih mudah mengendalikan arah kebijakan pemerintah, mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada rakyat serta mengarahkan opini publik sesuai agenda mereka. Akibatnya, suara rakyat yang seharusnya menentukan keputusan politik justru malah terdistorsi.
*Penulis adalah esais, alumnus FISIP Universitas Padjadjaran
Editor: Zulkifli Songyanan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id