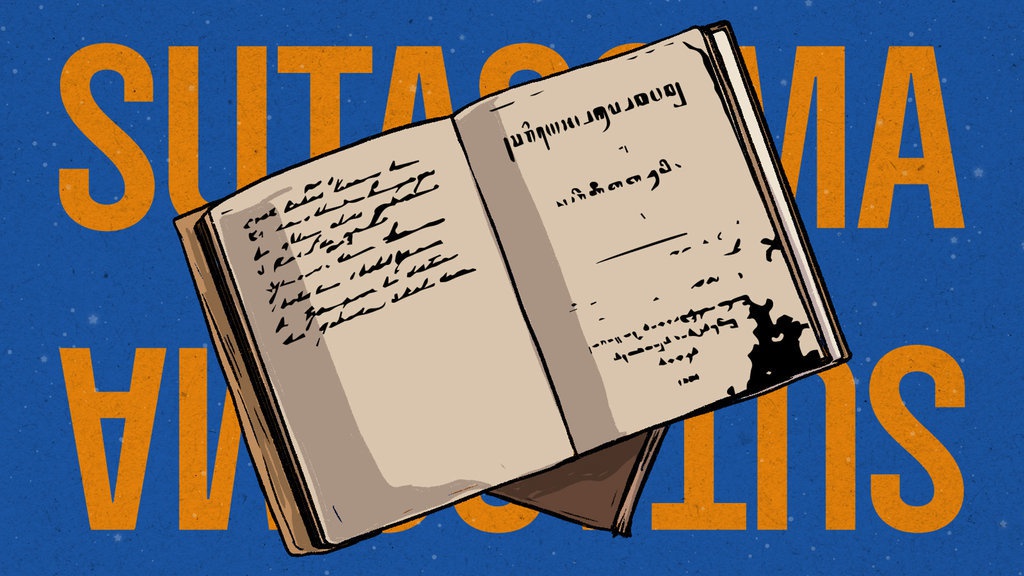tirto.id - Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional Indonesia barangkali jadi konsep politik paling awal yang diajari di sekolah, setidak sejak tingkat sekolah dasar. Semboyan yang juga melekat pada lambang negara ini secara historis pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI (Mei-Juni 1945) ketika merumuskan dasar-dasar negara.
Menurut Bambang Noorsena dalam “Bhinneka Tunggal Ika: Sejarah, Filosofi, dan Relevansinya sebagai Salah satu Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” (2011), popularitas Bhinneka Tunggal Ika makin umum diketahui setelah semboyan itu dilekatkan pada desain lambang negara pada sidang kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.
Saat memperkenalkan Bhinneka Tunggal Ika, Yamin mengutipnya dari salah satu ungkapan yang muncul pada sebuah teks kuno dari zaman Majapahit, yakni Kakawin Sutasoma pada Pupuh 139 bait ke-5:
“Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen, mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”
(Dikatakan Buddha dan Siwa adalah dua yang berbeda, mereka memang berbeda namun bagaimana bisa dikenali? Sebabnya ajaran Jina dan Siwa adalah satu, berbeda tetapi tetap satu, tiada kebenaran yang mendua).
Upaya pengadopsian istilah semacam ini memang bukan sesuatu yang salah, namun popularitas makna Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang telah menyebabkan luputnya perhatian pada sumber teks semboyan ini.
Inkarnasi Sang Buddha
Sutasoma yang kita ketahui hari ini terdiri atas dua jenis teks. Seperti disinggung oleh Dwi Woro R. Mastuti dan Hastho Bramantyo dalam Kakawin Sutasoma: Mpu Tantular (2009), bentuk teks paling awal yang dilaporkan adalah berupa kakawin (puisi). Belakangan diketahui bahwa bentuk prosa (parwa) dari teks Sutasoma juga dijumpai pada satuan naskah Cantakaparwa dari Bali.
Menurut Mastuti dan Brahmantyo, walaupun Sutasoma dapat diklasifikasikan sebagai teks Buddhis, teks ini amat populer dan dianggap penting oleh umat Hindu di Bali—terutama dalam pengalihwahaan ceritanya ke dalam dramatari, seni rupa, dan sebagainya. Sementara dari segi penanggalannya kemungkinan ditulis pada periode keemasan Majapahit di era rezim Rajasanagara atau Hayam Wuruk (1334-1389 M).
Secara garis besar, Kakawin Sutasoma berkisah tentang lahirnya inkarnasi sang Buddha Vairocana di dunia manusia pada zaman kaliyuga—zaman edan—yang bernama Pangeran Sutasoma. Sebagaimana tersurat dari gelarnya, Sutasoma merupakan seorang bangsawan, dan oleh karena itu ia merasa dirinya terkekang oleh keduniawian.
Sekali waktu, sang pangeran melarikan diri dari istana karena menolak dijodohkan oleh ayahnya. Ia memilih mengembara sembari memperdalam ilmu spiritual sampai ke Gunung Mahameru. Dalam pertapaannya ia mendengar seorang raja bengis bernama Purusada yang gemar memakan manusia—meski taat memuja Batara Kala.
Para dewa yang ketar-ketir menghadapi Purusada yang berniat memakan 100 raja, lantas meminta Sutasoma yang saleh untuk mengalahkannya. Namun, karena anti kekerasan, Sutasoma menolak dan malah mengembara kembali. Dalam pengembaraannya dikisahkan ia bertemu dengan tiga makhluk buas (raksasa berkepala gajah, naga, dan harimau) yang menjadi muridnya.
Sementara itu, Raja Purusada telah berhasil mengumpulkan 100 raja yang akan dikurbankan. Namun, Batara Kala menolak 100 raja itu dan hanya ingin memakan Sutasoma. Purusada kemudian menculik Sutasoma dan mempersembahkannya. Sutasoma bersedia dimakan dengan satu syarat: 100 raja yang lain harus dilepaskan. Mendengar permintaan tulus Sutasoma, hati Purusada tersentuh. Ia pun menyesali perbuatannya, bertobat, dan membebaskan semua raja yang telah ia tangkap.
Kritik Mpu Tantular
Fakta-fakta menarik mengenai substansi teks Sutasoma sebenarnya berkutat pada penggubah karya sastra itu sendiri, yakni Mpu Tantular. Mpu yang arti namanya “tidak goyah” ini sepertinya memiliki posisi yang penting dalam dunia religi Majapahit (kemudian Bali). Dalam Babad Arya Tabanan seperti dilaporkan I Made Purna dkk. (1994/1995), ia disebut-sebut merupakan putra dari Mpu Bahula dan juga Ratna Manggali.
Mpu Bahula merupakan putra Mpu Bharada—seorang pendeta agung nan legendaris dari era Airlangga, sedangkan Ratna Manggali adalah putri Calon Arang yang menganut aliran Hindu Tantrayana. Terlepas benar atau tidaknya susunan genealogis yang agak melompati pembabakan sejarah ini, tapi yang pasti Tantular bukan orang sembarangan dalam memori keagamaan Majapahit-Bali.
Soewito Santoso dalam disertasinya Boddhakawya-Sutasoma: A Study in Javanese Wajrayana Text-Translation-Commentary (1968) menyebutkan bahwa Sutasoma di luar pesan-pesan sinkretiknya, juga merupakan bentuk perpaduan dari bentuk teks jataka (cerita kehidupan lampau Siddharta Gautama) dan tradisi penulisan epos Hindu, Mahabharata—utamanya bagian Arjunawiwaha dan Bharatayuddha.
Tantular dengan cerdik menukil beberapa unsur dalam epsiode-episode itu, dengan kerangka cerita jataka yang berpusat pada tokoh Buddhis semacam Sutasoma. Beberapa kesinambungan bentuk detail adegan khas jataka pada Kakawin Sutasoma bahkan bisa dijumpai segelintir di relief Candi Borobudur.
Mengenai ungkapan “kesatuan” esensi Siwa dan Buddha yang terkenal dalam Kakawin Sutasoma, beberapa sarjana terdahulu semacam Santoso (1968) menganggap bahwa hal itu merupakan simbol dari keharmonisan kehidupan beragama di zaman Majapahit—tentu karena teks itu ditulis pada masa Hayam Wuruk berjaya.
Utomo dan Purwanto menganggap Tantular berpandangan bahwa kekuasaan mutlak atas seluruh Nusantara adalah titik nol dari zaman Kaliyuga atau kiamat. Proses penyatuan itu, dalam hal ini disimbolkan dengan hendak dimakannya 100 raja, bukanlah tanpa perlawanan sama sekali, di dalamnya ada aliran sungai darah yang tumpah lantaran ambisi kolektif Majapahit.
Melalui Kakawin Sutasoma, Tantular seakan-akan mengingatkan hakikat penting penyatuan bagi Hayam Wuruk dan mungkin Indonesia masa kini, yakni penyatuan substansi alih-alih unifikasi material.
Penulis: Muhamad Alnoza
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id