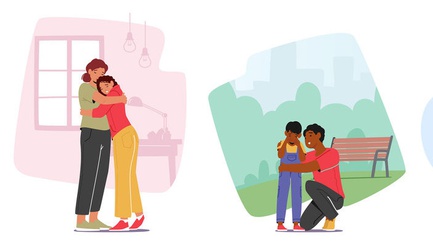tirto.id - Semua orang pasti pernah merasa bosan. Karena bosan, kita menyaksikan banyak tindakan aneh yang tak pernah terpikir dilakukan manusia rasional.
Pada 2019 lalu, ada seorang satpam yang memborgol dirinya sendiri karena bosan. Tapi, ia lupa, kunci borgolnya tertinggal di rumah. Karenanya, ia terpaksa harus menghubungi polisi untuk melepaskan borgol tersebut.
Di tahun yang sama,New York Post juga pernah mewartakan empat anak baru gede (ABG) yang membakar sebuah rumah. Alasannya sama: bosan.
Tidak hanya orang awam yang gemar melakukan hal "menyimpang" karena bosan. Bahkan akademisi terkenal dari Universitas Chicago, Agnes Callard, sering melakukannya. Saat sedang sendirian di malam hari dan jalanan sekitar rumahnya sedang sepi, ia suka berjalan di tengah-tengah marka jalan.
Suatu malam, tidak hanya berjalan, Agnes memutuskan untuk berbaring di tengah jalan raya, dan kendaraan lewat dari sisi kiri dan kanannya. Lantas, seorang polisi menghampirinya. Polisi itu mengira Agnes sedang mabuk atau dalam pengaruh obat-obatan, atau malahan percobaan bunuh diri.
Polisi bingung ketika Agnes menjelaskan bahwa ada banyak alasan ia berbaring di tengah jalan raya. Ia ingin melihat sudut pandang penampakan bintang-bintang dari tengah marka jalan. Alasan lainnya, ia hanya ingin tahu rasanya telentang di tengah jalan raya.
"Berbaring di tengah jalan bukan hal normal dilakukan manusia," tulis Agnes dalam esainya yang bertajuk "Unruliness" (2018). Orang-orang sukar memahami hal yang ia lakukan.
Secara naluriah, rasa bosan sebenarnya adalah hal lazim dalam hidup manusia. Jangankan manusia, para filsuf pun menyatakan bahwa dewa-dewi sebenarnya bosan dalam kehidupan mereka.
Maka itu, Soren Kierkegaard menyimpulkan, akar masalah di dunia ini adalah kebosanan.
“Asal-muasal tindakan jahat dan perilaku menyimpang bermuara dari kebosanan,” tulis Kierkegaard dalam Either-Or Part I (1987: 286).
Filsuf asal Denmark tersebut bahkan pernah berujar, “[Dahulu kala], Tuhan bosan. Karena itu, Dia menciptakan manusia. Adam pun bosan karena kesepian. Maka dari itu, Hawa diciptakan. Sejak itu, rasa bosan hadir di tengah-tengah kita, merasuki jiwa-jiwa manusia.”
Analogi Kierkegaard diamini oleh Nietzsche yang, dalam bukunya berjudul The Antichrist (1931), menyatakan, “Tuhan pun setiap harinya berusaha melawan kebosanan. Dia bosan pada hari ketujuh.”
Dalam literatur kristiani, Tuhan menciptakan semesta dalam rentang enam hari. Pada hari ketujuh, Dia beristirahat. Itulah barangkali landasan pernyataan Nietzsche, bahwa Tuhan pun merasa bosan karena tidak ada yang Dia kerjakan.
Ketika filsuf-filsuf di atas menyatakan Tuhan merasa bosan, bukan berarti mereka terang-terangan berujar bahwa Tuhan merasa bosan. Hal itu sekadar metafora bahwa fitrah manusia memang merasa bosan.
Kebosanan Bagai Pisau Bermata Dua
Menurut filsuf Bertrand Russel, “Kebosanan merupakan salah satu motivasi paling kuat dalam sejarah; demikian juga sekarang,” tulisnya dalam The Conquest of Happiness (1930).
Banyak inovasi dan hal-hal kreatif lahir dari kebosanan. Bagi sebagian besar orang, bosan dan rasa malas adalah masalah. Namun, apabila dikelola dengan baik, rasa bosan yang kita alami sebenarnya tidak semembosankan yang dibayangkan orang-orang. Bahkan, buah kebosanan itu bisa jadi amat berharga bagi orang lain.
“Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, tapi saya berjanji hal itu tidak akan membosankan,” ujar David Bowie di panggung Madison Square Gardens, dalam konser perayaan ulang tahunnya yang ke-50 pada 1997.
Bagi para seniman semacam David Bowie, kebosanan adalah suatu titik untuk melahirkan karya-karya barunya.
Lantas, bagaimana pikiran kita bekerja saat bosan? "Ada dua hal yang berlangsung di pikiran kita saat bosan," ujar John Eastwood, psikolog dari Universitas York, Kanada, dilansir oleh BBC.
"Hal pertama adalah ketika kita merasa terjebak pada kondisi saat ini [stuck] dan ingin melakukan suatu hal, tapi kita tidak mau melakukan hal-hal yang ada di depan mata kita," jelasnya.
"Kedua, ketika bosan, kapasitas mental kita sedang nganggur. Kita tergerak untuk berinteraksi dengan pikiran kita [untuk menghilangkan kebosanan tersebut]," lanjutnya.
Dua hal di atas tidak terpisah, tetapi dapat saling tumpang-tindih. Pada kasus pertama, kita ingin melakukan suatu hal menarik, tapi tidak tahu apa. Kalaupun ada pekerjaan yang mesti dikerjakan, kita tidak ingin mengerjakannya.
Misalnya, masih ada cucian piring atau baju kotor yang mesti diantar ke binatu. Kita tidak ingin melakukan dua hal tersebut sebab tidak menarik. Karena itu, kita bosan dan merasa kosong. Lasnta, keadaan ini dapat berlanjut pada kondisi kebosanan kedua: kapasitas mental kita menjadi nganggur dan tidak tahu apa yang mesti dilakukan.

Ketika merasa tidak nyaman atau bosan, kita berpikir bagaimana cara mengenyahkannya segera.
Sialnya, dengan banyaknya distraksi yang kini tersedia, hanya dengan satu klik gawai pintar, kita dapat menonton YouTube, berselancar di Instagram, menulis cuitan di X, dan seabrek media sosial lainnya.
Kita kemudian terbiasanya dengan stimulus instan, misalnya lewat video reels pendek di YouTube dan Instagram atau bertukar komentar di dunia maya.
Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan obat instan untuk membunuh kebosanan, yang pada akhirnya melahirkan rasa bersalah karena sebenarnya kita hanya duduk sendirian, dan tak melakukan apa-apa (kecuali jika pekerjaan kita memang berhubungan dengan internet dan media sosial).
Menilik masa lalu, pada 1980-an, sastrawan Budi Darma pernah bosan dan melamun ketika naik kereta api dari Madiun ke Surabaya.
Dalam lamunannya, ia seolah-olah melihat pesawat terbang, tetapi di sisi lain, ia yakin pesawat terbang itu sebetulnya tidak ada. Ia sadar otaknya mengada-ada. Namun, pesawat tersebut seolah-olah benar-benar hadir di hadapan matanya, jauh di sana, di angkasa raya.
Dia kemudian mengikuti terus pesawat terbang itu, sampai akhirnya hilang. Mungkin menabrak sebuah gunung yang sangat jauh dari pandangan, pikirnya.
Dalam bayangannya, Budi Darma merasa menaiki pesawat tersebut, dan ia terjebak nasib buruk: mengalami kecelakaan bersama tabrakan pesawat.
Selepas keretanya sampai, Budi Darma lantas mencari mesin ketik dan menuliskan ide tersebut. Buah lamunan dari kebosanan itu menjadi cikal bakal lahirnya novel terkenal Olenka (1983). Novel itulah yang mengantarkannya meraih penghargaan Hadiah Sastra ASEAN (SEA Write Award).
Coba kita bayangkan andai kata, ketika sedang bosan, Budi Darma meraih gawai pintarnya yang berisi 10 episode serial Layangan Putus (2021) atau unggahan di X yang riuh dengan keluhan netizen, mungkin Olenka tak akan pernah lahir. Kita pun tak akan pernah membaca salah satu novel terbaik yang pernah ditulis di Indonesia.
Sejauh ini, memang ada korelasi antara melamun karena bosan dan daya cipta kreativitas. Lantas, dari sanalah ide akan muncul.
"Tidak ada pendorong lebih besar daripada kebosanan untuk membuatmu menulis," ujar novelis terkenal Agatha Christie, dalam wawancaranya dengan BBC pada 1955.
Bagi seorang penulis, kebosanan adalah pemantik untuk berkreasi. Adapun pebisnis menganggapnya sebagai momen untuk memikirkan cara memperluas dan memperbaiki usahanya. Begitu seterusnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas.
Kebosanan adalah perasaan tidak nyaman dan menyakitkan. Lazimnya sebagai manusia, kita berusaha melepaskan diri dari perasaan tersebut. Di sanalah terdapat kesenjangan, sebuah ruang yang mesti diisi dengan aktivitas lain, baik aktivitas produktif, iseng, atau menyenangkan.
Dalam situasi bosan, biasanya kita akan terpikir hal yang terasa penting bagi kita, baik urusan hubungan romantik, pekerjaan, atau hal-hal yang luput dikerjakan. Di sinilah kreativitas bekerja. Karena itu juga, ide-ide kreatif kerap muncul ketika seseorang sedang mandi atau buang air besar. Terdengar familier, bukan?
Akan tetapi, bagi beberapa seniman atau penulis, mereka dengan sengaja menciptakan ruang untuk merasa bosan, sebagai titik awal untuk berkreasi.

Yang menjadi masalah dari kebosanan adalah ketika tak ada yang bisa dilakukan, banyak orang menyalurkannya pada hal-hal buruk. Dalam kasus ekstrem, sebagian orang yang kecanduan narkoba awalnya mencoba-coba karena bosan.
Banyak kenakalan remaja dilakukan karena tidak ada aktivitas apa pun sehingga melakukan hal-hal konyol atau bahkan merusak. Karena bosan, mereka melakukan tindakan-tindakan serampangan.
Robert Nisbet pernah berujar bahwa kebosanan dapat menjadi bencana bagi manusia. “Kebosanan bisa jadi merupakan sumber ketidakbahagiaan terbesar bagi orang-orang Barat … Jikapun ada kemerdekaan, itu sebenarnya kemerdekaan dari rasa bosan,” tulisnya.
Lantas, di sini lahir dua pertanyaan: Kapan kebosanan itu dapat menjadi inspirasi? Dan kapan kebosanan dapat melahirkan perbuatan merusak nan tercela?
Orang-Orang Hampa
Dari sudut pandang psikologi, ketika terjalin rapat dengan kehampaan, kebosanan dapat mengantarkan ke perbuatan buruk, sebagaimana dikutip dari Perspective of Psychological Science. Untuk memahami pernyataan ini, kita harus memahami konsep kehampaan (emptiness).
Secara umum, seseorang yang ditimpa kehampaan akan merasa kosong dan tak memiliki tujuan hidup bermakna. Akibatnya, pikirannya mudah goyah dan dipengaruhi orang lain. Pada saat bersamaan, bisa jadi ia juga akan mudah menyalurkan perilakunya pada hal-hal destruktif sebagai pelampiasan untuk memenuhi perasaan kosong dalam jiwanya.
Sebagai catatan, perilaku destruktif tidak bisa dijelaskan secara sederhana hanya dengan kebosanan dan kehampaan. Namun, dua faktor tersebut kerap mendasari perilaku destruktif, sebagaimana disinggung Kierkegaard di bagian awal tulisan ini.
Contoh klasik dari kebosanan dan kehampaan bisa dilihat dari kisah teologiwan Yunani kuno, Augustine, dalam "Confessions" yang ditulisnya sekitar tahun 400. Ia menceritakan, saat kecil, ia dan kawan-kawannya mencuri buah pir. Mereka mencuri bukan karena lapar. Nyatanya buah pir tersebut mereka lemparkan ke sekumpulan babi. “Perbuatan nakal yang serampangan,” demikian Augustine mendefinisikan kenakalan tersebut.
Yang menyedihkan dari rasa bosan dan hampa adalah tiadanya tujuan hidup dari orang bersangkutan. Ia tidak tahu alasannya menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konsep psikologi eksistensialis populer, ada kutipan yang diabadikan oleh Rollo May dalam Man’s Search for Himself (1953: 9): “Jika kau tidak tahu apa yang kau inginkan, orang lain akan menentukannya untukmu.”
Ketika kita tidak merumuskan sendiri keinginan dan makna hidup yang dijalani, kita akan diombang-ambingkan oleh lingkungan dan orang sekitar. Beruntung jika lingkungan kita baik. Tapi, sialnya, jika lingkungannya buruk, tak jarang, kita akan terlena, lalu terjerumus pada pergaulan yang buruk pula.
Berdasarkan laporan Gallup(2024), 20 persen dari orang-orang berusia 18 hingga 26 tahun tidak tahu makna dan tujuan hidupnya. Banyak orang merasa bahwa kejadian-kejadian dalam hidup mereka berlangsung tanpa alasan jelas atau secara acak.
Di salah satu kuesioner Gallup, 20 persen responden sering kali menjawab "tidak pernah" untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan hidup atau perkara penting dalam hidup mereka.
Dalam data lain, menurut survei CDC Amerika Serikat (AS), hanya sekitar 4 dari 10 orang yang menemukan tujuan dalam hidup mereka. Empat puluh persen di antaranya merasa bahwa hidupnya tak memiliki tujuan jelas atau netral (tak tahu apakah hidupnya punya tujuan atau tidak).
Hampir seperempat orang dalam survei tersebut merasa netral atau tidak memiliki pemahaman kuat tentang sesuatu yang membuat hidupnya bermakna.
Akan tetapi, survei tentang makna hidup di atas merujuk ke kondisi masyarakat di AS, yang belum tentu sesuai dengan orang Indonesia. Namun, setidaknya demikianlah gambaran yang terjadi.
Bagaimana mungkin mengatasi kehampaan jika seseorang tidak tahu "kenapa" dan "untuk apa" hidup yang dijalaninya? Lebih buruknya, mereka tidak punya keinginan untuk mencari makna hidup tersebut.
Perasaan bosan dan kosong akan menjadi pendorong emosi yang rentan, terlebih jika mereka mengalami kejadian yang berat. Mungkin kita akan bertanya-tanya: "Kenapa musibah ini menimpa saya?" atau jika bosan, tak jarang muncul keinginan-keinginan iseng yang malahan berbahaya atau membahayakan orang lain, yang kemudian dilakukan untuk mengisi ruang kosong dalam jiwa.
Untuk mengatasi kehampaan, dua psikolog kesohor, Viktor Frankl dan Roy Baumeister meresepkan obat mujarab: makna hidup. Orang yang tahu tujuan hidupnya akan memahami hal yang dia lakukan, bahkan dalam kebosanan sekalipun. Karena itu, dalam kondisi bosan pun, ia masih bisa terinspirasi.
Sebagai misal, seorang David Bowie yang bosan, sepi, dan hampa, tahu bahwa hidupnya adalah untuk bermusik. Maka dari itu, perasaan kelam yang ia rasakan, misalnya, bisa menjadi inspirasi dalam lirik-lirik lagunya.
“Planet Earth is blue. There is nothing I can do,” lantun Bowie dalam “Space Oddity” (1969). David Bowie menggambarkan, kehidupan di bumi menyedihkan (Planet Earth is blue). Tidak ada yang bisa kita lakukan.
Demikian juga yang dialami Budi Darma. Andaikata bukan seorang sastrawan, perasaan bosan yang ia rasakan, atau lamunan yang ia pikirkan, tak akan menjadi buah karya sastra yang indah.
Jika kita tahu hal yang akan kita lakukan dalam hidup ini, bahkan kebosanan pun dapat menjadi berkah. Pertanyaannya, apa yang ingin kita lakukan di hidup ini?
===============
Abdul Hadi merupakan akademisi di bidang psikologi, lulusan Magister Psikologi Sosial dan Kesehatan Utrecht University.
Tirto.id membuka peluang bagi para ahli, akademisi, dan peneliti, untuk memublikasikan hasil riset keilmuan. Jika berminat, silakan kirim surel ke mild@tirto.id untuk korespondensi.
Penulis: Abdul Hadi
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id