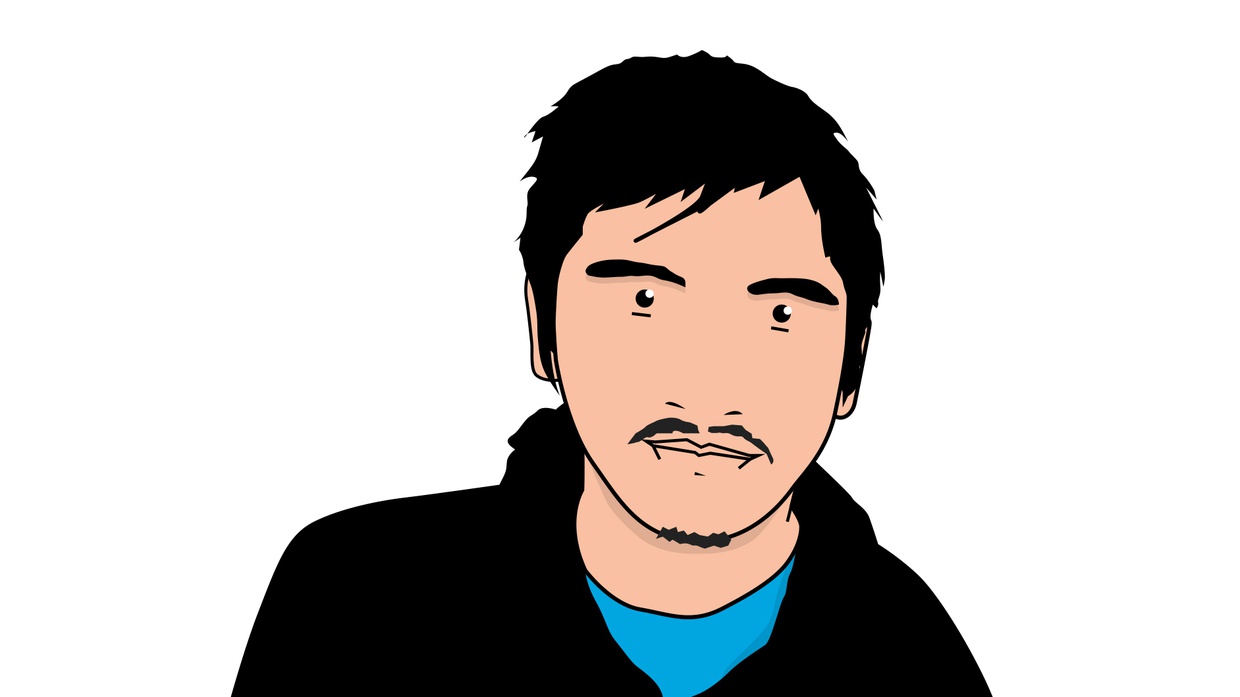tirto.id - Republik ini lahir karena semua orang tahu betapa pahitnya tertindas. Republik ini lahir karena tidak ada orang yang sudi terus-menerus diinjak. Cukup sudah penindasan kolonial. Sudah cukup. Saatnya keadilan ditegakkan. Ya basta!
Itulah inti pledoi “Indonesia Menggugat” yang dibacakan Sukarno di hadapan pengadilan kolonial di Bandung . Apa yang digugat? Penjajahan. Apa yang dituntut? Kemerdekaan. Mengapa kemerdekaan? Karena tanpa kemerdekaan, tidak akan ada keadilan.
Republik ini lahir karena rindu yang tak tertahankan kepada keadilan. Itulah utopia Indonesia.
Dan pada setiap Kamis Sore, sejumlah orang dalam pakaian hitam-hitam berdiri di beberapa tempat, dimulai di Istana Negara pada 17 Januari 2007, lalu berlanjut di beberapa tempat, di antaranya di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka berdiri di sana tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga agar utopia Indonesia tetap menyala, dan keadilan tidak berakhir sebagai nostalgia.
Tapi republik ini justru menjadi panggung penindasan-penindasan baru, menjadi kuil penindasan-penindasan yang lain. Atas nama kejayaan dan kemajuan NKRI, ada banyak sekali rakyat yang harus meregang nyawa. Atas nama stabilitas dan ketertiban NKRI, ada banyak sekali warga yang kehilangan orang-orang tercinta.
Peristiwa 1948, peristiwa 1965, peristiwa 1998, penembakan misterius Petrus, pembantaian di Santa Cruz, di Talangsari, di Tanjungpriok, di Semanggi, DOM di Aceh, operasi militer di Papua, konflik di Poso, di Ambon, di Kalimantan, Wiji Thukul, Munir. Dan jutaan yang lain. Juga yang sedang dan akan kehilangan penghidupan proyek-proyek pembangunanisme yang, dulu berlandaskan GBHN, lalu MP3EI, kini bertajuk RPJMN.
Mereka berdiri setiap Kamis sore untuk memastikan republik tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Mereka berdiri untuk memastikan republik tidak dikendalikan oleh londo-londo ireng yang malah menindas dan menjajah rakyatnya sendiri. Mereka berdiri di sana, terutama, untuk melawan impunitas:
tindakan membiarkan dan/atau melindungi pelaku kejahatan dari tanggung jawab dan hukuman!
Kita sedang menghadapi impunitas yang diberikan diam-diam. Secara resmi negara tidak pernah mengakui impunitas. Tapi kita semua tahu, impunitas sedang dan sudah berjalan. Dikatakan atau tidak, pada praktiknya impunitas sudah berlaku. Para pelaku kejahatan kemanusiaan, entah di Timor Leste, di Papua, di Tanjung Priok, Talangsari atau pada 27 Juli 1997, beberapa di antaranya malah menjadi bagian dari Istana hari ini.
Inilah yang disebut “auto-amnesti". Amnesti otomatis. Ketika rezim tidak berdaya menghadapi para pelaku kejahatan, sehingga rezim memilih cari aman dengan diam-diam, pada dasarnya negara telah memberikan “auto amnesti”. Ini amnesti ilegal, pengampunan tanpa cap resmi, namun dalam praktiknya menjadi pengampunan karena para pelaku kejahatan besar pada akhirnya bisa hidup tenang tanpa gangguan, tak kehilangan apa pun.
Mereka berdiri di sana, setiap Kamis sore, dengan pakaian hitam-hitam, untuk menampik impunitas, untuk menolak impunitas.
Sebab impunitas bukan sekadar kejahatan. Impunitas justru melampaui kejahatan karena memungkinkan kejahatan terulang. Lagi dan lagi. Dengan mengampuni kejahatan secara cuma-cuma, maka impunitas sesungguhnya memungkinkan para penjahat tetap ada dan malah berlipat ganda.
Impunitas bukan barang yang murah. Impunitas bukanlah kacang goreng yang dapat dibeli eceran di pinggir-pinggir jalan. Impunitas bukan milik maling-maling kelas coro, pencopet-pencopet di terminal, atau buruh-buruh di pabrik atau para pelacur di lokalisasi. Impunitas adalah barang yang mahal dan mewah. Impunitas adalah perhiasan orang-orang di lingkaran penguasa, makanan lezat mereka yang memegang senjata dan anggur mahal mereka yang ada di sekitar istana. Hanya penjahat-penjahat besar dan penjahat-penjahat yang terkait dengan mereka-mereka sajalah yang bisa mencicipi lezatnya impunitas.
Melalui impunitas, mereka yang istimewa tetaplah orang-orang lama, yang sama pula. Impunitas adalah antinomi demokrasi karena memungkinkan para penguasa di masa lalu tetap berkuasa di masa sekarang, secara langsung maupun tak langsung. Karena impunitas, siapa pun yang berkuasa, entah itu tukang tahu atau pun tukang kayu, ia akan berada dalam kendali orang-orang lama. Impunitas pada awalnya, dan pada akhirnya, adalah siasat politik untuk memastikan yang kalah tetap kalah, dan yang berkuasa tetap berkuasa.
Impunitas pada akhirnya adalah tali kekang yang menyandera sebuah bangsa agar tak sanggup membereskan persoalan-persoalan di masa silam. “Melawan lupa” akhirnya menjadi siasat untuk bertahan dari arus waktu yang melumerkan ingatan-ingatan tentang peristiwa-peristiwa buruk, kejahatan-kejahatan aparatus negara--pendeknya melawan impunitas.
Tapi impunitas pada awalnya adalah tentang masa lalu, perihal kejahatan yang terjadi pada masa silam. Maka menjadi penting agar “melawan lupa” tidak terjebak sebagai nostalgia. “Melawan lupa” mestinya mengatasi kelampauan, melampaui kesilaman. Caranya: sadar dengan situasi mutakhir, peduli dengan kondisi kiwari. Inilah yang memungkinkan kampanye “melawan lupa” sekaligus menjadi siasat untuk tidak tunduk pada bujuk rayu masa depan yang diiming-imingi oleh pembangunan(isme).
Penting untuk ingat bahwa korban-korban kekerasan dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo pada tahun 1980an juga setara dengan korban-korban penggusuran yang sedang terjadi hari ini: di Kertajati demi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, di Kulon Progo demi pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, di pegunungan Kendeng demi pembangunan Pabrik Semen, di Jakarta Utara dan Teluk Benoa demi reklamasi, dan di banyak tempat lainnya.
“Melawan lupa” seharusnya tidak terjebak pada masa lalu sebagai sebuah insiden an sich, kebetulan semata, melainkan juga memahami masa lalu sebagai sebuah konteks. Memahami konteks sebuah peristiwa kejahatan di masa lalu itulah yang memungkinkan kita bisa menarik benang merah antara yang silam, yang sekarang dan yang menjelang.
Memahami konteks adalah tameng untuk tidak terlena dengan kosa kata macam “relokasi” yang didengung-dengungkan hari ini. Sebab “relokasi” juga menjadi iming-iming rezim Orde Baru saat menggusur di mana-mana. Dengan iming-iming transmigrasi, tanah cuma-cuma, modal dan peralatan bertani (sesuatu yang bergema lagi dalam kosa kata “relokasi” hari ini) ribuan orang dipaksa meninggalkan kampung halamannya. Sudah banyak riset yang menjelaskan bahwa (1) iming-iming itu indah kabar daripada rupa, tak sesuai dengan yang dijanjikan, dan (2) menyediakan bubuk mesiu berupa bibit konflik-konflik yang akhirnya meledak sepanjang fase transisi 1998 dan tahun-tahun setelahnya.
Proyek-proyek pembangunan di rezim sekarang, dalam banyak kasus, juga serupa dengan proyek-proyek pembangunan di masa lalu dalam satu hal penting: dilibatkannya kembali militer sebagai juru gusur ketika perlawanan-perlawanan massa dianggap sudah terlalu solid untuk dicairkan dengan negosiasi. Ini terjadi di banyak tempat, di Jawa maupun luar Jawa.
Sepanjang 2015, menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), setidaknya ada 252 konflik agraria dengan luasan lahan sengketa mencapai 400.430 hektar yang melibatkan 108.714 keluarga. Dari berbagai kasus itu, korban tewas sebanyak lima orang, tertembak aparat 39, luka-luka 124 dan ditahan (kriminalisasi) 278 orang.
Karena mereka bertindak demi pembangunan, atas nama negara, persis seperti di masa silam, kebanyakan para pelaku tidak pernah mendapatkan hukuman yang pantas. Warga yang tewas dan terluka dianggap angin lalu, dan para pelaku bisa dengan tenang melanjutkan hidupnya, meneruskan karirnya. Lagi-lagi sama persis dengan yang terjadi di masa silam: para perwira yang terlibat dalam Tim Mawar yang menculik para aktivis beberapa di antaranya malah menjadi jenderal, dan tetap mendapat promosi jabatan di pemerintahan. Lagi-lagi impunitas!
Apa yang dialami oleh korban-korban di masa silam, apakah itu figur berpengaruh seperti Munir dan Wiji Thukul, maupun ribuan anonim yang tewas dan terluka dalam peristiwa Santa Cruz, Priok, Talangsari, Kedung Ombo, dll., juga sedang mengintai saudara-saudara kita di berbagai tempat: dari Rawajati di Jakarta, Stasiun Barat di Bandung, Sukamulya di Majalengka, Kulon Progo di Yogyakarta, dan ratusan ribu lainnya yang sedang menghadapi penetrasi korporasi-korporasi yang asyik masyuk dengan negara -- entah korporasi agro, tambang hingga properti.
Hari ini kita mengingat Munir, bulan lalu kita mengenang Wiji Thukul, seharusnya bukan semata karena mengenang sebuah nama melainkan merawat sebuah semangat: berpihak pada korban, berdiri di sisi mereka yang dikalahkan. Sebab itulah memang yang dilakukan Munir, sebab itulah juga yang dilakukan Wiji Thukul. Dengan itulah ingatan kepada Munir, ingatan kepada Wiji Thukul, juga ingatan kepada syuhada-syuhada lainnya di masa silam, akan menjadi kerja-kerja yang melampaui waktu.
Ini bukan populisme, ini usaha menghadapi fasisme lama dengan paras yang (agak sedikit) baru.
Jika memang hanya mengingat yang bisa dilakukan, maka teruslah mengingat! Sebab mengingat adalah tanda bahwa rasa sakit tak bisa punah oleh waktu, sebab kesakitan itu masih ada, masih akan ada, dan agaknya masih akan berlipat ganda.
Jika memang hanya mengenang yang bisa dilakukan, maka kita akan terus mengenang! Sebab mengenang adalah bukti bahwa korban bukan semata angka dalam cacah jiwa, tapi juga mereka-mereka yang belum menjadi angka, belum dicatat dan tercatat, sebab masih bergulat dengan kekinian yang begitu sulit dan sempit.
Jika hanya berdiri setiap Kamis yang bisa dilakukan, maka kita akan terus berdiri! Sebab berdiri adalah bukti pegunungan Kendeng, akan terus berlipat ganda--semata agar keadilan tak berakhir hanya sebagai nostalgia.
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id