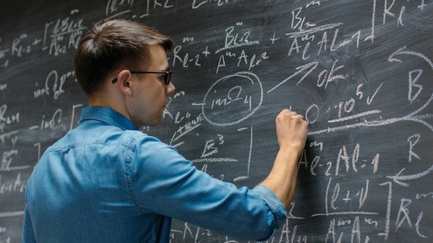tirto.id - Polarisasi politik di Indonesia cenderung tidak lagi begitu terasa sejak Joko Widodo menggandeng Prabowo Subianto masuk ke dalam kabinetnya pada periode kepresidenan 2019-2024. Sejak itu istilah "cebong" vs "kampret" yang sebelumnya mendominasi ruang publik, baik nyata maupun maya, seakan-akan menguap setelah kedua sosok itu memutuskan saling rangkul.
Hubungan keduanya berlanjut dengan berpasangannya Prabowo dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden. Ditambah dengan tidak ada oposisi di parlemen, ketiadaan polarisasi politik tersebut semakin terasa.
Perlu dicatat bahwa ketiadaan polarisasi politik bukannya tanpa konflik. Justru, semenjak para penguasa itu memutuskan bersatu, demonstrasi besar semakin sering terjadi. Pada akhir Agustus 2025 lalu, misalnya, rangkaian demonstrasi besar di berbagai kota kembali terjadi. Ini menunjukkan, meskipun polarisasi politik dalam kanal tradisional tidak lagi terlihat, gap antara (apa yang dilakukan) pemerintah dengan (apa yang dibutuhkan dan diinginkan) rakyat malah terasa semakin besar.
Artinya, polarisasi sebenarnya tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah wujud dan berpindah arena bertanding. Jika sebelumnya polarisasi ini terwujud dalam koalisi versus koalisi antara pemerintah dan parlemen, sekarang ia terejawantahkan dalam "pertarungan jalanan", baik lewat aksi demonstrasi langsung maupun melalui kritik-kritik di media sosial.
Di berbagai belahan dunia lain, polarisasi juga sudah jadi bagian dari kehidupan politik sehari-hari. Di Amerika Serikat, misalnya, khususnya sejak 2015 ketika Donald Trump pertama kali mengumumkan niatnya menjadi presiden, polarisasi ekstrem terus terpelihara hingga kini. Kedua belah pihak, baik kiri (liberal) maupun kanan (konservatif) sama-sama tidak kenal takut menyuarakan isi kepala dan hatinya.
Lalu di Eropa, misalnya, perang ideologi antara mereka yang pro dan kontra terhadap imigrasi masih terus terjadi. Selain itu, ada pula polarisasi yang bersifat global, yang semakin meruncing sejak 7 Oktober 2023, yaitu antara pembela Palestina dan pendukung Israel. Di sini tak jarang terlihat apa yang seharusnya merupakan isu kemanusiaan justru berubah menjadi adu sumpah serapah, bahkan ancaman kekerasan.
Metode Sama, Ideologi Berbeda
Semakin "ekstrem" pandangan seseorang, semakin rentan dia terjebak untuk menjadi sesuatu yang dia benci. Seorang pendukung Palestina, misalnya, menyuarakan dukungannya terhadap negara tersebut lantaran tidak terima melihat anak-anak kecil di Gaza menjadi korban kebiadaban Tentara Pendudukan Israel. Namun, semakin kerap dia terpapar dengan berita-berita yang mengusik hatinya, semakin besar pula kebenciannya terhadap Israel.
Lambat laun, aksinya berubah. Dari yang awalnya hanya menyuarakan dukungan pada Palestina, kini dia secara aktif menyuarakan pembunuhan terhadap orang Israel, bahkan mendukung genosida serupa terjadi pada orang-orang negara tersebut. Pada akhirnya, dia pun mulai menyerupai orang-orang yang dia benci.
Begitulah kira-kira yang dimaksud dengan horseshoe theory, atau teori tapal kuda. Menurut teori ini, spektrum politik tidak berbentuk garis lurus di mana kiri dan kanan sudah pasti berseberangan, melainkan berbentuk macam tapal kuda, di mana kedua ekstrem sejatinya sangat berdekatan.
Gagasan ini sebenarnya sudah muncul sejak era Republik Weimar di Jerman. Kala itu, Otto Strasser dan kelompok Black Front secara terang-terangan menggunakan bentuk tapal kuda (hufeisenschema) untuk menggambarkan posisi mereka sebagai "hibrida" antara komunisme dan nasional-sosialisme. Dua kutub ini berlawanan secara ekstrem dalam spektrum tradisional tetapi disatukan melalui penolakan terhadap kaum borjuis liberal.
Gagasan itu sempat hilang, tetapi bangkit kembali pasca-Perang Dunia II. Sampai akhirnya, di tangan filsuf Prancis, Jean-Pierre Faye, pada awal 1970-an, gagasan ini resmi menjadi horseshoe theory yang dikenal sampai sekarang.
Ada alasan mengapa horseshoe theory begitu populer, terutama karena ia menawarkan penjelasan yang mudah akan sebuah fenomena yang sebenarnya kompleks. Dalam beberapa kasus, kaum ekstrem kanan dan kiri memang tampak mirip.
Mereka sama-sama menaruh kecurigaan pada elite dan institusi arus utama (pemerintah, media, lembaga internasional), sama-sama suka menggunakan retorika untuk membingkai situasi sebagai sebuah pertarungan eksistensial, sama-sama enggan berkompromi dalam politik, dan sama-sama doyan menggunakan taktik seperti demonstrasi serta mobilisasi akar rumput.
Namun, tentu saja, horseshoe theory bukannya tidak punya penentang. Dari yang sudah dijabarkan sebelumnya, apa yang terlihat sama antara kaum kiri dan kanan itu hanyalah metodenya, bukan dari sisi ideologi serta tujuan dari ideologi itu sendiri.
Hal ini ditegaskan pengajar ilmu politik Kingston University London, Simon Choat, dalam kolomnya di The Conversation. Dia memberi contoh, baik kaum kiri maupun kanan sama-sama menentang globalisasi. Akan tetapi, keduanya punya alasan dan tujuan berbeda. Kaum kiri ingin versi berbeda dari globalisasi yang ada saat ini, yaitu versi yang tidak memberikan kendali penuh pada kapital dan tidak memperlebar jurang sosio-ekonomi. Sementara, kaum kanan ingin mengembalikan dunia ke era sebelum globalisasi di mana nilai tradisional negara mereka yang homogen masih terjaga dengan baik.
Solusi yang ditawarkan pun pada akhirnya berbanding terbalik, tulis Choat. Di saat kaum kiri menuntut agar semua orang punya kebebasan bergerak yang setara, kaum kanan justru ingin membatasi pergerakan manusia lintas negara.
Kritik serupa disampaikan penulis dan aktivis Cory Doctorow dalam esainya. Menurutnya, perbedaan antara kiri dan kanan terletak pada apa yang mereka kritik. Kaum kiri sering kali mengkritik suatu kebijakan karena belum cukup progresif (incomplete). Sebaliknya, kaum kanan mengkritik kebijakan karena dianggap sudah melewati batas (overshoot).
Artinya, horseshoe theory sering kali tampak masuk akal di permukaan. Akan tetapi, semakin dalam telaah yang dilakukan, ia sering kali gagal menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada. Celakanya pula, teori ini acap jadi cara suatu pihak mendelegitimasi pergerakan suatu kelompok. Biasanya, kelompok kirilah yang jadi korban delegitimasi ini hingga pada akhirnya orang awam melihat mereka tidak ada bedanya dengan kelompok kanan ekstrem (yang sering kali merupakan organisasi terlarang).
Hasil Riset: Ekstrem Kiri dan Ekstrem Kanan Sama Saja
Meski demikian, sebuah studi neurologi terbaru justru berpihak kepada horseshoe theory. Studi ini dilakukan oleh Daantje de Bruin dan Oriel FeldmanHall dari Brown University, dan diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology: Attitudes and Social Cognition tahun 2025. Mereka ingin mencari tahu, apakah otak orang-orang dengan pandangan ekstrem merespons politik dengan cara yang serupa, terlepas dari posisi mereka di spektrum.
Penelitian ini melibatkan 44 partisipan dengan spektrum ideologi yang beragam, dari ekstrem kiri hingga ekstrem kanan. Mereka kemudian diminta menonton potongan debat calon Wakil Presiden Amerika Serikat tahun 2016 antara Tim Kaine dan Mike Pence, yang berfokus pada isu imigrasi dan kepolisian.
Selama menonton debat tersebut, aktivitas otak partisipan direkam menggunakan fMRI, sementara respons fisiologis mereka diukur melalui skin conductance (reaksi keringat sebagai penanda gairah emosional). Setelahnya, peneliti juga melakukan eye-tracking untuk melihat fokus visual partisipan terhadap stimulus tertentu.
Debat tersebut juga dipecah menjadi segmen-segmen 15 detik dan dianalisis menggunakan model bahasa besar (LLM) untuk mengukur tingkat “ekstremitas bahasa” dalam setiap segmen. Fungsinya, agar para peneliti dapat menghubungkan intensitas bahasa politik dengan respons otak dan fisiologis partisipan.
Hasilnya? Semakin ekstrem pandangan ideologis seseorang, semakin tinggi pula aktivitas otaknya di area-area yang terkait dengan emosi, deteksi ancaman, dan pemrosesan sosial seperti amigdala, periaqueductal gray (PAG), dan posterior superior temporal sulcus (pSTS). Dan ini berlaku untuk partisipan beraliran ekstrem kiri maupun ekstrem kanan.
Menariknya lagi, ketika data mereka disandingkan, terlihat bahwa pola aktivitas otak orang-orang berhaluan ekstrem kiri dan kanan lebih sinkron dibandingkan dengan orang-orang berhaluan moderat.
Tak sampai di situ, bahasa juga mempertegas kesamaan yang terekam. Semakin ekstrem dan provokatif bahasa yang digunakan Pence dan Kaine, sinkronisasi otak di area seperti temporoparietal junction (TPJ) dan pSTS meningkat secara signifikan. Mereka juga menunjukkan respons fisiologis yang serupa.
Dengan kata lain, orang ekstrem kiri maupun kanan punya cara memproses informasi yang serupa, setidaknya secara neurologis. Ini artinya, yang menentukan cara otak memproses informasi bukan soal spektrum, melainkan soal seberapa ekstrem mereka berada dalam spektrum (tradisional) tersebut.
Meski demikian, para peneliti juga menyadari keterbatasan dalam penelitian mereka. Pertama, konteksnya memang sempit karena hanya di Amerika Serikat. Artinya, kultur dengan norma berbeda bisa jadi akan menunjukkan respons berbeda. Kedua, topik yang dibahas juga hanya berkisar pada imigrasi dan kepolisian. Topik lain, menurut mereka, bisa jadi juga akan membuat para partisipan menunjukkan tanggapan yang berbeda.
Mencari Jembatan dan Menumbuhkan Empati
Sebelumnya telah disebutkan bahwa studi De Bruin dan FeldmanHall tadi berpihak pada horseshoe theory. Akan tetapi, apakah itu berarti horseshoe theory sepenuhnya benar? Tidak sesederhana itu.
Dalam wawancara dengan PsyPost, De Bruin secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari eksperimen ini adalah untuk mencari jembatan antara kelompok ekstrem kiri dan kanan.
"Menyadari kesamaan pengalaman ini bisa menumbuhkan empati yang lebih besar sekaligus mengurangi dehumanisasi yang selama ini terjadi dalam politik yang terpolarisasi," ujarnya.
Artinya, De Bruin secara tidak langsung mengakui bahwa, ya, memang perbedaan itu ada. Kalau tidak, untuk apa jembatan diperlukan?
Kesamaan pola aktivitas otak tidak serta-merta jadi pembenaran terhadap teori tapal kuda, melainkan peluang untuk memahami dinamika emosional yang sering kali menjadi bahan bakar ekstremitas. Dan ekstremitas sendiri bukan posisi politik. Ia adalah cara seseorang merasakan dan merespons apa pun, termasuk dunia politik, secara intens.
Artinya, horseshoe theory lagi-lagi menemui kegagalan bahkan lewat studi yang tampak berpihak padanya. Iktikad De Bruin dan FeldmanHall sudah tepat karena mereka ingin mengurangi kadar dehumanisasi yang selama ini jadi senjata andalan para ekstremis tadi. Namun, bukan berarti menyamakan kanan dan kiri begitu saja, apalagi dengan nada peyoratif, bakal menyelesaikan masalah.
Pada praktiknya, kuncinya tak lain adalah dialog dengan kepala dingin. Dalam politik, diskursus adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan justru berbahaya kalau sampai tidak terjadi. Kanan dan kiri akan selalu ada, tinggal bagaimana mereka melakukan diskursus secara beradab dan bermartabat.
Penulis: Yoga Cholandha
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id