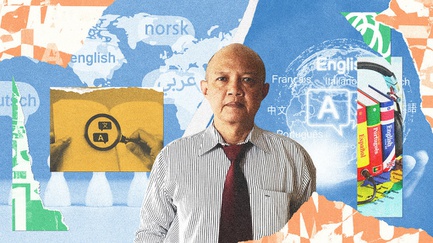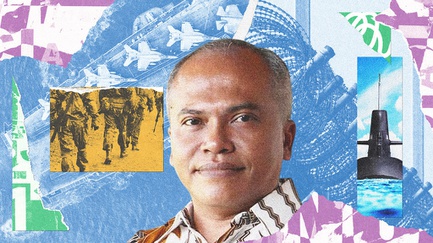tirto.id - Kalimat yang meluncur dari mulutnya tegas: "Kalau tidak mau (membeli gabah petani dengan HPP atau harga pembelian pemerintah Rp6.500/kg), kita tutup saja, enggak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih, negara akan ambil alih penggilingan padi. Berapa besar pun penggilingan padi itu kalau main-main saya akan tindak," kata Presiden Prabowo Subianto. Di depan jajaran Kementerian Pertanian, Senin (3/2/2025), Prabowo menggarisbawahi kembali kebijakan pemerintahannya: keberpihakan kepada rakyat (kecil).
Ketua Umum Partai Gerindra itu tahu pengusaha harus untung, tapi kesejahteraan petani harus diutamakan. Ia tak ingin pengusaha ambil untung seenaknya, misal, dengan alasan kadar air dan kualitas gabah. Sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dua periode (2004-2015), tentu ia tahu bagaimana petani kecil menjadi korban. Prabowo mengutip ucapan Sukarno yang amat tersohor: pangan adalah soal hidup-matinya bangsa. Bagi dia, petani, pengusaha, dan konsumen harus sama-sama untung. Tak boleh ada yang ditinggalkan.
Sejak dilantik sebagai presiden, 20 Oktober 2024, Prabowo menabalkan tekadnya untuk meraih kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, air, dan energi. Tekad dalam Asta Cita itu diulang-ulang di berbagai forum. Salah satu wujud konkret keberpihakan kepada petani (kecil) adalah mengharuskan BULOG, pedagang, dan penggilingan padi membeli Gabah Kering Panen (GKP), apa pun kualitasnya, dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp6.500/kg.
Saya tak bisa memastikan, tapi sepertinya regulasi tersebut adalah “sejarah baru”. Selama berpuluh tahun, yang berlaku adalah HPP dan rafaksi harga, yakni HPP yang turun sesuai kualitas.
Keputusan HPP itu, kata Prabowo, diambil dalam rapat terbatas bidang pangan yang ia pimpin pada 30 Desember 2024. HPP naik karena biaya usaha tani naik. Sebagai regulator perberasan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengatur HPP dan rafaksi gabah dan beras lewat Keputusan Kepala Bapanas No. 2/2025 pada 12 Januari 2025.
Dalam regulasi baru itu, HPP naik dari Rp6.000/kg jadi Rp6.500/kg GKP di petani. Syaratnya: maksimal kadar air 25% dan kadar hampa 10%. Pembelian beras di gudang BULOG naik dari Rp11 ribu/kg jadi Rp12 ribu/kg dengan kualitas derajat sosoh 100%, dan maksimal kadar air, butir patah, dan menir masing-masing sebesar 14%, 25%, dan 2%. Diatur pula rafaksi harga gabah. Misal, GKP berkadar air 26-30% dan kadar hampa 11-15% dihargai Rp5.950/kg alias turun Rp750/kg dari HPP yang jadi patokan.
Rupanya, sejak awal Januari 2025 daerah-daerah sentra produsen padi yang mulai panen, seperti Jawa, Sumatra Selatan, Lampung, dan Aceh diguyur hujan lebat. Sebagian sawah bahkan dilanda banjir. Kualitas gabah amat dipengaruhi cuaca. Ketika panen bersamaan dengan mendung atau hujan, mutu GKP bisa rendah. Mutu gabah semakin jelek tatkala padi terkena banjir. Kadar air yang biasanya 21–26% bisa melonjak di atas 30-35%. Kadar hampa naik, bulir gabah menghitam. Ujung dari semua ini, harga gabah jatuh. Di sejumlah daerah dilaporkan bahwa harga GKP turun, bahkan di bawah Rp5.500/kg.
Tak ingin menghukum petani dengan harga rendah akibat cuaca, lahirlah regulasi “sejarah baru” yang mengharuskan semua pihak membeli Rp6.500/kg GKP, apa pun kualitasnya. Ini diatur lewat Keputusan Kepala Bapanas No. 14/2025 pada 24 Januari 2025. Regulasi baru ini mengubah drastis isi Keputusan Kepala Bapanas No. 2/2025.
Pertama, HPP Rp6.500/kg GKP di level petani tanpa syarat kualitas. Kedua, rafaksi harga gabah ditiadakan. Tak ada pengaturan pembelian GKP di penggilingan dan di gudang BULOG serta pembelian Gabah Kering Giling (GKG). Pembelian beras di BULOG tidak diubah.
Beleid baru ini, di satu sisi, menguntungkan petani yang memiliki gabah kualitas rendah. Di sisi lain, bersifat disinsentif bagi petani dengan gabah kualitas baik, karena semua kualitas gabah dihargai sama: Rp6.500/kg GKP. Dari sisi ini, regulasi tersebut tentu tak mendidik. Akan tetapi, boleh jadi, ini strategi pemerintah untuk mengerek harga gabah lebih tinggi.
Selama ini harga pasar selalu di atas HPP. Hanya pada panen raya, Februari-Mei, adakalanya harga jatuh di bawah HPP. Karena kemampuan BULOG menyerap gabah hanya 10%, 90% sisanya diharapkan dibeli swasta dengan harga lebih tinggi.
Masalahnya, dengan HPP Rp6.500/kg GKP dan harga beras di gudang BULOG Rp12.000/kg, itu masih belum memungkinkan swasta (pedagang dan penggilingan) menyetorkan beras ke BULOG tanpa menanggung kerugian. Pelaku usaha baru bisa menyetorkan beras ke BULOG tanpa merugi apabila harga Rp6.100-Rp.6.150/kg GKP. Tentu ini tidak menguntungkan petani. Karena itu, harga pembelian beras di gudang BULOG perlu dinaikkan agar pengadaan beras BULOG berjalan lancar.
Pemerintah tidak menugaskan BULOG impor beras tahun ini seperti 2 tahun terakhir. Tahun 2023 BULOG mengimpor beras 3,06 juta ton dan 3,84 juta ton pada 2024. Keputusan ini konsekuensi target swasembada beras dipercepat. Implikasinya, BULOG harus mengalihkan semua sumber stok sepenuhnya dari produksi domestik.
Januari-April 2025 ini BULOG ditarget menyerap 3 juta ton beras dari klaim surplus 4 juta ton. Ini tak mudah, karena harus menyerap 0,75 juta ton beras/bulan. Sejak BULOG berdiri tahun 1967 belum pernah bisa menyerap sebesar itu dalam sebulan. Ini seperti mission impossible.
Tak Mungkin Jadi Mungkin
Agar mission menjadi possible, pertama, pemerintah perlu ‘menyederhanakan’ regulasi pengadaan gabah/beras. Pembelian gabah hanya berbentuk GKP tanpa syarat kualitas adalah bagian dari penyederhanaan itu. Makanya rafaksi harga gabah ditiadakan. Penyederhanaan ini menabrak kaidah “ada kualitas ada harga”. Tiadanya pengaturan rafaksi harga GKP bakal menyulitkan adjusment di lapangan.
Apakah BULOG diberikan peluang membuat aturan rafaksi harga GKP sendiri? Bagaimana pertanggung jawabannya ketika dilakukan audit? Uang APBN yang harus dipakai prudent. Kalau tidak, siap-siap antre masuk penjara.
Regulasi pembelian hanya GKP di petani bisa dimaknai agar BULOG menyerap langsung gabah dari petani. Ini baik dan ideal agar BULOG tidak lagi menyerap melalui mitra/pihak ketiga. Masalahnya, selain fasilitas pengeringan dan penggilingan terbatas, BULOG tidak biasa membeli gabah langsung dari petani karena jejaring terbatas. Karena itu kerja sama dengan penggilingan, termasuk yang tergabung di Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), menjadi keharusan.
Akan tetapi, PERPADI yang sebagian besar adalah penggilingan kecil meminta agar derajat sosoh beras diturunkan jadi 95%. Jika ini diakomodasi, penyerapan beras mungkin besar tetapi kualitas dikorbankan. Ini juga menabrak cita-cita bahwa penggilingan harus naik kelas.
Kedua, turbulensi berulang di tubuh BULOG sejak akhir Januari 2025 hingga saat ini adalah bagian dari mengubah agar mission menjadi possible. Posisi Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik yang strategis dibelah menjadi dua: Direktur Pengadaan dan Direktur Operasional dan Pelayanan Publik. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik tetap dipercayakan kepada Mokhamad Suyamto, lalu Direktur Pengadaan diisi oleh internal BULOG lewat promosi. Tentu harapannya ‘mesin’ pengadaan BULOG bergerak cepat.
Belum genap dua pekan menjabat, Direktur Pengadaan dicopot dan digantikan pejabat dari Kementerian Pertanian. Lalu, Ketua Dewan Pengawas BULOG yang dijabat Kepala Bapanas setahun terakhir dialihkan kepada Wakil Menteri Pertanian. Turbulensi berlanjut dengan pergantian Direktur Utama Wahyu Suparyono oleh Mayjen TNI Nova Helmy Prasetya, Direktur Keuangan Iryanto Hutagaol oleh eks Anggota dan Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, dan Anggota Dewan Pengawas Wicipto Setiadi oleh Komjen Pol. (Purn.) Verdianto Iskandar Bitticaca. Apa bongkar-pasang ini terkait ide Menteri Amran Sulaiman agar BULOG di bawah komando Kementerian Pertanian? Wallahua’lam.
Ketiga, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang sepenuhnya menggunakan dana bank berbunga komersial, untuk memperkuat penyerapan kali ini BULOG dibekali ‘amunisi’ Rp16,6 triliun. Semula anggaran ini untuk operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras. Ditambah pinjaman dengan subsidi bunga 3% dari bank-bank pemerintah, total tersedia dana Rp39 triliun.
Pengalihan anggaran Rp16,6 triliun ini, di satu sisi, berpeluang membuat penyerapan optimal tanpa kendala pendanaan. Di sisi lain, karena anggaran dialihkan, penyaluran beras berhenti. Beras BULOG menumpuk di gudang. Penerima bantuan harus membeli beras di pasar.
Saat ini di gudang BULOG ada stok 1,9 juta ton. Apabila target penyerapan 3 juta ton beras tercapai separuh saja, itu berarti total beras yang dikuasai BULOG mencapai 3,4 juta ton pada April 2025. Dengan aset sebanyak 474 kompleks gudang dengan 1.545 unit berkapasitas lebih 3,8 juta ton, gudang BULOG masih mampu menampung. Akan tetapi, jika target penyerapan 3 juta ton beras tercapai, terlepas bagaimana cara mencapainya, BULOG mau tidak mau harus bekerja sama dengan mitra yang memiliki gudang.
Akan tetapi, masalah belum selesai. Ketika tidak ada penyaluran, hal krusial lainnya adalah beras akan menumpuk di gudang sebagai stok mati (dead stock). Kualitas beras dapat turun, bahkan rusak, apabila terlalu lama disimpan. Idealnya usia beras hanya 4 bulan. Lebih dari itu harus disalurkan. Kalau penyaluran beras tak kunjung dipastikan karena anggaran cekak, pemerintah harus bersiap dengan segala risiko yang bakal terjadi. Salah satu konsekuensi penurunan derajat sosoh menjadi 95% adalah beras mudah tengik.
Apa yang hendak disampaikan dari uraian panjang-lebar ini adalah formulasi kebijakan perberasan saat ini semakin jauh dari akal sehat dan kaidah ilmiah. Dejavu, situasi ini seperti perulangan 10 tahun lalu. Saat itu, pelaku industri perberasan dihantui ketakutan karena pemerintah mengedepankan pendekatan non-pasar saat mengintervensi pasar.
Bisa jadi ada strategi tersembunyi yang tengah ditempuh pemerintah yang tidak mampu penulis ‘baca’. Misalnya, disrupsi ini sengaja dibuat untuk melihat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat BULOG menjadi super kuat, seperti keinginan Presiden. Jika dugaan ini benar, para pembantu presiden perlu meracik aneka kebijakan lanjutan yang komprehensif pascadisrupsi. Jika tidak, ongkos yang harus ditanggung terlalu mahal.
Penulis adalah pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), penulis buku "Bulog dan Politik Perberasan" (Penerbit Obor, 2022) serta "Ekonomi Politik Industri Gula Rafinasi: Kontestasi Pemerintah, Importir, Pabrik Gula, dan Petani" (IPB Press, 2021).
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id