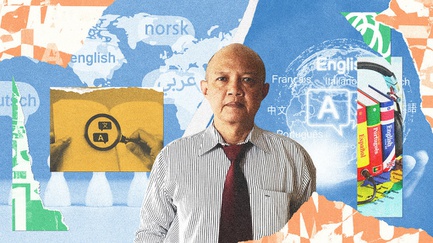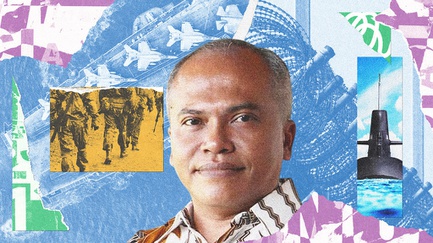tirto.id - Masih teringat jelas bagaimana mentor saya kehilangan istrinya pada Selasa, 20 Mei 2025 silam. Sang istri meninggal bukan karena penyakit yang tak bisa disembuhkan, tapi justru karena efek antibiotik. Sebelum meninggal, almarhumah mengidap tuberkulosis (TBC), penyakit menular yang hingga kini belum memiliki vaksin universal dan hanya bisa diatasi dengan antibiotik.
Sayangnya, antibiotik dengan dosis kuat, diberikan terus-menerus tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi organ dalam, justru menjadi bumerang. Organ hati tidak mampu memproses beban antibiotik tersebut, sehingga memicu kerusakan berantai pada paru-paru, sistem saraf, hingga infeksi yang menyebar ke otak.
Singkatnya, istri mentor saya meninggal bukan karena kalah melawan penyakit, melainkan karena tubuhnya lebih dulu ambruk disebabkan obat yang justru dipakai dengan maksud menyelamatkan.
Dalam kasus absennya vaksin universal, antibiotik memang menjadi satu-satunya harapan. Namun, harapan itu bisa berbalik menjadi ancaman jika tidak disertai dengan kewaspadaan menyeluruh.
Jika penggunaan antibiotik secara tepat saja mengandung risiko fatal, bagaimana jadinya dengan antibiotik yang digunakan tanpa resep, tanpa diagnosis, tanpa pemahaman? Inilah kenyataan yang kita hadapi hari ini. Di Indonesia, hal ini bukan sekadar kasus medis, melainkan persoalan budaya yang sudah mengakar di masyarakat.
Antibotik Bukan Panasea
Menurut Kementerian Kesehatan (2023), 6 dari 10 orang masih memperoleh antibiotik tanpa resep dokter. Tak jarang, antibiotik diberikan begitu saja oleh tetangga, dibeli di warung, atau direkomendasikan lewat grup WhatsApp keluarga, seolah-olah panasea, obat mujarab serba guna.
Generasi demi generasi mewarisi keyakinan yang keliru bahwa antibiotik adalah obat segala penyakit. Dampaknya, pola pikir demikian membentuk epidemi senyap; resistensi antibiotik berkembang karena kesalahan dianggap biasa.
Pada 2019, The Lancet mencatat lebih dari 34.500 kematian langsung dan 133.800 kematian tidak langsung di Indonesia akibat infeksi bakteri yang sudah kebal terhadap antibiotik. Secara global, resistensi antibiotik diprediksi akan merenggut 10 juta jiwa pada 2050, melampaui gabungan kematian akibat stroke, diabetes, dan HIV/AIDS.
Untuk memahami mengapa angka ini terus melonjak, kita perlu mengetahui bagaimana antibiotik bekerja. Antibiotik dirancang untuk menyerang bagian vital bakteri, ibarat merobohkan tembok atau merusak sistem replikasinya. Namun, antibiotik sama sekali tidak efektif untuk melawan virus atau jamur. Sayangnya, sebagian besar keluhan harian seperti flu, batuk, dan demam yang sering kali diobati dengan antibiotik justru disebabkan oleh virus, bukan bakteri.
“Penyakit yang umum diderita masyarakat (Indonesia) penyebabnya adalah virus. Jadi sebetulnya, minum antibiotik tidak tepat. Bahkan antibiotik mempunyai efek collateral damage yang memicu bakteri dalam tubuh kita berproses mutase menjadi resisten," Dr. dr. Hari Paraton SpOG(K), Ketua Aliansi Antimikroba Indonesia.
Bahaya Superbug, Mutasi Mikroba yang Melampaui Tubuh Kita
Resistensi tidak hanya berlangsung dalam tubuh manusia, tetapi juga menyebar ke lingkungan. 30%-90% antibiotik yang dikonsumsi tidak terserap dan dibuang melalui urin. Di Indonesia, pembuangan limbah domestik tanpa sistem pengolahan memadai telah mengubah sungai menjadi laboratorium terbuka bagi mutasi mikroba.
Tak kalah mengkhawatirkan, penelitian Kusuma dkk (2021) menyebutkan bahwa hanya 53,4% rumah sakit yang benar-benar menerapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara efektif. Padahal, rumah sakit adalah pengguna antibiotik dalam jumlah besar. Tanpa pengolahan limbah yang layak, fasilitas kesehatan justru menjadi simpul mutasi bakteri yang tak terkendali.
Dari fenomena-fenomena inilah muncul ancaman paling menakutkan dalam dunia mikrobiologi klinis bernama superbug. Bakteri tidak hanya tahan terhadap satu antibiotik, tetapi terhadap semua jenis antibiotik yang tersedia.
Laporan CDC (2023) mengklasifikasi superbug sebagai "pandemic potential pathogens." Artinya, jika tidak dikendalikan, ia dapat menyebabkan pandemi global seperti halnya COVID-19. Superbug bisa menjadi pemicu pandemi global berikutnya.
Bedanya, jika COVID-19 bisa dicegah dengan vaksin,superbug tidak bisa ditangkal dengan satu pun antibiotik. Jika infeksi menyebar, tak ada antivirus, tak ada vaksin, dan tak ada cadangan antibiotik baru. Ini bukan lagi spekulasi. Superbug telah muncul di India (NDM-1), Amerika Serikat (KPC), bahkan sudah ditemukan di Indonesia.
Ketika Tubuh Menjadi Medan Perang Tanpa Senjata
Ironisnya, ancaman sebesar ini tidak diimbangi oleh kesiapan sistem yang ada. Padahal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SKNI/1186 telah lama menyatakan bahwa antibiotik tergolong obat keras. Lemahnya pengawasan dan fragmentasi sistem informasi membuat peredarannya tetap tak terkendali.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, prosedur medis dasar seperti operasi usus buntu, melahirkan secara caesar, atau pencabutan gigi yang terinfeksi bisa berubah menjadi tindakan berisiko kematian. Bahkan aktivitas sederhana seperti memotong sayur, bermain di kebun, atau tergores duri pun bisa menjadi jalan masuk infeksi bakteri mematikan jika tubuh kita tak lagi kuat melawan.
Kisah Albert Alexander, polisi Inggris sekaligus orang pertama di dunia yang secara klinis diobati dengan penisilin, sudah seharusnya menjadi pengingat nyata. Pada 1941, Albert terkena infeksi parah hanya karena luka kecil akibat duri mawar. Meski kondisinya sempat membaik, keterbatasan pasokan penisilin saat itu membuat pengobatannya terhenti dan nyawanya tak tertolong.
Jika demikian halnya, kita akan hidup dalam ketakutan setiap hari, sebab luka kecil saja bukan lagi masalah kecil. Superbug menjadikan tubuh kita medan perang tanpa senjata untuk bertahan.
Preskripsi Digital Nasional, Upaya Menutup Celah
Untuk menutup celah tersebut, sistem Preskripsi Digital Nasional perlu diterapkan. Sistem ini mengandalkan QR Code sebagai identifikasi resep sah yang hanya dapat dikeluarkan oleh dokter melalui sistem milik Kementerian Kesehatan. Setelah diagnosis, dokter menginput resep, menghasilkan QR unik yang dapat dicetak atau diakses melalui aplikasi SATUSEHAT dan BPJS.
Di apotek, kode QR ini dipindai dan diverifikasi dengan KTP pasien. Jika diwakilkan oleh keluarga, verifikasi hubungan dengan KK atau catatan dokter diperlukan. Jika data tidak cocok, penebusan dibatalkan. Seluruh transaksi tercatat otomatis, sehingga pola penggunaan bisa dipantau, lonjakan resistensi terdeteksi, dan jalur distribusi ilegal bisa ditutup sejak awal.
Mewujudkan preskripsi digital bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi juga menuntut orkestrasi lintas sektor agar terbentuk ekosistem yang hidup dan adaptif. Kementerian Kesehatan perlu menjadi dirigen utama dan memastikan standar sistem dijalankan seragam secara nasional.
Pada saat bersamaan, BPOM harus mengawasi distribusi antibiotik dari pabrik hingga apotek. Ikatan Dokter Indonesia bertugas mensosialisasikan dan memastikan tenaga medis menerapkan prinsip presisi. Ikatan Apoteker Indonesia bertindak sebagai gerbang terakhir yang memverifikasi semua penebusan antibiotik.
Urgensi Pengawasan Menyeluruh Lintas Sektor

Tak hanya pada manusia, jejak penyalahgunaan antibiotik juga terjadi di sektor pangan. WHO (2024) mencatat, 7 dari 10 antibiotik global digunakan di peternakan, bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk mempercepat pertumbuhan. Di Indonesia, pemberian antibiotik pada unggas, ikan, dan udang masih lazim tanpa pengawasan ketat.
Residu dari praktik tersebut masuk ke tubuh manusia melalui makanan, memicu resistensi secara diam-diam. Sebab itu, preskripsi digital juga harus menjangkau sektor ini. Antibiotik hanya boleh disalurkan oleh dokter hewan berlisensi, tercatat dalam sistem digital, dan diawasi Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tanpa pengawasan menyeluruh dari hulu ke hilir, kebocoran akan terus terjadi.
Sebagai solusi, langkah ini bukan impian belaka. Inggris telah membuktikan efektivitasnya melalui English Surveillance Programme for Antimicrobial Utilisation and Resistance (ESPAUR), berbasis kerangka Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS) dari WHO.
Hasilnya? Konsumsi antibiotik turun 7% dalam 4 tahun dan resistensi ikut menurun signifikan. Kuncinya dua: pengawasan berbasis data dan verifikasi sistem, bukan kepercayaan belaka.
Teknologi tanpa pemahaman hanyalah ilusi solusi, dan sistem preskripsi digital sekadar alat. Hal yang membuatnya berdampak adalah literasi. Masyarakat perlu dibekali prinsip dasar bahwa antibiotik bukan untuk semua penyakit, semua orang, semua waktu. Ia spesifik dan temporal.
Edukasi harus menekankan pentingnya menyelesaikan resep, tidak berbagi obat, tidak melakukan self-diagnosis, serta memahami risiko penggunaan antibiotik. Bahkan saat antibiotik menjadi satu-satunya pilihan, pasien tetap harus menggunakan haknya untuk bertanya: Adakah alternatif lain? Apakah organ tubuh saya cukup kuat? Pemeriksaan menyeluruh menjadi langkah preventif yang wajib dilakukan.
Peringatan
Sebagai bagian dari pendekatan edukatif, setiap antibiotik yang ditebus wajib disertai lembar peringatan resmi. “Obat ini harus dihabiskan sesuai petunjuk dokter. Tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Konsumsi sembarangan dapat memperkuat bakteri di tubuh Anda.”
Efektivitas pendekatan ini diperkuat oleh temuan empiris Saleem dkk (2021) yang menunjukkan bahwa label berbasis pemahaman pasien meningkatkan kepatuhan hingga 83,6%. Dalam konteks resistensi, edukasi kecil seperti ini bisa menjelma menjadi system pertahanan besar.
Kita hidup pada zaman ketika kemajuan medis tidak lagi diukur dari seberapa banyak obat ditemukan, tetapi seberapa bijak kita menggunakannya. Antibiotik bukan sekadar obat. Ia adalah warisan sains, dan seperti semua warisan besar, antibiotik bisa hilang jika disalahgunakan.
Dengan demikian, perjuangan melawan resistensi bukan hanya urusan pemerintah, rumah sakit, atau dokter. Ini keputusan harian kita semua. Bertanya sebelum menelan. Menyelesaikan dosis. Menolak membeli tanpa resep. Dan terus bertanya, “Apakah antibiotik ini betul-betul perlu?”
Mungkin, pertanyaan paling sederhana itulah yang mampu menyelamatkan hidup. Bukan hanya hidup kita, tapi generasi yang akan datang. Bila sistem ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, terintegrasi, berbasis data, serta disertai edukasi yang kuat, Indonesia punya peluang nyata untuk memperlambat laju resistensi.
Namun, sebaliknya, superbug akan menjadi pandemi berikutnya jika upaya preventif semacam itu tidak segera dilakukan. Jangan sampai bencana global datang dan tak bisa dilawan dengan vaksin serta tak bisa diobati dengan antibiotik, bukan karena kelalaian satu orang, melainkan karena kelengahan kita semua.
*Penulis adalah mahasiswa jurusan Bioteknologi Universitas Brawijaya, penerima Djarum Beasiswa Plus (Beswan Djarum) 2024/2025. Tirto.id bekerjasama dengan Djarum Foundation menayangkan 16 Finalis Nasional Essay Contest Beswan Djarum 2024/2025. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
*Penulis adalah mahasiswa jurusan Bioteknologi Universitas Brawijaya, penerima Djarum Beasiswa Plus (Beswan Djarum) 2024/2025. Tirto.id bekerjasama dengan Djarum Foundation menayangkan 16 Finalis Nasional Essay Contest Beswan Djarum 2024/2025.
Editor: Zulkifli Songyanan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id