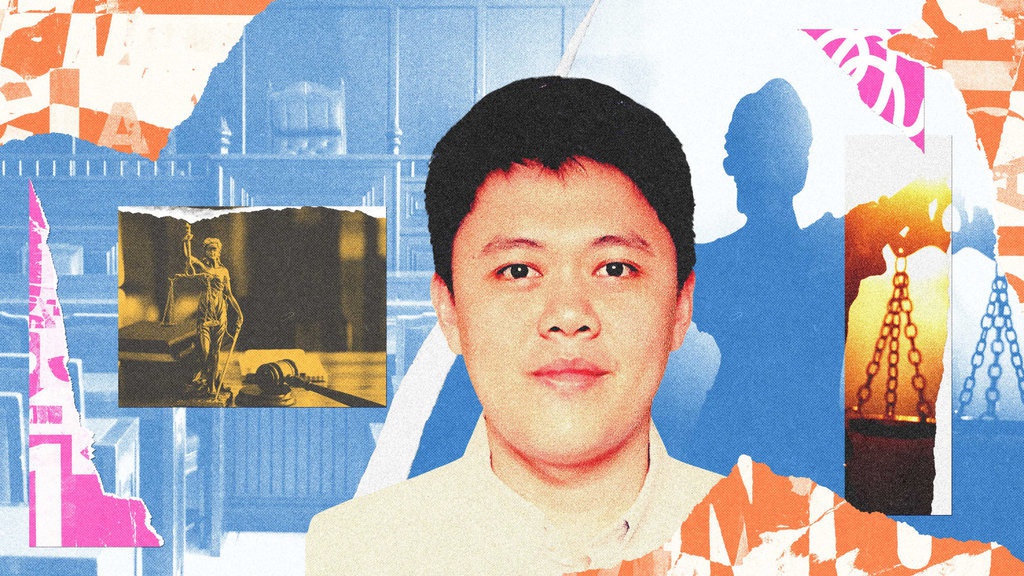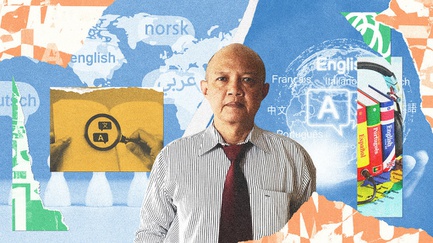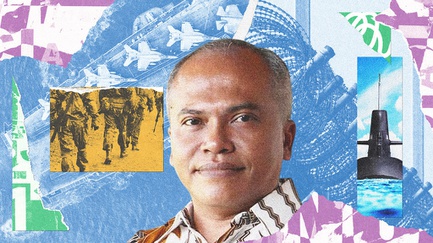tirto.id - Kontroversi tentang kebijaksanaan Presiden memberikan abolisi bagi Tom Lembong dan amnesti bagi Hasto Kristianto perlu dipahami berdasarkan paradigma hubungan hukum dan politik.
Di satu sisi, pemerintah dan elite politik telah mengungkapkan bahwa Presiden memang telah membuat keputusan demi kepentingan politik, seperti yang diberitakan. Di sisi lain, terdapat tudingan bahwa keputusan tersebut merupakan politisasi penegakan hukum yang sangat berbahaya.
Baik sisi pro maupun kontra tersebut memiliki asumsi tentang legalitas dan legitimasi. Perbedaannya terletak pada apa yang paling dianggap memiliki daya ikat atau normatif oleh setiap sisi. Keputusan yang dibuat Presiden dikatakan legal, sah menurut aturan konstitusi, namun legitimasinya lemah menurut para aktivis antikorupsi. Sebaliknya, kritik tentang politisasi hukum bertumpu di atas pendasaran legal bahwa korupsi harus diberantas, sekali pun langit runtuh. Tapi justru kemungkinan langit runtuh tersebut menimbulkan keragu-raguan: bukankah masih ada yang lebih penting, yakni seperti persatuan dan pembangunan?
Pendekatan realisme hukum menawarkan jalan keluarnya.
Paham ini mengajak kita untuk melihat hukum sebagai pengalaman empiris mengenai kinerja pranata, profesi, dan budaya hukum. Pandangan yang khas realis tentang hukum, antara lain, dinyatakan eksponen utamanya, Stewart Macaulay (2003) di dalam artikelnya “The Real and the Paper Deal: Empirical Pictures of Relationships, Complexity and the Urge for Transparent Simple Rules”, yakni bahwa “Orang dapat merespons masalah dengan cara menyangkalnya”.
Dengan itu, masalahnya adalah bukan apa yang seharusnya paling mengikat, tetapi apakah abolisi Tom dan amensti Hasto adalah bentuk penyangkalan terhadap masalah empiris tentang pranata, profesi, dan budaya hukum Indonesia?
Analisis yuridis tentang polemik pemberantasan korupsi di tanah air kerap diarahkan pada keberadaan pasal karet UU Tipikor. Padahal pasal karet yang demikian tidak akan berdampak jika penegak hukum tidak menggunakannya.
Bahaya sesungguhnya dari pasal karet adalah ketika “pengadilan kanguru” menerapkannya. Di sini perbandingan hukum menjadi penting. Istilah ini lahir dari budaya hukum Amerika Serikat (justru bukan dari Australia) yang memiliki pengalaman tentang jenis pengadilan manipulatif. Dalam memutus perkara, pengadilan ini bukan mengacu pada asas-asas hukum acara dan tujuan-tujuan hukum tentang kebenaran, melainkan klaim sepihak, seperti halnya para penambang ilegal Amerika Serikat di abad ke-19 yang sesuka hati mendaku lahan milik orang lain (claim-jumper).
Bagi semua pencari keadilan dan keluarganya mendapat pengampunan adalah ibarat menemukan oase sejuk di tengah padang gurun. Motivasi Presiden untuk menjaga persaudaran nasional pun patut kita apresiasi karena ikhtiarnya untuk membina stabilitas politik. Tetapi, para yuris akan memandang bahwa itu semua merupakan kemenangan Pyrrhis. Konon di tahun 281 SM, Raja Pyrrhus sukses mengalahkan pasukan Romawi di tenggara Italia. Harga yang mesti dibayar dari kesuksesan ini sangatlah mahal dan Raja Pyrrhus pun terlampau banyak kehilangan. Alhasil, kemenangan itu sama dengan kekalahan.
Kehilangan pertama dari kemenangan ini adalah pencaplokan sistem peradilan sebagai pranata negara (state capture) yang terus leluasa dilangsungkan berkat budaya patronase para pejabat. Yang kedua adalah krisis keilmuan hukum doktriner yang relevansinya menjadi lenyap karena antara ranah praktis dan akademis hukum tidak ada lagi kesinambungan metodologi. Kesibukan memperdebatkan legalitas dan legitimasi membuat setiap analisis hukum dan politik lalai memperhatikan keduanya.
Gambaran Empiris
Kini saatnya memikirkan ulang konsep politisasi hukum dan kriminalisasi untuk menyingkap penyebab terjadinya pengadilan kanguru. Di dalam budaya hukum kita, keduanya mengalami peyorasi akibat kompleksitas yang harus dihadapi setiap wacana tentang kinerja pranata hukum. Politisasi hukum sedemikian mudah dikatakan sehingga makna “politik” menjadi nihil, sedangkan pengertian kriminalisasi menjadi sulit dibedakan dari penyalahgunaan hak (misbruik van recht). Untuk itu, dibutuhkan gambaran yang lebih empiris tentang pencaplokan pranata peradilan kita.
Peradilan adalah panggung depan tempat pergulatan yang serius mengenai hak warga dan argumen-argumen formal khas dari hakim, advokat, dan jaksa. Yang tak kalah serius adalah panggung belakang di mana berbagai klaim sepihak bertarung untuk menang dalam menentukan hasil panggung depan. Operasi panggung depan dan belakang ini bukan sekadar suatu kontradiksi atau paradoks makna, melainkan cara berpikir ganda (double thinking, double thought) dan disonansi kognitif yang efektif berlangsung di dalam pengadilan kanguru. Ini serupa dengan kisah-kisah fiksi George Orwell dan Franz Kafka.
Upaya menganalisis relasi panggung depan dan belakang tersebut paling banter menghasilkan dua penjelasan. Pertama, terdapat cawe-cawe penguasa pada sistem peradilan, seperti yang umum dipersepsikan oleh masyarakat kita. Kedua, ancaman otokrasi, seperti yang ditampilkan para pengamat kritis, seperti yang ditulis R. William Liddle tentang “Kisah Dua Demokrasi” (Kompas, 27 Juli 2025). Perspektif seperti ini menganggap bahwa panggung belakang lebih penting. Akibatnya, berbagai penjelasan tentang panggung depan tidak dapat diseriusi dan kita pun tidak sanggup menunjuk relasi keduanya.
Relasi panggung depan dan belakang dimungkinkan berkat adanya personalisasi pranata hukum. Hakikat dari sebuah pranata adalah fasilitas yang berasal dari bahasa Perancis, facilité. Artinya, suatu pranata ada untuk mempermudah segala hal yang tadinya dianggap sulit. Pranata hukum ada karena dibutuhkan oleh kekuasaan negara modern untuk mempermudah tercapainya tujuan-tujuan melayani bangsanya.
Pranata hukum yang diubah menjadi panggung ganda malah membuatnya mempersulit. Ini adalah semacam instrumentalisasi hukum dalam arti yang negatif. Alih-alih didorong oleh tuntutan supaya hukum lebih responsif terhadap kesejahteraan warga, di Indonesia hari ini instrumentalisasi dilakukan oleh penguasa atau pejabat, yakni lewat patronase terhadap kepemimpinan pranata hukum. Praktis, lembaga-lembaga yudisial, termasuk penegak hukum, berubah menjadi perumus klaim-klaim sepihak yang didasarkan pada formalitas aturan.
Krisis Ilmu Hukum Doktriner
Apa yang lenyap sekaligus yang paling menderita kekalahan melalui abolisi Tom dan amnesti Hasto adalah otoritas hukum.
Kehilangan ini pertama-tama menyangkut ketiadaan kapabilitas analisis yuridis. Otoritas hukum yang dicampur-aduk dengan klaim sepihak di dalam pengadilan kanguru membuat analisis yuridis apa pun tidak bernilai karena terbentuk dikotomi yang sesat, yakni antara formalitas versus informalitas di dalam cara berpikir dan menalar hukum.
Semua calon sarjana hukum paham bahwa seharusnya kebalikan dari formalitas dalam cara berpikir hukum doktriner (yakni bahwa aturan harus dideskripsikan dan disistematisasi, lantas disubsumsikan ke dalam fakta) adalah cara berpikir substantif (yakni berdasarkan evaluasi atau pertimbangan ekstra-legal, seperti moralitas dan policy). Ketika formalitas aturan malah dikaitkan dengan informalitas klaim sepihak, maka yang terbentuk adalah persis relasi panggung depan dan belakang. Akibatnya argumentasi hukum dan putusan hakim diragukan sebagai sekadar formalitas, bungkus, atau panggung depan yang penentunya berasal pemenang klaim dari panggung belakang.
Kehilangan ini memberikan sinyal paling kuat bagi dunia pendidikan tinggi hukum nasional, yakni untuk segera memperbaharui metodologinya mempelajari hukum supaya lebih empiris dan realis. Fakultas hukum dan para pengajarnya sangat mungkin untuk menyangkal urgensi ini dan persis di situlah letak krisisnya. Bagaimana pun, kehilangan dan kekalahan ini adalah momentum untuk memperkuat sistem hukum dari akar pendidikannya yang sudah keburu tertatih-tatih di belakang kecepatan pembentukan opini media sosial,
Semua Demi Bangsa
Supaya kita tidak menikmati kemenangan Pyrrhis, maka janganlah semua hal dilakukan demi pemerintahan, tapi demi bangsa. Abolisi dan amnesti adalah pranata hukum, sama halnya dengan sistem peradilan dan pemberantasan korupsi. Instrumentalisasi hukum dalam konteks negara kesejahteraan atau negara penyelenggara memang tak terhindarkan. Pertanyaannya adalah demi siapa hukum itu dibuat atau ditegakkan?
Ini mengingatkan kita pada petuah mendiang tokoh hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo. Ia berada di garis depan dalam merespon pengalaman instrumentalisasi hukum atas nama trilogi pembangunan Orde Baru. Katanya: “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.
Secara konstitusional, negara memiliki kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga pemerintah (tanpa akhir -an) alias eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudisial. Ketika bekerja atas nama bangsa, ketiganya itu berkapasitas sebagai pemerintahan dan bertanggung jawab hanya untuk mewujudkan empat tujuan negara di dalam Pembukaan UUD 1945.Pranata hukum bukanlah alat dari pemerintah, pemerintahan, atau siapa pun itu, melainkan berfungsi mengemban kekuasaan negara. Maka, kemenangan yang sejati adalah dengan memberdayakan otonomi sistem peradilan dan pendidikan tinggi hukum supaya lebih realis dan empiris. []
Dosen Filsafat dan Perbandingan Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Memperoleh Lingling Wiyadharma Fellowship dari Universitas Leiden, Belanda.
Editor: Nuran Wibisono
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id