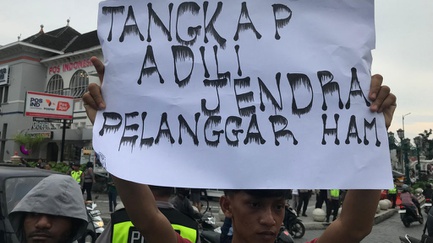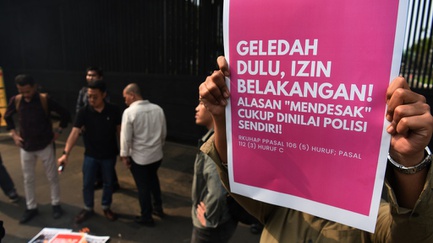tirto.id - Saat memasuki Kabupaten Gianyar, tampak petak-petak sawah milik warga terhampar menguning. Petani sudah bangun sejak ayam berkokok, siap memanen gabah karena masa panen telah tiba menjelang akhir Mei ini.
Tidak ada raut lelah di wajah mereka, bahkan di kala mereka harus menyabit berpuluh-puluh hektar sawah yang tersebar di subak-subak atau mengangkat dedak untuk memberi pakan ternak di kandang-kandang sekitar sana.
Hal yang sama turut terjadi di Desa Keliki yang terletak di Kecamatan Tegalallang. Pagi itu, tampak beberapa petani mengisi galon dengan air dari sumur bor, sementara yang lainnya bergerak mendorong thresher (mesin perontok padi) untuk mengolah hasil panen raya secara langsung.
Uniknya, mesin-mesin tersebut tidak digerakkan oleh energi listrik yang pembangkitnya digerakkan dengan bahan bakar fosil, melainkan oleh energi dari panas matahari.
Desa tersebut berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan posisi di tengah pulau Bali yang memungkinkannya mendapatkan paparan sinar matahari sepanjang tahun.

Potensi tersebut lantas dimanfaatkan Desa Keliki yang memiliki pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dan tersebar di tujuh titik subak, yakni Subak Lauh Batu, Subak Tain Kambing, Subak Uma Desa Keliki, Subak Uma Desa Sebali, Subak Jungut Sebali, Subak Malikode, dan Subak Bangkiang Sidem yang masing-masing memiliki kapasitas 2,5 kWp (kilowatt peak).
“Kendala kita di subak itu pertama, air irigasi di subak kita itu pada saat musim kemarau itu kita kekurangan air. Kedua, kita punya pura, tempat ibadah di masing-masing subak itu yang umumnya jauh dari akses air bersih dan listrik, sehingga kita arahkan PLTS itu ke masing-masing subak,” kata Kepala BUMDes Yowana Bakti Desa Keliki, I Wayan Sumada, kepada Tirto yang sedang mengunjungi lokasi bersama Institute for Essential Services Reform (IESR), Rabu (21/05/2025).
PLTS tersebut merupakan buah dari program tanggung jawab sosial oleh PT Pertamina (Persero) yang dimulai pada 2021. Program tersebut digunakan untuk mendukung demonstration plot (demplot) padi organik milik Desa Keliki, yang seluruh tahapannya—mulai dari pengolahan dan pemupukan—tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Alhasil, hasil tani meroket dari 5,5 ton per hektare menjadi 8,7 ton per hektare.
“Penanaman di Desa Keliki sendiri konsepnya masih banyak spiritualnya, sehingga beras atau nasi yang dihasilkan dari padi kami di sini sudah penuh dengan doa-doa, penuh dengan ritualnya. Contoh, pas padi kita baru mau keluar buah, itu ada upacara mebiukukung, konsepnya kita bersyukur kepada Tuhan karena padi kita sudah mau menghasilkan,” jelas Sumada.
Menurut Sumada, keberadaan PLTS yang menggerakkan pompa air tersebut mampu membuat masyarakat berhemat air bersih untuk keperluan upacara adat, sebab upacara adat biasanya diselenggarakan sebanyak 3 sampai 4 kali dalam siklus panen. Selain itu, instalasi PLTS juga menyelamatkan Desa Keliki ketika musim kemarau panjang tiba, terutama pada puncaknya pada Juli hingga Agustus.
Energi bersih yang dimanfaatkan oleh Desa Keliki menjadi katalis bagi pariwisata di daerah tersebut. Sebelum adanya PLTS, desa tersebut hanya dapat menonton wisatawan berkunjung ke desa terdekat, sebab mereka cenderung melewati Desa Keliki tanpa mampir sejenak.
Namun, ungkap Sumada, sekarang peningkatan kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 200 persen, terbukti tingginya tingkat hunian penginapan dan vila-vila yang ada di sana.
“Kita hanya jadi penonton, sehingga kita hanya mendapatkan komplain-komplain dari mereka (pemandu wisata). Dari sanalah, kita mulai menata desa, yaitu dengan membuat suatu program di BUMDes berupa unit usaha pengelolaan sampah,” terangnya.

Tingginya tingkat hunian vila di Desa Keliki tersebut memberikan dampak positif bagi Desa Keliki yang namanya sudah terkenal hingga mancanegara, bahkan kerap digunakan sebagai percontohan Desa Berdikari oleh berbagai kementerian. Alih fungsi lahan yang dikhawatirkan menjadi dampak negatif dapat dikendalikan melalui pararem (peraturan) desa adat.
“Investor luar tidak dapat sembarangan masuk, yang sekarang ini semuanya lokal, yang punya sawah sendiri, dia membangun sendiri-sendiri. Itu tidak lebih dari 30 persen lahannya mereka, sisanya tetap sawah,” tegasnya.
Sumada mengakui, Desa Keliki sayangnya masih bergantung pada Pertamina yang merupakan inisiator dan pendamping dari keberadaan PLTS tersebut. Apabila terdapat kerusakan pada salah satu PLTS, maka Sumada harus memanggil teknisi Pertamina dari kota untuk menanganinya. Oleh sebab itu, dia mengatakan belum saatnya menambah jumlah PLTS di desa tersebut.
“Namun, beberapa bulan yang lalu, dua orang warga kita diberikan pelatihan ke Jakarta. Mereka sudah sedikit-sedikit mengerti dengan PLTS ini. Masih belum berpengalaman karena mereka ini basic-nya bukan di sini,” ungkapnya.
Mengolah Sampah Menjadi Pupuk Pertanian
Selain di tujuh subak Desa Keliki, satu instalasi panel surya turut terpasang di tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, and recycle (TPS3R) dengan kapasitas 10 kWp. Tempat itu dapat dikatakan kecil dan sederhana, tetapi cukup untuk mengolah sampai dengan 3 hingga 4 ton sampah per minggu untuk menjadi pupuk kompos bagi pertanian warga setempat.
“Di sini (TPS3R) kita pilah lagi, yang besar kita cacah menggunakan mesin cacah. Setelah itu, kita fermentasi dengan eco-enzyme yang dibuat sendiri menggunakan sisa-sisa buah-buahan yang sudah termasuk sampah juga. Kita tumpuk selama 2 minggu, baru kita balik supaya fermentasinya merata,” jelas Manager Fasilitas TPS3R Desa Keliki, Gede Adnyana, di lokasi.
Aroma tidak sedap yang biasa menguar dari sampah tidak tercium dari TPS3R Desa Keliki. Adnyana mengungkap hal tersebut diakibatkan warga setempat telah teredukasi dengan pengolahan sampah dari sumber. Terdapat 21 kader kebersihan yang menjadi ujung tombak perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah menjadi tiga jenis: organik, anorganik, dan residu.
“Sampah yang basah ditaruh di atas, di bawahnya sampah kering, lalu ditumpuk kembali dengan sampah kering. Jadi bau dari sampah itu tidak menyengat. Selama 12 minggu kita kontrol suhu dan kelembapan dia, rata-rata suhunya 70 hingga 75 derajat Celcius,” bebernya.

Sebanyak 1028 KK Desa Keliki dapat menghasilkan sekiranya 7 ton sampah setiap harinya. Sekiranya 1 ton sampah organik di antaranya masuk ke TPS3R Desa Keliki untuk diolah menjadi kompos. Selama dua minggu, mereka mampu menghasilkan 500 hingga 600 kilogram kompos yang digunakan untuk pertanian di subak-subak warga setempat.
“Kita banyak menyalurkan kepada petani-petani yang ada di sekitaran TPS3R. Selain untuk mendukung padi organik, kita juga mendistribusikan ke penduduk yang memerlukan kompos, itu kita jual dengan harga yang relatif murah,” kata Adnyana.
Sementara itu, Alvin Sisdwinugraha, Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan dari IESR, menilai keberhasilan yang telah diraih Desa Keliki dapat menjadi model yang dapat direplikasi ke komunitas-komunitas lainnya. Sebelumnya, desa itu menjadi atensi dunia usai dikunjungi delegasi-delegasi Energy Transition Working Group (ETWG) pada helat G20 2022.
“Pemanfaatan energi terbarukan di tingkat komunitas menjadi aspek krusial dalam mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) 2045. Contoh nyata dari penerapan ini adalah penggunaan PLTS atap di banjar-banjar, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan listrik lokal, tetapi juga meningkatkan kemandirian energi komunitas,” tutup Alvin.
Desa Puhu Manfaatkan Kotoran Jadi Biogas
Tidak hanya masyarakat Desa Keliki yang memanfaatkan alam untuk membantu kehidupan sehari-harinya. Beranjak kian ke utara, masyarakat Desa Puhu di Kecamatan Payangan berhasil memanfaatkan sapi dan babi untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti memasak dan listrik. Hingga 2024, desa padat peternakan tersebut memiliki 117 unit reaktor keluarga dengan produksi rata-rata 1,5 m³ biogas per hari.
Salah satu sosok yang memanfaatkan biogas untuk penghidupannya adalah Ketut Sepot (62), warga Banjar Carik di Desa Puhu yang berprofesi sebagai peternak babi. Dia telah memanfaatkan biogas semenjak tahun 2008 akibat mendengar informasi dari tetangganya mengenai kotoran hewan yang dapat diubah menjadi bahan bakar untuk kompor dapur.
“Makanya saya tertarik juga bikin itu karena bahan-bahannya cuma kotoran. Terpenting tetap memelihara ternak, bisalah jadi lancar. Saya cari orang yang tahu bikin ini (instalasi biogas), saya ajak ke sini, lalu dibuatkan juga,” ucap Sepot kepada Tirto yang bertandang ke lokasi, Rabu (21/05/2025).
Sepot memiliki enam ekor babi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas pada instalasi berukuran 4 kubik. Setiap hari, kotoran-kotoran ternak tersebut masuk melalui pipa ke dalam tabung instalasi. Dari hasil kotoran babi setiap harinya, dia dapat menyalakan dua kompor secara bergilir untuk memasak nasi beserta lauk pauknya, atau sampai dengan 2 jam pemakaian.
“Dulu, awalnya instalasinya sejajar dengan tempat ternak. Makanya saya kewalahan, terus ambil kotorannya terus langsung diaduk di sini. Sekarang sudah pindah, babinya di atas, langsung dia masuk ke bubah. Kadang-kadang (kotorannya) digunakan untuk pupuk,” katanya.

Dari instalasi tabung, tersambung pipa sepanjang 70 meter ke kompor di rumah Sepot dan warungnya. Pipa tersebut dikontrol menggunakan keran dengan gasometer yang terhubung. Apabila terjadi kerusakan pipa, maka aliran biogas dari kandang menuju tabung instalasi dan kompor dapat dihentikan.
Menurut Sepot, pembuatan lubang penampungan kotoran beserta instalasinya secara lengkap membutuhkan biaya sebesar Rp5 juta pada 2008. Ia berencana menambah kapasitas menjadi 6 meter kubik, namun biaya pembangunannya melonjak hingga Rp15 juta pada 2025.
Tingginya biaya tersebut membuatnya lebih berhati-hati dalam mengatur pakan ternaknya. Pada 2015, saluran pembuangan kotoran sempat tersumbat akibat kotoran babi yang masih mengandung banyak partikel kasar. Untuk menghindari kejadian serupa, saat ini ia menggunakan campuran dedak dan konsentrat yang bertekstur lebih cair.
“Pernah macet gara-gara makan babinya dulu dicampur dengan ketela rambat dan pohon pisang. Ada gumpal-gumpalannya, banyak yang mengendap. Makanya sampai tersumbat, enggak mau masuk airnya. Saya minta saran teman, disuruh ngobok-obok dengan bambu yang dipecah empat, langsung kembali bisa,” tutur Sepot sambil tertawa, mengenang kejadian tersumbatnya saluran tersebut.
Sayangnya, pemanfaatan biogas di Banjar Carik dapat terbilang cukup minim. Hanya Sepot yang masih konsisten menggunakan biogas dari kotoran ternak. Dia masih telaten merawat instalasi biogas yang harus dibersihkan secara rutin, terutama agar bisa bertahan hingga lebih dari 15 tahun.

Babi-babi di kandang Sepot dapat dikatakan terawat dan bersih. Enam babi indukan yang digunakan sebagai sumber kotoran biogas tampak sehat dengan berat 50 hingga 300 kilogram. Alih-alih dijual, babi-babi tersebut memang digunakan oleh Sepot untuk keperluan sehari-harinya.
“Ini (biogas dari babi) sangat mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau dulu, tetap pakai LPG, tetapi sekarang LPG cuma digunakan untuk serep (cadangan), terutama di upacara hari raya besar, seperti Galungan,” ujarnya.
Di sisi lain, Manager Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum, mengatakan bahwa Desa Puhu merupakan contoh nyata transisi energi dan ekonomi sirkular yang berkaitan dengan kearifan lokal.
Menggunakan limbah peternakan untuk menghasilkan biogas dan pupuk organik, Desa Puhu tidak hanya berhasil menghemat energi dan menurunkan emisi, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi peternaknya melalui koperasi.
“Setiap rumah tangga dapat menghemat kurang lebih 180 kilogram LPG. Koperasi ‘Puhu Lestari’ menampung dan menjual pupuk organik, menambah pendapatan peternak kurang lebih 4 juta per tahun. Inilah inovasi desa yang tidak boleh dipandang sebelah mata,” tutupnya.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Anggun P Situmorang
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id