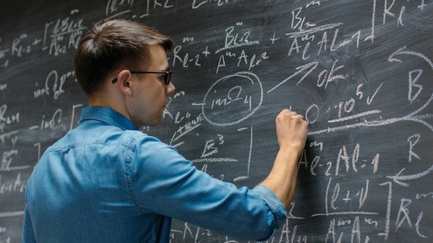tirto.id - Bangsa Indonesia adalah bangsa paling dermawan. Itu bukan klaim tak berdasar, bukan pula slogan jingoisme. Itu adalah temuan nyata dari riset tahunan yang dilakukan oleh Charities Aid Foundation (CAF) dan diterbitkan dalam bentuk World Giving Index (WGI).
Setelah pada 2018 sukses mendongkel Myanmar dari pucuk "klasemen", posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan tak pernah tergoyahkan hingga 2024. Skor indeks Indonesia pun terus naik dalam kurun tersebut, dari yang awalnya 59 pada 2018 hingga mencapai ponten 74 pada 2024. Angka itu jauh sekali dari rata-rata dunia yang ada di angka 31 pada 2018 dan mentok di skor 40 pada 2024.
Namun, Indonesia akhirnya kehilangan "gelar" tersebut pada 2025, seiring dengan berubahnya WGI menjadi World Giving Report (WGR). Tak tanggung-tanggung, posisi Indonesia melorot ke ranking ke-21 dari 101 negara. Tanpa menyebutkan skor kedermawanan Indonesia, WGR menyebutkan, rakyat Nigeria, sebagai negara paling dermawan, mengeluarkan 2,83 persen pendapatannya untuk berdonasi. Sementara itu, persentase yang dikeluarkan orang Indonesia berada di angka 1,55 persen.
Satu hal yang pasti, ada perubahan metodologi antara WGI dan WGR. Oleh karena itu, tidak diketahui secara pasti pula apakah orang Indonesia memang jadi lebih pelit dibanding sebelumnya atau tidak. Yang jelas, angka 1,55 persen itu masih membuat level kedermawanan Indonesia berada di atas rata-rata global. Dengan demikian, klaim bangsa yang dermawan itu, secara teknis, masih berlaku untuk Indonesia.
Ditambah lagi, sebuah makalah bertajuk Guilt drives prosociality across 20 countries yang diterbitkan oleh empat peneliti—masing-masing dari Prancis, Belanda, Jerman, dan Amerika—justru menunjukkan hal bertolak belakang dari temuan CAF. Dari 20 negara yang diteliti, Indonesia berada di posisi terbawah, bahkan lebih rendah dari negara-negara Barat macam Jerman, Belanda, serta Amerika Serikat.
Kok, bisa?
Studi Rasa Malu vs. Rasa Bersalah
Studi dalam makalah Guilt drives prosociality across 20 countries tadi melibatkan 7.978 peserta dari 20 negara yang dianggap mewakili konteks budaya berbeda. Indonesia, misalnya, dalam studi tersebut dianggap mewakili "African, Islamic", sama seperti Mesir, Kenya, Maroko, Nigeria, dan Turki. Adapun kultur lain yang ikut dipelajari adalah Amerika Latin, Negara Berbahasa Inggris, Konfusianisme, Protestan Eropa, Asia Barat dan Selatan, serta Katolik Eropa.
Tujuan dari penelitian itu sederhana saja: mencari tahu hal sebenarnya yang mendorong orang berbuat baik. Para peneliti mengajukan satu pertanyaan besar: apakah orang akan lebih terdorong berbuat baik jika mereka mengetahui konsekuensi dari perbuatannya atau justru jika tindakan tersebut disaksikan oleh orang lain?
Dalam penelitian itu, para peneliti menggunakan eksperimen ekonomi yang dikenal sebagai dictator game. Setiap partisipan, ceritanya, menerima sejumlah uang dan harus memutuskan akan menggunakan uang itu untuk apa. Apakah mereka bersedia membantu orang yang tidak diketahui identitasnya atau justru menyimpannya untuk diri sendiri?
Eksperimen dilakukan dalam tiga kondisi berbeda yang dirancang untuk membedakan antara peran rasa bersalah (guilt) dan rasa malu (shame) dalam proses pengambilan keputusan.
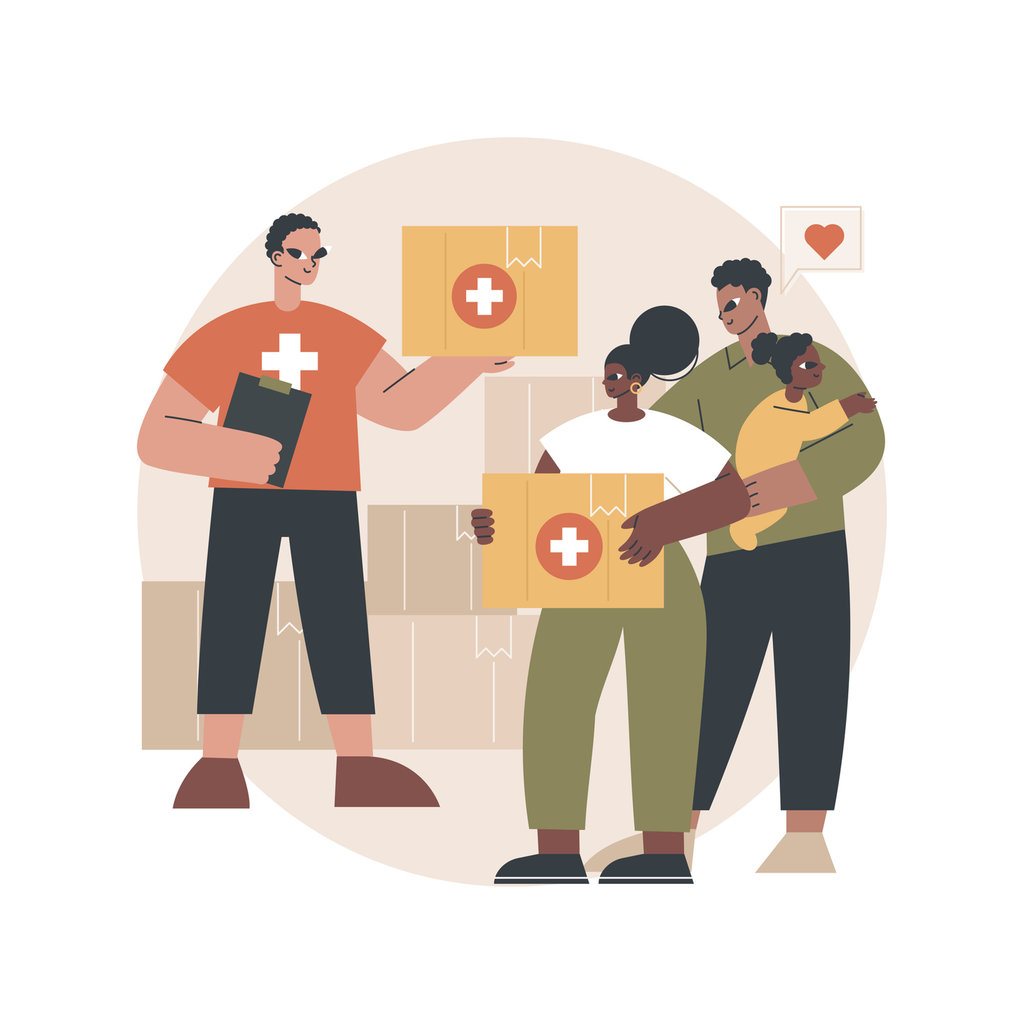
Dalam kondisi pertama yang disebut "Informasi Tersembunyi", partisipan tidak mengetahui dengan pasti dampak keputusannya terhadap pihak lain. Mereka bisa mencari tahu, atau tidak mencari tahu, hal yang akan terjadi terhadap penerima jika mereka tidak membagikan uangnya. Dengan demikian, partisipan dapat mengambil keputusan tanpa merasa bertanggung jawab secara langsung terhadap akibatnya.
Adapun kondisi kedua disebut "Informasi Penuh, Privat". Artinya, dalam kondisi itu, partisipan mengetahui secara penuh konsekuensi dari keputusannya dan apa pun keputusan itu hanya diketahui secara privat olehnya. Di sini, yang coba ditimbulkan adalah rasa bersalah.
Kondisi terakhir disebut "Informasi Penuh, Publik". Itu hampir sama seperti kondisi ketiga, tetapi semua keputusan dibeberkan kepada pihak lain dengan nama samaran. Di sini yang diuji adalah rasa malu.
Hasilnya konsisten. Begitu informasi mengenai konsekuensi diberikan secara penuh (kondisi kedua), tingkat kedermawanan meningkat tajam antara 19-33 persen. Dari sini, para peneliti pun menyimpulkan bahwa rasa bersalah berperan universal dalam mendorong perilaku prososial (perilaku yang memberi manfaat kepada orang lain).
Ketika seseorang tidak dapat berpaling dari kenyataan bahwa tindakannya akan berdampak buruk bagi orang lain, mereka cenderung bertindak dermawan. Sebaliknya, memublikasikan keputusan secara publik, yang dimaksudkan untuk menyentil rasa malu, tidak mengubah perilaku. Artinya, rasa bersalah lebih kuat dibanding rasa malu dalam upaya mendorong seseorang melakukan tindakan prososial.
Bagaimana "Capaian" Indonesia?
Sebelumnya sudah disebutkan bahwa studi lintas negara menunjukkan betapa "tidak dermawannya" orang Indonesia. Akan tetapi, perlu dicamkan bahwa peringkat terbawah yang ditempati Indonesia dalam studi itu bukan berarti orang Indonesia tidak mampu bersikap dermawan sama sekali.
Orang Indonesia hanya menempati posisi terbawah dalam eksperimen kondisi pertama--ketika konsekuensi terhadap orang lain tidak diketahui oleh mereka. Banyak orang Indonesia, dalam eksperimen tersebut, memilih tidak mencari tahu dan kemudian tidak memberikan uang. Hanya sekitar 25 hingga 30 persen yang memilih untuk memberi dalam situasi itu.

Tidak dijelaskan alasan orang Indonesia jadi seperti itu. Akan tetapi, dapat diasumsikan, mengingat data dari riset ini diambil dalam kurun 2018-2019, faktor utamanya adalah rasa percaya. Di Indonesia banyak ditemukan pengemis, misalnya, yang ternyata punya mobil sehingga memberi uang tanpa tahu persis peruntukannya bisa jadi hal sulit bagi orang Indonesia.
Buktinya, ketika partisipan Indonesia diberi informasi penuh mengenai konsekuensi dari keputusannya (kondisi kedua), tingkat kedermawanan mereka meningkat tajam, yakni di kisaran 55 hingga 60 persen. Artinya, ketika mengetahui konsekuensi dari keputusannya, orang Indonesia terdorong untuk bertindak lebih dermawan. Dalam hal ini, mereka sama sekali tidak berbeda dibanding orang dari negara lain.
Adapun, pada kondisi ketiga, saat keputusan partisipan diumumkan kepada peserta lain secara anonim, tidak ditemukan perbedaan berarti dibanding kondisi kedua. Ini menarik karena, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Indonesia sering mendengar cerita tentang orang yang bersedekah atau berbuat baik hanya karena ingin dipuji. Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang berbuat ria itu hanyalah outlier dari masyarakat secara umum.
Apa yang Menggerakkan Kedermawanan?
Setelah terbukti bahwa "ketidakdermawanan" orang Indonesia hanya terjadi pada situasi tertentu, lantas apa sebenarnya yang membuat Indonesia pernah tujuh kali berturut-turut jadi negara paling dermawan sedunia?
Jawabannya adalah ekosistem, ketika konteks moral, sosial, dan keagamaan mendominasi lanskap kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Eksperimen seperti yang dilakukan oleh para peneliti dari empat negara tadi sengaja dirancang untuk menghilangkan semua konteks tersebut. Tujuannya adalah melihat tindakan seseorang ketika keputusan memberi sepenuhnya bergantung pada dorongan internal, tanpa tekanan sosial, keagamaan, maupun reputasi. Namun, realitasnya, justru faktor-faktor eksternal itulah yang membentuk dan menggerakkan kedermawanan masyarakat Indonesia.
Salah satu penjelasan yang paling masuk akal terletak pada peran agama. Membantu sesama bukan cuma disarankan tetapi diwajibkan. Praktik filantropi, seperti zakat, infak, dan sedekah, sudah jadi bagian dari keseharian orang Indonesia. Bahkan, data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan kenaikan signifikan dalam lima tahun dalam kurun 2018-2023. Pada 2018, dana yang terkumpul "hanya" sekitar Rp10,2 triliun, sementara pada 2023 angkanya mencapai Rp27,5 triliun.
Nilai gotong royong, yang sudah melekat pada diri masyarakat Nusantara sejak lama, juga punya peranan. Dalam berbagai situasi, membantu orang (asal juntrungannya jelas) bukan cuma datang dari niat pribadi, melainkan juga bagian dari identitas seseorang sebagai anggota komunitas. Dengan kata lain, belum jadi orang Indonesia namanya kalau belum membantu orang, apa pun wujudnya.
Ketika semua konteks ini hadir, masyarakat Indonesia menjadi sangat dermawan, sebagaimana tecermin dalam data World Giving Index. Namun, ketika konteks tersebut dilucuti, ya, hasilnya jadi kontradiktif. Ini sekaligus membuktikan betapa kuatnya peran konteks sosial, agama, dan sejarah, dalam membentuk kedermawanan masyarakat Indonesia.
Penulis: Yoga Cholandha
Editor: Fadli Nasrudin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id