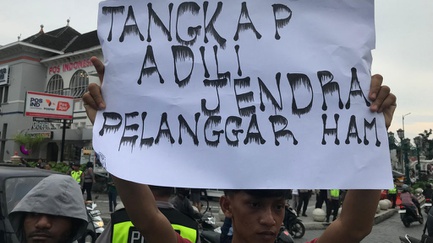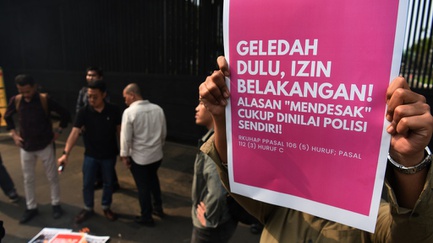tirto.id - Ada dua wajah stigma yang dilekatkan awam pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ): individu berbahaya dan korban yang ditelantarkan. Yang jarang dibicarakan publik adalah bahwa negara sebenarnya juga turut melanggengkan situasi itu karena ia abai menata kebijakan kesehatan jiwa masyarakat.
Kasus viral yang melibatkan ODGJ baru-baru ini menebalkan kondisi tersebut. Di Bengkulu, polisi menangkap NR (18) lantaran membunuh ibu kandungnya, YT (49), pada Sabtu (2/8/2025). Menurut polisi, NR diduga mengalami gangguan kejiwaan dan baru keluar dari Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto, Kota Bengkulu, pada 29 Juli 2025 lalu.
Seturut pemberitaan Antara, RSKJ Soeprapto juga membenarkan bahwa NR menjalani pengobatan kejiwaan sejak 2023. RSKJ Soeprapto memulangkan NR dengan catatan kondisinya baik, tenang, emosinya stabil, dan bisa melakukan aktivitas harian secara mandiri.
NR juga diduga mengalami perundungan, tapi hal ini masih didalami otoritas setempat.
Sementara itu, di Kendal, ODGJ dibunuh oleh seorang pemuda yang tidak menyukai keberadaannya. Tersangka pembunuhan berinisial MHY (30) kini sudah ditahan oleh penyidik Polres Kendal. Kepada polisi, MHY mengaku menusuk korban sebanyak tiga kali hingga korban tergeletak.
Dua kejadian itu setidaknya menunjukkan bahwa negara belum memperhatikan hak-hak ODGJ secara menyeluruh dan malah cenderung abai. Hal ini membuat ODGJ menjadi rentan jadi korban persekusi dan memperburuk kondisinya.
Dewan Pengawas DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), Mahesa Paranadipa Maikel, menyatakan bahwa secara hukum, pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejadian ODGJ yang terlantar.
Pasal 27 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Tanggung jawab ini, ungkap Mahesa, mencakup juga pelayanan kesehatan jiwa, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
“Dasar konstitusionalnya sangat kuat, yaitu Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Mahesa kepada wartawan Tirto, Selasa (5/8/2025).
Menurut Mahesa, pemerintah daerah bisa dianggap lalai apabila ada ODGJ yang terlantar dan membahayakan dirinya serta orang lain. Jadi, pemerintah daerah berkewajiban menjamin ODGJ mendapatkan hak-hak dasarnya.
Layanan Kesehatan Jiwa Belum Ideal
Selain UU Kesehatan, pemeliharaan dan perlindungan ODGJ juga bersandar pada UU Nomor 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa. UU ini mengamanatkan pemenuhan bagi ODGJ, mulai dari hak mendapatkan perawatan yang manusiawi, bebas diskriminasi, hingga rehabilitasi berbasis komunitas.
Mahesa menjelaskan bahwa salah satu kekuatan UU Kesehatan Jiwa adalah pergeseran paradigmanya, dari perawatan di rumah sakit menjadi perawatan terintegrasi di masyarakat.
“Namun, seperti yang sering terjadi, kekuatan regulasi tidak selalu sejalan implementasi di lapangan. Komitmen politik dan alokasi sumber daya di daerah sering kali menjadi hambatan utama,” ujar Mahesa.
Ketidakefektifan regulasi di tingkat daerah disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran dan sumber daya. Berdasarkan data Kemenkes, alokasi anggaran kesehatan jiwa nasional baru sekitar 1 persen dari total anggaran kesehatan di APBN. Di tingkat daerah, angkanya bahkan bisa lebih kecil.
Alokasi ini masih jauh dari standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu minimal 5 persen dari anggaran kesehatan umum. Selain itu, Indonesia masih kekurangan tenaga profesional kesehatan jiwa, seperti psikolog klinis dan psikiater, terutama di puskesmas.
Di Indonesia, hanya tersedia sekitar 0,3 psikiater per 100.000 penduduk—jauh di bawah standar WHO, yakni 1 per 10.000 penduduk. Sebagian besar pusat layanan kesehatan jiwa juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Beberapa provinsi di Indonesia bahkan masih ada yang belum memiliki rumah sakit jiwa atau psikiater.
Layanan kejiwaan di puskesmas pun baru menjangkau sekitar 60 persen unit saja di Indonesia. Artinya, sekitar 40 persen puskesmas tidak menyediakan layanan dasar kesehatan mental.
“Gugatan warga negara [citizen lawsuit] memungkinkan masyarakat menuntut pemerintah daerah yang dianggap lalai dalam menyediakan layanan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa dan hak atas layanan rehabilitasi jiwa berbasis komunitas,” ucap Mahesa.
Sementara itu, staf bidang advokasi Perhimpunan Jiwa Sehat sekaligus anggota Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas, Nena Hutahaean, menyatakan bahwa layanan rehabilitasi ODGJ di tingkat puskesmas dan desa masih sangat terbatas karena tenaga spesialis, seperti psikiater, psikolog klinis, dan perawat jiwa, masih terkonsentrasi di kota-kota besar.
Selain itu, anggaran kesehatan jiwa masih terpusat untuk rumah sakit jiwa. Puskesmas selama ini tidak memiliki alokasi dana khusus untuk layanan kejiwaan berkualitas, termasuk layanan lanjutan dan penyediaan obat.
“Tenaga spesialis juga tidak termasuk dalam formasi standar Kemenkes maupun pemda untuk puskesmas sehingga secara struktural memang tidak tersedia,” ujar Nena kepada wartawan Tirto, Selasa (5/8/2025).
Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial terhadap ODGJ yang masih kuat di masyarakat. Hal itu membikin keluarga enggan melapor atau melakukan asesmen ketika ada anggotanya yang menunjukkan gejala gangguan jiwa. Situasi ini membuat permintaan terhadap layanan kesehatan jiwa rendah, yang akhirnya menghambat pengembangan layanan yang seharusnya dibutuhkan.
Menurut Nena, Kemenkes memiliki peran yang strategis karena berwenang untuk menyusun pedoman, SOP, dan supervisi teknis lewat Direktorat Kesehatan Jiwa. Kemenkes mampu untuk menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) untuk layanan kejiwaan.
Kemenkes sebenarnya sudah berupaya dengan mendorong pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) sebagai salah satu langkah deteksi dini gangguan kejiwaan. Tim ini telah memulai pilot project di Manado pada Oktober 2023.
Menurut Nena, langkah itu sudah tepat untuk mengembangkan layanan promosi-preventif di tingkat komunitas, tak sebatas kuratif di rumah sakit jiwa.
Menghapus Stigma, Membangun Empati
Kemenkes sebenarnya juga terus melakukan upaya destigmatisasi dan deinstitusi untuk mendorong perawatan kejiwaan berbasis masyarakat serta penghapusan pasung.
“Reviktimisasi melalui pengulangan pasung apabila tidak terpantau dan mendapat layanan lanjutan disebabkan tingginya biaya perobatan dan tidak ada layanan lanjutan dengan basis masyarakat yang murah dan berkualitas,” ujar Nena.
Dalam rentang November 2014 hingga Januari 2016, Human Right Watch (HRW) sempat melakukan penelitian tentang praktik pemasungan para penyandang disabilitas psikososial di Indonesia. Hasil riset di Jawa dan Sumatera mendokumentasikan 175 kasus penyandang disabilitas psikososial yang pernah dipasung atau saat ini masih mengalaminya.
HRW juga mencatatkan 200 kasus lain yang terdokumentasi selama beberapa tahun terakhir. Kasus pasung paling lama yang didokumentasikan HRW menimpa seorang perempuan yang dikurung dalam kamar selama hampir 17 tahun.
Peneliti psikologi sosial dari Universitas Indonesia (UI), Wawan Kurniawan, memandang stigma sosial terhadap ODGJ membentuk lanskap psikologis yang penuh prasangka, ketakutan, dan penolakan. Di ruang publik, keberadaan ODGJ sering kali dipandang sebagai gangguan, bukan sebagai bagian dari keberagaman manusia yang sah.
Akibatnya, masyarakat tidak merespons keberadaan ODGJ dengan empati atau pemahaman, melainkan dengan stereotip yang diwariskan secara sosial: bahwa ODGJ berbahaya, tidak terduga, dan mengganggu ketertiban.
Psikologi sosial menyebut fenomena ini sebagai hasil dari proses kategorisasi sosial yang menggolongkan individu ODGJ ke dalam kelompok liyan (out-group) dan dipersepsikan secara negatif.
“Mereka diperlakukan bukan sebagai subjek manusia dengan hak dan kebutuhan, melainkan sebagai objek yang harus dikendalikan, dihindari, atau disingkirkan,” ujar Wawan kepada wartawan Tirto, Selasa (5/8/2025).
Meminggirkan dan menelantarkan ODGJ secara sosial dan struktural menciptakan lingkaran setan eksklusi yang sulit diputus. Di tingkat individu, ODGJ yang terus-menerus distigma dan dijauhkan dari lingkungan sosial akan mengalami isolasi, penurunan harga diri, hingga kekambuhan karena tidak mendapatkan dukungan yang layak.

Tanpa akses ke layanan kesehatan mental, pekerjaan, atau tempat tinggal yang aman, mereka cenderung hidup dalam kondisi yang semakin rentan. Dari sisi sosial, peminggiran memperkuat persepsi bahwa ODGJ adalah beban atau ancaman, bukan bagian dari masyarakat.
Ketika ODGJ tidak diberi ruang untuk berpartisipasi secara setara, masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun sistem yang inklusif dan berkeadilan.
“Lebih dari itu, pengabaian struktural terhadap kesehatan jiwa akan menciptakan beban sosial dan ekonomi jangka panjang: meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran tersembunyi, serta krisis kesehatan mental yang meluas dan tak tertangani,” beber Wawan.
Psikolog klinis, Veronica Adesla, turut menjelaskan bahwa ODGJ membutuhkan penanganan yang tepat untuk dapat pulih, mengelola kondisinya, dan berfungsi dengan baik serta menjalani hidup produktif di tengah masyarakat.
ODGJ dengan tingkat keparahan berat ditandai dengan halusinasi, delusi, dan tingkat agresivitas tinggi, baik ke dalam diri maupun luar diri apabila tidak mendapatkan pengobatan dan tidak berada di bawah pengawasan.
Karenanya, ODGJ membutuhkan penanganan tepat dan dilakukan intensif sesuai dengan anjuran psikiater maupun psikolog dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat keparahan. Penanganan berkesinambungan dapat meliputi terapi medis, terapi psikologi, dan dukungan yang tepat dari sekitar.
“Melalui penanganan yang tepat dapat membantu ODGJ untuk membangun keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat pulih ataupun kembali berfungsi dengan baik hidup berdampingan di tengah masyarakat,” terang Vero kepada wartawan Tirto, Selasa (4/8/2025).
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id