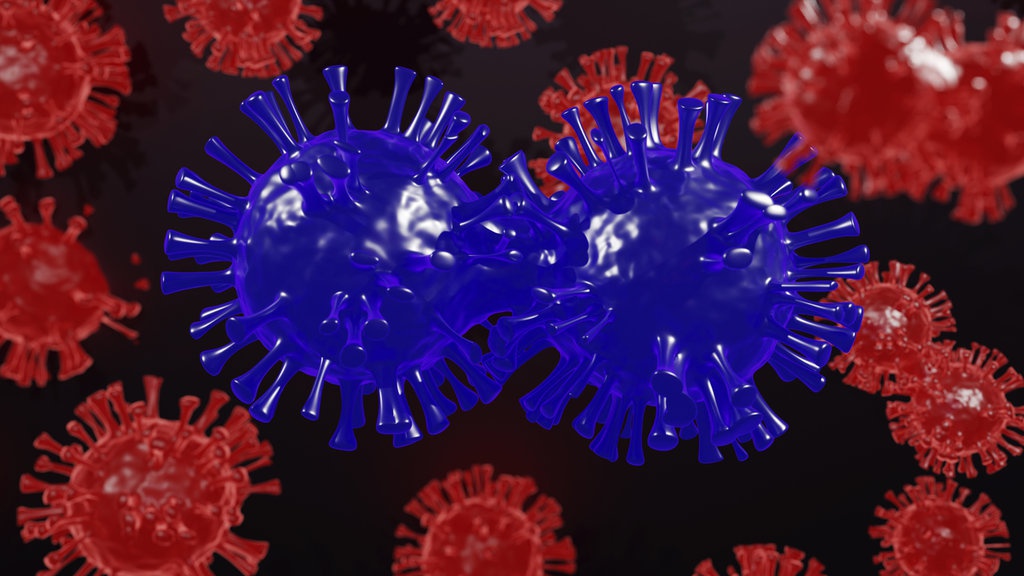tirto.id - Tepat pada 1904, tatkala menjadi peneliti di Cavendish Laboratory, University of Cambridge, Inggris, John Butler Burke hendak melakukan aksi revolusioner di bidang sains. Beberapa tahun sebelumnya, fisikawan asal Perancis bernama Henri Bacquerel dan Marie Curie menemukan fakta bahwa uranium dapat menghasilkan partikel yang memiliki energinya sendiri bernama radium melalui proses radioaktivitas. Burke menduga temuan Bacquerel dan Curie memiliki kesamaan prinsip dengan kehidupan, di mana atom radium yang tercipta dari uranium tidak berbeda jauh dengan ulat yang bertransformasi menjadi ngengat.
Radium dan ngengat memang berbeda dengan partikel/organisme yang melahirkannya, tetapi, sebagaimana dipaparkannya dalam artikel berjudul "The Radio-Activity of Matter" (Monthly Review 1903), "substansinya tetap sama dengan partikel/organisme yang melahirkannya."
"Maka," menurut Burge, "segala perbedaan yang diyakini ahli biologi, misalnya makhluk hidup dan benda mati, keliru. Segala benda (matter) sesungguhnya adalah makhluk hidup. Ini tesis saya." Tesis inilah yang menjadi inti tindakan revolusioner di bidang sains yang kelak diambil Burke, yakni menciptakan kehidupan dari benda mati.
Dalam upaya membuktikan tesisnya, Burke melakukan eksperimen dengan memasak potongan daging sapi dalam air yang telah ditaburi garam dan gelatin. Tentu, bukan sop buntut yang hendak diciptakannya, melainkan kaldu yang kemudian dimasukan ke dalam tabung reaksi untuk disterilkan melalui proses pembakaran di atas tungku api. Usai meyakini bahwa kaldu yang dibuatnya terbebas dari sel atau mikroba sapi apapun, secuil radium (garam radium atau radium bromide) ditambahkan untuk kemudian didiamkan semalaman. Tatkala racikan tersebut didiamkan, terjadi proses radioaktivitas yang menghasilkan lapisan-lapisan tipis berbentuk seperti awan.
Awalnya, Burke menduga bahwa lapisan-lapisan tipis tersebut hanyalah bakteria (yang muncul karena ketidaksterilan) atau kristal semata. Namun, setelah menyelidiknya dengan seksama melalui mikroskop, Burge meyakini bahwa lapisan-lapisan tipis itu adalah makhluk hidup baru atau "artificial life". Dalam studi berjudul "On the Spontaneous Action of Radio-Active Bodies on Gelatin Media" (Nature Vol. 72 1905), Burke menamai makhluk-mahluk ini "radiobes". Tatkala penelitian tersebut diterbitkan sebagai buku berjudul The Origin of Life: Its Physical Basis and Definition (1906), seketika Burke menjadi selebritas dunia. Namanya dianggap sejajar dengan Charles Darwin karena berhasil membuka tabir tentang "kehidupan".
Naas, popularitas dan keyakinan Burke telah menciptakan makhluk hidup dari benda mati hanya bertahan sementara waktu. Rekannya di Cavendish Laboratory bernama W. A. Douglas Rudge, yang melakukan uji-ulang penelitian tersebut, membuktikan bahwa lapisan-lapisan yang dihasilkan dari proses radioaktivitas kaldu dan radium hanyalah gelembung semata, bukan makhluk hidup ataupun radiobes. Terlebih, hidup tak sesederhana mencampurkan kaldu dan radium. Bahkan, para ilmuwan hingga saat ini masih kebingungan meletakkan batas antara "hidup" dan "mati."
Hidup dan Mati
"Bagi saya," tulis Erwin Schrodinger, ilmuwan yang menggenggam status Bapak Mekanika Kuantum sekaligus peraih Nobel di bidang fisika, dalam buku berjudul What is Life? The Physycal Aspect of the Living Cell (1967), "kunci utama dari sesuatu dapat disebut 'hidup' adalah 'aperiodic crystal'." Hidup, bagi Schrodinger, terjadi karena mekanisme hereditas, yakni pewarisan ciri-ciri fenotipe (karakter) dari induk kepada keturunannya, dan mekanisme ini dilakukan oleh aperiodic crystal atau material substrat (semisal molekul) yang melakukan pengulangan (pewarisan) secara tidak ketat atau tidak teratur.
Ketidakteraturan ini, seperti yang dipaparkan Carl Sagan dalam Cosmos (1980), "merupakan buah dari ketidaksempurnaan lingkungan," di mana induk dari segala hal yang disebut "hidup" tinggal, dan ketidaksempurnaan ini disampaikan/diwariskan guna menciptakan apa yang disampaikan Charles Darwin dalam On the Origin of Species (1859): evolusi.
Maka, menurut Schrodinger, hidup merupakan proses evolusi. Proses yang mula-mula dilakukan oleh aperiodic crystal--molekul dalam tataran filosofis yang kemudian melahirkan DNA atau Deoxyribonucleic acid. Singkat, "hidup" dan "mati" ditentukan oleh adanya DNA atau tidak.
Tentu, menentukan sesuatu "hidup" atau "mati" melalui ada atau tidaknya DNA memang tak berlebihan. Sebagaimana dituturkan Akira Hiyoshi dalam "Does a DNA-less Cellular Organism Exist on Earth?" (Genes to Cell Vol. 16 2011), DNA ada pada semua organisme seluler, bahkan pada yang melakukan reproduksi secara mandiri (self-reproducing cellular). Sebaliknya, segala hal yang diyakini sebagai "benda mati," semisal batu, memang tidak memiliki DNA.
Masalahnya, banyak makhluk (dalam hal ini mikroorganisme) yang didaulat manusia sebagai makhluk hidup--katakanlah virus--tidak memiliki DNA alih-alih versi sederhananya saja, RNA. Maka, Akira berargumen, sangat mungkin terdapat makhluk (dalam hal ini organisme seluler) yang tidak memiliki DNA ataupun RNA di alam yang belum terindentifikasi. Terlebih, menjadikan DNA sebagai patokan hidup/mati terlalu sukar dicerna, paling tidak oleh manusia.
Carl Zimmer, dalam bukunya berjudul Life's Edge: The Search for What It Means to be Alive (2021), menyebut bahwa secara umum manusia membedakan yang hidup dengan yang mati melalui sejumlah ciri khas (hallmarks). Salah satu ciri yang diyakini sebagai pembeda mutlak antara yang hidup dan yang mati adalah otak, organ yang tercipta dan berkembang berkat bergabungnya beberapa sel progenitor tatkala manusia, atau makhluk hidup lainnya, tengah berada di titik embrio. Organ ini, usai indera (entah kulit ataupun mata) menyalurkan sinyal berbentuk neuron melalui saraf atas interaksi yang dilakukannya dengan lingkungan, memproses sinyal yang diterima selayaknya prosesor komputer. Pada bagian otak bernama insural cortex, otak menerima sinyal dari berbagai bagian tubuh, dan dari titik ini, makhluk yang memiliki otak dapat memahami apa yang dilihat, didengar, dicium, dirasa, dan disentuh hingga menyebabkan pemilik otak tahu "hidup" dan "mati". Otak, dengan kata lain, memberikan sensasi "kesadaran". Atau, menukil bahasa yang digunakan Zimmer, "otak merupakan katedral tempat bersemayamnya jiwa (soul)," ciri lain yang membedakan hidup/mati dari kalangan teolog.
Karena otak tercipta/berkembang tatkala manusia (makhluk hidup lain) berada di titik embrio, Hakim asal Inggris bernama William Blackstone pada 1765 akhirnya memutuskan bahwa haram hukumnya manusia melakukan aborsi. Keputusan yang dikukuhkan oleh Paus Pius IX pada abad ke-19 yang menganggap jiwa telah ditautkan Tuhan pada manusia berbarengan dengan terbentuknya otak kala berada di titik embrio.
Sebagai modul utama berpikir, tak sulit bagi manusia memutuskan bahwa otak merupakan pembeda yang hidup dan yang mati. Masalahnya, beberapa organisme yang telah disepakati manusia sebagai makhluk hidup diketahui tak memiliki otak.
Seorang ilmuwan dari Stanford Consortium for Regenerative Medicine bernama Cleber Trujillo berhasil menciptakan versi mungil otak hanya melalui kulit manusia (organoid) yang dapat melakukan pemrosesan serupa dengan otak versi utuh. Maka, kembali merujuk buku yang ditulis Zimmer, peraih Nobel di bidang biologi bernama Joshua Lederberg pada 1967 terang-terangan menolak otak sebagai organ tunggal yang menentukan hidup/mati. Baginya, tanpa organ lain, otak tak berbeda jauh dengan benda mati. Begitu pula dengan ciri-ciri lain,yang hanya pas dicap sebagai benda mati jika hanya punya satu ciri penentu kehidupan.
Pemikiran ini seturut dengan apa yang diucapkan fisikawan sekaligus dokter asal Perancis bernama Xavier Bichat. Usai meneliti kepala-kepala manusia yang dipenggal menggunakan guillotine pada abad ke-18, Bichat menyebut bahwa "hidup" merupakan "hubungan intim antara paru-paru, jantung, dan otak", di mana paru-paru bertugas untuk menyerap oksigen sebagai bahan-baku untuk mengurai gula (dalam makanan) menjadi energi, dan energi tersebut disalurkan ke seluruh organ memanfaatkan jantung, termasuk pada otak sebagai medium pemrosesan utama.
Artinya, yang hidup adalah yang kembang-kempis paru-parunya, berdetak jantungnya, dan terangsang otaknya--suatu kerjasama intim yang dilakukan, menukil bahasa yang digunakan Bichat, "untuk melawan apa itu yang disebut sebagai 'mati."
Semua itu benar hingga tardigrada, nematoda, hingga virus membuktikan sebaliknya.
Mati untuk Hidup Kembali
Pada akhir 1600-an, sebagaimana dikisahkan Carl Zimmer dalam buku Life's Edge: The Search for What It Means to be Alive (2021), seorang pedagang asal Belanda bernama Antonie van Leeuwenhoek berhasil membuka tabir dunia mikroskopis melalui mikroskop ciptaannya.
Kala itu, berbekal rasa keingintahuannya terhadap setetes air, Leeuwenhoek menemukan animalcule, makhluk hidup berukuran sangat kecil yang kelak dipahami manusia sebagai bakteria dan protozoa. Tak puas dengan bakteria dan protozoa, Leeuwenhoek memanfaatkan kembali mikroskop buatannya, menggiringnya menemukan animalcule jenis baru dari setetes air selokan berwarna kemerahan di depan rumahnya. Yang menarik, jika bakteria dan protozoa yang ditemukannya Leeuwenhoek meledak dan mati tatkala setetes air yang diteliti menggunakan mikroskop dikeringkan, animalcule baru ini tak demikian. Dari sisa-sisa tetesan yang telah dikeringkan di bawah sinar matahari selama berhari-hari (dan tempat di mana tetesan yang telah dikeringkan itu dituangkan kembali air), animalcule baru miliknya menyeruak hidup kembali.
Di titik itulah Leeuwenhoek menemukan makhluk hidup super kecil nan unik, rotifera, yang jauh dari deskripsi tentang apa itu "hidup" ala manusia karena dapat bangkit dari kematiannya.
Tapi Rotifera tak sendiri. Ada cukup banyak mahluk yang bangkit dari kematian dan bertahan di lingkungan ekstrem. Pada 1950, misalnya, ilmuwan berhasil menemukan makhluk bernama tardigrada yang telah mati dan membeku di Antartika. Tardigrata diketahui dapat kembali hidup usai dialiri air hangat. Hal ini pun terjadi pada virus. Sebagaimana dikisahkan Zimmer dalam buku lainnya berjudul A Planet of Viruses (2011), virus berhasil ditemukan di gua bernama Sierra de Naica di Meksiko yang penuh ribuan kristal gipsum tembus cahaya, mirip seperti fiksi temuan jejak-jejak planet Krypton oleh Kal-El (Superman) di bumi, yang menurut geolog asal University of Granada bernama Manuel Garcia-Ruiz telah berusia 26 juta tahun dan sejak itu terputus dari dunia biologi hingga mustahil "kehidupan" dalam bentuk apapun ditemukan di sana.
Bahkan, SARS-CoV-2, virus di balik wabah Covid-19 yang tengah melanda dunia saat ini, diyakini beberapa kalangan ilmuwan sebagai virus purba yang telah mati ribuan tahun lalu tapi muncul kembali saat ini. Salah satu ilmuwan yang percaya SARS-CoV-2 merupakan virus purba adalah Yassine Souilmi, peneliti Australian Centre for Ancient DNA, Australia. Kepercayaan ini muncul karena, merujuk studinya berjudul "An Ancient Viral Epidemic Involving Host Coronavirus Interacting Genes more than 20,000 Years Ago in East Asia" (Current Biology Vol. 31 2021), terdapat jejak untai RNA Corona (dalam hal ini nenek moyang SARS-CoV-2 bernama CoV-VIPs) pada DNA manusia modern yang tinggal di Cina, Jepang, dan Vietnam. Menurut analisis komputasional DNA yang dilakukannya, merasuknya untaian RNA Corona pada manusia terjadi 20.000 tahun silam, waktu yang ia duga sebagai titik mula Corona hadir di dunia. Entah keajaiban apa yang terjadi, Corona akhirnya muncul kembali.
Maka, melalui keajaiban yang dilakukan tardigrada, nematoda, hingga virus, "hidup" terkadang tak selalu berlawanan dengan "mati".
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id