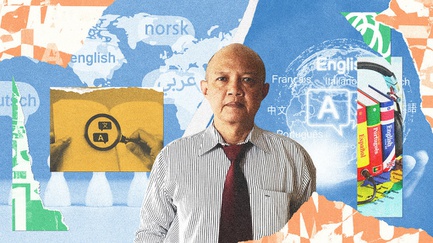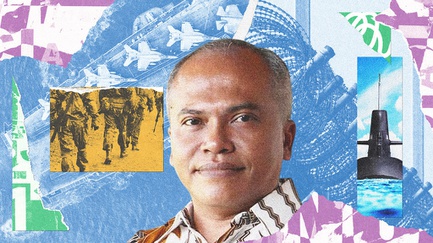tirto.id - Demokrasi kerap dipahami sebagai sistem yang menjamin kebebasan, akuntabilitas, dan kompetisi politik yang setara. Maka ancaman terhadap demokrasi umumnya diasosiasikan dengan tindakan represif: pembubaran parlemen, pelarangan partai politik, atau sensor terhadap media.
Namun, seperti ditunjukkan oleh David Landau dalam artikel pentingnya berjudul Abusive Constitutionalism, kini ancaman demokrasi tidak selalu datang melalui jalur kekerasan atau kudeta militer, melainkan melalui jalur yang justru tampak legal dan sah secara formal.
Ancaman terhadap demokrasi melalui jalur yang tampak legal ini bisa disebut sebagai abusive constitutionalism. Konstitusionalisme abusif merupakan praktik penggunaan mekanisme perubahan konstitusi baik dalam bentuk amandemen maupun penggantian menyeluruh untuk memperkuat kekuasaan dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi.
Dengan kata lain, demokrasi kini bisa digerogoti dari dalam oleh aktor-aktor politik yang menguasai hukum untuk mengaburkan semangat demokrasi, bukan untuk menjaganya. Contoh konkret dari tiga negara yang pernah mengalami gejala ini: Kolombia, Venezuela, dan Hungaria.
Di Kolombia, Presiden Álvaro Uribe menggunakan amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya, sebuah langkah yang kemudian dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi. Di Venezuela, Hugo Chávez menulis ulang konstitusi untuk melemahkan institusi lawas dan memperpanjang masa kekuasaannya. Sementara di Hungaria, Partai Fidesz yang menguasai parlemen memanfaatkan supermayoritas untuk mengubah struktur konstitusi dan melemahkan pengadilan, media, serta komisi pemilu.
Menariknya, semua tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang tampak legal dan sesuai prosedur, namun mengandung muatan politik yang otoriter. Di sinilah letak bahaya konstitusionalisme abusif: ia tidak tampak sebagai kudeta, tetapi justru berjalan melalui jalan-jalan hukum yang telah dimanipulasi.
Konstitusi dalam ancaman
Kondisi abusif terhadap konstitusi secara perlahan terjadi di Indonesia. Beberapa revisi undang-undang penting dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala serupa: cepat, minim partisipasi publik, dan menguntungkan elite politik yang sedang berkuasa.

Revisi terhadap Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), revisi UU TNI dan yang terakhir revisi KUHAP dari produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah dan DPR menunjukkan adanya kecenderungan pelemahan terhadap mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan kita.
Kita juga menyaksikan reduksi terhadap kekuatan oposisi di parlemen, konsolidasi kekuasaan di tangan eksekutif, serta kecenderungan pemusatan kekuasaan dalam pengambilan keputusan strategis nasional. Padahal, demokrasi bukan hanya tentang penyelenggaraan pemilu lima tahunan, tetapi juga soal akuntabilitas kekuasaan, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan partisipasi warga negara dalam proses legislasi.
Jika dibiarkan, Indonesia bisa saja tergelincir menjadi negara dengan sistem demokrasi prosedural belaka: pemilu tetap ada, tetapi kompetisi tidak setara; lembaga tetap berdiri, tetapi kehilangan taringnya; suara rakyat tetap diminta, tapi hanya sebagai legitimasi formal, bukan aspirasi substantif.
Pemusatan Kekuasaan dan Ketiadaan Oposisi
Kondisi ini diperparah oleh konfigurasi politik pasca-Pemilu 2024, di mana hampir seluruh partai politik berada dalam koalisi pemerintah.
Parlemen yang semestinya menjadi penyeimbang eksekutif justru sering menjadi stempel kebijakan. Sementara kekuatan masyarakat sipil dan media kerap dibungkam secara halus melalui represi digital, persekusi, atau pembingkaian wacana “anti-nasional”.
Semua ini tidak serta-merta membuat Indonesia menjadi negara otoriter. Tapi ia menciptakan apa yang disebut ilmuwan politik sebagai rezim hibrida atau otoritarianisme elektoral: ada pemilu, tapi tidak kompetitif; ada parlemen, tapi tidak kritis; ada partisipasi publik, tapi dibatasi. Demokrasi dibiarkan hidup, tapi dalam bentuk yang dikendalikan.

Perlunya Kewaspadaan Kultural dan Institusional
Konstitusionalisme abusif bukan hanya soal prosedur hukum, tapi juga soal budaya politik. Ketika elite merasa nyaman memonopoli legislasi, ketika publik makin apatis karena suaranya tak didengar, dan ketika pengadilan tak lagi berdiri independen, maka di situlah demokrasi secara perlahan digerogoti dari dalam.
Perangkat hukum seperti militant democracy atau unconstitutional constitutional amendments tidak selalu cukup untuk menahan gelombang penyalahgunaan kekuasaan melalui konstitusi.
Dalam konteks Indonesia, kita harus melampaui pendekatan legal-formal. Kita perlu mengembangkan semacam etik konstitusional: bahwa perubahan hukum harus berpijak pada nilai keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan politik—bukan sekadar legitimasi suara mayoritas.
Teori-teori konstitusional klasik maupun perangkat hukum internasional belum cukup siap menghadapi tantangan ini. Misalnya, doktrin militant democracy seperti di Jerman yang memungkinkan pelarangan partai anti-demokrasi, hanya efektif terhadap ancaman ideologis ekstrem seperti Nazisme, namun tidak cukup untuk menghadapi otoritarianisme yang menyusup lewat prosedur demokratis.
Demikian pula doktrin unconstitutional constitutional amendment, seperti yang dikembangkan di India atau Kolombia, yang memungkinkan pengadilan membatalkan amandemen yang bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi. Namun penerapannya kerap terbatas, apalagi ketika pengadilan sudah dikuasai oleh aktor politik yang sama.
Artinya, mekanisme hukum perlu dirancang ulang agar tidak mudah dibajak.
Apa yang bisa dilakukan? Pertama, kita harus mengembalikan orientasi bahwa konstitusi bukan hanya sekadar teks, melainkan kontrak sosial yang menjamin demokrasi substansial. Jika perubahan konstitusi (atau undang-undang penting) dilakukan dengan cara yang manipulatif dan tidak partisipatif, maka ia tidak hanya cacat secara prosedural, tetapi juga mencederai esensi demokrasi.
Kedua, masyarakat sipil dan komunitas akademik harus lebih jeli membaca niat di balik setiap perubahan hukum. Kita tidak bisa lagi puas dengan argumen legal-formal semata, tetapi harus bertanya: untuk siapa perubahan ini dibuat? Apakah ini memperkuat atau justru melemahkan demokrasi?
Ketiga, partai politik dan parlemen harus memperkuat dirinya sebagai penyeimbang kekuasaan, bukan sekadar stempel bagi kekuatan eksekutif. Ketika semua lembaga negara tunduk pada satu kekuasaan, maka demokrasi kehilangan daya tahan.
Demokrasi yang sehat bukan hanya soal menang pemilu. Demokrasi harus menjamin bahwa yang menang tidak bisa semena-mena mengubah aturan untuk terus menang. Karena jika konstitusi digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, maka pada titik itu demokrasi hanya menjadi bungkus kosong—indah secara prosedural, tapi membusuk secara substansial.
Di tengah derasnya revisi hukum, pemusatan kekuasaan, dan lemahnya oposisi, Indonesia perlu lebih waspada terhadap ancaman legalistik yang justru menjauhkan kita dari cita-cita reformasi. Demokrasi tidak akan runtuh dengan teriakan, tapi dengan tepuk tangan terhadap regulasi yang tampak legal—tapi sarat tipu daya kekuasaan.
Demokrasi tidak mati karena peluru. Demokrasi sering mati karena prosedur. Ketika konstitusi tidak lagi menjaga kekuasaan, melainkan digunakan untuk mempertahankannya, maka saat itulah kita sedang menyaksikan demokrasi yang dikorbankan atas nama legalitas.
Maka dari itu, konstitusi harus terus dibela—bukan hanya oleh pengadilan, tetapi juga oleh kesadaran publik yang kritis dan berdaya.
Editor: Rina Nurjanah
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id