tirto.id - Kerusuhan meledakdi markas DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Jalan Pangeran Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 27 Juli 1996. Suara benda saling beradu membuat bising. Wakil Komandan Satgas PDI pro-Megawati Soekarnoputri, Soesilo Muslim, susah-payah melaporkan keadaan kantor yang kacau-balau.
Muslim, sepenuturannya kepada majalah Tempo (Juli 2004), baru saja menolak tawaran Komandan Kodim dan Kepala Polresta Jakarta Pusat yang meminta kubu Megawati untuk menyerah dan meninggalkan kantor.
Kubu Megawati kebingungan karena belum ada juga seruan untuk melawan balik kendati sudah sore. Salah satu pesan yang tiba di kediaman Megawati di Kebagusan, Jakarta Selatan menyebut ada 59 korban akibat serangan terhadap kantor PDI.
Pangkal persoalannya adalah terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI pada 22 Desember 1993. Pada musyawarah nasional yang digelar di Kemang, Jakarta Selatan, Megawati mendapat dukungan secara aklamasi sebagai Ketua Umum.
Namun pada 1996, tiba-tiba situasi PDI bergejolak. Mantan Ketua Umum PDI, Soerjadi, tidak terima dan tetap ingin ada Konferensi Luar Biasa (KLB) dalam pembentukan pengurus partai.
Penelitian ilmuwan politik Australia, Edward Aspinall, berjudulOpposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia (2005) menyebut ada laporan bahwa Departemen Dalam Negeri dan perwira ABRI menekan jajaran PDI di daerah untuk menandatangani gelaran Konferensi Luar Biasa (KLB) PDI tahun itu.
Mendagri Yogie S. Memet dan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung mendukung KLB tersebut. Dalih mereka adalah KLB yang rencananya digelar di Medan akan mengatasi krisis internal partai yang sedang bersitegang: kubu Megawati dan kubu Soerjadi.
Pemerintah Orde Baru memang gemar merecoki urusan internal partai. Soerjadi, pemimpin hasil KLB PDI di Medan, pernah mengakuinya juga. Pada medio 1993, Soerjadi terpilih menjadi Ketua Umum PDI pada Kongres IV PDI di Medan. Tapi tiga hari kemudian, pada 24-25 Juli 1993, sekelompok orang yang menamakan diri Kelompok 17 tiba-tiba menduduki arena kongres. Panglima ABRI Feisal Tanjung kemudian mengklaim Soerjadi tidak sah sebagai Ketua Umum PDI karena terlibat kasus penculikan kader.
Posisi Soerjadi kian lemah. Pada Agustus 1993 Menkopolkam Soesilo Soedarman mengatakan Kongres Medan tidak sah dan memutuskan menggelar kongres luar biasa (KLB) PDI di Surabaya (selanjutnya KLB Surabaya). Pemerintah menunjuk pengurus sementara yang dipimpin Latief Pudjosakti.
"Pemerintah dan ABRI melalukan langkah-langkah untuk menghambat pencalonan saya menjadi ketua umum kembali," ujar Soerjadi seperti dilansir Forum Keadilan (9 Juli 2000).
Sedangkan keinginan mengganti Megawati seakan-akan menguatkan pernyataan Soerjadi. Stefan Eklöf dalam Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Suharto, 1996-1998 (1999) mencatat Soerjadi terpilih sebagai ketua umum versi KLB Medan tanpa hambatan. Tempat acara bahkan dijaga ketat oleh tentara. Padahal sebelumnya tidak ada penjagaan semacam ini pada kongres-kongres sebelumnya dan selalu berakhir ricuh.
Yang juga tidak biasa, keinginan PDI untuk mengganti Megawati. Selain PDI di bawah Megawawati cukup populer, pergantian ketua umum ini terlampau mendadak; hanya berselang satu tahun sebelum Pemilu 1997. Megawati juga tidak mendapat protes dari pengurus daerah PDI.
"Karena itu, bagi pengamat politik, jelas bahwa inisiatif untuk mengadakan kongres dan mengganti Megawati datang dari luar partai, yaitu dari pemerintah," tulis Eklöf.
Hasil keterlibatan pemerintah pada masalah internal partai ini kemudian menimbulkan banyak korban jiwa. Komnas HAM mencatat peristiwa Sabtu Kelabu itu membuat setidaknya 5 orang kehilangan nyawa, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang.
Dampak Kerusuhan 27 Juli atau dikenal dengan sebutan Kudatuli juga tidak berhenti sampai hari itu saja. Kejadian ini membuat Wiji Thukul, penyair dan editor Suluh Pembebasan, suplemen kebudayaan Partai Rakyat Demokratik, menjadi buron pemerintah. Pada 1998 dia hilang dan tak diketahui keberadaannya sampai sekarang.
Campur tangan pemerintah kepada urusan internal partai memang menjadi salah satu memori buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Bagaimana di Era Jokowi?
Jika PDI pernah terpecah di akhir era Orde Baru, maka Partai Demokrat saat ini mengalami kejadian yang hampir mirip. Partai yang identik dengan sosok Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu terpecah menjadi dua kubu. Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dan Demokrat kubu Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum.
Nama Demokrat yang terakhir merujuk kepada tempat diadakannya Konferensi Luar Biasa (KLB), yakni Deli Serdang, Sumatra Utara pada 5 Maret 2021. Kendati disebut dualisme, Demokrat Deli Serdang sebenarnya sudah setengah jalan, jika tidak seutuhnya, menuju kegagalan.
Pengajuan pengesahan KLB Deli Serdang yang mengamanatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum sudah ditolak Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu (31/3/2021).
Menkumham Yasonna Laoly menyebut alasan tidak diterimanya pengajuan itu karena jumlah perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak cukup dan tidak ada mandat dari Ketua DPD atau DPC mayoritas.
Sejauh ini pilihan Demokrat kubu Moeldoko ada dua. Pertama, menggugat keputusan Yasonna melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diprediksi akan kandas. Kedua, menggugat AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang juga berisi penetapan pengurus baru. Cara kedua telah dipilih. Gugatan itu sudah diajukan pada Selasa (6/4/2021).
Sepanjang pemerintahan Jokowi, kasus Demokrat adalah anomali. Beberapa kali isu dualisme partai memang terjadi. Pertama Partai Golkar, kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Berkarya. Ketiganya dimenangkan oleh kubu yang mendukung pemerintah.
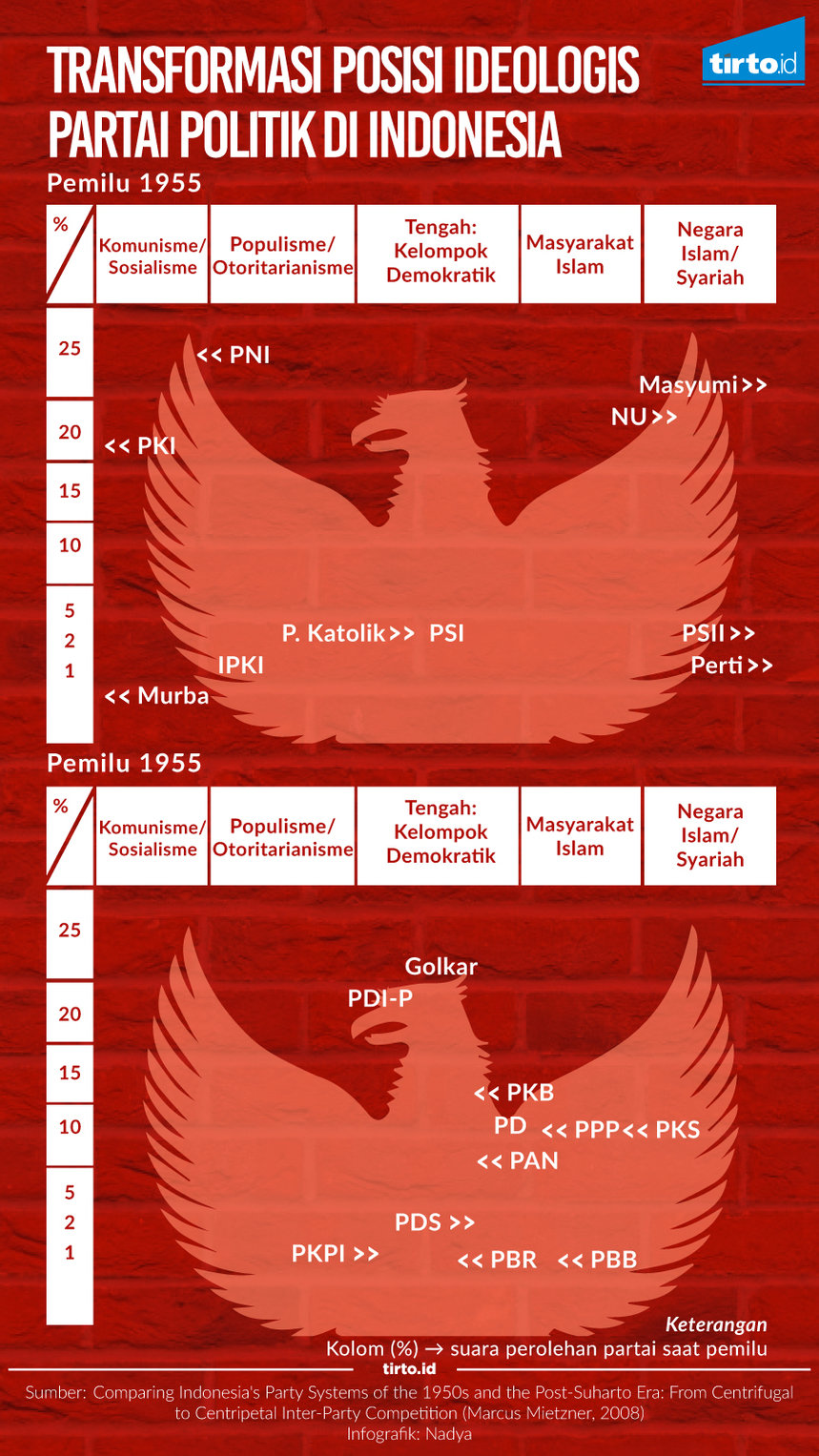
Perebutan tampuk kekuasaan Partai Golkar terjadi tahun 2014-2016 antara kubu Aburizal Bakrie (Munas Bali) dan Agung Laksono (Munas Ancol). Dua kubu ini sempat dipanggil ke Istana Negara oleh Jokowi pada 2016. Jokowi menganggap konflik ini tidak akan baik bagi jalannya pemerintahan. Pada kesempatan yang sama, Jokowi, melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, mengaku tidak akan ikut campur dalam masalah internal partai ini.
Namun keberpihakan Jokowi sebenarnya sudah bisa terlihat jauh sebelumnya, tepatnya pada 2014. Ketika itu Partai Golkar yang dipimpin Aburizal mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sedangkan Agung membelot dan mendukung Jokowi. Beberapa kader lain juga ada yang mengekor, misalnya Agus Gumiwang Kartasasmita yang kemudian dipecat Aburizal. Setelah kisruh selesai, dia menjadi menteri di kabinet Jokowi.
Ketika kubu Aburizal melakukan Munas di Bali tahun 2014, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, mengatakan perlakuan pemerintah kepada dua kubu Partai Golkar tidaklah adil. Baginya, sejak detik itu, pemerintah telah ikut campur urusan internal partai.
“Pernyataan Menko Polhukam yang meminta Polri tidak memberikan ijin kepada Munas Golkar di Bali, semakin mengonfirmasi campur tangan dan intervensi kekuasaan terhadap rumah tangga Partai Golkar," kata Bamsoet sebagaimana dilansir Kontan, Selasa (25/11/2014).
Dualisme di PPP adalah antara kubu Romahurmuziy atau kerap disapa Romy (Muktamar Pondok Gede) dengan Djan Faridz (Muktamar Jakarta). Singkatnya, Mahkamah Agung sempat menetapkan PPP Djan Faridz adalah kepengurusan yang sah tahun 2015. Namun Menkumham Yasonna tidak mau mengesahkan kepemimpinan tersebut dengan alasan sebaiknya masalah partai diselesaikan di luar pengadilan.
Setelah melalui Peninjauan Kembali tahun 2017, PPP kubur Romy yang mendapat kesempatan untuk bisa berkontestasi dalam Pileg 2019. Pada 2018, Djan Faridz mengundurkan diri sebagai Ketua PPP Muktamar Jakarta.
Partai Berkarya, kendati bukan salah satu partai pemilik suara di DPR, juga jadi rebutan antara Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dengan Muchdi Pr. Konflik ini terjadi tahun lalu dan kubu Muchdi Pr. mendapat pengesahan berdasar SK Menkumham.
Baru pada Maret 2021, PTUN akhirnya mengabulkan gugatan pembatalan SK Menkumham dari Tommy Soeharto. Putusan ini masih belum final. Babak berikutnya, keputusan PTUN akan ditinjau di tingkat banding.
Namun, dari berbagai kisah dualisme partai di era Jokowi, mereka yang berhasil menang adalah yang merapat kepada pemerintah. Partai Golkar, setelah islah, mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. PPP dan Berkarya juga sama, dipimpin oleh ketua umum yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Padahal baik Partai Golkar, PPP, dan Berkarya pada 2014 seluruhnya mendukung Prabowo. Demokrat adalah satu-satunya contoh sengketa partai yang tidak dimenangkan oleh pendukung Jokowi, dalam hal ini Moeldoko.
Kejadian dualisme Partai Berkarya sudah memberikan harapan pada Moeldoko. Setidaknya, meski Menkumham Yasonna dan pemerintah tidak mendukung pengambilalihan Partai Demokrat melalui KLB Deli Serdang, ada kemungkinan PTUN memutuskan sebaliknya.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id


































