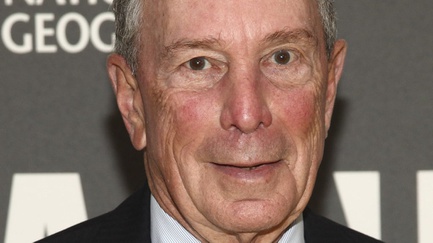tirto.id - Indonesia merupakan salah satu negara dengan kandungan mineral yang melimpah. Tanah Air tercatat memiliki setidaknya setidaknya 22 komoditas mineral strategis (critical mineral).
Alhasil, industri pertambangan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Tanah Air. Pada tahun 2023 industri ekstraktif ini menyumbang 10,52 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB).
Salah satu mineral strategis dengan prospek cukup cerah adalah tembaga. Tren positif permintaan atas mineral ini tidak terlepas dari fakta bahwa tembaga adalah metal yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Logam ini diaplikasikan untuk kontruksi, tenaga listrik, transportasi, dan lainnya.
Terlebih lagi tembaga saat ini dipandang sebagai kunci utama transisi energi ramah lingkungan. Keunggulan konduktor listrik pada tembaga menjadikannya mineral yang ideal untuk beragam teknologi dekarbonisasi.
International Copper Association (ICA) memprediksi bahwa permintaan global atas tembaga murni akan menyentuh 50 juta ton pada 2050, dua kali lipat dibandingkan permintaan saat ini.
Indonesia termasuk salah satu negara produsen tembaga dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Merujuk laporan United States Geological Survey (USGS) 2024, tercatat jumlah cadangan tembaga Ibu Pertiwi sebanyak 24 juta ton dengan volume produksi tambang 840 ribu ton pada 2023.
Harta dari Ampas Tembaga
Dengan masifnya jumlah cadangan yang tersedia, pemerintah terus mendorong industri tambang tembaga untuk meningkatkan produksi, termasuk pembangunan smelter demi proyek hilirisasi. Hal ini mengingat Indonesia memiliki ambisi untuk menjadi salah satau pemain kunci dalam teknologi hijau.
Di satu sisi, peningkatan kapasitas produksi tentu akan berujung dengan semakin banyaknya hasil residu penambangan tembaga. Residu tembaga tergolong limbah yang sulit diurai dan jika terakumulasi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan.
Pengelolaan manajemen residu yang buruk dapat studi dan menghilangkan kesuburan tanah, menganggu ekosistem dan berbahaya bagi kesehatan karena kandungan toksik timbal dan arsen.
Akan tetapi di saat yang sama residu ini juga merupakan sumber daya sekunder penting yang masih mengandung logam berharga. Sebuah studi berjudul “Comprehensive Review on Metallurgical Recycling and Cleaning of Copper Slag” menyebutkan residu tembaga mengandung besi (Fe), seng (Zn), kobalt (Co), tembaga kadar rendah hingga nikel (Ni).
Oleh karena itu, ampas tembaga dapat juga dikatakan sebagai ‘harta karun sampingan’. Terlebih lagi volume harta karun ini sangat masif. Hasil studi yang sama menyebut bahwa setidaknya terdapat 70 ton residu yang dihasilkan setiap tahunnya.
Mempertimbangkan potensi kerusakan, nilai berharga yang terkandung di dalamnya, dan volume yang besar, pelaku industri tembaga di dunia didorong untuk mengolah kembali residu dengan memegang prinsip ekonomi sirkular.
Berbeda dengan model linear (konvensional) yang memiliki pendekatan ‘ambil-pakai-buang’, ekonomi sirkular adalah model yang bertujuan untuk memperpanjang siklus hidup suatu produk, bahan baku, dan sumber daya. Prinsip utamnya adalah meminimalisir limbah dan menjaga agar sumber daya dapat digunakan selama mungkin.
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam studinya menyampaikan bahwa secara umum penerapan ekonomi sirkular di Tanah Air berpotensi menambah PDB hingga Rp638 triliun dan pengurangan limbah hingga 52 persen pada tahun 2030.
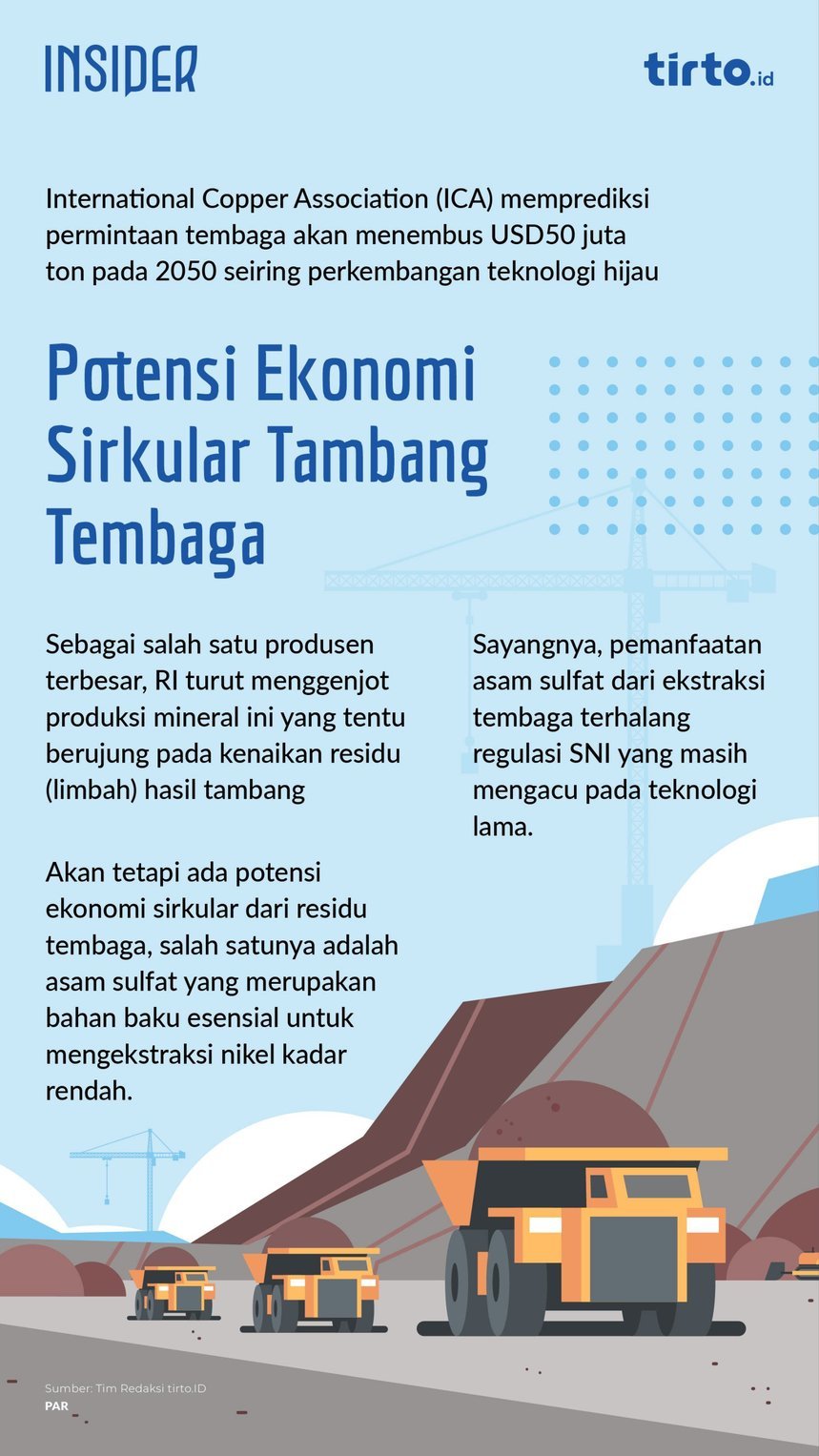
Cerita dari Wetar ke Morowali
Kini, proses metalurgi untuk pengolahan dan pemurnian lebih lanjut residu tembaga belum sepenuhnya berkembang. Meskipun sudah banyak penelitian yang mencoba untuk mengulik isu ini. Selain itu, sejatinya industri tambang tidak termasuk dalam lima sektor prioritas penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Hal ini jika merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-204.
Meskipun demikian, beberapa pemain industri tambang tembaga berinisiasi untuk menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam bisnis mereka, salah satunya adalah PT Merdeka Copper Gold (MCG/Merdeka).
Merdeka saat ini mengelola 4 proyek tambang, di mana Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar dalam fase produksi. Kemudian Proyek tembaga Tujuh Bukit dan Proyek Emas Pani masih dalam tahap uji kelayakan. Selain itu juga terdapat proyek tambang dan hilirisasi nikel yang dinahkodai oleh anak perusahaan, PT Merdeka Battery Materials (MBM).
Apabila dihitung potensi dan produksi atas logam, maka perusahaan mengelola sumber daya sebanyak 35,2 juta ounces emas, 8,4 juta ton tembaga, 13,8 juta to nikel, dan 1 juta ton kobalt. Dengan sumber daya dan produksi yang melimpah, tentu jumlah residu yang dihasilkan perusahaan juga tak kalah besarnya.
Agar dapat memaksimalkan siklus hidup tambang dan mengekstraksi secara maksimal residu yang ada, perusahaan melakukan inovasi melalui Proyek Acid, Iron, Mineral (AIM). Proyek AIM dioperasikan oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI) dan terletak di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.
Proyek AIM ini nantinya akan mengolah batuan (residu) sisa pengolahan dari Tambang Tembaga Wetar yang masih memiliki nilai tambah. Pengolahan dari batuan-batuan tersebut menghasilkan asam sulfat, pelet bijih besi, uap panas, lumpur emas, spons tembaga, timbal dan seng.
Material-material ini merupakan bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan baterai dan teknologi hijau lainnya yang diproduksi oleh pabrik-pabrik di IMIP. Ambil contohnya asam sulfat yang merupakan material dasar penting untuk mengestraksi nikel kadar rendah (limonit) melalui teknologi HPAL (High Pressure Acid Leaching).
Polaris Market Research menganalisa bahwa permintaan asam sulfat akan meningkat signifikan seiring dengan peningkatan produksi smelter seluruh dunia. Pangsa pasar material ini diperkirakan akan tumbuh 10 persen tiap tahunnya dan menyentuh 31 miliar dolar AS pada 2030. Naik hampir tiga kali lipat dari tahun 2021 yang sebesar 13,4 miliar dolar AS.
Lonjakan permintaan asam sulfat ini diamini oleh Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan PERHAPI, M Toha. Dirinya menyebut bahwa satu smelter nikel membutuhkan 1-2 juta ton asam sulfat per tahun.
Kapasitas produksi asam sulfat domestik saat ini baru ada di kisaran 3-4 juta ton per tahun. Dengan puluhan pabrik smelter di IMIP tentu ke depan akan ada kebutuhan setidaknya 30 juta ton asam sulfat tiap tahunnya.
“(Permintaan) asam sulfat dengan pabrik HPAL ini akan meningkat pesat, berkali-kali lipat. Satu pabrik HPAL bisa memakan asam sulfat sampai 1-2 juta ton per tahun,” ungkap Toha kepada Tirto, Senin (20/5/2024).
Meskipun demikian, ada tantangan besar yang menghadang pemanfaatan asam sulfat di Indonesia, yakni regulasi SNI (Standar Nasional Indonesia). Musababnya, apabila tidak dapat memenuhi SNI, maka perusahaan tidak diizinkan menjual dan mengekspornya.
Kebijakan SNI mengatur kandungan logam maksimal dari asam sulfat. Penentuan baku mutu tersebut merujuk pada kebutuhan asam sulfat untuk industri makanan dan farmasi. Hal ini tentu saja tidak selaras dengan kebutuhan pabrik HPAL yang notabenenya tidak terlalu mempermasalahkan kandungan logam.
“Asam sulfat untuk HPAL tidak mengharuskan kandungan minimal besi sekian. Artinya harus ada ketentuan berbeda antara asam sulfat untuk pabrik HPAL dengan asam sulfat untuk industri makanan dan farmasi,” tegas Toha.
Salah satu akar permasalahan ini terletak pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang dalam penyusunannya masih mengacu pada teknologi yang ada (existing) saat pembuatan beleid tersebut.
Toha mengungkapkan karena Indonesia bukan negara pionir dalam teknologi, jadi banyak sekali aturan yang tidak memperhitungkan potensi perkembangan teknologi di masa depan.
“Itulah yang sering terjadi. Kegagalan kita untuk menyelaraskan perkembangan teknologi di sektor industri dengan regulasi,” imbuhnya.
Dirinya menyayangkan sikap pemerintah yang kurang fleksibel, padahal ada potensi pendapatan yang sangat besar. Aturan yang ada selalu ketinggalan dan akhirnya tidak berhasil menggapai momen tersebut.
“Kita kekunci dengan sebuah aturan yang mengunci diri kita sendiri tanpa mempertimbangkan perubahan teknologi di masa depan. Padahal prinsip dasarnya kalau sudah diolah dan ada nilai tambah, ngapain dibatasi kandungannya. Kalaupun memang dibatasi, setidaknya harus cepat menyesuaikan,” pikir Toha.
Secara keseluruhan, implementasi ekonomi sirkular dalam industri tambang tembaga di Indonesia bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga peluang besar untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan cadangan mineral yang melimpah dan permintaan global yang terus meningkat, Ibu Pertiwi memiliki potensi untuk menjadi pemain kunci dalam industri ini.
Namun, untuk mencapainya, tantangan regulasi dan inovasi teknologi harus diatasi. Inisiatif seperti Proyek AIM yang dilakukan oleh Merdeka menunjukkan bahwa pengolahan residu tambang dapat menghasilkan produk berharga dan mendukung teknologi hijau.
Dengan dukungan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dari sektor ini sambil meminimalkan dampak lingkungannya. Langkah menuju ekonomi sirkular ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Editor: Nuran Wibisono
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id