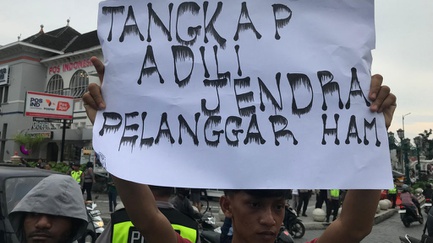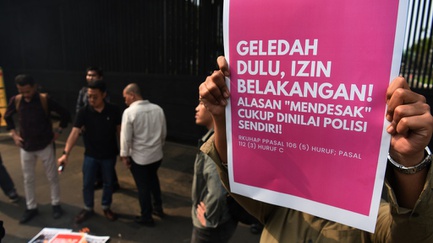tirto.id - Ada sekira 13 nama kampus mentereng di Indonesia yang masuk dalam daftar perguruan tinggi dengan integritas penelitian “dipertanyakan”. Rincian itu diungkap dalam Research Integrity Index (RI²) yang disusun oleh peneliti dari American University of Beirut, Lokman Meho.
Menukil informasi di laman resminya, pengukuran RI² ini diambil dari rata-rata dua indikator, yaitu:
(1) jumlah artikel yang ditarik per 1.000 publikasi karena pelanggaran etik dan
(2) proporsi artikel di jurnal yang belakangan dicabut/delisted dari basis data Scopus atau Web of Science (WoS), lantaran gagal memenuhi standar kualitas atau penerbitan.
Dari 13 perguruan tinggi, lima di antaranya bahkan masuk kategori “red flag”. Mereka adalah Bina Nusantara University (BINUS), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan Universitas Sebelas Maret (UNS). Lima perguruan tinggi itu mendiami zona merah atau ekstrem anomali.
Kemudian di zona oranye, “high risk”, ada Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Padjadjaran (UNPAD). Melengkapi daftar, di zona kuning, “watch list”, bertengger Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Latar Belakang Indeks RI²
Dari daftar itu, sederhananya, semakin merah zona suatu kampus, maka semakin darurat bagi institusi untuk melakukan pembenahan tata kelola risetnya. "Bukan berarti ada pelanggaran, tetapi menunjukkan adanya tantangan struktural atau konteks yang perlu ditangani agar tata kelola riset bisa lebih kuat dan akuntabel," begitu penjelasan singkat dari laman RI².
Di atas BINUS (urutan 11 dunia), yang berada di deretan urutan 1 - 10, nangkring kampus-kampus India dan Bangladesh, di mana posisi teratas diduduki Graphic Era University, India.
Indeks ini tercipta sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran tentang pemeringkatan universitas global. Sejumlah lembaga pemeringkat memberi insentif terhadap penerbitan berbasis jumlah dan sitasi, dengan mengorbankan integritas ilmiah.
“RI² mengalihkan fokus dari kuantitas ke integritas, menawarkan alat yang konservatif, transparan, dan memiliki tolok ukur global yang menyoroti kerentanan struktural yang sering terlewatkan oleh metrik arus utama,” demikian tulis Lokman Meho dalam keterangan resminya.
Merespons temuan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Togar Simatupang mengatakan pihaknya menyambut baik sebagai bahan refleksi. Ia juga menilai laporan ini bisa jadi cerminan dan pembanding posisi pendidikan tinggi Indonesia di dunia.
Dia mengatakan adanya temuan ini menjadi dorongan perguruan tinggi dalam negeri untuk meningkatkan kualitas publikasi menjadi bermutu dan berdampak.
"Publikasi hendaknya jangan lagi mengejar jumlah, tetapi mutu dan dampak, misalnya menyasar jurnal bereputasi dan sitasi, bahkan produk yang digunakan oleh industri maupun masyarakat luas," kata Togar mengutip Antara, di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Ia menambahkan hal ini memerlukan upaya yang serius untuk menumbuhkan kesadaran integritas akademik. Harapannya perguruan tinggi Indonesia dalam daftar tersebut bergerak menuju risiko minim, zona hijau atau putih.
Tata Kelola Pendidikan sebagai Akar Masalah
Indeksasi atau reputasi internasional memang kini menjadi obsesi perguruan tinggi. Seolah perguruan tinggi hanya mementingkan kuantitas dan ranking di level global.
Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Satria Unggul Wicaksana Prakasa, mengatakan kampus-kampus akhirnya memilih cara instan. Cara instan itu, kata Satria, sebagai bagian dari risiko integritas akademik.
Dia menambahkan, kampus-kampus “besar” yang berada dalam zona berisiko ini menunjukkan adanya situasi anomali.
Akar masalahnya terkait tata kelola kebijakan pendidikan tinggi. Pemerintah, menurut dia, tidak mempersiapkan cara yang terukur untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi yang baik. Misalnya, pemerintah terlalu membebani kampus dengan kewajiban publikasi Scopus bagi dosen dan mahasiswa, baik di level master dan doktoral.
“Nah, inilah sebenarnya yang menjadi masalah sistemik. Dan kekeliruan kebijakan ini kemudian justru berdampak kepada reputasi kita di mata global. Kampus-kampus besar ini kemudian justru tercoreng namanya, dalam artian reputasi global,” ucap Satria.
Persoalan sistemik ini kemudian menciptakan kepanikan di kalangan dosen. Dosen sekaligus Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki, melabelinya sebagai panic academia.
Kondisi ini mengacu saat dosen diminta publikasi sebanyak mungkin. Sebab semakin banyak publikasi atau jumlah sitasi, maka suatu kampus akan dianggap “berkelas”. Pada akhirnya, indeks ini bukan hanya menyasar individual, melainkan institusional.
“Jadi, panic itu kan diksinya psikologis, bahwa orang itu mengalami ketakutan tentang karirnya, bagaimana sebagai dosen, harus punya publikasi. Sementara ekosistem tidak mendukung sepenuhnya, itu satu. Panic juga melanda perguruan tinggi, karena dia harus dianggap berkelas. Nah, lalu dia kemudian bikin program-program yang instan, akrobat-akrobat kebijakan, yang pusatnya terutama di indikator metrik publikasi,” ungkap dosen yang akrab disapa Adink tersebut, kepada Tirto, Selasa (8/7/2025).

Dengan begitu, menurut dia, ekosistem pendidikan tinggi yang terbentuk bukan mendorong akademisi atau kampus untuk menghasilkan publikasi yang berkualitas. Perangkat pendidikan malah berlomba-lomba memproduksi artikel jurnal sebanyak-banyaknya.
“Jadi sekali lagi, kesimpulannya ini soal bagaimana sebetulnya memahami universitas integritas itu. Yang kita keliru karena kita memang mengikuti metrik-metrik gitu. Akhirnya Indonesia termasuk yang tinggi jumlah publikasinya di Asia Tenggara. Sekarang –katanya– nomor 1, sudah melampaui Singapura dan Malaysia. Tetapi kalau dicek kualitasnya itu buruk,” lanjut Adink.
Lewat artikel jurnal bertajuk Ranking researchers: Evidence from Indonesia (2023), Fry, dkk memang mengungkap bahwa Indonesia menjadi negara penghasil penelitian ilmiah tertinggi di antara negara-negara ASEAN dalam kurun waktu tiga tahun. Padahal sebelumnya perguruan tinggi dalam negeri menduduki peringkat terburuk kedua. Namun, kebanyakan peningkatan publikasi antara 2016-2019 itu merupakan jurnal berdampak rendah.
Ini belum lagi mempertimbangkan temuan kalau Indonesia jadi juara kedua dalam publikasi artikel ilmiah pada jurnal predatori setelah Kazakhstan. Kasarnya, Indonesia jadi negara kedua soal ketidakjujuran akademik. Temuan ini berdasar penelitian Vit Machacek dan Martin Srholec. Mereka menelaah berdasar artikel akademik yang terbit di jurnal predator antara 2015-2017.

Oleh karenanya, Adink bilang, fenomena 13 perguruan tinggi masuk zona berisiko ini hanyalah puncak gunung es. Masih banyak perguruan tinggi di Tanah Air yang tidak terungkap. Sebab, kata dia, fenomena plagiarisme dan “obesitas publikasi” melanda semua level jurnal akademik.
“Saya kira hampir semua kampus bermasalah. Karena ini berbicara berawal dari Kemendikti Saintek, yang belum mengubah standar kemajuan perguruan tinggi atau integritas perguruan tinggi itu,” ucap Adink.
Ia menyoroti percepatan jenjang karier dosen dan sistem akreditasi yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
Dalam pasal 71 Permendikbud disebutkan, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilakukan melalui Akreditasi. Akreditasi sendiri dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
“Nah, disitu semua clear. Semua mengarah pada publikasi. Sebagai syarat utama. Tapi di situ tidak menyertakan misalnya bagaimana proses publikasi itu harus dibuktikan. (Itu poin) satu. Yang kedua, kita tahu ada mafia di dalam review kenaikan jabatan dosen itu juga masalah. Itu banyak diungkap juga kemarin di media kan. Banyak orang tiba-tiba jadi guru besar. Publikasinya tidak begitu jelas,” kata Adink.
Utamakan Bangun Ekosistem
Untuk mengatasi terbentuknya kepanikan di antara perguruan tinggi dan akademisi, yang bermuara kepada rendahnya integritas akademik, diperlukan adanya perbaikan dari hulu ke hilir. Adink, Guru Besar UII, mendorong pemerintah dan kampus untuk lebih dahulu membangun ekosistem.
“Gak usah meraih yang sifatnya artifisial, yang misalnya jumlah, quantity, tapi quality. Maka harus dibangun ekosistemnya. Budaya menulis, budaya meneliti,” ungkapnya.
Lebih jauh, Adink bilang, kampus harusnya bisa memulai dengan program enrichment alias mengadakan pelatihan menulis. Opsi lainnya dengan mengirim dosen-dosen untuk melakoni studi lanjut dan melakukan riset-riset kolaboratif dengan peneliti asing, sehingga para tenaga pendidik terbiasa menulis.
Selain itu, kampus juga penting untuk memperkuat audit. Hal ini mencakup kinerja dan publikasi dosen, termasuk penerapan kode etik, di tengah meluasnya pemanfaatan akal imitasi (Artificial Intelligence, AI). Pemerintah pun, disebut Adink, harus meninjau ulang standar-standar reputasi yang mengedepankan publikasi secara kuantitas semata.
Dia kembali menekankan pad pentingnya produk perguruan tinggi yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Akhirnya, temuan indeks RI² ini, idealnya menjadi refleksi kolektif, untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi yang baik. Tanpa perbaikan kebijakan dari hulu, maka di level hilir pun akan carut-marut. Kampus tak lebih akan menjadi mesin produksi “artikel jurnal”.
Penulis: Fina Nailur Rohmah
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id