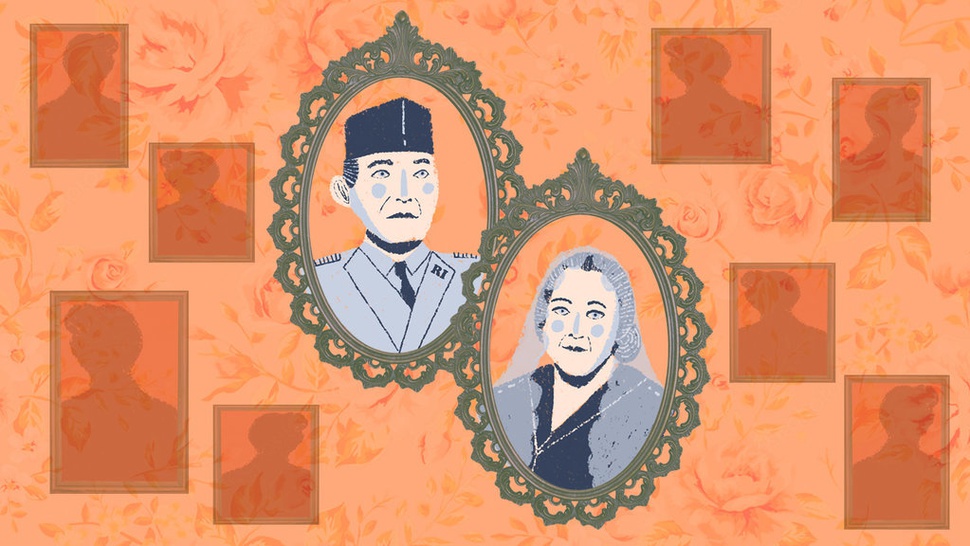tirto.id - Suatu hari pada Agustus 1938, Fatmawati bersemuka dengan Sukarno. Fatmawati, anak semata wayang Hasan Din, pemimpin Muhammadiyah Bengkulu, baru beranjak 15 tahun. Pertemuan keduanya berjalan biasa. Saat itu belum ada pertanda apa pun jika kelak Fatmawati bakal jadi istri Sukarno.
Malam itu Fatmawati tak pulang ke Curup. Sukarno menawari Fatmawati untuk bersekolah di Rooms Katholik Vakschool bersama Ratna Juami, anak angkat Sukarno dan Inggit Garnasih. Fatmawati masih mempertimbangkannya karena, pertama-tama, terbentur persyaratan masuk.
“Bung Karno menjamin akan mengurus hal itu dan mulai hari itu juga aku tinggal di rumah Bung Karno,” kenang Fatmawati dalam memoar Fatmawati, Catatan Kecil Bersama Bung Karno (1985: 32-33).
Akhirnya Fatmawati menerima tawaran itu dan Sukarno menyambutnya sebagai anggota keluarga. Sukarno, 37 tahun saat itu, memandang Fatmawati sebagai gadis remaja yang spesial. Menurutnya, Fatmawati adalah gadis cantik yang menyenangkan dan cukup cerdas; pelipur rasa sepi bagi Sukarno.
Tetapi, Sukarno agaknya belum berani berharap lebih. “Yang aku rasakan padanya adalah kasih-sayang seorang ayah,” kata Sukarno seperti dituturkan kepada Cindy Adams dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (2014: 170).
Sukarno bisa beranggapan demikian, tapi Inggit Garnasih bisa membaca perasaan terdalam suaminya. Sebagai perempuan yang peka, ia merasakan percik-percik ketertarikan dari pandangan suaminya itu. Sekali Inggit menyatakannya, Sukarno membantahnya. Tetapi Inggit terlanjur cemburu, yang menimbulkan suasana rikuh di antara keduanya.
Kehampaan Sukarno
Sehebat apa pun Sukarno di lapangan pergerakan nasional, ia tetaplah lelaki biasa. Hampir dua dekade berumah tangga, Inggit tak mampu memberinya anak. Kenyataan itu membuatnya limbung.
“Istriku sudah mendekati usia 53 tahun. Aku masih muda, penuh vitalitas, dan memasuki usia terbaik di puncak kehidupan. Aku menginginkan anak. Istriku tidak dapat memberikannya padaku. Aku menginginkan kegembiraan hidup. Inggit tidak lagi memikirkan soal-soal seperti itu,” kata Sukarno kepada Cindy Adams (hlm. 171).
Sebab ini pula yang membikin hubungan Inggit dan Fatmawati memburuk. Inggit menyesal telah memperbolehkan anak orang lain memasuki rumah tangganya. Sukarno sendiri tak tega jika harus melepas Inggit. Bagaimanapun ia mencintai Inggit.
Seperti dicatat Ramadhan K.H. dalam Kuantar ke Gerbang: Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno (1981: 383-384), Sukarno ingin Inggit tetap jadi istrinya. “Bukankah bisa aku mengawininya sementara kita tidak bercerai?”
Tetapi, Inggit sudah berketetapan. “Ya, kalau mau kawin dengannya, boleh. Tetapi ceraikan dahulu aku,” ujar Inggit sebagaimana dicatat Ramadhan.
Sukarno Menyatakan Cinta
Sukarno berusaha menekan perasaannya kepada Fatmawati demi cintanya kepada Inggit. Lebih dari ketertarikannya kepada Fatmawati, yang utama dalam benak Sukarno adalah memiliki anak. Karena itu ia meminta kepada Inggit mencari perempuan lain, yang sekiranya lebih cocok untuknya, dan bersedia melupakan Fatmawati.
“Tunjukkan seorang perempuan yang tidak seperti anak kita lagi dan dengan demikian dapat membebaskanmu dari kebencian yang kau rasakan sekarang,” pinta Sukarno kepada Inggit (Cindy Adams, 2014: 173).
Hubungan mereka tegang, tapi mereka tetap meneruskannya. Keadaan tambah berat manakala Ratna Juami kembali ke Jawa untuk meneruskan sekolah. Sukarno semakin kesepian. Di saat itu Fatmawati adalah satu-satunya penghiburan.
Pertahanan Sukarno rubuh tatkala suatu kali Fatmawati mendatanginya untuk meminta saran soal pinangan seorang anak wedana. Bukannya memberi saran, Sukarno justru berterus terang kepada Fatmawati.
“Fat, sekarang terpaksa aku mengeluarkan perasaan hatiku padamu. Dengarlah baik-baik,” ujar Sukarno. “Begini Fat ... sebenarnya aku sudah jatuh cinta padamu pertama kali aku bertemu denganmu, waktu kau ke rumahku dahulu pertama kali.”
Fatmawati bingung. Pelik. Dalam memoarnya, ia mengenang saat itu hanya mampu menjawab: "Fat kasihan sama Bapak.”
Fatmawati tahu belaka bahwa Sukarno telah berkeluarga. Karenanya, tak terbersit perasaan apa pun di hatinya kepada Sukarno selain rasa hormat seorang anak kepada bapak angkat. Sukarno sendiri tak berhenti pada sebatas pengakuan; rayuan maut diutarakannya.
“Aku seorang pemimpin rakyat yang ingin memerdekakan bangsanya dari Belanda, tapi rasanya aku tak sanggup meneruskan jika kau tak menunggu dan mendampingi aku. Kamu cahaya hidupku, untuk meneruskan perjoangan yang maha hebat dan dahsyat.”
Menghadapi rayuan Sukarno itu Fatmawati bergeming. Tak mampu ia memutuskannya sendiri. Dan lagi, sebagai sesama perempuan, Fatmawati tak ingin melukai hati Inggit. Setali tiga uang dengan Inggit, Fatmawati tak bisa menerima poligami.
Selang beberapa waktu, Hasan Din dan Fatmawati menyatakan keberatan atas pinangan Sukarno karena statusnya masih beristri. Kepada Hasan Din, Sukarno meminta waktu enam bulan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Inggit.
Tetapi, lepas enam bulan, tak ada kabar dari Sukarno. Hubungan mereka tetap menggantung hingga kedatangan bala tentara Jepang ke Hindia Belanda pada awal 1942.
Hubungan mereka semakin sulit karena Sukarno harus mengungsi dan kembali ke Jawa. Meski begitu, keduanya tetap berkomunikasi. Saat itu Fatmawati mulai benar-benar jatuh hati pada Sukarno (Fatmawati, 1981: 41-42).

First Lady Fatmawati
Karena perselisihan-perselisihan yang tak terjembatani antara Sukarno dan Inggit, pada akhirnya mereka bercerai pada pertengahan 1943. Sukarno memulangkan kembali Inggit ke Bandung.
Tak berapa lama Sukarno segera mengusahakan pernikahan dengan Fatmawati. Karena Sukarno tak bisa datang ke Bengkulu, pernikahan berlangsung dengan cara perwalian. Sukarno diwakili oleh seorang utusan. Melalui telegram, Fatmawati diberi kabar: “Fatmawati, nikah dengan wakil; yaitu Saudara opseter Sarjono, tanggal 1 Juni 1943 berangkat ke Jakarta. Sukarno.” (Fatmawati, 1981: 48)
Fatmawati kemudian mendampingi Sukarno melewati masa-masa pendudukan Jepang di Jakarta. Anak pertama mereka, Guntur, lahir pada 1944. Ketika Indonesia merdeka dan Sukarno menjadi presiden, Fatmawati dihadapkan pada peran baru sebagai ibu negara.
Menjadi istri presiden di negara baru adalah beban berat. Apalagi situasi pasca-kemerdekaan memanas dengan cepat karena kedatangan Sekutu dan Belanda. Perlawanan dan kontak senjata antara pejuang republik dan tentara Belanda pada akhir tahun 1945 semakin sering terjadi. Dalam situasi genting seperti itulah Fatmawati berdiri di antara peran istri dan ibu negara.
Ia harus membiasakan diri hidup berpindah dan terpisah dari Sukarno untuk menghindari penangkapan Belanda. Dalam memoarnya, Fatmawati berkisah:
“Kalau sudah Magrib aku berpisah dengan Bung Karno. Bung Karno jalan sendiri, sedangkan aku bersama ibuku pergi untuk menginap di tempat kenalan baik dengan pengawalan pistol dan golok. Biasanya kami melalui lorong-lorong kampung menuju tempat rahasia, di mana Bung Karno sudah menunggu atau menyusul. ... Kadang-kadang aku terpaksa menyamar sebagai tukang pecel, dan Bung Karno menyamar sebagai tukang sayur dengan gaya berjalan pincang.” (Fatmawati, 1981: 89)
Ketika pusat pemerintahan dipindah ke Yogyakarta, peran Fatmawati sebagai ibu negara kian terasa. Jika fokus Sukarno pada soal-soal politik dan pemerintah, Fatmawati mendukungnya dengan mengurus rumah tangga istana.
“Dalam keadaan begitu aku berusaha mengatur suasana kekeluargaan seberapa dapat, di samping mengurus dan memperhatikan kepentingan ‘keluarga besar’ yang keluar masuk di tempat itu,” tulis Fatmawati (2010: 130-131).
Fatmawati tak canggung ikut mengurus keperluan pasukan gerilya. Ia memasak makanan yang awet untuk dikirim ke front. Sekali waktu ia pergi sendiri berbelanja tanpa pengawalan. Padahal saat itu Fatmawati sedang hamil (Fatmawati, 1981: 133).
Ia juga kerap mendampingi Sukarno dalam kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah. Tidak hanya sebagai pendamping, ia tampil berpidato menyemangati massa rakyat seperti yang terjadi dalam kunjungan ke Cirebon.
Saat itu Fatmawati diminta massa untuk turut memberi pidato usai Presiden Sukarno turun podium. Fatmawati menyanggupi. Sukarno kelihatan senang dan bangga dengan keberanian istrinya (Fatmawati, 1981: 134).
Peran Fatmawati kian sentral sesudah revolusi. Ketika pemerintahan kembali lagi ke Jakarta, Fatmawati kembali jadi pengatur Istana Merdeka yang terbengkalai.
Ia ikut pula dalam perjalanan Presiden Sukarno ke luar negeri. Ia piawai membangun kedekatan dengan pemimpin-pemimpin negara sahabat Indonesia seperti Perdana Menteri India Nehru dan Perdana Menteri Pakistan Begun Aga Khan.
Peran Fatmawati sebagai first lady berakhir ketika ia memutuskan untuk keluar dari Istana Merdeka sekitar tahun 1955.
Sukarno menikah lagi dengan Hartini pada pertengahan 1954. Itu melukai hati Fatmawati. Seperti sudah diutarakan kepada Sukarno saat kali pertama menyatakan cinta, Fatmawati pantang dipoligami.
Ia lebih memilih keluar dari Istana dan menanggalkan statusnya sebagai ibu negara untuk prinsip tersebut.
Penulis: Fadrik Aziz Firdausi
Editor: Fahri Salam