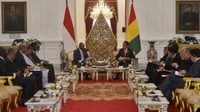tirto.id - Republik Afrika Tengah, sebuah negara tanpa laut yang berbatasan langsung dengan Kamerun, Chad, Sudan dan Kongo dalam beberapa dekade terakhir menghadapi konflik berkepanjangan yang berujung perang sipil.
Pertikaian antar etnis dan konflik sektarian turut mengiringi pertumpahan darah dari 2003 sampai 2007, yang meletus kembali sejak 2012 sampai sekarang. Para pekerja kemanusiaan juga tak luput dari serangan.
Pada Desember 2016 lalu, jawatan PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyebutkan ada sekitar 336 serangan terhadap pekerja kemanusiaan selama perang sipil Republik Afrika Tengah edisi 2012 sampai hari ini.
Baca juga: Dunia yang Semakin Tidak Damai
Sebanyak 56,8 persen dari mereka melakukan perampokan dan pembegalan. Lima pekerja kemanusiaan tewas dalam tugas selama tahun 2016. Sementara sejak tahun 2013 total ada 24 orang pekerja kemanusiaan yang terbunuh.
Terbaru, Stephen O’Brien, Kepala Bantuan PBB pada Senin (7/8) kemarin melontarkan peringatan akan tanda-tanda awal terjadinya genosida di Republik Afrika Tengah. Ia mengimbau pengiriman lebih banyak tentara dan polisi untuk memperkuat misi pasukan penjaga perdamaian PBB.
"Tanda-tanda peringatan dini genosida sudah terlihat," ujar O'Brien pada sebuah pertemuan PBB menyusul kunjungannya baru-baru ini ke Republik Afrika Tengah dan Republik Demokratik Kongo seperti dilansir dari Aljazeera.
"Kita harus bertindak sekarang, tidak mengurangi usaha PBB, dan berdoa agar kita tidak menyesalinya."
Sebenarnya peristiwa genosida memang sudah terjadi di negara bekas jajahan Perancis yang memiliki deposit sumber daya alam melimpah dari minyak mentah, uranium sampai emas.
Perang dimulai dari para kelompok bersenjata. Pada tanggal 10 Desember 2012 di Kota Ndele sebuah pertarungan pecah yang melibatkan pasukan bersenjata dengan pasukan militer keamanan Republik Afrika Tengah.
Baca juga: Sudan Selatan, Negara Baru yang Terus Bergejolak
Menurut sumber militer kepada AFP , ada banyak penduduk mengungsi ketika orang-orang bersenjata mulai memasuki kota dan melepaskan tembakan disertai suara ledakan keras. Antara 2007 sampai 2010, Ndele memang menjadi titik kontak senjata berbagai kelompok pemberontak dan tentara.
Aliansi pemberontak ini tidak lain terdiri dari faksi-faksi yang memisahkan diri dari berbagai kelompok pemberontak besar seperti Konvensi Patriot untuk Keadilan dan Perdamaian (CPJP), Persatuan Pasukan Demokratik untuk Persatuan (UFDR), Konvensi Patriotik untuk Menyelamatkan Negara (CPSK) yang ikut bermain dalam perang sipil 2003 dan telah menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah tahun 2007 silam.
Aliansi baru bernama Séléka (“persatuan” dalam bahasa lokal Sango), beranggotakan mayoritas Muslim dan dipimpin oleh Michael Djotodia. Mereka merasa tidak puas dengan perkembangan perjanjian kesepakatan damai antara pemerintah dengan pemberontak. Mereka juga mengancam akan menggulingkan Presiden Republik Afrika Tengah, Francois Bozize. Pada maret 2013, Bozize digulingkan.
Baca juga: Kisah Berlian Berdarah di Sierra Leone
Djotodia masuk ke pemerintahan sebagai wakil perdana menteri pertama untuk pertahanan nasional pada Februari 2013. Kesepakatan damai kembali dirintis untuk menyelesaikan konflik, akan tetapi masih menemui kegagalan.

Setelah Séléka merebut Kota Bangui, Djotodia mengambil alih kekuasaan menjadi presiden pada 24 Maret. Bozize yang tersingkir terpaksa mengasingkan diri dari negerinya. Kendati berjanji memimpin masa transisi menuju perdamaian, api telah menyeret akar rumput ke dalam kekerasan sektarian. Kalangan Muslim, Kristen dan penganut kepercayaan lokal dalam hal ini terlibat pertikaian berdarah.
Kelompok milisi bersenjata Kristen dan beberapa penganut kepercayaan lokal terbentuk bernama Anti-balaka. Menurut laporan The Centre on Religion & Geopolitics, jumlah mereka bertambah khususnya dari para mantan anggota tentara nasional yang dibubarkan Djotodia.
Baca juga: 7 April 1994, Dimulainya Pembantaian Etnis
Pembunuhan bermotif dendam pun tak terhindarkan antara Séléka dan Anti-balaka. Pada Desember 2013, Amnesty Internasionalmelaporkan bahwa dalam waktu dua hari, para mantan pemberontak Séléka yang secara de facto dalah pasukan pemerintah, membunuh hampir 1.000 orang di Bangui, ibukota Republik Afrika Tengah dengan dalih membalas dendam atas serangan milisi Anti-balaka yang telah membunuh 60 laki-laki Muslim.
Sementara aksi para milisi Anti-balaka juga tak kalah sadis. Laporan Human Right Watch pada September 2013 menyebutkan bahwa di kota utara Bossangoa, milisi Kristen menyerang komunitas Muslim, memotong leher anak-anak sambil memaksa orang-orang dewasa untuk menyaksikannya. Pada 2014, dengan kode operasi MUNISCA, Pasukan Perdamaian PBB diterjunkan ke lokasi.
Sampai detik ini, kondisi mencekam masih membayangi negeri yang kaya sumber daya alam itu. Perang sipil yang melibatkan berbagai faksi milisi memaksa 410.000 lebih penduduk Republik Afrika Tengah mengungsi.
Setengah dari populasi negera tersebut, atau sekitar 2,4 juta orang membutuhkan bantuan pangan untuk bertahan hidup.
Baca juga: Kekeringan dan Kelaparan Parah di Somalia
Meski begitu, suara perdamaian terus didengungkan, termasuk oleh sekelompok orang yang terdiri dari lima pastor dan seorang imam. “Tidak ada perbedaan antara Muslim dan Kristen di sini,” kata Pastor Leon Dollet dilansir dari Deutsche Welle. “Kami selalu hidup harmonis”.
Selama ini mereka terus mengirimkan surat pesan perdamaian demi berakhirnya konflik.
“Itu ulah 3R (kelompok bersenjata yang didominasi Muslim) dan Anti-balaka yang menyebabkan ketegangan, tapi kami ingin hidup bersama lagi dengan damai, dan kami ingin orang-orang yang kehilangan tempat tinggal dari desa-desa tetangga untuk pulang dan tinggal bersama kami lagi,” ucap Leon Dollet.
Penulis: Tony Firman
Editor: Windu Jusuf