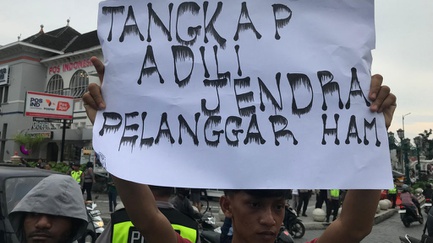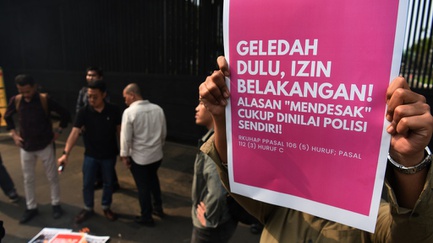tirto.id - Jutaan orang Indonesia hidup dengan penyakit kronis menghadapi kenyataan pahit: kerap dikecualikan dari kerangka disabilitas, sehingga diabaikan haknya dan lepas dari dukungan vital. Pengecualian ini bukan hanya tak adil, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip inti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD).
Ketika orang-orang penyandang penyakit kronis dipinggirkan, mereka kehilangan akses atas perlindungan hukum dari diskriminasi, rekognisi kebijakan pada tempat kerja atau sekolah, afirmasi hak disabilitas, hingga perawatan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Fadel Nooriandi, 31 tahun, telah menyandang talasemia mayor sejak berusia 8 bulan. Talasemia merupakan suatu kelainan darah yang diturunkan dari orang tua, yang membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Anemia yang dialami penderita talasemia akan menimbulkan keluhan cepat lelah, mudah mengantuk, hingga sesak napas. Akibatnya, aktivitas penderita talasemia akan terganggu.
Kembali ke Fadel. Setiap tiga minggu sekali, ia harus transfusi darah. Seumur hidup. Setiap hari ia wajib menelan obat kelasi besi untuk mengeluarkan kelebihan zat besi imbas transfusi.

Jika tidak terkontrol rutin, penumpukan zat besi menciptakan kondisi komplikasi bagi dirinya. Organ vital seperti jantung, hati, limpa, dan pankreas akan terdampak.
Tahun 2022, Fadel sempat dilarikan ke IGD dan ICU karena kondisinya melemah dan kritis. Ternyata, hasil pemeriksaan menunjukkan terjadi komplikasi jantung dan diabetes karena efek dari transfusi darah.
Imbasnya, Fadel diwajibkan lagi minum obat tambahan dan suntik insulin setiap hendak makan dan sebelum tidur. Ini efek dari penumpukan zat besi karena transfusi darah yang menyerang jantung dan pankreas.
“Namun, saya sudah belajar berdamai dan ikhlas,” kata Fadel kepada wartawan Tirto, Rabu (22/10/2025).
Fadel sepakat jika penyintas dan penyandang penyakit kronis – seperti talasemia – dikenali sebagai bagian ragam disabilitas. Konsep invisible disability atau disabilitas tak kasat mata sayangnya, masih belum dipahami luas di Indonesia. Itulah mengapa Fadel ikut berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) bersama penyandang penyakit kronis lainnya dalam uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Pada Selasa (21/10/2025), Fadel hadir di MK sebagai saksi Pemohon untuk Perkara Nomor 130/PUU-XXIII/2025 yang dilayangkan oleh dua penyandang penyakit kronis, yakni Raissa Fatikha dan Deanda Dewindaru. Pemohon menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Para pemohon menilai hak konstitusional mereka dirugikan karena tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap penyakit kronis sebagai salah satu ragam disabilitas di UU Disabilitas.
Keterbatasan Serius
Menurut Fadel, banyak orang dengan penyakit kronis seperti talasemia, gagal ginjal, lupus, kanker, hingga autoimun yang mengalami keterbatasan serius dalam aktivitas harian. Ini adalah salah satu efek dari kondisi medis kronis yang berkelanjutan dan pengobatan yang berat.
Ketika Undang-Undang Disabilitas hanya mengakui disabilitas yang tampak, negara seolah mengabaikan jutaan orang yang hidup dengan penyakit kronis tetapi memiliki keterbatasan yang nyata. Padahal prinsip dasar Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: kesetaraan dan nondiskriminasi.

“Saya hadir di sidang MK untuk menegaskan pengakuan, bukan tentang belas kasihan, tapi tentang keadilan sosial. Dengan pengakuan itu, penyintas seperti kami bisa mendapatkan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, fasilitas umum, dan layanan kesehatan tanpa stigma negatif atau penolakan,” ujar Fadel.
Dalam sidang lanjutan Selasa lalu, sebagai saksi, Fadel menyampaikan kesaksian terkait hambatan yang dialaminya. Ia mengaku kerap mengalami diskriminasi dan kesulitan di dunia kerja akibat kebutuhan transfusi darah rutin, serta stigma sosial terhadap kondisinya.
Sidang lanjutan ini juga menghadirkan perwakilan DPR, setelah sebelumnya menghadirkan dari sisi pemerintah. Sayangnya, perwakilan dari DPR dan pemerintah langsung meminta MK agar menolak permohonan dari para pemohon.
Dalam sidang, Anggota Komisi III DPR Sari Yuliati menegaskan pentingnya asesmen medis dalam menentukan status disabilitas seseorang. Menurutnya, tidak semua penyakit kronis bisa serta-merta dikategorikan sebagai disabilitas.
DPR menilai, perluasan definisi disabilitas untuk mencakup kondisi seperti penyakit kronis, autoimun, nyeri kronis, dan kanker bakal berpotensi kontraproduktif. Hal itu dinilainya dapat menimbulkan multitafsir dan menyulitkan implementasi kebijakan perlindungan disabilitas.
Sementara pemerintah, yang diwakili Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial, Supomo, dalam sidang sebelumnya, pada Selasa (7/10/2025), turut meminta agar MK menolak permohonan para pemohon. Alasannya hampir sama, penyakit kronis diklaim bukan disabilitas, walaupun dapat menjadi penyebab seseorang menjadi disabilitas.
Mirna (30), penyandang talasemia mayor, mendukung gugatan UU Disabilitas di MK yang diajukan Raissa Fatikha dan Deanda Dewindaru. Mirna merasa bahwa talasemia sebagai penyakit kronis merupakan disabilitas yang tidak tampak. Sejak usia 8 bulan, ia mesti lakoni transfusi darah sepanjang hayatnya kelak.
Dukungan agar penyakit kronis seperti talasemia masuk dalam ragam disabilitas didasari atas pengalaman diskriminatif yang masih diterima Mirna. Misal ketika menjalani pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi, pihak pengajar kerap tidak memahami kondisi Mirna yang berimbas sulitnya ia mendapatkan izin untuk berobat rutin.
Begitupun ketika ia mendaftar pekerjaan. Cuma sedikit rekrutmen yang memahami bahwa ia memiliki kondisi talasemia, sehingga sering tidak diloloskan ketika melakukan tes kesehatan calon pegawai.
“Juga di sarana transportasi umum, kami juga memiliki kendala dimana yang saya rasakan adalah ketika saya pulang transportasi, plaster masih ada di tangan kanan saya ataupun kiri. Saya coba berikan penjelasan, tetapi sulit ada yang paham, ada yang tidak paham jadi tidak adanya space, memang disabilitas tidak tampak untuk kami,” tutur Mirna kepada wartawan Tirto, Rabu (22/10/2025).
Sementara penyintas talasemia lainnya, Nisa (31), mengaku belum dapat mengambil posisi pro atau kontra terhadap gugatan di MK supaya penyakit kronis dimasukkan dalam ragam disabilitas. Kendati begitu, Nisa mengaku masih kerap mendapatkan tantangan baik ketika melakukan penanganan medis rutin maupun dalam pergaulan sosial.
Misal, kata dia, sistem rujukan nasional yang harus diperbarui setiap 3 bulan sekali. Nisa menilai bahwa waktu 3 bulan merupakan jendela durasi yang sempit bagi seorang penyintas penyakit kronis yang harus hidup berdampingan dengan rumah sakit. Hal itu membuatnya perlu waktu lebih untuk mengurus administrasi keperluan perpanjangan rujukan.
Selain itu, diskriminasi dalam ranah pekerjaan juga masih diterima. Padahal, kata dia, bukan kehendak dan kesalahan dari seorang penyandang penyakit kronis karena memiliki kondisi yang berbeda dengan orang lainnya.
“Saya sangat berharap ada tangan negara yang dapat membantu kami untuk menghapus diskriminasi dan stigma negatif tersebut. Bantu kami untuk dapat kehidupan yang layak, bisa bekerja, bisa sekolah, bisa berkarya dengan bebas seperti orang lainnya,” ungkap Nisa kepada wartawan Tirto, Rabu (22/10/2025).
Memperluas Definisi Disabilitas
Pemerhati hak disabilitas sekaligus mantan Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad, menyatakan bahwa tidak perlu ada pendefinisian ulang soal disabilitas, tapi penafsirannya perlu lebih luas dan inklusif. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf (a), kata dia, seharusnya dipahami secara fungsional dan interaksional, sesuai semangat UNCRPD dan UU Nomor 8 Tahun 2016.
Menurut pria yang akrab dipanggil Cak Fu itu, penjelasan bukan batasan kaku, melainkan contoh ilustratif. Maka, disabilitas fisik tak boleh dibatasi hanya pada gangguan fungsi gerak, namun juga mencakup fungsi tubuh lain.

“Baik yang terlihat maupun tidak, permanen, jangka panjang, atau episodik. Selama ada hambatan lingkungan atau sosial yang menghalangi partisipasi setara,” ujar Cak Fu, yang juga menjadi saksi ahli bagi para pemohon gugatan UU Disabilitas di MK.
Dalam konteks itu, MK memiliki peran penting memberi tafsir konstitusional terhadap norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau diskriminasi. Tafsir ini jadi bentuk koreksi yang proporsional karena tidak mengubah isi dari undang-undang, tetapi memastikan penerapan yang sesuai dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.
Pendekatan seperti itu, menurut Cak Fu, sejalan peran MK sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga, khususnya kelompok rentan.
Banyak negara sudah mengakui penyakit kronis sebagai ragam disabilitas, termasuk Inggris Raya, Australia, dan Filipina. Namun, penyakit kronis maupun disabilitas tak tampak belum diakui sebagai disabilitas dalam undang-undang Indonesia.
Cak Fu mencontohkan, negara Inggris, lewat Equality Act 2010, mendefinisikan disabilitas sebagai gangguan fisik ataupun mental yang berdampak signifikan jangka panjang terhadap aktivitas normal. Menariknya, kondisi yang naik-turun atau muncul secara episodik juga tetap diakui sebagai disabilitas, semisal kambuh mengganggu fungsi hidup sehari-hari.
Hal serupa juga berlaku di AS lewat Americans with Disabilities Act Amendments Act atau ADAAA. Aturannya bahkan memperluas perlindungan untuk orang dengan kondisi episodik atau dalam masa remisi.
Karenanya, ia menilai pernyataan DPR dan pemerintah yang secara terbuka mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan terhadap UU Disabilitas perlu disikapi dengan hati-hati dan kritis. Sebagai institusi yang mewakili rakyat dan menjalankan fungsi pelayanan publik, mestinya DPR dan pemerintah menempatkan diri sebagai pihak pendengar aspirasi, bukan sekadar menolak.

“Intinya, yang dilihat bukan diagnosisnya, tapi sejauh mana kondisi itu membatasi aktivitas penting seperti berjalan, belajar, bekerja, atau berpikir. Jadi, ukurannya adalah dampak nyata terhadap kehidupan, bukan label medisnya,” terang Cak Fu.
Kuasa hukum para pemohon perkara Nomor 130/2025, Fauzi, menerangkan kliennya yakni Raissa (penyandang Thoracic Outlet Syndrome) dan Deanda (penyandang autoimun Sjogrën’s Disease) menilai bahwa penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) UU Disabilitas belum mengakomodasi kondisi disabilitas fisik yang tak tampak.
Sebab, penjelasan pasal 4 ayat (1) secara terbatas mendefinisikan penyandang disabilitas fisik sebagai “terganggunya fungsi gerak”. Padahal, kata Fauzi, mengacu ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), bentuk keterbatasan fungsi pada disabilitas fisik dapat pula bersifat tak tampak, seperti kelelahan kronis, nyeri, maupun penurunan atau masalah pada fungsi organ/sistem organ.
Lebih jauh lagi, UNCRPD yang menjadi dasar dari UU Disabilitas mendefinisikan disabilitas sebagai “evolving concept” alias konsep yang berkembang. Artinya, konsep maupun definisi disabilitas itu sendiri tidak boleh dibatasi secara kaku.
Oleh karena itu, pemohon ingin penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) dari disabilitas fisik dapat diperluas pemaknaannya menjadi “terganggunya fungsi fisik”.
“Perlu ditekankan pula, para Pemohon tidak bermaksud menjadikan semua penyakit kronis sebagai disabilitas. Melainkan, para Pemohon menekankan pentingnya UU Disabilitas untuk mengakui adanya disabilitas fisik tak tampak akibat penyakit kronis tertentu yang secara signifikan menyebabkan keterbatasan fungsi sosial,” terang Fauzi kepada wartawan Tirto, Rabu (22/10/2025).
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Farida Susanty
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id