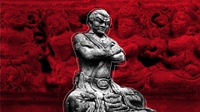tirto.id - Selain Kiai Mojo dan Sentot Prawirodirjo yang asli Jawa, beberapa orang dalam lingkaran terdekat Pangeran Diponegoro adalah kaum peranakan. Sebagian dari mereka, selain memiliki hubungan darah dengan sang pangeran, juga dikenal pemberani dan ahli siasat.
Setelah larut dalam perang saudara, pada 1755 Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi, kemudian bergelar Hamengku Buwono I, menyepakati Perjanjian Giyanti. Akibat perjanjian itu, Kasultanan Mataram pecah menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.
Pada tahun yang sama, seorang perantauan Arab bernama Sayid Alwi Ba’abud mendarat di pantai utara Jawa. Selain saudagar kuda dari Hadramaut, ia adalah ulama dan tabib.
Menurut satu versi, Sayid Alwi Ba’abud sudah menjalin hubungan dengan Keraton Yogyakarta ketika Hamengku Buwono I bertakhta. Ia bahkan bersahabat dengannya, dan karena kedalaman ilmunya tentang Islam, ia dipercaya menjadi penasihat agama di lingkungan keraton.
Versi lain menyebutkan bahwa kontak antara Sayid Alwi Ba’abud dengan keluarga keraton terjadi di Ceylon (Sri Lanka), ketika Hamengku Buwono II diasingkan Inggris ke negeri tersebut. Saat kembali ke Yogyakarta, Hamengku Buwono II menjodohkan putrinya yang bernama Raden Ayu Samparwadi dengan Sayid Husain Ba’abud, putra Sayid Alwi Ba’abud.
Menurut Siti Hidayati Amal dalam Menelusuri Jejak Kehidupan Keturunan Arab-Jawa di Luar Tembok Keraton Yogyakarta (hlm. 164-165), perjodohan tersebut bermula saat Samparwadi--kala itu 14 tahun--sakit keras dan tak kunjung sembuh. Seperti dalam kisah pewayangan, Hamengku Buwono II kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menyembuhkan putrinya, jika perempuan akan diangkat sebagai saudara anaknya, dan jika laki-laki akan dinikahkan dengannya.
Singkat cerita, Samparwadi sembuh di tangan Sayid Alwi Ba’abud yang saat itu sudah 65 tahun. Merasa tak pantas menikahi gadis remaja, diaturlah perjodohan antara Samparwadi dengan putranya, Sayid Husain Ba’abud.
Ketika Perang Jawa (1825-1830) meletus, menurut Peter Carey dalam The Power of Prophecy (hlm. 627), Sayid Husain Ba’abud yang juga dikenal dengan nama Kiai Haji Hasan Munadi atau Tumenggung Samparwadi, menjabat panglima Barjumungah, sebuah resimen khusus pengawal Pangeran Diponegoro.
Seturut Siti Hidayati Amal dalam “Menelusuri Jejak Kehidupan Keturunan Arab-Jawa di Luar Tembok Keraton Yogyakarta” (2005:164), putra sulung Sayid Husein Ba’abud adalah Sayid Ibrahim Ba’abud alias Pekih Ibrahim, juga aktor penting dalam Perang Jawa. Tugasnya sebagai juru runding Diponegoro.
Salah satu misi yang pernah dijalankannya adalah menemui Kolonel Cleerens untuk membicarakan rencana perundingan antara sang pangeran dengan pucuk pimpinan pasukan Belanda, yakni Letnan Jenderal Hendrik Merkus de Kock di Magelang, 28 Maret 1830.
Belakangan terbukti perundingan itu hanya akal-akalan Belanda untuk menjebak Diponegoro.
Setelah Perang Jawa dipadamkan, Sayid Ibrahim Ba’abud dibuang Belanda ke Ambon, sementara Diponegoro ke Makasar. Hingga akhir hayatnya, mereka tidak pernah kembali ke Yogyakarta. Masing-masing meninggal di Benteng Victoria dan Benteng Rotterdam.
Sama-sama Berdarah Biru
Sayid Ibrahim Ba’abud sadar betul dalam tubuhnya mengalir darah Arab. Namun, pria yang oleh Hamengku Buwono II diberi nama Raden Mas Haryo Madiokusumo itu tak bisa mengingkari bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga Keraton Yogyakarta.
Adalah Ratu Ageng Tegalrejo, permaisuri Sultan Hamengku Buwono I yang juga anggota persaudaraan sufi Syattariyah, yang berjasa mendidiknya dengan nilai-nilai Islam dan budaya Jawa. Bersama nenek buyutnya itu, ia meninggalkan keraton dan hidup laiknya kawulo alit di sebuah desa yang berada di tengah-tengah persawahan, Tegalrejo.
Sayid Ibrahim Ba’abud tidak sendiri. Sepupunya yang merupakan pewaris takhta Keraton Yogyakarta yakni Raden Mas Ontowiryo juga ikut. Nama yang terakhir, selanjutnya dikenal dengan Pangeran Diponegoro, kelak menolak statusnya sebagai putra mahkota dan memilih bergerilya melawan Belanda.
Meski berdarah Arab, Sayid Ibrahim Ba’abud lebih suka memakai pakaian Jawa, berbeda dengan Diponegoro, yang meski Jawa tulen tapi gemar memakai jubah dan sorban. Bagi Diponegoro, busana Arab secara simbolis menegaskan dirinya sebagai pemimpin spiritual umat Islam di Tanah Jawa dalam perang melawan Belanda.
Selain Sayid Husain Ba’abud dan Sayid Ibrahim Ba’abud, tokoh penting lain dalam pasukan Diponegoro yang juga berdarah campuran adalah Pangeran Joyokusumo, dikenal juga dengan Pangeran Ngabehi.
Seturut Peter Carey dalam The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855 (2008:98), Pangeran Joyokusumo adalah putra Hamengku Buwono II dengan salah satu selir atau garwa ampeyan yang berdarah Cina dan paling dicintainya, yakni Raden Mas Ayu Sumarsonowati.
Penulis yang sama dalam Orang Cina, Bandar Tol, Candu, & Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825 (2015:45-46) menyatakan bahwa dalam sebuah riwayat sejarah Madura-Jawa, Pangeran Joyokusumo digambarkan sebagai “bangsawan yang bertubuh bagus, cerdas, serta penuh kewaspadaan”.
Sebagai peranakan Cina-Jawa yang mewarisi kulit kuning ibunya, penampilan Pangeran Joyokusumo memang tampak berbeda dibanding keturunan Hamengku Buwono II yang lain.
Di kalangan keluarga keraton, kulit kuning dipandang sebagai puncak kecantikan seorang wanita. Tak heran Hamengku Buwono II menggemari wanita berkulit kuning dan lazim mengutus para pesuruhnya ke pesisir utara Pulau Jawa untuk menangkap wanita peranakan Cina dan menjadikannya pengiring atau bagian dari korps srikandi bernama Langen Kusuma.
Seturut Hendra Kurniawan dkk dalam “Public History of Chinese-Javanese Harmony in Yogyakarta for History Learning with Diversity Insights” (2023:143), dalam Perang Jawa, Diponegoro juga terbantu oleh keberadaan sejumlah prajurit wanita yang sebagian anggotanya merupakan kaum peranakan Cina.
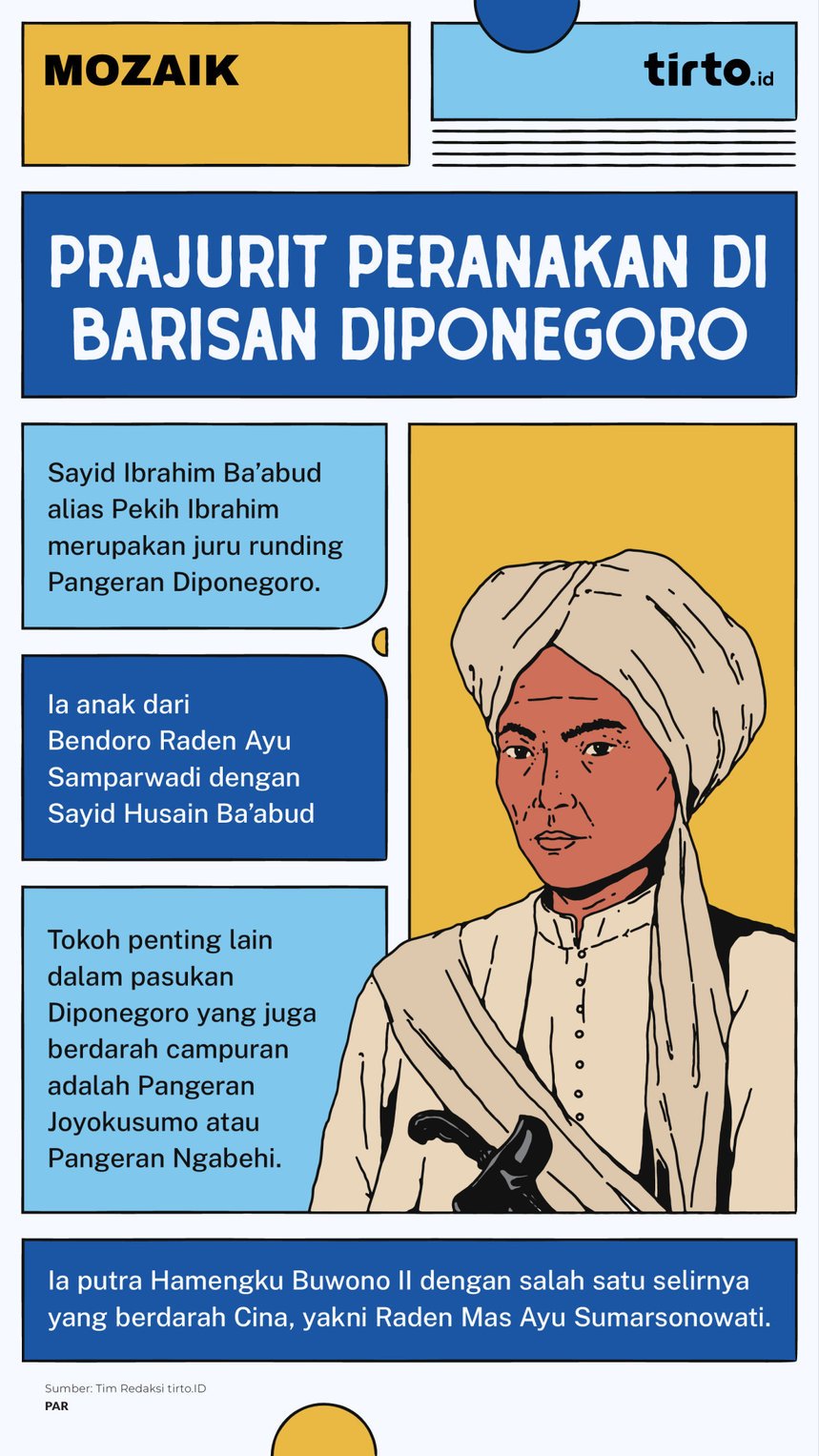
Ahli Siasat Peranakan Cina
Selain penampilannya yang berbeda, Pangeran Joyokusumo juga memiliki nyali dan kecerdasan di atas rata-rata. Ketika benteng keraton dibombardir pasukan Sir Thomas Stamford Raffles dalam peristiwa Geger Sepehi (19-20 Juni 1812), ia adalah satu dari sedikit pangeran yang memilih bertahan di dalam keraton menghadapi serangan itu.
Sikap tersebut berbeda dengan sejumlah pangeran yang memilih bersembunyi dan berpura-pura sakit, melarikan diri ke rumah keluarga istri mereka di desa-desa di sekitar keraton, atau mengungsi bersama keluarganya ke komplek permakaman keraton di Imogiri.
Ketika Perang Jawa meletus, tujuh dari 19 putra Hamengku Buwono II bergabung dalam barisan Diponegoro, keponakan mereka. Mereka adalah Bintoro, Joyokusumo, Mangkubumi, Notodipuro, Purwokusumo, Singosari, dan Wiromenggolo.
Dari tujuh nama tersebut, hanya Joyokusumo dan Wiromenggolo yang selalu mendampingi Diponegoro di setiap pertempuran. Dibanding Wiromenggolo, hubungan Joyokusumo dan Diponegoro lebih dekat. Sebabnya, Joyokusumo memiliki banyak pengalaman dalam siasat perang. Lain itu, ia adalah besan Diponegoro.
Karena pengalaman tempurnya, ia diberi mandat sebagai komandan senior dan panglima kavaleri. Di antara para penasihat dan ahli siasat Diponegoro, Pangeran Joyokusumo adalah salah satu yang paling dipercaya.
Tidak seperti Diponegoro atau Sayid Ibrahim Ba’abud yang pada 1830 ditangkap dan dibuang ke luar Jawa, sepak terjang Pangeran Joyokusumo terhenti dengan menjadi martir di Gunung Kelir, Bagelen. Ia tewas bersama dua anaknya, Joyokusumo II dan Adikusumo, setelah disergap pasukan Belanda pada 21 September 1829.
Ketika berita kematian Pangeran Joyokusumo dan dua anaknya sampai ke telinga Diponegoro, ia sangat terpukul. Babad Dipanagara mengisahkan bagaimana perasaan sang pangeran tatkala mengetahui kabar duka itu.
Sarta mijil wespanèki/
rumaos kantun pribadya/
lawan ing Tanah Jawané/
rumaos tan saged nata/
lamun amrih salaminya/
dhumateng kang samya kantun.
"Air mata menggenang dan sultan
merasa dirinya ditinggal sendiri
di Tanah Jawa.
Dia merasa tak bisa mengendalikan,
meski dirinya terus berusaha,
bagi mereka yang tersisa."
Penulis: Firdaus Agung
Editor: Irfan Teguh Pribadi