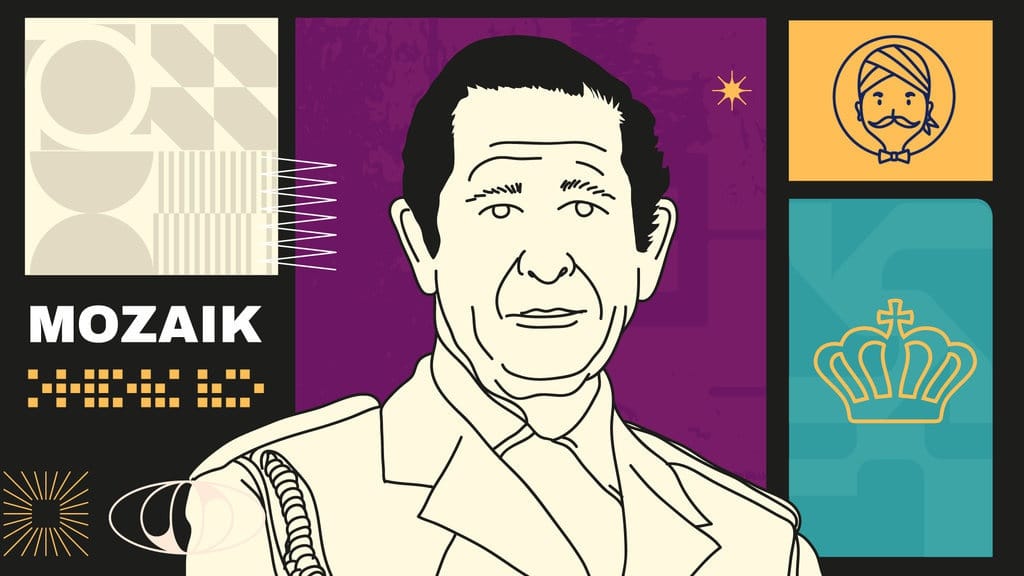tirto.id - “Pekerjaan resmi Charles sebagai Raja Inggris adalah menjaga iman Gereja Anglikan yang dibiayai negara. Namun, dia berulang kali bilang ingin menjaga semua iman. Ini kesombongan yang dia kembangkan dalam enam dekade melakukan satu-satunya tugas resmi: menunggu ibunya meninggal.”
Demikian pendapat jurnalis Christopher Hitchens di media analisis dan komentator politik Slate.com pada 2010. Esai lengkapnya juga dimuat dalam kumpulan tulisan berjudul Arguably: Essays by Christopher Hitchens (2011, hlm. 494).
Esai Hitchens secara garis besar mengkritik Kerajaan Inggris yang membangun prinsip berpolitik dari nilai-nilai keagamaan keluarga Raja Henry VIII yang berkuasa pada 1509 hingga 1547.
Nujum Hitchens itu terjadi 12 tahun kemudian. Ketika mengambil alih takhta Kerajaan Inggris dari Ratu Elizabeth II yang mangkat pada 8 September 2022, Raja Charles III tidak hanya mendapatkan tanggung jawab sebagai pewaris kerajaan beserta seluruh wilayah persemakmurannya. Raja baru itu juga harus mengambil peran sebagai “penjaga iman” dengan gelar Defender of the Faith atau Fidei Defensor.
Gelar itu pertama kali diberikan oleh Paus Leo X kepada Raja Henry VIII pada 1521 sebagai penghargaan atas jasa sang raja membela agama Katolik Romawi dari gerakan Reformasi Protestan yang dilakukan oleh Martin Luther. Akan tetapi, konteks pemberian gelar itu sebenarnya berbeda dengan gelar yang kini diemban Raja Charles III.
Kontroversi sang Fidei Defensor Pertama
Ketika Luther melancarkan protes keras terhadap Vatikan, dia menuliskan garis besar pemikirannya dalam bentuk 95 poin tesis atas khasiat pengampunan dosa. Kala itu, Luther menjabat sebagai profesor bidang teologi moral dan proposisi itu ditujukan sebagai naskah akademik di Universitas Wittenberg pada 1517.
Dengan naskah itu, Luther ingin membuka ruang diskusi yang mempertanyakan kebijakan otoritas Vatikan.
Empat tahun kemudian, Raja Henry VIII menerbitkan risalah pembelaan terhadap agama Katolik Romawi berjudul Assertio Septem Sacramentum—Pertahanan atas Tujuh Sakramen. Henry VIII mulai menulis risalah itu sejak 1519 usai membaca naskah “serangan” Luther terhadap indulgensia.
Sebenarnya, banyak yang curiga bahwa risalah itu sebenarnya ditulis oleh Sir Thomas More. Kala itu, More punya posisi penting dalam lingkaran istana raja Inggris. Sebagai filsuf, negarawan, ahli hukum, dan humanis, dialah yang sebenarnya punya kapabilitas mumpuni untuk menulis risalah sedetail itu.
Sikap More terhadap naskah Luther sangat jelas, menentang keras dan mati-matian membela agama Katolik. Sikap itu melahirkan polemik intelektual berkepanjangan antara dirinya dengan para aktivis reformasi Protestan seperti Martin Luther, Huldrych Zwingli, John Calvin, dan William Tyndale. Sampai akhir hayatnya, More tetap berpegang teguh pada iman yang ia yakini.
Meski demikian, gelar Fidei Defensor tetap diberikan pada Henry VIII. Dengan sandangan gelar agung itu pun, Pemerintahan Raja Henry VIII sebenarnya penuh dengan kontroversi.
Sejak muda, dia hidup di tengah suasana Renaissance. Ketika menjadi raja Inggris, dia tercatat mengirimkan dua orang mantan istrinya untuk dieksekusi mati. Tindakan ini ditentang oleh More.
Bukan sekali itu saja More menentang Raja Henry VIII. Dia bahkan beberapa kali terang-terangan menentang Henry VIII, termasuk untuk urusan pernikahan sang raja yang tak sesuai hukum Katolik.
Ketidakcocokkan dan selisih paham antara More dengan Henry VIII pada akhirnya berujung pemecatan More dari posisi Lord Chancellor Kerajaan Inggris.
More kemudian dieksekusi mati pada 1535. Keberanian More membela Katolik Romawi itu membuatnya dikanonisasi sebagai martir oleh Paus Pius XI dan diangkat menjadi salah satu orang kudus (Santo) pelindung negarawan dan politisi oleh Paus Yohanes Paulus II pada 2000.
Memisahkan Diri dari Vatikan
Sepeninggal Thomas More, polemik yang muncul dari gerakan Martin Luther itu tetap menjadi perdebatan hangat di Inggris. Akan tetapi, kelompok Protestan kala itu merupakan golongan minoritas.
Di Inggris, gema perdebatan itu kemudian menjadi semakin politis, dan bukan teologis. Henry VIII bahkan membuatnya menjadi semakin rumit dengan urusan rumah tangga ketika dia meminta otoritas Vatikan membatalkan pernikahannya dengan Ratu Catherine of Aragon.
Dengan aturan yang ketat selama ratusan tahun, Vatikan tidak mungkin menyetujui rencana Henry VIII menceraikan istrinya itu. Terlepas dari penolakan Paus, Henry tetap berpisah dengan Catherine pada 1531.
Untuk melegalkan tindakannya itu, Henry VIII memerintahkan Uskup Agung Canterbury Thomas Cranmer—pejabat Gereja tertinggi di Inggris—untuk mengadakan pertemuan besar. Agenda pertemuan itu adalah menghapus otoritas keagamaan Katolik Romawi di seluruh daratan Inggris Raya dan menyusun legalitas keagamaan untuk urusan pernikahannya.

Pada 23 Mei 1533, dengan landasan hukum Gereja yang baru dibuat khusus untuk Kerajaan Inggris, Cranmer mengeluarkan keputusan legal mengenai peresmian perceraian Raja Hendy VIII dan Catherine.
Lima hari kemudian, Cranmer mengumumkan bahwa Raja telah resmi menikah dengan Anne Boleyn sesuai dengan landasan hukum Gereja dan Kerajaan Ingris. Pernikahan ini juga secara sah memisahkan Kerajaan Inggris dari agama Katolik Romawi.
Peristiwa ini sekaligus menjadi momentum utama lahirnya Church of England alias Gereja Anglikan. Pada tahun yang sama, Parlemen Inggris juga mencabut tuntutan banding perceraian Henry VIII dan Catherine.
Parlemen Inggris lalu mengesahkan Undang-undang Supremasi 1534 yang mengakui raja sebagai kepala tertinggi Gereja di Inggris dengan “kekuatan dan otoritas penuh” untuk “mereformasi” institusi dan “mengubah” semua kesalahan dan ajaran sesat.
Raja Henry VIII kemudian menunjuk Thomas Cromwell untuk menjadi penasihat urusan spiritual. Cromwell langsung mengambil langkah tegas. Antara 1536 hingga 1538, semua ritual penyembahan selain dengan cara Anglikan dianggap berhala dan dilarang. Para penentang aturan itu pun dihukum mati.
Vatikan bereaksi terhadap tindakan Inggris itu dengan mencabut gelar Fidei Defensor Raja Henry VIII. Paus Paulus III tak punya pilihan lain selain mengasingkan Kerajaan Inggris dari dominasi Katolik Romawi Eropa pada 1538.
Terlepas dari pengasingan oleh Vatikan, Gereja Anglikan justru berkembang pesat setelah itu. Cabang agama baru ini sukses menarik pengikut hingga jauh di luar daratan Inggris Raya. Meski begitu, tetap ada beberapa kantong perlawanan di Inggris yang tetap menyatakan kesetiaan teologis pada Katolik Roma.
Meski Gereja Anglikan telah berdiri, Raja Henry VIII sebenarnya tidak pernah benar-benar melepaskan diri dari tradisi Katolik. Dia tetap menjalankan ritual Katolik Romawi sambil menunggu sistem ajek yang dikembangkan di bawah bendera Anglikan.
“Penulis biografi modern pertama Henry VIII, A.F. Pollard, bersikeras bahwa raja tidak pernah goyah dalam pemaknaannya yang mendalam terhadap poin-poin utama iman Katolik,” kata Peter Marshall dalam bukunya Religious Identities in Henry VIII’s England (2006, hlm. 169).
Setelah beberapa tahun berlalu, Parlemen Inggris merasa perlu ada sosok “penjaga iman” dalam Kerajaan Inggris. Lagipula, mereka kalah gengsi dari Vatikan dan kerajaan-kerajaan lain di Eropa ketika gelar itu dicabut paksa dari Henry VIII.
Oleh karena itu, pada 1544, Parlemen Inggris memberikan lagi gelar itu kepada sang raja. Untuk mengenang momen penting itu, Pemerintah Inggris sepakat menyematkan singkatan Fid. Def. atau F.D. pada setiap koin mata uang. Gelar inilah yang terus diwariskan kepada raja dan ratu penerus takhta Kerajaan Inggris berikutnya hingga Charles III.
Penulis: Tyson Tirta
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id