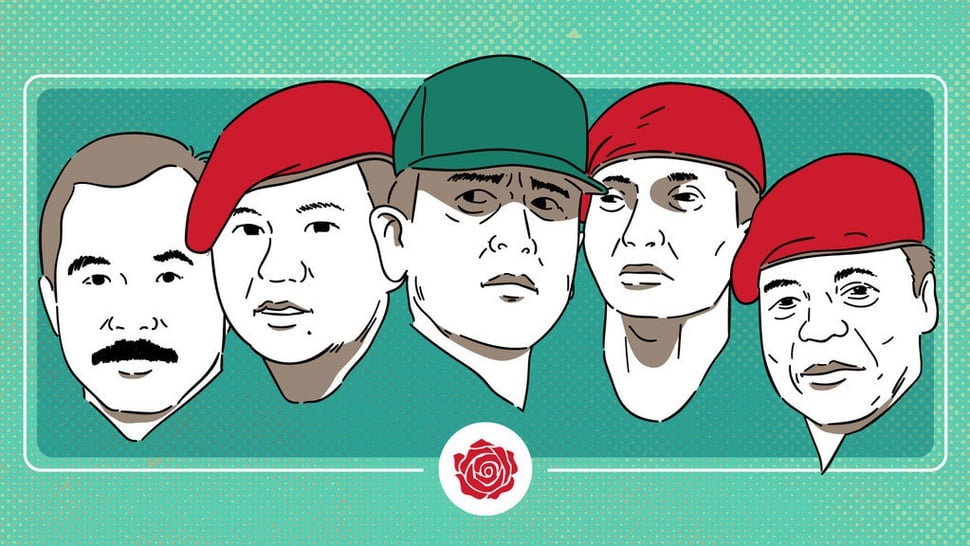tirto.id - Sepuluh hari menjelang pemilihan presiden 2019, sebuah video amatir beredar di media sosial. Purnawirawan jenderal bintang dua Kivlan Zen, yang mendukung Prabowo Subianto, beradu mulut dengan pensiunan jenderal bintang empat Wiranto, yang membela Joko Widodo. Dengan nada tinggi, Kivlan berkata kepada Wiranto, “Bukan aku yang nuduh, aku ngomong harusnya Abang bertanggung jawab, bukan dalang. Abang sebagai panglima (ABRI waktu itu).”
Pernyataan Kivlan merujuk peristiwa penculikan aktivis dan kerusuhan 1998, yang selama ini dibebankan kepada Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Panglima Kostrad yang dipecat dari dinas militer saat Wiranto memimpin ABRI—nama saat itu untuk Tentara Nasional Indonesia.
Pada 28 Maret 2019, dalam dialog ‘Sejarah 1998’ di Solo, Kivlan mengusulkan para jenderal 1998 buka-bukaan terkait penculikan aktivis. Sebulan sebelumnya, Kivlan menuding Wiranto sebagai dalang kerusuhan, bertanggung jawab atas penculikan aktivis, dan turut melengserkan Soeharto.
Pernyataan Kivlan pada Februari 2019 ditanggapi Wiranto dengan tantangan sumpah pocong. “Saya berani katakan,” kata Menkopolhukam Wiranto di Istana Presiden, “berani untuk sumpah pocong saja.”
“Apakah 1998 yang menjadi bagian kerusuhan itu saya, Prabowo, atau Kivlan Zen? Sumpah pocong kita, siapa yang sebenarnya dalang kerusuhan itu?”
Wiranto berdalih telah berhasil “mengamankan” negara pada 13-15 Mei 1998: “Tanggal 13 Mei terjadi penembakan Trisakti. Siang kerusuhan di Jakarta. 14 Mei kerusuhan memuncak. Malamnya saya kerahkan pasukan dari Jawa Timur masuk Jakarta sehingga 15 Mei pagi, Jakarta aman dan situasi nasional aman,” kata Wiranto, yang kini menjabat ketua dewan pertimbangan presiden di periode kedua pemerintahan Jokowi.
Jauh sebelum adu mulut Kivlan dan Wiranto terkait peristiwa 1998, Prabowo telah membela diri.
Kepada majalan Panji edisi 27 Oktober 1999, Prabowo berkata seharusnya Wiranto tahu situasinya saat itu. “Dia tahu kok ada perintah penyelidikan itu. Begitu dia jadi Panglima ABRI, saya juga laporkan sedang ada operasi intelijen, Sandi Yudha.”
Menurut Prabowo, nama-nama aktivis Partai Rakyat Demokratik yang diculik oleh Tim Mawar, satuan tugas dalam grup Kopassus yang dipimpinnya, diberikan oleh polisi sesudah kejadian ledakan di rumah susun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Ledakan itu terjadi di rumah petak yang ditempati oleh sejumlah kader PRD pada 18 Januari 1998. Peristiwa ini dianggap oleh para petinggi militer Orde Baru sebagai ancaman paling serius untuk menggagalkan Sidang Umum MPR pada Maret 1998.
Tim Mawar menyekap enam aktivis PRD, yakni Aan Rusdianto, Andi Arief, Faisol Riza, Mugiyanto, Nezar Patria, dan Raharja Waluyo Jati, di Markas Kopassus, Cijantung, antara Februari hingga Maret 1998. Khusus untuk ketiga nama lain—yakni Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, dan Pius Lustrilanang—Prabowo menyebutnya “kecelakaan” dan “saya tak pernah perintahkan untuk menangkap mereka.”
“Bahwa kemudian anak buah saya menyekap lebih lama sehingga dikatakan menculik," kata Prabowo kepada majalah Panji, "itu saya anggap kesalahan teknis."
Prabowo berkata “seingat saya, Pak Harto sendiri sudah mengakui kepada sejumlah menteri bahwa itu adalah operasi intelijen. Di kalangan ABRI, sudah jadi pengetahuan umum.”
Sementara terkait kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Jakarta, kepada jurnalis Jose Manuel Tesoro dari Asiaweek pada 3 Maret 2000, Prabowo membantah menjadi dalang, “Apa motivasi kami merancang kerusuhan?”
“Kepentingan kami adalah mempertahankan kekuasaan. Saya bagian dari rezim Soeharto. Jika Pak Harto bertahan tiga tahun lagi, saya mungkin sudah jadi jenderal bintang empat. Mengapa saya harus membakar ibu kota? Itu bertentangan dengan kepentingan saya...”
Bantahan Prabowo diperkuat pernyataan Panglima Kodam Jaya saat itu Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin dalam laporan Asiaweek. Ia membantah Prabowo memegang kendali atas dirinya selama kerusuhan 13-15 Mei 1998. “Dia (Prabowo) itu teman saya, tetapi saya harus memegang prosedur tugas saya,” kata Sjafrie.
Prosedur tugas yang dimaksud Sjafrie adalah Operasi Mantap. Operasi ini berlangsung dari 25 Maret 1996 sampai 30 Juni 1998 untuk mengamankan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Dalam dokumen tim penyelidikan Komnas HAM 2006 tentang kasus penghilangan paksa, komandan operasi saat itu adalah Panglima ABRI Feisal Tanjung (Mei 1993-Februari 1998) dan Kapolri Jenderal Dibyo Widodo (Maret 1996-Juni 1998).
Operasi itu dilakukan di seluruh Indonesia dengan Pangdam Jaya Sjafrie sebagai panglima komando operasi (Pangkoops) dan Kapolda Metro Jaya Mayjen Hamami Nata sebagai wakilnya. Karena saat itu berlaku pengarusutamaan polisi memegang kendali “keamanan dan ketertiban sipil”, Polri memberlakukan Operasi Mantap Brata untuk menindaklanjuti Operasi Mantap. Catatan khususnya, apabila situasi tak terkendali, komando dikembalikan ke Pangdam Jaya dengan tanggung jawab langsung kepada Pangab, sementara Pangab bertanggung jawab kepada Presiden Soeharto.
Memasuki kuartal pertama 1998, komposisi pimpinan elite militer berganti. Jenderal Feisal Tanjung diganti Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI terakhir di masa Orde Baru (Februari 1998-Oktober 1999). Posisi strategis lain seperti Danjen Kopassus masih dipegang Prabowo Subianto sebelum dialihkan ke Mayjen Muchdi Purwoprandjono pada 21 Maret 1998. Prabowo sendiri naik pangkat Letjen sebagai Panglima Kostrad. Adapun Kepala Staf Angkatan Darat dijabat Jenderal Subagyo HS.
Di DKI Jakarta, operasi ini menggunakan nama Mantap Jaya dan Mantap Brata Jaya. Pada 28 Agustus 1998 Pangdam Jaya Sjafrie dan Kapolda Jakarta Hamami Nata menyatakan kepada Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan 1998 bahwa pada 14 Mei sore terjadi penyerahan komando dari Kapolda ke Pangdam. Pangdam saat itu bertanggung jawab langsung ke Pangab Wiranto, bukan ke Pangkostrad Prabowo.
Pertanyaannya, kenapa hanya Prabowo yang selama ini disebut “dalang” peristiwa sekitar 1998?
Persaingan Menuju Pucuk Pimpinan Militer
Memasuki 1990-an muncul isu perpecahan di tubuh perwira ABRI, yakni antara faksi Merah Putih dan faksi Hijau. Faksi Merah Putih adalah kelompok perwira nasionalis dan dalam taraf tertentu bisa dikatakan sekuler. Faksi ini dimotori Jenderal Benny Moerdani (Pangab 1983-1988) bersama perwira lain seperti Edi Sudrajat, Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, Theo Sjafei, dan A.M Hendropriyono.
Sementara faksi Hijau adalah perwira yang memiliki simpati terhadap kelompok Islam, dalam hal ini Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dipimpin B.J. Habibie. Barisan jenderal yang termasuk dalam faksi ini, antara lain, Feisal Tanjung (Pangab 1993-1998), R. Hartono (KSAD 1995-1997), dan Sjafrie Sjamsoeddin (Pangdam Jaya 1997-1998).
Akan tetapi, simpati para perwira itu kepada kelompok Islam tak lepas dari peran Prabowo. Seperti diungkapkan Kivlan Zen dalam Konflik dan Integrasi TNI AD (2004), Prabowo-lah yang mendekati para perwira untuk bersimpati kepada Habibie dan ICMI.
Alasan yang dipakai Prabowo adalah membendung pengaruh Moerdani yang berusaha melakukan suksesi, termasuk melalui kudeta terhadap Soeharto.
Prabowo pernah menjadi staf khusus Moerdani pada 1983. Ia pernah melaporkan kepada Soeharto mengenai upaya kudeta oleh jenderal didikan Ali Moertopo itu. Laporan itu berakibat Moerdani berang dan memutasi Prabowo dari baret merah (Kopassus) ke baret hijau (Kostrad).
Prabowo menganggap Moerdani adalah batu ganjalan bagi karier militernya. Sewaktu Soeharto dan keluarga beribadah haji pada 1991, Prabowo menyiapkan rencana kontra-kudeta untuk menghadapi kemungkinan Moerdani melakukan kudeta.
Moerdani tak pernah terbukti mengudeta Soeharto. Namun, Prabowo tetap saja cemas. Ia menilai karier militernya bisa lancar sampai menjadi panglima hanya di bawah rezim Soeharto. Prabowo adalah menantu Soeharto dan saat itu mendapatkan kepercayaan dari mertuanya, demikian Kivan dalam bukunya.
Maka, dukungan Prabowo kepada Habibie adalah cara lain untuk memastikan karier militernya aman.
Pada awal 1990-an, Soeharto mengubah haluan politiknya dengan bersimpati kepada kelompok Islam dan merestui pendirian ICMI. Habibie praktis menjadi sosok paling berpeluang mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden pada Pemilu 1992.
Dalam Sidang Umum MPR 1993, Habibie mendapatkan suara tertinggi dari seluruh fraksi MPR untuk menjadi wapres. Namun, ia batal karena manuver Fraksi ABRI yang mengusulkan Try Soetrisno. Meski begitu, prediksi Prabowo tak meleset sepenuhnya. Habibie tetap dipercaya Soeharto dan akhirnya menjadi wapres pada 1998 pada akhir Orde Baru.
Upaya Prabowo bersama perwira faksi Hijau efektif membendung gerakan Moerdani, terlihat dari bercokolnya perwira hijau pada posisi strategis sepanjang 1990-1998, seperti Feisal Tanjung yang menjadi Panglima ABRI, R. Hartono menjadi Kepala Staf AD, Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Pangdam Jaya, dan Prabowo menjadi Danjen Kopassus. Sebaliknya, faksi Merah Putih tersingkir.
Megawati sebagai ‘Proxy’
Akan tetapi, bukan berarti Moerdani Cs tak melakukan upaya apa pun. Mereka melakukan dukungan kepada Megawati Soekarnoputri, saat itu menjadi figur oposisi Orde Baru.
Pada 1993 atau sebelum tersingkirnya Edi Sudrajat dari Pangab, terselenggara Kongres Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Medan, yang berakhir buntudan berlanjut ke Kongres Luar Biasa di Surabaya. Di sini, ABRI Merah Putih bermain. Mereka mendukung Megawati menjadi Ketua Umum PDI. Dukungan diberikan melalui Kassospol ABRI Letjen Haryoto PS dan Danjen Kopassus Agum Gumelar.
Dalam pertemuan pimpinan ABRI pada 1993, Agum secara terbuka menyarankan para perwira tidak menjadikan Megawati dan Abdurrahman Wahid sebagai musuh. Pernyataan ini memiliki konsekuensi Agum dimutasi ke Medan sebagai Kepala Staf Daerah Militer Bukit Barisan.
Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016, hlm. 136-137) menyebut selain Agum, Hendropriyono menjadi perwira yang menaruh simpati pada gerakan Megawati saat itu.
Operasi kelompok Merah Putih berhasil. Megawati menjadi ketua umum PDI di kongres Surabaya.
Namun, tiga tahun setelahnya, operasi tandingan dilancarkan kelompok Hijau. Pangab Jenderal Feisal Tanjung dan Kasospol ABRI Letjen Syarwan Hamid mengatakan secara terbuka mendukung terselenggaranya Kongres PDI di Medan pada 1996. Dengan restu Mendagri Yogie S. Memet dan Dirjen Sosial Politik Depdagri Soetojo NK, kongres terlaksana. Soerjadi menjadi ketua umum PDI versi pemerintah dan mendapat keabsahan hukum sebagai peserta Pemilu 1997.
Gerakan suksesi faksi jenderal Merah Putih lewat ‘proxy’ Megawati bersentuhan dengan gerakan perlawanan rakyat dari aliansi pro-demokrasi, di antaranya dari anak-anak Persatuan Rakyat Demokratik. (Pada 22 Juli 1996, PRD dideklarasikan menjadi partai dan dalam manifestonya menyebut “Orde Baru tidak bisa lagi dipertahankan oleh rakyat Indonesia.”)
Itu membuat faksi ABRI Hijau ketakutan. Mereka menilai kemungkinan ada upaya menggagalkan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Maka, sebagai langkah preventif atas perintah Pangab Feisal Tanjung, berlakulah Operasi Mantap pada 25 Maret 1996.
Lebih kurang tiga bulan setelahnya, terjadi kekerasan politik atau dikenal “Kerusuhan 27 Juli” alias “Kudatuli”. Peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor PDI di Jakarta Pusat oleh kelompok Soerjadi ini menyebabkan 5 orang tewas dan 149 lain terluka, menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Pada 29 Juli 1996, pemerintah menyebut PRD sebagai dalang Kudatuli. Soeharto bahkan menuding PRD adalah “kelompok bersikap mental makar” dan manifestonya “berpikir dan bertindak seperti PKI” dalam sidang kabinet Pembangunan VI pada 7 Agustus 1996. (Jawa Pos edisi 8 Agustus 1996)
Meski begitu, dalam narasi lain, peristiwa Kudatuli terindikasi pula atas hasil operasi tingkat tinggi Theo Sjafei sebagai kelompok Moerdani demi melambungkan Megawati sebagai tokoh perlawanan Soeharto.
Rivalitas Elite Militer & Politik Memengaruhi Operasi Penculikan?
Dalam struktur komando saat itu, bersumber dari analisis yang digambarkan oleh tim penyelidik Komnas HAM 2005-2006, perintah tertinggi operasi penculikan dan penghilangan orang 1997-1998 berada di tangan Panglima ABRI dan perintah operasi daerah di bawah Pangdam, yang di Jakarta dijabat Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin. Salah satu wewenang keduanya adalah memerintahkan Bawah Kendali Operasi alias BKO pasukan dari Kopassus ke satuan tertentu.
Perintah BKO diberikan Pangab kepada kesatuan atas permintaan komando teritorial, menurut Mayjen Samsuddin seperti dilansir Kompas edisi 29 Agustus 1998.
Sebagaian besar operasi penculikan terjadi di Jakarta—termasuk terhadap lima simpatisan PDI dan Partai Persatuan Pembangunan pada 1997: Sonny dan Yani Afri pada 26 April; Deddy Hamdun, Ismail, dan Noval Alkatiri pada hari Pemilu 29 Mei. Sementara mengacu kepada mekanisme pelaksanaan Operasi Mantap yang berakhir pada 30 Juni 1998, korban penculikan di luar Jakarta yakni Suyat di Solo diduga disekap lebih dulu di Kandang Menjangan, markas Grup 2 Kopassus, sebelum dirinya hilang, menurut laporan tim penyelidik Komnas HAM 2006.
Saat Suyat, aktivis PRD, dihilangkan pada 13 Februari 1998 di rumah familinya, Komandan Grup 2 saat itu dijabat Kolonel Slamat Sidabutar. Sementara Komandan Korem Solo dijabat Kolonel Sriyanto Muntasram, Komandan Korem Pamungkas Yogyakarta dipegang Kolonel Djoko Santoso, dan Pangdam Diponegoro dipegang Mayjen Mardianto.
Sebelumnya Sriyanto Muntasram adalah mantan Komanda Grup 2 Kopassus (1996-1997). Lulusan Akademi Militer tahun 1974 yang satu angkatan dengan Prabowo ini kelak menjabat Danjen Kopassus (2002-2005); ia pensiun berpangkat mayjen saat menjabat Gubernur Akmil (2006-2007). Sementara sewaktu Danjen Kopassus dijabat Muchdi Purwoprandjono pada Maret 1998, posisi Slamat Sidabutar sebagai Komandan Grup 2 digantikan oleh Kolonel Tisna Komara. Sidabutar naik jabatan sebagai Komandan Korem di Dili; ia meninggal dalam kecelakaan helikopter di Timor Timur pada 4 Juni 1998.
Adapun Djoko Santoso, yang pernah menjabat Panglima TNI (2007-2010), kelak memegang Ketua Tim Sukses Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. (“Dulu Pak Prabowo adalah ketua batalion, saya wakilnya,” kata Djoko Santoso, anggota Dewan Pembina Gerindra, saat menerima pinangan Prabowo.)
Indikasi lain persaingan ABRI Merah Putih dan Hijau memengaruhi operasi penculikan 1998 adalah kesaksian para korban selamat kepada tim penyelidik Komnas HAM 2005-2006. Para interogator di Markas Kopassus mengajukan pertanyaan seputar keterkaitan aktivis-aktivis PRD—di antaranya Andi Arief, Faisol Riza, dan Raharja Waluyo Jati—dengan Moerdani, Jusuf Wanandi, dan Megawati.
Andi Arief dalam kesaksiannya mengungkap penculiknya sempat menyatakan “dia ditipu” Moerdani sehingga mau melakukan aktivitas melawan Orde Baru atau dalam bahasa penculik “melawan negara”.
Mencurigai aktivisme PRD dengan tudingan konspiratif, imbas dari persaingan antar-elite militer di akhir kekuasaan Soeharto, juga menjadi logika aparat Orde Baru saat menyelidiki ledakan di rumah susun Tanah Tinggi. Sejumlah dokumen, buku-buku, dan sebuah laptop yang disita dari lokasi perkara dikembangkan oleh otoritas keamanan pemerintahan Soeharto sebagai material yang memicu spekulasi politik, menurut laporan majalah Tempo edisi 17 Mei 1999.
Sofjan Wanandi, pengusaha sekaligus pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), sempat diperiksa aparat kepolisian dan Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakostranas), karena dituding punya hubungan dengan ledakan di Tanah Tinggi—sebuah tuduhan tanpa dasar kokoh.
Prabowo Subianto sendiri mengakui dalam wawancara dengan majalah Panji edisi 27 Oktober 1999 bahwa “para aktivis … enggak begitu ahli merakit bom.” Bom rakitan ini meledak tanpa sengaja karena dipicu suhu panas.
Wiranto Menggunting Lipatan Karier Prabowo
Pada 10 Maret 1998, Sidang Umum MPR berjalan lancar dan memilih Soeharto sebagai presiden lagi dan B.J. Habibie menjadi wakilnya. Durian runtuh bagi Prabowo. Dua orang dekatnya menjadi pimpinan nasional. Sebelas hari setelahnya, Prabowo mendapatkan bintang tiga di bahunya dan menjabat Panglima Kostrad. Ia selangkah lagi mencapai impiannya meraih bintang empat dan akhirnya menjabat Panglima ABRI.
Secara teori dalam tradisi ABRI, Prabowo tinggal menunggu masa jabatan Wiranto sebagai Pangab dan digantikan Subagyo HS, yang saat itu menjabat Kepala Staf AD. Lalu, Prabowo akan menjadi KSAD dan akhirnya menjadi Pangab. Kepada Jose Manuel Tesoro dari Asiaweek, proses ini paling tidak hanya perlu waktu tiga tahun.
Namun, yang luput diperhatikan Prabowo saat itu adalah agenda Wiranto.
Sebagai Panglima ABRI dan pernah menjadi ajudan pribadi Soeharto (1987-1991), Wiranto mendapatkan keuntungan strategis dan lebih leluasa bergerak pada detik-detik menjelang 21 Mei 1998.
Dalam buku autobigrafinya, Bersaksi di Tengah Badai (2003), Wiranto mengaku pada 15 Mei 1998 ia mengikuti rapat terbatas bersama Soeharto, Menkopolhukam Feisal Tanjung, Mendagri R. Hartono, Mensesneg Saadilah Mursjid, Menteri Kehakiman Muladi, Menteri Penerangan Alwi Dahlan, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) Moetojib, dan Jaksa Agung Soedjono Atmonegoro. Rapat ini diadakan oleh Soeharto untuk mendengar situasi politik terakhir, khususnya selama ia berada di Kairo sejak 9 Mei untuk mengikuti satu konferensi tingkat tinggi.
Wiranto menyatakan dalam rapat itu Soeharto menginginkan penggunaan TAP MPR Nomor V/1998 tentang pemberian wewenang khusus kepada presiden mandataris untuk "mengambil langkah-langkah khusus dengan alasan situasi nasional yang memburuk.” Salah satunya mengaktifkan kembali Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), lembaga adikuasa yang memberangus pandangan politik demi menopang pemerintahan Soeharto pasca-1965.
Pimpinan Kopkamtib 1998, kata Wiranto, akan diberikan Soeharto kepada dirinya sebagai Menhankam/Pangab. Namun, belum sampai pada rincian tugas dan pelaksanaan teknis, rapat disudahi Soeharto.
Kemewahan peran seperti itu tak dimiliki Prabowo. Pada hari yang sama ketika menjemput Soeharto di Bandara Halim Perdanakusuma, Prabowo justru menerima raut masam dari mertuanya, menurut pengakuannya kepada Tesoro dari Asiaweek. Prabowo menduga muka cemberut Soeharto kepadanya karena beredar kabar ia berencana menggulingkan mertuanya dengan sengaja menciptakan kerusuhan.
Soal kerusuhan, Prabowo berpendapat pada 14 Mei 1998 Jakarta ditinggalkan oleh perwira tinggi ABRI. Saat itu mayoritas perwira tinggi militer mengikuti apel di Malang yang dipimpin Wiranto, ujar Prabowo kepada Tesoro. Padahal suhu politik Jakarta sudah membara menyusul penembakan empat mahasiswa Trisakti pada 12 Mei. Prabowo mengaku menelepon Wiranto berulangkali untuk membatalkan apel, tapi permintaannya ditolak.
Sebaliknya, Wiranto dalam autobiografinya membantah tudingan Prabowo. Apel di Malang, ujar Wiranto, untuk serah terima Komando Pengendalian Pasukan Pengendali Reaksi Cepat; bukan sengaja mengosongkan Jakarta. Ia menuding justru Prabowo yang memintanya memimpin serah terima itu—kendati tak menjelaskan alasan permintaan Prabowo.
Pada 18 Mei, Soeharto menandatangani instruksi presiden nomor 16 dan menyerahkan ke Wiranto pada 20 Mei sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional, yang mirip Kopkamtib. Salah satu perintahnya memberi wewenang Wiranto untuk “mengambil langkah pencegahan … atau mengatasi peristiwa yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban,” termasuk melibatkan aparat sipil dan militer melaksanakan komando operasi.
Kelak, pada 2016, Wiranto berkata kepada Andy F. Noya dalam Kick Andy bahwa ia tak menggunakan instruksi itu lewat pemberlakuan darurat militer, tetapi mengikuti proses peralihan kekuasaan secara damai.
Posisi Wiranto saat itu membuatnya sering di Cendana, rumah keluarga Soeharto, khususnya setelah 15 Mei 1998. Wiranto dalam autobiografinya mengaku di Cendana dalam berbagai keperluan, salah satunya pada 17 Mei ketika menegur Prabowo yang dituduh mengkhianati Soeharto. Prabowo mengaku bertemu Wiranto di Cendana dalam rentang 15-20 Mei 1998, salah satunya pada 18 Mei ketika menerima informasi dari Wiranto bahwa anak-anak Soeharto “ingin berperang.”
B.J. Habibie dalam memoarnya, Detik-Detik yang Menentukan (2006), menyebut Wiranto bolak-balik antara Cendana dan rumahnya di Kuningan. Pada 20 Mei malam, saat Habibie ke Cendana usai mendengar rencana pengunduran diri Soeharto, Wiranto ada di situ. Usai perbincangan dengan Soeharto, Habibie meminta Wiranto membatasi perwira yang ingin bertemu Soeharto dan harus melalui izin Wiranto.
Kewenangan strategis Wiranto yang lain saat memerintahkan Pangdam Jaya Sjafrie Sjamsoeddin mengawal long march mahasiswa ke parlemen pada 18 Mei 1998. Mahasiswa akhirnya berhasil menduduki parlemen setelah sebelumnya selalu terhalang. Wiranto kelak sesumbar keputusannya membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR demi “menghindari pertumpahan darah.”

Sebaliknya, gerakan Prabowo terbatas. Dalam pengakuannya kepada Tesoro dari Asiaweek, ia bertemu dengan dua tokoh oposisi, Adnan Buyung Nasution dan Abdurrahman Wahid, pada 14 Mei demi meredam kerusuhan; dan pada 16 Mei 1998 mengecek kebenaran selebaran rilis berita dari Mabes ABRI yang mendukung pernyataan Nahdlatul Ulama agar Soeharto mundur.
Di Cendana pada 18 Mei saat bertemu Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut, putri sulung Soeharto, Prabowo memberi opsi kepada Soeharto mengganti Pangab Wiranto atau menerapkan darurat militer. Namun, kata Tutut, Soeharto menolaknya.
Prabowo sempat terkunci tugas dari Wiranto pada 19 Mei untuk mengamankan rencana demonstrasi Amien Rais di Monas pada 20 Mei.
“Rapat yang diketuai Wiranto memutuskan bahwa perintahnya mencegah arak-arakan dengan segala cara,” kata Prabowo kepada Tesoro. “Saya berkali-kali menanyakan apa maksudnya? Apakah kami menggunakan peluru tajam? Ia (Wiranto) tidak memberi jawaban jelas.”
Nanti, langkah-langkah Prabowo itu membuatnya terjungkal karena menguatkan anggapan ia mendalangi kerusuhan. Wiranto dalam autobiografinya berkata tindakan Prabowo di lapangan, terutama menemui Buyung Nasution dan Gus Dur, telah menyalahi aturan.
“Seharusnya Pangkostrad berorientasi pada wilayah, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pangkostrad yang menggerakkan pasukan atas perintah Panglima ABRI. Bukan ke sana ke mari ngurusin masalah politik dan kenegaraan. Walaupun hal itu dilakukan, harus sepengetahuan pimpinan, bukan atas kehendak sendiri dan sama sekali tidak melaporkan kepada atasan,” tulis Wiranto.
Petaka menimpa Prabowo pada 19 Mei 1998 malam. Dari rumah Habibie untuk mengabarkan kemungkinan Soeharto mundur, ia pulang ke Cendana dengan berharap dapat pujian karena berhasil mencegah aksi demonstrasi.
Prabowo melihat Wiranto duduk dengan keluarga Soeharto. Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek), putri bungsu Soeharto, berdiri dan menatap Prabowo. Lalu, Mamiek menudingkan jarinya ke Prabowo dan berkata, “Kamu pengkhianat! Jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi.”
Prabowo keluar dan menunggu penjelasan, tapi ia hanya mendengar tangisan Titiek, istrinya.
Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri. Habibie secara resmi menjadi presiden. Esoknya, Prabowo mendengar tuduhan bahwa dirinya merancang kudeta terhadap Habibie.
Informasi kudeta itu disampaikan Wiranto kepada Habibie usai pelantikan dan diperkuat ajudan Habibie, Sintong Panjaitan—rival Prabowo di Kopassus. Mereka menyebut Prabowo menggerakkan pasukan Kostrad dan Kopassus ke Istana Negara dan kediaman Habibie.
Kabar kudeta membuat Habibie marah dan meminta Wiranto mencopot jabatan Prabowo sebagai Pangkostrad sebelum matahari terbenam. Mendengar perintah itu, Prabowo berusaha meminta penjelasan kepada Habibie. Prabowo mengklarifikasi bahwa kabar kudeta dengan mengerahkan pasukan sesungguhnya untuk melindungi Habibie. Namun, pendapatnya diabaikan Habibie. Hari itu juga jabatan Pangkostrad Prabowo dicopot—hanya menjabat selama sebulan.
Dalam hitungan bulan setelah pencopotan itu, karier militer Prabowo benar-benar tamat.
Pada Agustus 1998, Wiranto mengeluarkan surat pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk mengusut Prabowo terkait kasus penculikan aktivis. DKP diketuai oleh Kepala Staf AD Jenderal Subagyo HS, wakil ketua Letjen Fachrul Razi dan Letjen Yusuf Kertanegara serta enam anggota lainnya, di antaranya Letjen Agum Gumelar dan Letjen Susilo Bambang Yudhoyono.
Keputusan DKP pada 21 Agustus menyebut, di antara hal lain, bahwa Prabowo—yang menyandang NRP 27082—telah melanggar wewenang dengan memerintahakan Tim Mawar di bawah Kopassus menculik para aktivis; serta tidak melaporkan operasi kepada Wiranto, yang baru dilaporkan pada awal April 1998 setelah didesak oleh Kepala Badan Intelijen ABRI Mayjen Zacky Anwar Makarim.
Kesimpulannya, Prabowo “cenderung mengabaikan sistem operasi, hierarki, disiplin, dan hukum di lingkungan ABRI”. DKP merekomendasikan agar Prabowo “diberhentikan dari dinas keprajuritan”.
Prabowo mengaku dalam wawancara dengan majalah Panji edisi 27 Oktober 1999 bahwa ia tak kaget atas keputusan DKP. Ia mengaku Soeharto sendiri yang menginginkan kariernya di militer tamat karena hal itu “lebih baik bagi ABRI.”
Prabowo juga mengaku karier tentaranya dimatikan sewaktu bertemu dengan Moerdani, jenderal yang paling ingin disingkirkannya, tak lama sebelum DKP bekerja. “Jadi keputusan untuk menyingkirkan saya sudah jatuh sebelum DKP dibentuk,” klaim Prabowo.
Dua hari setelah keputusan DKP, Prabowo menemui Wiranto. Pertemuan selama 10 menit ini berlangsung dingin. Wiranto berkata seolah lepas tangan, cerita Prabowo.
“Kamu, kan, tahu kondisinya,” kata Wiranto sebagaimana diklaim Prabowo.
“I don’t like it,” balas Prabowo sambil menatap mata Wiranto.
Pada 20 November 1998, Presiden Habibie resmi “memberhentikan dengan hormat” Letjen Prabowo Subianto dari dinas militer.
Kelak, Prabowo sempat menyinggung kembali perkara kudeta 1998 saat berorasi dalam kampanye Pemilihan Gubernur Jawa Barat untuk pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu dari koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. “Terus terang saja,” katanya di Depok pada 1 April 2018, “dalam hati saya nyesel. Kenapa saya enggak kudeta dulu?”
Reuni di Pemerintahan Jokowi
Rabu jelang siang, 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memperkenalkan 38 menteri barunya sambil duduk di pelataran Istana Negara. Mereka berpakaian batik dan semringah. Di antara mereka ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Akmil 1974), Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Akmil 1970), dan Menteri Agama Fachrul Razi (1970).
Lebih kurang dua bulan setelahnya, Jokowi melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, salah satunya adalah Wiranto (Akmil 1968), mantan Menkopolhukam di periode pertama Jokowi.
Mengenai barisan pensiunan jenderal dalam pemerintahan Jokowi itu, seorang purnawirawan jenderal Angkatan Darat yang kami temui pada awal Januari 2020 mengaku heran mengingat persaingan mereka di masa lalu. Ia menyoroti langkah Jokowi mengangkat Prabowo, yang menurutnya jenderal pecatan, dianggap kurang memahami “etika dan norma” keputusan negara—merujuk keputusan Dewan Kehormatan Perwira, 22 tahun lalu.
“Kalau sampai Prabowo [mendapatkan] bintang empat—pangkat jenderal—itu sama saja Jokowi telah menampar pipi kanan saya,” katanya.
Ia menitipkan harapan kepada para jenderal dari faksi Merah Putih di lingkaran terdekat Jokowi agar kecemasannya itu tak menjadi kenyataan, meski dia sendiri ragu.
“Persaingan antara Prabowo dan Wiranto dan Luhut sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dinafikan lagi,” katanya. “Saya juga heran mereka sekarang dengan Prabowo mesra sekali. Tapi ya… itu politik.”
______
Laporan ini disusun berkat kolaborasi antara Tirto dan peneliti militer Made Tony Supriatma dan Aris Santoso serta kontributor Ahsan Ridhoi, Muammar Fikrie, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Artikel ini berbasis dokumen laporan akhir tim penyelidikan Komnas HAM pada 30 Oktober 2006 tentang pelanggaran HAM berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa. Basis materi primer lain adalah dokumen keputusan Dewan Kehormatan Perwira pada 21 Agustus 1998 dan keputusan Presiden B.J. Habibie pada 20 November 1998.
Materi sekunder adalah wawancara Prabowo Subianto dengan majalah Panji edisi 27 Oktober 1999; pengakuan Prabowo kepada Jose Manuel Tesoro dari Asiaweek pada 3 Maret 2000; buku memoar Habibie, autobiografi Wiranto, buku yang ditulis Kivlan Zen, buku yang ditulis Salim Said, buku yang ditulis A. Pambudi mengenai Sintong Panjaitan dan Prabowo, serta pencarian informasi di media massa.
Laporan keempat ini bagian dari enam artikel yang kami siapkan untuk dirilis selama pekan berikutnya.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Fahri Salam