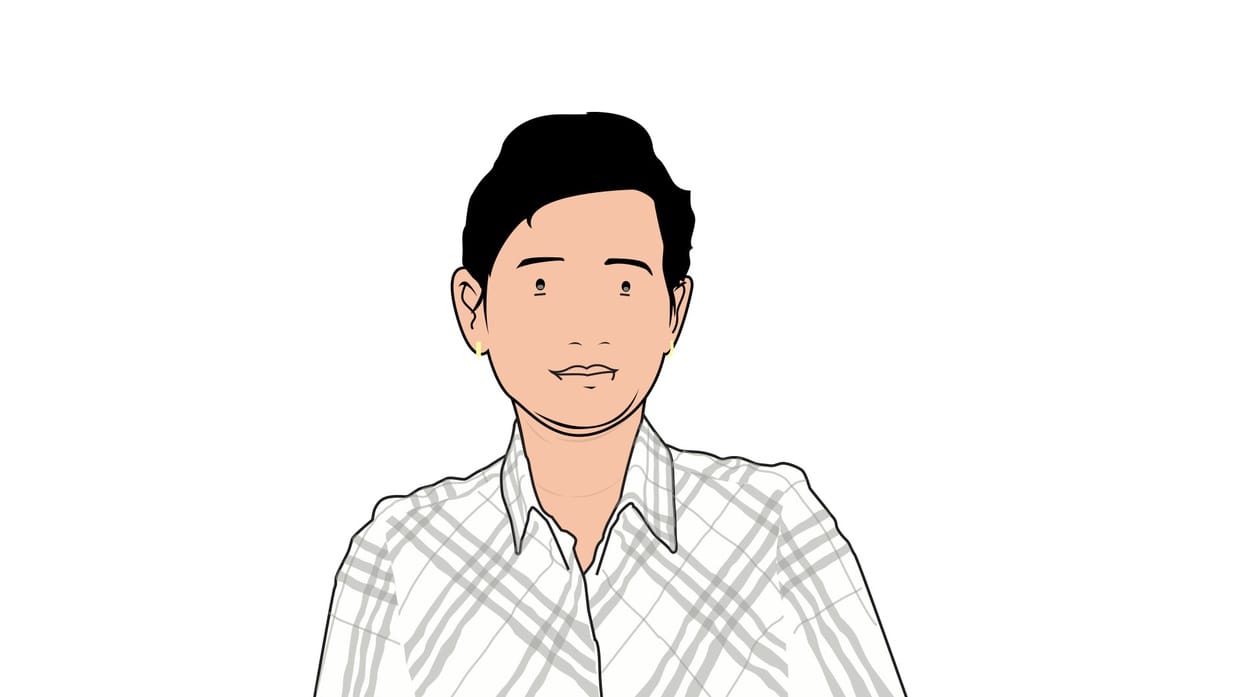tirto.id - Film dokumenter Nyanyian Akar Rumput (Yuda Kurniawan, 2018), yang berkisah tentang perjalanan Fajar Merah sebagai musisi, telah turun layar setelah bertengger selama 9 hari di layar bioskop. Fajar adalah anak bungsu Wiji Thukul, penyair dan aktivis politik yang dihilangkan paksa oleh negara.
“Siapa pun presidennya nanti, harapannya semoga ia mampu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Karena aku sudah terlalu lelah menanti sesuatu yang enggak pasti,” ungkap Fajar dalam film tersebut.
Ia nyaris tak pernah mengenal ayahnya. Usianya masih balita ketika sang ayah hilang dan kemungkinan diculik pada 1998.
Ada sepotong adegan dramatis saat penyerahan penghargaan Yap Thiam Hien 2002 untuk Wiji Thukul. Dyah Sujirah, istri Thukul, kerap dipanggil Sipon, tak kuasa melanjutkan pidato di atas panggung. Ia terisak sebelum jatuh terkulai.
Pada film yang merekam gambarnya pada 2014, Sipon tampak bungah menatap layar televisi yang menayangkan pelantikan Joko Widodo sebagai presiden 2014-2019. Sipon mengenakan kaos bergambar Jokowi, yang disebutnya “orang yang tulus. Ketika Wani menikah, beliau datang ke rumah ini.” Saat itu Jokowi masih sebagai Wali Kota Solo.
Kali lain, dalam wawancara dengan media saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkata: “Wiji Thukul itu, saya sangat kenal baik. Dia, kan, orang Solo. Anak-istrinya saya kenal. Puisi-puisinya saya juga tahu.”
Saat itu Jokowi menegaskan keberpihakannya terhadap kasus penculikan Wiji Thukul. “Harus ditemukan. Harus jelas. Bisa ketemu hidup atau meninggal. Masak 13 orang bisa ndak ketemu tanpa kejelasan?”
Dalam Nyanyian Akar Rumput, terpampang wajah Pak Kemis, ayah Thukul; Mbok Sayem, ibu Thukul. Ada juga Asmara Nababan, saat itu Sekjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
“Praktik penghilangan paksa merupakan kejahatan kemanusiaan di muka bumi ini. Dan ini menjadi lonceng peringatan kepada kita semua untuk menyelesaikannya,” demikian Asmara Nababan saat penyerahan anugerah Yap Thiam Hien 2002 untuk Wiji Thukul yang diterima oleh keluarganya.
Kini, Asmara Nababan telah meninggal. Pak Kemis telah meninggal. Mbok Sayem juga telah meninggal. Wani dan Fajar, dulu masih anak-anak ketika bapaknya hilang, kini telah dewasa. Wani telah menikah dan memberikan Thukul seorang cucu yang manis.
Semua berubah. Hanya satu yang kekal: Thukul tetap tak pulang dan negara tetap bungkam.
Hingga hari ini, Bu Paian Siahaan, ibunda Ucok Munandar—salah satu korban orang hilang—tak pernah bisa melupakan derai tawa anaknya saat berpamitan dan kemudian tak pernah pulang. Hingga detik ini dalam dompet Pak Utomo, ayah Petrus Bima Anugerah, masih terselip selembar foto putranya yang telah pudar dimakan usia. Hingga bertahun lalu, Mami Koto tak putus berharap menemukan kubur Yani Afri—jika benar telah mati—hingga sang bunda sendiri yang dijemput ajal.
Ketika Wani hendak menikah, Sipon kerepotan mengurus wali nikah. Bagaimana harus mencantumkan status kehidupan Wiji Thukul? Apakah suaminya harus dianggap mati? Bagaimana menjelaskan suaminya "hilang"?
Demikian juga ayah Suyat dan ayah Ucok ketika mereka hendak membagi warisan. Komnas HAM memang memberikan status surat yang menyatakan mereka adalah korban penghilangan paksa, tapi surat itu tak bernyali di hadapan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
Bagaimana juga dengan status Sipon, janda cerai mati, atau apa?
Para keluarga ini telah menunggu selama sedikitnya 8.030 hari. Telah menempuh pelbagai jalan demi mencari titik terang nasib anak dan keluarga mereka. Keinginannya sederhana: kejelasan.
Setidaknya mereka bisa mendoakan secara layak jika benar orang-orang yang mereka cintai telah mati. Mereka juga mengirim pesan: agar peristiwa ini jangan sampai terulang lagi. Tak ada lagi orang-orang yang dihilangkan paksa oleh negara.
Pada Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang dipecat karena dianggap bertanggung jawab atas kasus penculikan. Keluarga korban kemudian memilih dan mendukung Jokowi serta menaruh harapan kepadanya. Jokowi berkali-kali menyatakan, “Saya tidak memiliki beban masa lalu.”
Pada 9 Desember 2014, di hadapan para korban dan penyintas di Yogyakarta, Jokowi berkata: “Pemerintah terus berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara berkeadilan. Ada dua jalan yang bisa kita lalui, yaitu lewat jalan rekonsiliasi secara menyeluruh; yang kedua, lewat pengadilan HAM adhoc.”
Pernyataan itu dikuatkan kembali dalam pidato kepresidenan 14 Agustus 2015: “Saat ini pemerintah berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di tanah air.
Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara.”
Ungkapan itu tak ada jejaknya.
Jokowi sempat bertemu dengan perwakilan korban di Istana, sekali saja, dan setelah itu tak ada kelanjutan apa-apa. Setiap Kamis sore, para korban masih terus berdiri dengan payung hitam di depan Istana. Pada pidato pelantikan kedua, 20 Oktober 2019, persoalan HAM sama sekali tak diulik lagi oleh Jokowi. Yang terjadi justru kejutan: Ia merangkul Prabowo Subianto dan memberikan jabatan prestisius: Menteri Pertahanan.
Kini, kita telah berjarak 22 tahun dari momentum reformasi. Militer tetap kuat. Para pelaku bertengger di tampuk kekuasaan. Struktur politik tetap oligark yang sama. Sementara euforia massa untuk perubahan politik semakin menurun.
Jika kekuasaan terus menutup mata dan mengulur waktu atas kasus-kasus HAM, sesungguhnya, ia hanya menyimpan bom waktu yang berdampak pada siklus rantai kebal hukum (impunitas), yang kita alami sepanjang waktu: Polisi dan tentara terus merepresi masyarakat karena nyaris tak pernah ada hukuman memadai.
Masyarakat belajar dari lingkaran kekerasan yang tak pernah diakhiri oleh negaranya sendiri. Para korban kembali menjadi korban berulang kali. Diberi janji. Disuguhi harapan. Kemudian, dibiarkan mati pelan-pelan.
Editor: Fahri Salam
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id