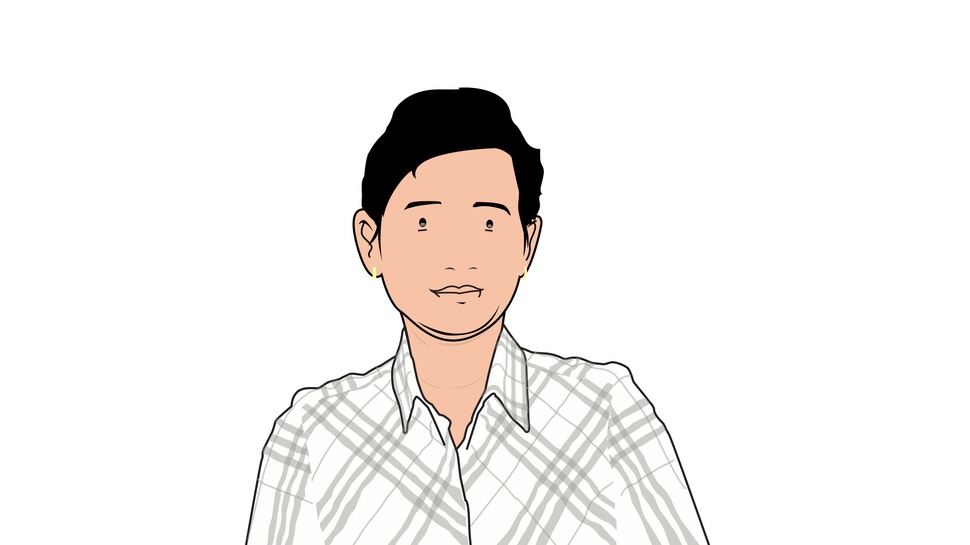tirto.id -
Ada tiga orang saya jumpai usai lari pagi. Pertama adalah Mbah Karno, 74 tahun. Ia tengah menenteng satu kantung besar berisi dua ratus potong tahu goreng yang hendak dititip ke kios makanan dekat pasar Panggungrejo ketika saya menyapa dan membantu membopong kantung plastiknya. Mbah Karno tersenyum, membenahi letak kerudung yang melorot yang bikin anak-anak rambut putihnya mencuat keluar. Ia bilang, tahun 1960-an ia berdagang batik di Pasar Klewer. Modalnya habis untuk menyekolahkan tujuh anak.
Mendengar ia menyebut tahun 1965, tiba-tiba saya ingat berita tentang pidato Prabowo Subianto yang tengah ramai dibincang: "Dengan demikian ideologi komunis dan gerakan komunisme di Indonesia patut diduga masih tetap eksis!" Teks pidato itu dibacakan oleh Rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal Tri Legionosuko dalam pembukaan acara bedah buku “PKI Dalang dan Pelaku G30S 1965” di kantor Lembaga Ketahanan Nasional, pada Sabtu, 23 November 2019.
Saya pun tergelitik bertanya pada Mbah Karno,
“Waktu gegeran 1965, Simbah menyaksikan tidak?”
“Waaa.. ya sudah. Saya dengar ada gegeran di desa saya. Lha itu orang-orang dijemputi dari rumahnya. Trus dibuang, ke bengawan itu….”
Saya memungkasi obrolan. Matahari baru saja menyembul keluar, rasanya janggal membahas tema yang begini berat. Kami pun beralih ke tema-tema enteng. Tentang jenis tahu yang cocok untuk dibuat tahu isi dan tahu bacem.
Esoknya, saya bertemu Mbah Wulan, 65 tahun, penjual tengkleng, makanan maknyus khas Solo berbahan baku tulang dan kepala kambing. Ia tengah menguliti empat buah kepala kambing ketika saya lewat. Senyumnya merekah. Saya pun berhenti, membenarkan tali sepatu yang ambyar, lalu membuka percakapan soal cara mengolah tengkleng. Ia sudah berjualan tengkleng sejak 30 tahun lalu. Mulai dari digendong keliling kampung, hingga sekarang sudah punya kios tetap dan pelanggan setia. Mengingat usianya, saya tak tahan untuk bertanya tentang ‘tahun yang tak pernah berakhir’ yang telah mengubah peradaban Indonesia, yakni peristiwa 1965.
“Wah, ya, saya tahu. Waktu itu ada gegeran. Di kali sebelah desa saya banyak yang mayit-mayit mengambang!” ujarnya sambil mengayun pisau, membelah kepala kambing yang telah dikuliti bulu-bulunya. “Itu baunya sampai berbulan-bulan ndak ilang…”
Lagi-lagi saya kemudian menyudahi obrolan. Adegan ia menguliti kepala kambing dan tema tentang 1965 itu bikin ulu hati saya mendadak ngilu.
Esok paginya, saya bertemu dengan Mbah Ahmad, penjual buah dari Jumantono, Karanganyar, sekira 20 km dari kampus UNS. Ia menyerahkan KTP kepada saya ketika saya dengan hati-hati menanyakan umurnya, 77 tahun. Hari itu ia membawa beberapa sisir pisang bawen, mangga manalagi, buah naga dan beberapa butir durian asli Jumantono. Pukul 04.00, anaknya mengantar ke Terminal Karanganyar naik sepeda motor dengan dua keranjang besar di kanan dan kiri. Lalu ia naik bis jurusan terminal Solo dan turun di depan kampus UNS.
“Waktu gegeran 1965, sampai ke Jumantono, ndak, Pak?”
Ia memicingkan matanya sebentar, menatap saya lekat-lekat lalu menjawab agak keras.
“Wah, lha, iya. Waktu Gestok itu ya di Jumantono juga geger. Ada yang diambil. Masih saudara juga. Itu kan gara-gara Soeharto mau berkuasa, mau mengambil dari Pak Karno!”
Perbincangan pun harus terinterupsi oleh seorang pembeli yang memilih-milih durian.
Sambil berjalan menuju penginapan, saya termangu. Kisah-kisah seperti ini tercecer sepanjang jalan. Menjadi gumpalan ingatan orang-orang yang menyaksikannya secara langsung. Ada keluarga dekat yang diambil paksa lantas tak pulang. Ada tetangga yang mereka temukan mengapung di tengah bengawan. Berjarak lebih dari 50 tahun sejak peristiwa, tak serta-merta membuat seluruh ingatan lindap. Ada memori kelompok yang terlanjur mengakar di alam bawah sadar. Pengalaman-pengalaman personal warga di tengah tahun-tahun penuh gejolak itu saling bertaut dan membentuk suasana kebatinan yang kental: ngeri, sedih, marah, takut, masgul, serta gamang menatap zaman.
Sore harinya, di sebuah pameran Biennale Jogja XV di Taman Budaya Yogyakarta, saya terkesima di sebuah ruang pameran instalasi Kelompok Studio Malya yang mengusung tema “Have You Heard It Lately?” Ruangan temaram itu diisi dengan 65 kaleng dengan kabel terjuntai, berisi rekaman audio para korban 65.
Seorang gadis berkerudung asyik memotret. Saya bertanya “Ini pameran tentang apa ya?”
Ia menggeleng. “Enggak tahu, Kak. Motret saja. Lucu. Kaleng-kalengnya kayak telepon. Artistik.”
Oh. Okay.
Saya menyapa seorang anak muda yang tampak kusyuk mendengarkan suara-suara dari telepon kaleng.
“Itu cerita tentang apa sih?”
“Tentang PKI. Komunis. Yang kejam-kejam itu, lho...”
Oh, baiklah.
Esok paginya, di kampus FISIP UNS menggelar acara seminar “Melaung HAM Bersama Sivitas Akademika UNS” yang diselenggarakan oleh Indonesia untuk Kemanusiaan, Komnas HAM dan FISIP UNS, seorang perempuan sepuh mengangkat tangannya. Namanya Mbah Bethet, salah seorang penyintas peristiwa 1965. “Kami ingin menuntut keadilan, meskipun kami sadar jalannya akan sangat panjang. Mungkin sampai saya mati keadilan itu juga tidak datang. Saya cerita di sini, agar kita semua, khususnya anak-anak tahu peristiwa ini. Agar tidak sampai terulang kembali…” Suasana pun menjadi sejenak hening.
Dipaksa Kebas
Tentu tidak mudah menjalani hidup di sebuah negeri yang tak pernah punya kehendak untuk membuka sejarah kelam bangsanya sendiri. Semua serba membuat gamang. Peristiwa 1965 yang dialami langsung oleh para korban telah menyisakan torehan luka hingga bergenerasi selanjutnya. Disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya yang mau tidak mau turut menelan trauma di kepala. Kekerasan negara telah menerjang hingga hal-hal paling subtil dan personal dalam hidup manusia. Lalu Orde Baru yang dipimpin Soeharto sukses membangun narasi sejarahnya sendiri, kisah tentang Kesaktian Pancasila, pembunuhan para jendral dan aneka mitos kekejaman yang terus-menerus direproduksi. Narasi tunggal versi Orba dikokohkan lewat buku-buku sejarah, film, bangunan museum dan kurikulum sekolah.
Pasca-Orde Baru, mulai banyak terbit tulisan-tulisan sejarah dari perspektif korban. Forum-forum testimoni untuk bicara kebenaran digelar di banyak tempat. Sastra, film, lagu-lagu mulai bersenandung di banyak ruang. Akan tetapi, tetap tak sanggup menandingi narasi raksasa Orba yang kadung menjalar hingga ke tulang sumsum. Museum-museum dengan narasi tunggal masih tegak berdiri. Buku-buku sejarah tak juga direvisi. Ajaibnya, film Pengkhianatan G30S/PKI yang telah sempat berhenti tayang, kini kembali diputar di televisi dan layar tancap dengan sponsor dari institusi tentara.
Hantu komunisme terus saja bergentayangan bahkan hingga lebih dari 50 tahun kemudian. Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat adalah satu di antara pihak yang terus menjadi pengusungnya. Beberapa bulan lalu ia tersandung kasus dugaan kepemilikan senjata api. Oleh karenanya, September tahun ini Kivlan tak lagi bernyanyi senyaring biasanya. Kivlan terdiam, giliran Prabowo, mantan rival Jokowi dalam dua kali Pilpres yang kini diangkat sebagai Menhan, yang kini melaungkan kembali tentang hantu komunisme.
Pernyataan Prabowo ini mengerikan. Ia bisa menjadi legitimasi untuk membenarkan ‘hantu komunisme’ yang baru lenyap usai Pilpres 2019. Sebagai menteri pertahanan, Prabowo adalah representasi negara. Alih-alih merintis jalan untuk pelurusan sejarah, justru Prabowo kembali menabuh genderang perang. Ia membuka ruang yang berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil. Pada tahun-tahun belakangan, masih saja ada razia buku, film, dan segala atribut yang dianggap mengandung ideologi komunisme.
Inilah dampak dari negara yang tak pernah punya kehendak untuk meluruskan sejarah bangsanya. Seluruh bangsa ini diajak berjalan sambil terus memanggul luka sejarah yang tak pernah diobati. Akan kekerasan negara yang tak pernah dibuka dan dimintakan maaf. Kita terperangkap dalam semak belukar impunitas yang tak ada ujungnya. Akibatnya, rupa-rupa keberingasan baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun kelompok masyarakat sipil hilir mudik di hadapan kita. Lontaran “Bunuh!”, dan “Halal darahnya!” bisa kita dengar dari panggung ceramah agama hingga pawai di jalan-jalan raya. Dan kita hanya bisa terkesiap sesaat, untuk kemudian memakluminya. Nalar kita dibuat tumpul. Batin kita dipaksa menjadi kebas.
Menolak Kebohongan
Zaman terus berputar. Para korban dan saksi sejarah satu satu pergi. Satu generasi terus bertumbuh dengan rasa asing atas sejarah bangsanya sendiri. Tak ada upaya memutus rantai kekerasan. Tak ada bangunan penanda ingatan akan peristiwa di masa lampau seperti Museum Holocaust atau Jewish Holocaust Memorial Wall sebagai penanda jejak kekejaman Nazi di Jerman, atau The May 18 Democratic Archive di Gwangju, yang merekam jejak peristiwa pembantaian Gwangju tahun 1980 yang menjadi titik tonggak transisi demokratik di Korea Selatan.
Patahan ingatan akan peristiwa gelap itu tetap berderak di masing-masing kepala yang semakin rapuh dan mudah lupa. Peristiwa 50 tahun silam semakin berjarak dari generasi hari ini.
Namun, demikian hukum besi sejarah bekerja, selalu ada anak-anak zaman yang menolak bungkam dan enggan disumpal kebohongan. Salah satunya, sebuah metafora indah dari instalasi Studio Malya yang dipamerkan di Biennale XV Yogyakarta, yang menyimbolkan perbincangan isu 65 yang hadir samar-samar. Setiap kaleng berisi hasil rekaman audio dari wawancara dengan kolaborator memuat pesan utama mengenai komitmen untuk memutus kekerasan dan membagi praktik rekonsiliasi sehari-hari yang sedang diupayakan. Mereka bilang, ini sebagai ruang untuk memantik isu ini sebagai perbincangan sehari-hari. Telepon kaleng, suara-suara dari masa silam yang terdengar sama, perlu didengarkan kembali. Didekatkan kembali kepada generasi kini.
Prabowo, Kivlan Zein, dan lain-lainnya boleh saja terus jualan hantu komunisme. Rezim pun bermain aman tak mau repot dengan urusan pelurusan sejarah masa lalu. Namun, selalu ada anak-anak muda yang menatah keberanian untuk merawat ingatan.
Mumpung Mbah Karno, Mbah Wulan dan Mbah Ahmad masih bisa berkisah. Mumpung Mbah Bethet dan para korban masih bisa bercerita. Agar membincang peristiwa 1965 tak lagi dianggap tabu dan menakutkan, ia harus hadir dalam ruang sehari-hari, menjadi bagian pengetahuan dan pergulatan generasi masa kini. Karena perisitiwa 1965 salah satu fondasi yang membentuk cara kita bernalar dan berbangsa hari ini.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.